Suratu Nuh 71 ~ Tafsir al-Mishbah (2/4)
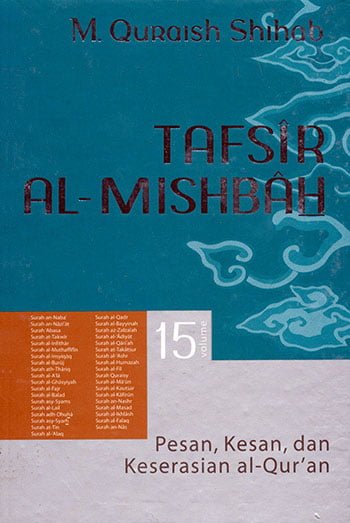
Tafsir al-Mishbāḥ
(Jilid ke-15, Juz ‘Amma)
Oleh: M. Quraish Shihab
Penerbit: Penerbit Lentera Hati
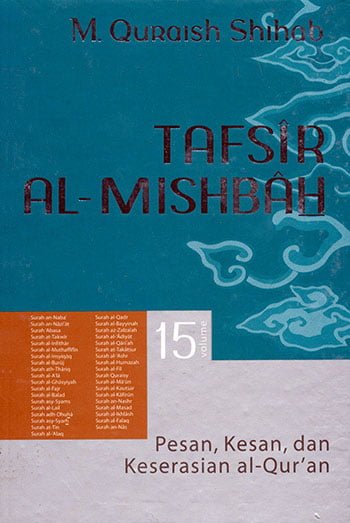
Tafsir al-Mishbāḥ
(Jilid ke-15, Juz ‘Amma)
Oleh: M. Quraish Shihab
Penerbit: Penerbit Lentera Hati
AYAT 5-7.
71: 5. Dia (Nūḥ) berkata: “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang,
71: 6. maka seruanku itu hanyalah menambah mereka kecuali lari.
71: 7. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka agar Engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan jari mereka ke dalam telinga mereka dan menutupkan bajunya dan mereka tetap bersikeras dan mereka menyombongkan diri dengan amat sangat.
Ajakan Nabi Nūḥ a.s., yang dilukiskan oleh ayat-ayat yang lalu, tidak disambut oleh kaumnya. Karena itu, Nabi mulia itu mengadu kepada Allah. Dia (Nūḥ) berkata: “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku untuk beriman kepada-Mu dengan berbagai ragam cara, dengan hikmah, nasihat serta diskusi yang terbaik dan itu kulakukan malam dan siang, yakni secara terus-menerus tanpa henti, maka seruanku itu hanyalah menambah sesuatu dari keadaan mereka kecuali lari dari kebenaran dan menghindar dari agama-Mu dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada keimanan dan ketaatan kepada-Mu agar Engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinga mereka karena enggan bahkan benci mendengarnya dan mereka secara bersungguh-sungguh menutupkan bajunya ke muka mereka agar tidak melihatku dan mereka tetap bersikeras dalam kedurhakaan mereka dan mereka juga menyombongkan diri dengan amat sangat sehingga tidak mempan dilunakkan oleh aneka ajakan kepada kebaikan.
Kata (أَصَابِع) ashābi‘ adalah bentuk jama‘ dari kata (أُصْبُع) ushbu‘, yakni jari-jari. Sebenarnya, mereka menyumbat telinga mereka dengan ujung anak jari, tetapi agaknya ayat ini menggunakan kata jari-jari untuk melukiskan betapa enggan mereka mendengar dan betapa keras upaya mereka menutup pendengaran mereka masing-masing sampai mereka menggunakan seluruh jari-jari mereka, bukan hanya satu jari atau bahkan ujung jari, dan itu pun dengan memasukkan jari-jari ke dalam telinga sehingga mereka mengharap tidak ada celah masuk buat suara.
Diungkapkannya oleh ayat-ayat di atas pengaduan Nabi Nūḥ a.s. yang bertujuan menggambarkan kepada generasi sesudah beliau, khususnya kepada kita, bahwa beliau adalah seorang yang mengembalikan segala sesuatu kepada Allah, beliau berserah diri kepada-Nya setelah upaya maksimal yang beliau lakukan. Memang, manusia hanya berusaha sekuat kemampuannya sedang keberhasilan atau kegagalan kembali kepada Allah s.w.t. berdasar hikmah-Nya dan karena itulah Nabi Nūḥ a.s. melaporkan hasil usahanya sambil menanti pertolongan dan petunjuk-Nya lebih jauh.
AYAT 8-12.
71: 8. Kemudian sungguh aku telah mengajak mereka dengan cara terang-terangan,
71: 9. kemudian sungguh aku telah menyeru mereka dengan terang-terangan dan juga merahasiakan.
71: 10. Maka aku katakan kepada mereka: “Mohonlah ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Dia senantiasa Maha Pengampun.
71: 11. Niscaya Dia akan mengirimkan langit kepada kamu dengan lebat,
71: 12. dan melapangkan harta serta anak-anak kamu, dan mengadakan untuk kamu kebun-kebun dan mengadakan untuk kamu sungai-sungai.
Nabi Nūḥ a.s. melanjutkan pengaduannya kepada Allah dengan berkata: Wahai Tuhan, kemudian kendati telah terus-menerus aku mengajak mereka beriman dengan berbagai cara itu dan selalu saja mereka menolak dan menolak, aku tetap saja mengajak mereka. Sungguh aku telah mengajak – secara khusus – buat mereka dengan cara terang-terangan, yakni dengan suara yang keras dan di hadapan umum kemudian pada kesempatan lain sungguh aku telah menyeru buat mereka dengan menggabung dua cara, yakni dengan terang-terangan dan juga merahasiakan ajakanku, yakni mengajak orang per orang secara diam-diam, siapa saja yang boleh jadi takut menampakkan keimanannya. Itu semua telah kulakukan Maka aku katakan kepada mereka: “Mohonlah ampun kepada Tuhan Pemelihara kamu atas dosa-dosa kamu khususnya dosa syirik – sesungguhnya Dia senantiasa Maha Pengampun bagi siapa yang tulus memohon ampunan-Nya. Kalau kamu benar-benar memohon ampunan-Nya, niscaya Dia akan mengirimkan air hujan atau keberkatan dari langit kepada kamu dengan lebat dan berulang-ulang, dan melapangkan harta serta memperbanyak anak-anak kamu, dan mengadakan pula untuk kamu kebun-kebun yang dapat kamu nikmati keindahan dan buah-buahannya dan mengadakan pula untuk kamu sungai-sungai untuk mengairi kebun-kebun kamu dan memberi minum binatang ternak yang Kami anugerahkan kepada kamu.
Nabi Nūḥ a.s. pada ayat di atas menyebut akan turunnya hujan yang lebat bila mereka beriman dan memohon ampun. Ini dapat dipahami sebagai isyarat tentang pekerjaan umum masyarakat ketika itu, yakni bertani. Atau bisa juga kata tersebut dipahami dalam arti tercurahnya aneka rezeki buat mereka, baik melalui pertanian maupun perternakan atau apa saja.
Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa ada kaitan antara keimanan dan taqwa dengan curahan rezeki serta terhindarnya kesulitan. Sebaliknya, ada juga kaitan antara kedurhakaan dengan jatuhnya musibah dan hilangnya anugerah. Sekian banyak ayat dan hadits Nabi s.a.w. yang menguraikan hakikat di atas. Lihat misalnya QS. al-A‘rāf [7]: 96, atau QS. al-Jinn [72]: 16, dan lain-lain.
Sayyid Quthub berpendapat bahwa hakikat yang disebut ayat di atas, yang mengaitkan permohonan ampun dengan limpahan rezeki serta keterikatan antara kesalehan hati dan konsistensinya, keimanan dengan kemudahan rezeki dan tersebarnya kesejahteraan, merupakan kaidah yang berulang-ulang disebut al-Qur’ān. Itu telah terbukti sepanjang masa. Hanya saja, menurut ulama ini, kaidah tersebut berlaku pada masyarakat umum, bukan pada pribadi-pribadi. Memang – tulisnya – bisa saja ada umat yang memperoleh kesejahteraan material padahal mereka tidak melaksanakan tuntunan syariat. Kesejahteraan itu buat mereka adalah ujian, yang akan berakhir dengan keruntuhan mereka. Ulama ini kemudian menunjuk dua kekuatan besar pada masanya – Kapitalisme Barat dan Komunisme Timur. Yang pertama meruntuhkan nilai-nilai moral hingga mencapai tingkat kebinatangan dan meruntuhkan nilai hidup sehingga hanya dinilai dengan dolar. Sedang, yang kedua meruntuhkan nilai-nilai kemanusiaan hingga menempatkan mereka pada posisi budak yang menjadikan semua yang berada dalam wilayah kekuasaannya hidup dalam ketakutan tidak dapat terjamin kelangsungan hidupnya. Demikian lebih kurang Sayyid Quthub dan yang telah terbukti kebenaran uraiannya dengan runtuhnya salah satu dari kedua adi kuasa yang disebutnya. Kita menanti keruntuhan adi kuasa yang lain, yang selama ini menerapkan standar ganda dalam penilaiannya terhadap situasi yang mereka hadapi.
AYAT 13-14.
71: 13. Mengapa kamu tidak mengharap bagi Allah penghormatan?
71: 14. Padahal sungguh Dia telah menciptakan kamu berfase-fase?.
Nabi Nūḥ a.s., yang menasihati kaumnya seperti terbaca pada ayat-ayat yang lalu, melanjutkan nasihat beliau dengan berkata: Mengapa kamu tidak mengharap bagi Allah penghormatan? Padahal sungguh Dia telah menciptakan kamu berfase-fase?. Dari nuthfah, ke ‘alaqah, ke mudhghah, dan seterusnya dan pada setiap fase itu Dia melimpahkan rahmat dan pemeliharaan-Nya kepada kamu.
Berbeda-beda pendapat ulama tentang makna ayat 13 di atas. Ada yang memahaminya dalam arti “Mengapa kamu tidak mengharapkan penghormatan Allah kepada kamu, yaitu dengan jalan beriman kepada-Nya.” Dengan makna ini, ayat di atas merupakan perintah untuk beriman dan taat kepada Allah dan Rasūl-Nya yang mengantar kepada harapan perolehan nikmat-Nya. Memang, siapa yang mengharapkan “penghormatan Allah”, ia harus beriman kepada-Nya serta beramal shalih dan inilah yang mengantarnya berharap memperoleh ganjaran-Nya yang juga merupakan salah satu bentuk penghormatan Allah kepada-Nya.
Al-Biqā‘ī menggarisbawahi penggunaan kata (تَرْجُوْنَ) tarjūna/mengharap. Menurutnya, kata itu digunakan di sini untuk menggembirakan mitra bicara tentang dampak baik dari amal perbuatan mereka dan bahwa amal-amal itu memiliki peranan dalam perolehan ganjaran-Nya, sedang penggunaan kata (طَمَع) thama‘ pada ayat-ayat yang lain – seperti dalam QS. al-Ma‘ārij [70]: 38 – untuk mengingatkan bahwa tidak ada satu sebab pun yang menjadikan seseorang memperoleh ganjaran-Nya kecuali rahmat Allah.
Imām Fakhruddīn ar-Rāzī berpendapat bahwa kaum Nabi Nūḥ a.s. sangat melecehkan beliau. Ayat di atas memerintahkan agar mereka menghormati beliau, seakan-akan menyatakan: “Kalau kamu menghormati Nabi Nūḥ a.s. dan tidak melecehkannya maka itu merupakan penghormatan bagi Allah s.w.t. Maka, mengapa kamu tidak melakukannya?” Ada juga yang memahami kata tarjūna/mengharap dalam arti (تَخَافُوْنَ) takhāfūn/takut sehingga ayat tersebut berarti: “Mengapa kamu tidak takut kepada Allah yang memilik kebesaran dan kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi kepada kamu? Atau mengapa kamu tidak mengharap ganjaran Allah dan takut akan sanksi-Nya?”
Ada juga ulama, seperti al-Baidhawī, memahami kata tarjūna dalam arti mempercayai sehingga ayat di atas dipahaminya dalam arti: “Apa yang terjadi pada diri kamu sehingga kamu dalam keadaan tidak mempercayai keagungan Allah – keagungan yang mengharuskan kamu beriman dan taat kepada-Nya.”
Thabāthabā’ī berpendapat lain. Menurutnya, kata (تَرْجُوْنَ) tarjūna/mengharap adalah lawan dari kata (تَخَافُوْنَ) takhāfūn/takut. Tidak mengharap mengandung makna putus asa, seperti jika anda berkata: “Saya tidak mengharap adanya kebaikan dari dia”, yakni anda telah berputus asa menemukan kebaikannya. Sedang kata (الوقار) al-waqar dipahami oleh ulama ini dalam arti kemantapan. Kemantapan yang dinisbahkan kepada Allah berarti kemantapan sifat rubūbiyyah yang mengantar kepada pengakuan Ketuhanan-Nya dan keharusan beribadah kepada-Nya. Penyembah berhala itu – dari kaum Nabi Nūḥ tersebut – bagaikan mencari Tuhan yang memiliki kemantapan dalam rubūbiyyah agar mereka menyembahnya. Mereka telah berputus asa menemukannya pada Allah sehingga mereka menyembah selain-Nya. Di sisi lain, mereka juga menyadari bahwa Allah tidak dapat dijangkau oleh pemahaman manusia dan karena itu tidak dapat diarahkan kepada-Nya peribadatan. Peribadatan adalah pelaksanaan hak rubūbiyyah yang atas dasar rubūbiyyah itu terlaksana pengaturan dan pengendalian alam raya, dan ini telah diserahkan-Nya kepada malaikat dan jinn. Maka, merekalah tuhan-tuhan yang disembah oleh para penyembah berhala itu dengan tujuan mendekatkan para penyembahnya kepada Allah yang tidak lain kecuali Pencipta tuhan-tuhan yang mereka sembah itu, sekaligus Pencipta penyembah-penyembahnya – tanpa mengatur dan mengendalikan mereka. Demikian lebih kurang Thabāthabā’ī.
Kata (أَطْوَارًا) athwāran adalah bentuk jama‘ dari kata (طَوْر) thaur yang antara lain berarti fase atau masa. Ia juga digunakan dalam arti kondisi yang dialami sesuatu. Banyak ulama memahami fase-fase dimaksud adalah fase-fase yang disebut antara lain pada QS. al-Mu’minūn [23]: 12-14. Rujuklah ke sana! (361).
Penciptaan manusia melalui fase-fase menunjukkan betapa luas kekuasaan ilmu dan pengaturan Allah s.w.t. Betapa tidak, dari setetes sperma yang bertemu ovum lahir anak yang sebelum kelahirannya melalui aneka fase dalam perut. Setelah kelahiran pun manusia mengalami aneka pergantian fase, dari kanak-kanak, remaja, dewasa, tua dan pikun. Kesemuanya adalah fase-fase yang dapat dialami manusia sekaligus menunjukkan kuasa, ilmu, dan rubūbiyyah Allah dalam penciptaan manusia. Karena itu, sungguh aneh jika manusia enggan mengakui Ulūhiyyah, Rubūbiyyah, serta ilmu dan Kuasa-Nya. Sungguh aneh jika ada manusia yang berpaling dan durhaka kepada-Nya.
Sayyid Quthub menggarisbawahi bahwa tentulah maksud kata athwāran dipahami oleh mitra bicara Nabi Nūḥ a.s. Boleh jadi pemahaman mereka tentang fase-fase tersebut adalah proses kejadian manusia sejak dalam perut ibu sebagai janin yang bertahap dari pertemuan sperma dan ovum hingga lahir sebagai manusia yang sempurna pembentukan fisiknya. Ini bisa saja terjangkau oleh mereka jika itu disampaikan kepada mereka atau jika mereka melihat janin yang gugur sebelum sempurna kejadiannya. Bisa juga yang dimaksud dengan fase-fase tersebut adalah perkembangan janin sebagaimana dikemukakan oleh pakar-pakar embriologi, yakni bermula dari sel tunggal yang sangat sederhana, kemudian berkembang sehingga menjadi bagaikan binatang yang memiliki banyak sel, lalu berkembang menjadi seperti binatang yang hidup di air, lalu menjadi seperti binatang mamalia, lalu menjadi manusia. Ini tentu saja di luar kemampuan kaum Nabi Nūḥ untuk menjangkaunya. Ini adalah satu pertemuan baru. Bahkan, boleh jadi juga teks di atas dan apa yang diuraikan dalam QS. al-Mu’minūn itu mempunyai makna lain yang belum diungkap oleh ilmu pengetahuan. Demikian lebih kurang tulis Sayyid Quthub.
Penulis tambahkan bahwa ayat di atas dipahami oleh sementara orang sebagai isyarat tentang teori Darwin yang menguraikan tentang proses kejadian manusia dari makhluk yang sangat kecil hingga meningkat sampai ke kera dan akhirnya menjadi manusia. Hemat penulis, pendapat ini terlalu jauh ke depan. Cukuplah kita memahami fase-fase yang dikemukakan ayat di atas dalam batas-batas yang dijelaskan al-Qur’ān. Kita tidak perlu mencari dan memaksakan penafsiran ayat-ayat al-Qur’ān untuk mendukung atau membatalkan teori itu. Kita serahkan saja pada ilmuwan untuk mendukung atau membatalkannya melalui penelitian ilmiah dan atas namanya karena al-Qur’ān tidak berbicara tentang proses kejadian manusia pertama kecuali bahwa awalnya yang dinyatakan dari tanah dan akhirnya diembuskan ruh kepadanya. Al-Qur’ān hanya menyebut A dan Z. Apa yang terjadi sesudah A, yakni sesudah adanya bahan tanah, dan sebelum Z, yakni sebelum diembuskan ruh, tidak disinggung oleh al-Qur’ān. Silakan ilmuwan mencari dan menemukannya, tetapi hendaknya mereka tidak memperatasnamakan al-Qur’ān.