Surah at-Takwir 81 ~ Tafsir Syaikh Fadhlallah (1/3)
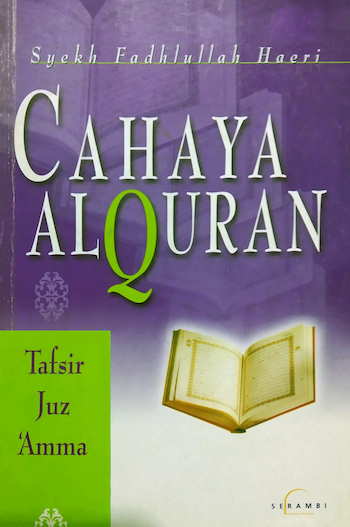
Tafsir Juz ‘Amma
(Judul Asli: Beams of Illumination)
Oleh: Syaikh Fadhlallah Haeri
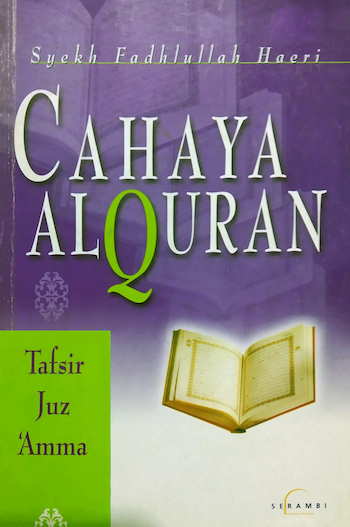
Tafsir Juz ‘Amma
(Judul Asli: Beams of Illumination)
Oleh: Syaikh Fadhlallah Haeri
“MENGGULUNG”
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ
Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Lagi Maha Penyayang.
Surah ini dimulai dengan membicarakan dimensi alam semesta, lalu bergerak ke dimensi manusia, kemudian memfokuskan pada kehidupan batin. Ia mulai dengan alam semesta, kembali kepada manusia, dan kemudian membicarakan manifestasi terbuka dari semua hal tersembunyi dalam rangka menampakkan kita secara lahir dan batin agar kita menemukan kesatuan dalam diri kita.
إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ
Kawwara artinya ‘menjadikan bulat, memadatkan, melipat sesuatu, menggulung’. Kurah adalah bola. Takwīr adalah gerakan sesuatu yang melipat dirinya sendiri menjadi bulat.
Pengetahuan bahwa matahari bersifat eksplosif dan ekspansif jelas-jelas sudah ada pada saat diturunkannya ayat ini. Ayat ini merupakan keterangan mengenai proses berbaliknya ekspansi penciptaan. Adapun matahari, ia terus-menerus meledak. Proses serupa terjadi pada bom hidrogen, yakni, melebur atau meledak sendiri secara terus-menerus. Kalau penciptaan yang meledak sendiri itu sampai pada akhirnya, maka matahari benar-benar akan melipat dirinya sendiri.
وَ إِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ
Inkadarat berasal dari akar kata kerja kadura, yang berarti ‘berlumpur, berawan, keruh, kehitam-hitaman’. Menurut beberapa sumber, inkadara artinya ‘menembak jatuh atau menukik ke bawah’. Manusia bersifat ekspansif: ia merefleksikan keekspansifan seluruh alam semesta. Sebagai buku pedoman kehidupan, al-Qur’an memperhatikan peran dan keadaan manusia dalam penciptaan. Realitas batin Nabi Muḥammad menggetar dalam kata-kata sebagai wahyu untuk seluruh umat manusia. Oleh karena itu, jika al-Qur’an tidak digunakan sebagai buku pedoman hidup, sebagai sesuatu yang dapat kita pahami dalam keadaan kita sekarang atau dalam keadaan lainnya di mana kita mungkin berada, berarti kita belum menggali dan menjadikannya berguna bagi kita. Kita harus menggemakan realitas Qur’ani dalam kehidupan sehari-hari kita dan kita harus mengambil manfaat darinya sebanyak mungkin. Pada setiap tahap kehidupan, al-Qur’an mampu menghilangkan noda yang telah menutupi sumber pengetahuan dalam diri kita. Sumber pengetahuan itu berada dalam diri kita, dan kegunaan al-Qur’an adalah untuk membawa kita kepada penyadaran.
Secara naluriah manusia tidak menyukai kegagalan sebab ia merefleksikan ekspansi alam semesta. Kita mencintai Sifat-sifat Allah, dan Sifat Allah dalam penciptaan adalah ekspansif. Tak seorang pun di antara kita ingin rugi; kita hanya ingin berhasil, dan makna keberhasilan zaman sekarang adalah ekspansi. Namun, kadang-kadang keberhasilan terletak pada penyusutan. Ketika bentuk lahiriah manusia menyusut, aspek batinnya kemungkinan meluas. Kehidupan dan realitas manusia berlanjut sehingga ia tidak memperhatikan kematian pribadinya sendiri. Karena yang hakiki hidup selamanya, maka, mengapa ia harus takut? Yang ia butuhkan hanyalah sikap yang lurus.
Ayat ini berkenaan dengan jatuhnya bintang-bintang. Bintang-bintang disatukan oleh kekuatan sentrifugal, elektromagnetis, dan gravitasi, dan mereka membentuk satu entitas sempurna yang berada dalam keadaan ekspansif. Bila kekuatan ekspansif ini diintervensi—disebabkan oleh munculnya suatu fase tertentu dalam proses jalannya penciptaan secara keseluruhan—maka mereka akan jatuh. Setiap yang diciptakan mesti berakhir pada waktunya, apa pun itu. Surah ini memberikan suatu gambaran tentang bagaimana babak akhir ini akan terjadi pada skala kosmik, mulai dengan yang paling ekspansif dan menyeluruh kemudian menyusut ke skala individu.
Kita juga dapat melihat makna dari dua ayat ini dari sudut pandang mikrokosmik. Sejauh mengenai individu, maka matahari adalah rohnya, dan najm (bintang) adalah nafs (diri)-nya. Ketika matahari, atau roh, berhenti memberikan makanan kepada nafs, yakni bintang, maka bintang kemudian menyusut atau melipat dirinya. Nafs akan menyerah karena pada saat itu ia akan dipadamkan, ditutupi dan dilenyapkan.
وَ إِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ
Suyyirat adalah kata kerja pasif sayyara, yang berarti ‘menggerakkan, menghidupkan, mengedarkan’. Sayyārah artinya ‘kendaraan’. Ketika gunung-gunung mulai bergerak, mereka tidak akan bergerak dengan satu sentakan, tapi bergerak dalam gerakan yang terus-menerus. Bagaimana mungkin gunung bergerak dengan cara ini, kalau proses pembentukkan dan peluncuran bumi tidak berhenti? Karena kita sedang mengitari angkasa dengan kecepatan ribuan mil per jam, ketika saat akhirnya tiba dan bumi tercengkam lalu berhenti mendadak, gunung-gunung pun, niscaya, akan tercerabut dari tempatnya dan hancur. Untuk merasakan proses ini coba saja kita berhenti mendadak dalam kendaraan yang sedang bergerak. Pencabutan ini merupakan satu aspek dari babak akhir drama kecil kita di atas planet yang mungil ini.
وَ إِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
Gunung-gunung yang terlepas dan binatang-binatang yang dibiarkan tidak terpelihara adalah kejadian yang luar biasa. Semua kesan ini melukiskan suatu keadaan berlawanan yang menyatu seketika itu juga. ‘Isyār adalah seekor unta yang hamil sepuluh bulan. Bagi bangsa ‘Arab gurun pasir pada waktu itu, unta melambangkan harta yang paling diinginkan. Jika unta-unta tak dipelihara, itu berarti bahwa irama yang nonnal dari berbagai peristiwa yang biasanya menyatukan kehidupan padang pasir tidak lagi berjalan. Akar kata ‘uththilat artinya ‘mengabaikan, meninggalkan tanpa peduli, memutuskan, menghentikan’. ‘Uthlah berarti ‘liburan atau tidak bekerja’, yakni, istirahat dari rutinitas normal seseorang. Ketika proses-proses penciptaan yang alamiah terganggu, maka akan terjadi kemacetan total dalam proses kehidupan. Ketika dunia sampai pada akhirnya, maka tidak ada orang waras yang akan merawat unta!
وَ إِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ
Semua margasatwa akan berkerumun saling mendekat. Ḥasyara artinya ‘berkerumun, berhimpun, berkumpul’. Lagi-lagi ini mencerminkan sifat dasar penciptaan. Segala sesuatu pada dasarnya bersifat ekspansif. Meskipun semua margasatwa cenderung bergerak bersama-sama dalam beberapa kawanan atau kelompok, namun binatang-binatang tidak berkumpul terlalu rapat; mereka mempertahankan individualitasnya, mempertahankan jaraknya masing-masing. Pada hari ketika semua sistem kehidupan sampai pada ujungnya, mereka akan bergerak dengan cara yang berlawanan dengan sifat dasarnya. Rasa takut menyebabkan mereka tidak berpencar tapi berkumpul bersama, karena tidak akan ada tempat bagi mereka untuk melarikan diri mencari keselamatan.
وَ إِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ
Sajjara, akar dari sujjirat, berarti ‘bergelombang, meluap’, dan bentuk pertamanya, sajara, berarti ‘menyalakan, membakar, mendidihkan’. Seringkali bila sesuatu berakhir, secara sepintas kita melihat seperti apa permulaannya. Dengan kata lain, ayat ini mungkin berarti bahwa api akan benar-benar keluar dari tanah pada akhir penciptaan persis seperti ketika bumi pertama kali diciptakan. Ketika itu bumi mulai sebagai sebuah bola api yang kemudian mendingin begitu proses penciptaan dibentangkan.
Kiasan ‘lautan memanas’ mungkin menunjuk kepada gunung-gunung berapi yang meletus dari lautan, atau bahkan kepada neraka yang membara di lautan akibat tumpahan minyak yang terbakar besar-besaran. Apa pun makna persisnya, perujukkan kepada lautan yang bernyala menunjukkan bahwa hal yang biasa digantikan oleh hal yang luar biasa.
Air melambangkan kesejukan dan ketenangan, tapi di sini kita diberitahukan bahwa akan tiba suatu saat di mana bagian bumi yang berair akan mendidih. Hal-hal yang kita anggap semestinya berbeda dan terpisah dihubungkan dengan kebalikan-kebalikannya. Semua kejadian ini merupakan peristiwa yang berlangsung pada saat proses kehidupan yang terus berkembang berhenti.
وَ إِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ
Nafs di sini artinya roh. Zuwwijat (bersatu) berasal dari akar kata zawwaja, yang artinya ‘berpasangan, bergandengan, bersatu’. Ayat ini bisa berarti bahwa roh akan dipersatukan dengan roh pasangan atau kawannya ketika di dunia atau dengan roh yang dikenalnya, atau bahwa roh itu akan dipasangkan dengan masa lalu duniawinya. Di alam kosmos, perpasangan terjadi secara konstan di mana hal-hal yang berlawanan bertemu. Manusia terdiri dari dua aspek: aspek jasmaniah yang merupakan bagian dari apa yang dinamakan ‘aku’ dan aspek yang tak dapat dilihat yang disebut rohaniah. Kita bisa membayangkan eksistensi roh dengan bertanya, ‘Di mana aku berada saat tertidur lelap? Di mana aku berada ketika mimpi?’ Kita mengatakan, ‘Aku bermimpi mendaki lereng gunung yang curam,’ tapi kenyataannya tubuh kita tidak bergerak. Dengan kata lain, roh adalah aspek lain dari manusia yang memiliki pengalamannya sendiri. Memahami penyatuan dari dua hal yang berlawanan ini—jasmani dan rohani—adalah satu cara untuk memahami makna ayat ini.
Cara lain untuk memahaminya adalah bahwa kita tidak berada dalam keadaan penyatuan karena bermacam-macam keadaan yang muncul dari nafs kita. Berbagai harapan, keinginan dan kebutuhan kita harus dipenuhi jika kita ingin ternetralisir dan mengalami penyatuan. Itulah sebabnya kebanyakan kita dapat direhabilitasi melalui penyatuan ‘perkawinan’. Perkawinan merupakan sarana pemenuhan, terutama bila kedua belah pihak saling respek, dan menyadari bahwa manusia datang ke dunia ini sendirian dan akan pergi dari dunia sendirian pula. Jika mereka saling membantu untuk mencapai pemenuhan diri selama persinggahan di dunia ini, mereka akan mencapai sesuatu.
Dengan demikian, ada dua cara yang mungkin untuk memahami ayat ini. Ketika nafs seseorang hancur, ia menyatu dengan lawannya. Segala sesuatu dalam kehidupan berada pada tingkat dualitas; ada baik dan ada juga buruk. Segala sesuatu yang dapat dibayangkan, disentuh, dirasakan atau sedikit banyaknya diamati, muncul dengan salah satu dari dualitas itu. Namun kita semua sedang mencari Yang Satu, karena kita takkan pemah dapat terpuaskan oleh dualitas.
Implikasi dari ayat ini adalah bahwa dualitas akan berakhir. Dalam kehidupan ini, dualitas akan berakhir bila manusia mencapai kebebasan diri yang sempurna, dan bila sudah tidak ada yang dapat memenuhinya karena ia sudah terpenuhi. Hal ini juga akan terjadi ketika manusia memahami sifat realitas yang sejati pada saat mati. Dalam realitasnya yang ada hanyalah Tuhan, yang ada sebelumnya hanyalah Tuhan, dan yang akan ada hanyalah Tuhan. Pengetahuan ini datang melalui batin—realisasi pengalaman—dan tidak perlu dipelajari.
Jika seseorang ingin mencapai esensi al-Qur’an, maka yang dapat ia lakukan hanyalah persiapan untuk menanggalkan segala sesuatu—dan itu berarti mati. Ia harus berada dalam keadaan fana. Ia harus mendekatinya dengan hati yang bersih, tanpa ada asumsi atau prasangka apa pun. Jika tidak, ia tetap terperangkap dalam penderitaan dualitas dan dunia kearifan yang, paling banter, hanya bersifat lahiriah dan eksistensial belaka. Sebaliknya, ia hanya akan berinteraksi dengan kulitnya—ajaran lahiriah— ketimbang berubah dengan mendengarkan kebenaran. Pencari yang tulus akan mendengar al-Qur’an seakan langsung dari bibir Nabi. Pencari yang tersadarkan mendengar al-Qur’an seakan digemakan dari luar waktu oleh Allah.
Ketika seseorang memahami al-Qur’an, berarti ia menemukan keluasannya. Namun, esensi manusia itu sendiri adalah luas. Pemahaman tergantung pada seberapa kuat dan lurusnya hati seseorang. Al-Qur’an mengatakan, “Bacalah apa yang mudah dari al-Qur’an“ (Q.S.73:20). Membaca apa? Apa maksudnya? Kita membaca apa yang sudah ditulis, apa yang ditulis pada kita. Pernyataan ini dibuat untuk mempertajam pandangan kita, untuk membuka apa yang sudah ada dalam diri kita.
Dalam ayat ini kita membaca, ‘Dan tatkala roh-roh dipertemukan’, artinya pada saat kita dipertemukan Dengan lawan kita atau pada saat kita dinetralisir. Sekarang ini hasrat kita tidak pernah terpuaskan. Kita selalu mengidamkan sesuatu, terus beralih dari satu aspek dualitas ke aspek dualitas lainnya dengan mengubah keadaan luar kita. Namun, kecenderungan ini akhirnya tidak akan berguna sebab yang mesti berubah adalah diri kita sendiri.
Kita hidup dalam dualitas, karena itu kita berusaha menetralisir. Bagaimana kita menetralisir? Kita menetralisir nafs kita dalam keheningan, secara sungguh-sungguh dan positif. Dalam keheningan itu kita memiliki pengetahuan langsung tentang makna Ḥajar Aswad (Batu Hitam) yang terpasang di sudut Ka‘bah di Mekkah.
Tidak banyak kaum muslim yang mengetahui makna Ḥajar Aswad, meskipun mereka melakukan thawaf (lari-lari kecil mengitari Ka‘bah) dan menciumnya pada waktu ibadah haji setiap tahun. Hitam mengandung semua warna—ia melambangkan kematian, dari mana muncul kehidupan. Kehidupan tidak dapat dipahami kecuali jika kita siap mati. Makna jihād (secara harfiah, upaya keras, dan perang membela diri melawan kaum kafir) tidak hanya tentang darah dan kematian fisik; ia adalah kesiapan untuk mempertahankan kehidupan tanpa kenal takut, kehidupan rohani. Nabi tidak menginginkan perang dan kematian yang diakibatkannya. Beliau menggunakan nalar untuk menghindarinya. Ia tak gentar untuk bersikap rasional, karena ia menggunakan akalnya dan telah menyimpang dari warisan politeisme sukunya.
Ḥasan ibn ‘Alī menggunakan nalar ketika ia melepaskan khilāfah. Imām Ḥasan memiliki ribuan prajurit tapi ia tahu bahwa mereka tak mungkin mampu bertahan dan gigih. Oleh karena itu ia beranggapan tidaklah bijaksana menggiring mereka ke dalam peperangan sementara mereka tidak akan mampu bertahan, karena mereka tidak memiliki keyakinain yang dalam.
Kejahilan terjadi bila kita tidak mensyukuri penciptaan. Kejahilan ada dalam substansi manusia, karena segala sesuatu mengandung kebalikannya. Bagian dari manusia yang ingin hidup juga mengandung kehancurannya yang terakhir. Kita semua akan mati dan akan melihat indahnya kesempurnaan dalam kenyataan ini. Meskipun kita mungkin masih menggemakan rasa cinta terhadap al-Bāqī (Yang Abadi), namun kesempurnaan kehidupan dan kematian manusia terletak dalam pengetahuan bahwa hidup dan mati hanyalah suatu siklus yang melahirkan kesadaran.
Kita akan mengetahui siapa kita sebenarnya kala kita sampai pada keadaan penyatuan yang sejati. Kita memahami mengapa kita semua—dalam realitasnya—mencari tauḥīd. Pengalaman pertama kita adalah pengalaman keterpisahan, dengan jalan mana kita dapat mengatakan bahwa esensi adalah satu. Yang ada hanyalah Keesaan, hanya Allah, tapi untuk mencapai realisasi ini kita harus berjalan melalui beberapa tahap. Tahap pertama kita meyakini keesaan. Tahap selanjutnya kita mampu mengatakan ‘Aku mulai mengerti!’ Namun, sepanjang ada ‘Aku’ kita berada dalam syirik (menyekutukan Allah dengan selain Allah). Ketika si ‘Aku’ tumbang, maka yang kita lihat hanyalah Allah, hanyalah Sifat-sifatNya, dan itulah kedamaian terakhir yang melahirkan perbuatan. Kedamaian ini bersifat dinamis, tidak statis atau mati, juga tidak ada sandiwara dan penderitaan di dalamnya. Orang luar bisa saja melihat penderitaan, tapi sang muwaḥḥid (pemersatu) tidak melihat penderitaan; yang dilihatnya tak lain hanyalah cinta. Pada saat itu segala sesuatu akan dapat dimengerti dan dilihat sebagai kesempurnaan. Gambaran eksistensi duniawi mungkin tidak diinginkan bila manusia sudah memahaminya, tapi itulah kesempurnaan. Mungkin saja kita tidak ingin minum obat yang pahit rasanya, tapi kesempurnaannya terletak dalam kemanjuran obat tersebut dalam mengembalikan kita ke keadaan sehat. Namun, tahap ini sangat halus dan hanya akan diungkapkan kepada teman yang paling intim.
Dengan demikian, makna dari ayat ini adalah bahwa esensi manusia adalah satu, dan hanya ada satu esensi. Ia mulai dengan syirik, dengan mengatakan, ‘Esensiku adalah satu’, dan kemudian ‘Yang ada hanya esensi, tak ada yang lain di samping Allah.’