Surah al-Muzzammil 73 ~ Tafsir al-Mishbah (2/5)
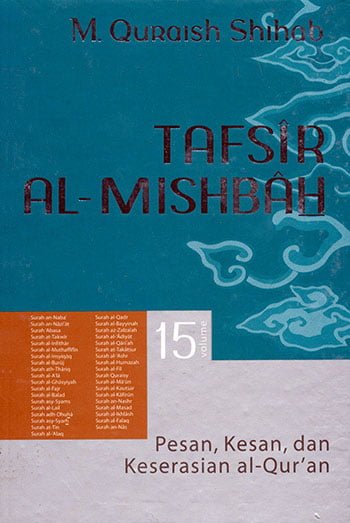
Tafsir al-Mishbāḥ
(Jilid ke-15, Juz ‘Amma)
Oleh: M. Quraish Shihab
Penerbit: Penerbit Lentera Hati
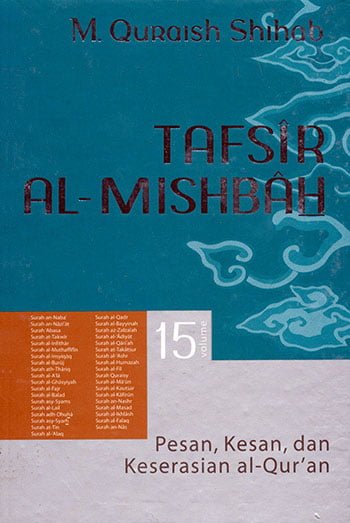
Tafsir al-Mishbāḥ
(Jilid ke-15, Juz ‘Amma)
Oleh: M. Quraish Shihab
Penerbit: Penerbit Lentera Hati
AYAT 6-7
“Sesungguhnya bangun di waktu malam, dia lebih berat dan bacaan di waktu itu, lebih berkesan. Sesungguhnya bagimu di siang hari kesibukan yang panjang.”
Kedua ayat di atas menjelaskan mengapa Allah memerintahkan Nabi-Nya bangkit malam hari sebagaimana diperintah oleh ayat yang lalu. Allah berfirman: Sesungguhnya bangun di waktu malam, dia secara khusus lebih berat, yakni berat kesulitannya, atau lebih mantap persesuaiannya dengan qalbu sehingga dapat melahirkan kekhusyu‘an yang lebih besar dibandingkan dengan di siang hari dan bacaan di waktu itu, lebih berkesan serta lebih mudah untuk dipahami dan dihayati. Sebaliknya, Sesungguhnya bagimu di siang hari kesibukan yang panjang, yakni banyak. Karena itu, bagunlah di malam hari agar pekerjaanmu di siang hari yang banyak itu dapat sukses dengan bantuan Allah.
Kata (نَاشِئَةَ) nāsyi’ah terambil dari kata (نَشَأَ) nasya’a yang antara lain berarti bermula, terjadi, datang sedikit demi sedikit serta bangkit.
Dalam al-Qur’ān, kata itu hanya sekali ini saja ditemukan. Ulama-ulama berbeda pendapat tentang maksudnya. Ada yang berpendapat bahwa ia adalah “waktu atau saat yang terjadi sedikit demi sedikit” sehingga diartikan sebagai “waktu-waktu sepanjang malam”. Ada juga yang memahaminya sebagai “kejadian-kejadian di waktu malam”. Betapapun, terdapat perbedaan tentang arti kata ini, namun mereka sepakat memahami ayat enam sebagai berbicara tentang Shalāt-ul-Lail. Perbedaan pendapat – setelah persepakatan tersebut – muncul lagi ketika mereka membicarakan “kapan Shalāt-ul-Lail dapat dilaksanakan?”
Sahabat Nabi s.a.w., Ibn ‘Umar dan Anas Ibn Mālik, memahami pelaksanaannya dimulai antara shalat Maghrib dan ‘Isyā’ karena, menurut mereka, kata nāsyi’ah berarti bermula atau permulaan sedang permulaan malam adalah Maghrib.
Menurut al-Qurthubī, Sayyidinā ‘Alī Ibn al-Ḥusain (cicit Nabi Muḥammad s.a.w.) melaksanakan shalat antara Maghrib dan ‘Isyā’ kemudian menjelaskan bahwa: “Inilah Nāsyi’at-ul-Lail”. Istri Rasūlullāh s.a.w., ‘Ā’isyah r.a., dalam salat satu riwayat dari Ibn ‘Abbās menyatakan bahwa: (نَاشِئَةَ اللَّيْلِ) nāsyi’at-ul-lail adalah “bangkit di waktu malam setelah tidur”. Kata beliau: “siapa yang bangkit untuk shalat sebelum tidur, maka ia belum melaksanakan kandungan ayat ini”.
Paling tidak, kita dapat berkata bahwa tidaklah keliru mereka yang melaksanakan Shalāt-ul-Lail sebelum tidur. Al-Marāghī dalam tafsirnya mengutip ucapan Ibn ‘Abbās: “Siapa yang shalat dua rakaat atau lebih setelah ‘Isyā’, maka ia telah dinilai berada di waktu malam dalam keadaan sujud dan berdiri di hadapan Allah.”
Namun demikian, tentunya shalat setelah tidur atau pada saat malam telah heningnya dan manusia pada umumnya tidur nyenyak adalah lebih baik karena suasana semacam itulah yang mengantarkan kepada kemantapan dan kekhusyu‘an serta kejernihan pikiran.
Pada masa Rasūl s.a.w. dan sahabat-sahabat beliau, saat-saat Maghrib dan ‘Isyā’ adalah saat-saat hening, sebagian besar anggota masyarakat telah berada di rumah bahkan mungkin telah beristirahat atau tidur, sama halnya dengan keadaan di kampung dan desa-desa khususnya yang belum dijangkau oleh penerangan listrik. Wajar sekali bila saat-saat itu telah dianggap oleh sementara sahabat sebagai saat di mana Shalāt-ul-Lail dapat dilakukan karena keheningan telah dirasakan.
Kata (وَطْئًا) wath’an hanya ditemukan sekali dalam al-Qur’ān. Bila ia dianggap terambil dari kata (وَاطَأَ) wātha’a, artinya adalah sesuai. Dan, jika dinilai terambil dari kata (وَطِئَ) wathi’a, maknanya adalah berat. Pendapat pertama menjadikan ayat di atas berarti “waktu-waktu shalat malam adalah waktu yang lebih sesuai”. Persesuian yang dimaksud adalah pada bacaan, pandangan, dan penglihatan pelakunya dengan hatinya sendiri, yang pada akhirnya menimbulkan rasa khusyu‘ kepada Allah s.w.t. Kekhusyu‘an ini ditimbulkan oleh keheningan malam yang disaksikan dan dirasakan sehingga penghayatan makna shalat atau bacaan lebih berkesan. Pikiran dan perhatian ketika itu tertuju sepenuhnya kepada Allah s.w.t. dan suasana sekeliling menciptakan rasa keterbatasan dan kelemahan manusia sehingga mengantarnya menuju satu totalitas mutlak, yakni Allah s.w.t., sedang pendapat kedua mengartikannya sebagai: “Shalat malam pelaksanaannya lebih berat.”
Hemat penulis, ayat ini tidak bermaksud menjelaskan sisi beratnya shalat tersebut. Karena, jika demikian, ayat ini seakan-akan ingin menyatakan bahwa shalat malam diperintahkan karena ia berat. Penggalan ayat ini bermaksud menjelaskan mengapa shalat di waktu malam diperintahkan sebabnya sebagaimana disebutkan di atas, sesungguhnya waktu malam adalah waktu yang lebih tepat dan sesuai untuk mendapatkan rasa kekhusyu‘an. Karena itu, pendapat pertamalah yang lebih tepat walaupun harus diakui bahwa memang ia berat dibandingkan dengan shalat di siang hari.
Kata (سَبْحًا) sabḥan pada mulanya berarti pergi menjauh. Perenang dinamai (سَبَّاح) sabbāḥ karena dengan berenang ia pergi menjauh. Mensucikan Allah dalam arti menjauhkan segala sifat serta perbuatan buruk sehingga tidak dinisbahkan kepada-Nya sesuatu keburukan bahkan kesempurnaan yang tidak penuh dan wajar bagi-Nya dinamai (تَسْبِيْح) tasbīḥ. Usaha mencari nafkah dengan susah-payah yang puncaknya adalah bepergian ke tempat jauh dari daerah asal, atau tidur, atau keluangan waktu semuanya dilukiskan dengan kata (سبح) sabḥun. Dengan tidur, seseorang seakan-akan pergi menjauh. Demikian pula dengan keluangan waktu, ia menjauh dari kesibukan. Dari makna-makna di atas, terlihat antara lain bahwa kata “sabḥan dapat mengandung dua arti yang bertolak-belakang, yaitu keluangan waktu dan kesibukan (ketiadaan waktu).”
Atas dasar perbedaan makna yang dimungkinkan oleh penggunaan bahasa tersebut, ulama-ulama tafsir berbeda paham tentang maksud firman Allah dalam ayat ke 7 ini. Ada yang berpendapat bahwa ayat ini menjelaskan bahwa pada siang hari Rasul s.a.w. mempunyai kesibukan untuk mencari nafkah sehingga waktu untuk memusatkan seluruh pikiran dan perhatian kepada Allah tidak banyak tersisa lagi. Ada juga ulama yang memahami ayat ini sebagai menyatakan bahwa: “Di siang hari engkau mempunyai cukup waktu luang sehingga, jika ada yang tidak dapat engkau laksanakan di malam hari, pada siang harinya hal tersebut dapat engkau laksanakan.”
AYAT 8-9
“Ingatlah nama Tuhanmu dan beribadatlah kepada-Nya dengan penuh. Tuhan Timur dan Barat, Tiada tuhan selian Dia, maka jadikanlah Dia wakil.”
Ayat yang lalu memerintahkan Nabi s.a.w. untuk mendekatkan diri kepada Allah di waktu malam karena malam adalah waktu yang tepat dan lebih sesuai untuk maksud tersebut karena keheningannya. Sedang, siang adalah waktu kesibukan. Namun, itu bukan berarti bahwa di siang hari boleh melupakan Allah. Tidak! Ayat di atas memerintahkan bahwa Ingatlah dan sebutlah selalu nama Tuhanmu dan beribadahlah kepada-Nya secara penuh ketekunan. Itu disebabkan Allah adalah Tuhan Pemilik, Pemelihara, dan Pengelola arah Timur dan Barat, yakni alam semesta, Tiada tuhan yang mengendalikan alam raya dan berhak disembah selain Dia, maka jadikanlah Dia wakil, yakni serahkan segala urusanmu kepadanya setelah berusaha semaksimal mungkin.
Kata (تَبَتّل) tabattul, demikian juga kata (تَبْتِيْلًا) tabtīlan, terambil dari kata (بتل) batala yang berarti memotong/memutus. Seseorang yang memusatkan perhatian serta usahanya kepada sesuatu berarti memutuskan hubungannya dengan segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan pusat perhatiannya itu. Orang yang demikian itu dinamai (بَتُوْل) batūl. Ayat ini berpesan agar setiap orang hendaknya selalu menghubungkan diri dengan Allah walaupun dalam aktivitas duniawi. Memang ia sama sekali tidak berarti bahwa yang bersangkutan meninggalkan segala aktivitas keduniaan. Karena, aktivitas apa pun dapat dilaksanakan selama dikaitkan dengan usaha memperoleh keridhaan Allah s.w.t.
Dari segi bahasa, kata (رَبّ) rabb mempunyai banyak arti, antara lain pendidik dan pemelihara. Anak tiri yang berada dalam pemeliharaan dan didikan seorang suami dinamai (رَبِيْب) rabīb. Kata ini juga berarti pemilik.
Arti-arti di atas dan arti-arti lainnya yang belum disinggung di sini pada akhirnya bermuara kepada suatu makna, yaitu: Rabb adalah yang memiliki atau diserahi segala urusan berkenaan dengan seseorang atau sesuatu lainnya yang memerlukan perbaikan, pengelolaan, pengembangan, dan sebagainya. Allah adalah “Rabb Timur dan Barat”, dalam arti bahwa “Dia adalah Pemilik, Penguasa, Pengelola yang menangani segala persoalan Timur dan Barat yakni keseluruhan jagat raya. Dalam kedudukan-Nya sebagai Rabb, Dia mencipta, menyempurnakan ciptaan, memberi rezeki, kesehatan, pertolongan, rahmat, dan kasih-sayang dalam segala bentuknya sehingga pada akhirnya tercakup dalam pengertian Rubūbiyyah-Nya segala sesuatu yang dapat menyentuh makhluk-makhlukNya. Tidak ada tuhan yang mengendalikan alam raya serta berhak disembah kecuali Dia.
Kata (وَكِيْلًا) wakīlan terambil dari kata (وَكَلَ – يَكِلُ) wakala-yakilu yang berarti mewakilkan. Apabila seseorang mewakilkan pihak lain, ia telah menjadikannya sebagai dirinya sendiri dalam persoalan tersebut sehingga yang diwakilkan (wakil) melaksanakan apa yang dikehendaki oleh yang menyerahkan kepadanya perwakilan.
Namun, harus diingat bahwa Allah s.w.t. yang kepada-Nya diwakilkan segala persoalan adalah Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, dan segala Maha yang mengandung makna pujian. Manusia sebaliknya memiliki keterbatasan dalam segala hal. Kalau demikian, makna “mewakilkan-Nya” berbeda dengan perwakilan manusia.
Memang, wakil diharapkan serta dituntut untuk dapat memenuhi kehendak dan harapan orang yang mewakilkan kepadanya. Namun, karena dalam perwakilan manusia “sering kali” atau paling tidak “boleh jadi” yang mewakilkan lebih tinggi kedudukan dan atau pengetahuannya dari sang wakil, ia dapat saja tidak menyetujui atau membatalkan tindakan sang wakil atau menarik kembali perwakilannya bila ia merasa berdasarkan pengetahuan dan keinginannya bahwa tindakan tersebut merugikan. Ini bentuk perwakilan manusia. Tetapi, jika seseorang menjadikan Allah sebagai wakīl, hal serupa tidak akan terjadi karena sejak semula seseorang telah menyadari keterbatasannya dan menyadari pula kemahamutlakan Allah s.w.t. Apakah ia tahu atau tidak hikmah satu perbuatan Tuhan, ia akan menerimanya dengan sepunuh hati.
Ini salah satu segi perbedaan antara perwakilan manusia terhadap Tuhan dengan terhadap selain-Nya. Perbedaan yang kedua adalah dalam keterlibatan yang mewakilkan.
Jika anda mewakilkan orang lain untuk melaksanakan sesuatu. Anda telah menugaskannya melaksanakan hal tersebut. Anda tidak perlu lagi melibatkan diri. Dalam hal menjadikan Allah s.w.t. sebagai Wakīl, manusia dituntut untuk melakukan sesuatu yang berada dalam batas kemampuannya. Kata tawakkal, yang juga berakar kata sama dengan wakil, bukannya berarti penyerahan secara mutlak kepada Allah, tetapi penyerahan tersebut harus didahului dengan usaha manusiawi “Tambatlah terlebih dahulu (untamu) kemudian setelah itu bertawakkallah.” Demikian sabda Nabi s.a.w.
AYAT 10
“Dan bersabarlah atas apa yang mereka ucapkan dan tinggalkanlah mereka dengan cara meninggalkan yang indah”
Setelah ayat yang lalu berpesan agar menjadikan Allah sebagai Wakīl, yakni berserah diri kepada-Nya sambil berusaha semaksimal mungkin, tentu saja dalam usaha tersebut diperlukan kesungguhan dan kesabaran apalagi dalam menyampaikan kebenaran. Yang berdakwah sering kali dicemoohkan bahkan disakiti. Untuk itu, Allah berpesan lagi bahwa: Dan, di samping berserah diri dan berusaha, bersabarlah juga atas apa, yakni segala kebatilan dan kebohongan, yang mereka, yakni kaum musyrikin, selalu lakukan dan ucapkan dan tinggalkanlah mereka dengan cara meninggalkan yang indah sehingga mereka tidak merasa bahwa engkau memusuhi mereka dan dalam saat yang sama engkau tidak mengorbankan tugas-tugasmu dan prinsip-prinsip ajaran Ilahi.
Sabar adalah “menekan gejolak hati demi mencapai sesuatu yang baik atau lebih baik”. Dalam konteks ayat di atas, mungkin terlintas di hati Nabi keinginan untuk mengundurkan diri dari gelanggang dakwah sehingga membiarkan mereka yang berada dalam kesesatan itu bergelimang di dalamnya. Mungkin Nabi berkata dalam hatinya: “kalau memang mereka memakiku, mengapa aku harus bersusah-payah?” Mungkin Nabi s.a.w. akan bersikap sebagaimana sikap Nabi Yūnus yang “lari” pergi meninggalkan kewajiban dakwah (baca QS. ash-Shāffāt [37]: 140). Nah, di sini gejolak hati yang demikian itulah yang dituntut oleh ayat ini untuk ditekan, tidak diperturutkan, dan yang digambarkan dengan perintah “bersabarlah”.
Petunjuk awal yang diterima Nabi dalam surah al-Muzzammil ini mengandung pengajaran, yaitu “risiko penganjur kebenaran paling sedikit adalah mendengar cemoohan, makian serta kritik”. Jika seseorang bermaksud menjadi “muballigh”, terlebih dahulu ia harus menyiapkan mentalnya agar ia tidak berhenti di jalan atau mundur karena mendengar cemoohan dan kritik.
Kata (اُهْجُرْ) uhjur adalah bentuk perintah dari kata (هجر) hajara yang berarti meninggalkan sesuatu karena dorongan ketidaksenangan kepadanya, Nabi berhijrah dari Makkah ke Madinah dalam arti meninggalkan kota Makkah karena tidak senang dengan perlakuan penduduknya. Perintah ayat ini disertai dengan kalimat (هَجْرًا جَمِيْلًا) hajran jamīlan/cara meninggalkan yang indah. Ini berarti bahwa Nabi Muḥammad s.a.w. dituntut untuk tidak memperhatikan gangguan mereka sambil melanjutkan dakwah sekaligus mereka dengan lemah-lembut, dan penuh sopan santun tanpa harus melayani cacian dengan cacian serupa.