Surah al-Muzzammil 73 ~ Tafsir al-Mishbah (1/5)
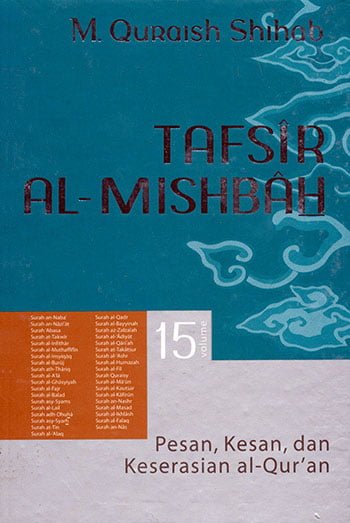
Tafsir al-Mishbāḥ
(Jilid ke-15, Juz ‘Amma)
Oleh: M. Quraish Shihab
Penerbit: Penerbit Lentera Hati
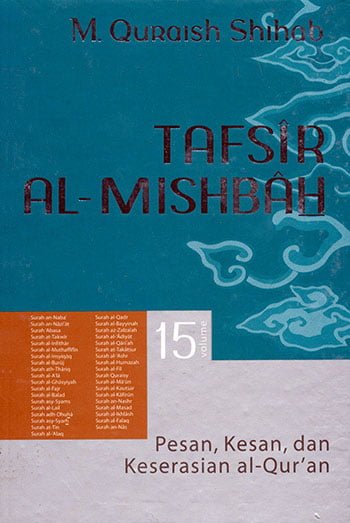
Tafsir al-Mishbāḥ
(Jilid ke-15, Juz ‘Amma)
Oleh: M. Quraish Shihab
Penerbit: Penerbit Lentera Hati
Surah ini terdiri dari 20 ayat.
Surah ini dinamakan AL-MUZZAMMIL,
yang berarti “Orang yang Berselimut”,
diambil dari ayat pertama.
Surah al-Muzzammil – kecuali ayat akhirnya – merupakan salah satu surah yang diturunkan sebelum Nabi Muḥammad s.a.w. berhijrah ke Madīnah. Demikianlah kesepakatan ulama. Ada juga yang berpendapat bahwa akhir ayat surah ini pun turun di Makkah setahun setelah turunnya awal surah. Akan tetapi, pendapat ini mengandung kemusykilan karena pada ayat terakhir itu disebutkan tentang adanya kaum muslimin yang berperang, padahal peperangan baru terjadi pada tahun kedua dari hijrah Nabi s.a.w. ke Madīnah. Jika kita berkata bahwa surah ini Makkiyyah, itu tidaklah mutlak berarti bahwa surah ini atau bagian awal dari ayat-ayatnya merupakan wahyu ketiga yang diterima Nabi s.a.w. setelah awal surah Iqra’ dan surah al-Qalam. Memang, banyak ulama berpendapat demikian, berdasarkan beberapa riwayat yang menjelaskan sebab turunnya. Antara lain bahwa, suatu ketika Nabi Muḥammad s.a.w. sedang berjalan, tiba-tiba beliau mendengar suara dari atas, dan ketika beliau mengarahkan pandangan ke langit, beliau melihat malaikat yang datang kepadanya di Gua Ḥirā’. Rasa takut yang mencekam melihat malaikat atau mengingat peristiwa di Gua Ḥirā’ di mana beliau ketika itu dipeluk sedemikian kerasnya oleh malaikat sehingga terasa bagaikan nyawanya telah akan putus, menyebabkan beliau tergesa-gesa kembali dan meminta untuk diselimuti. Ketika itu, turunlah awal surah ini, atau dalam riwayat yang lain awal surah al-Muddatstsir.
Pendapat yang menyatakan bahwa awal surah ini termasuk wahyu-wahyu pertama yang diterima Nabi Muḥammad s.a.w., bukanlah hal yang sulit untuk dibuktikan, melihat kandungannya yang sejalan dengan kandungan wahyu-wahyu pertama yang semuanya merupakan bimbingan dan petunjuk praktis demi suksesnya misi dakwah. Tetapi, menyatakan bahwa ia merupakan wahyu ketiga atau keempat tidaklah mudah untuk membuktikannya, bahkan mungkin justru sebaliknya. Apalagi dengan adanya riwayat lain yang mengisyaratkan bahwa ayat-ayat pertama surah ini justru turun menanggapi sikap Nabi dan kaum musyrikin setelah turunnya sekian banyak ayat al-Qur’ān. Sahabat Nabi s.a.w., Jābir ibn ‘Abdillāh r.a., menceritakan bahwa tokoh-tokoh kaum musyrikin berkumpul di balai pertemuan “Dār-un-Nadwah” membahas keadaan Nabi apakah beliau seorang tukang tenung atau penyihir atau gila, dan ketika Nabi mendengar kesimpulan mereka, beliau sangat sedih sehingga menyendiri dan berselimut.
Dari riwayat di atas, dapat dipahami bahwa pembicaraan tokoh-tokoh kaum musyrikin tersebut tentunya setelah sekian banyak ayat al-Qur’ān yang turun dan, dengan demikian, sulit untuk diterima pendapat yang menyatakan bahwa wahyu ini adalah wahyu ke-3 atau ke-4.
Surah ini dikenal dengan nama Surah al-Muzzammil. Ini adalah satu-satunya namanya. Tema utama surah ini adalah bimbingan kepada Nabi agar mempersiapkan mental untuk menerima tugas penyampaian risalah serta rintangan-rintangannya, sekaligus ancaman kepada para pengingkar kebenaran. Tujuan utamanya, menurut al-Biqā‘ī, adalah informasi bahwa amal-amal kebajikan menampik rasa takut dan menolak marabahaya. Ia meringankan beban, khususnya bila amal kebajikan berupa kehadiran kepada Allah serta berkonsentrasi mengabdi kepada-Nya pada kegelapan malam. Namanya al-Muzzammil (Yang berselimut) menunjukkan tema dan tujuan pokok itu.
Jumlah ayat-ayatnya menurut cara perhitungan ulama Madīnah delapan belas ayat, menurut ulama Bashrah sembilan belas, dan selain mereka dua puluh ayat.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
KELOMPOK 1
AYAT 1-10.
يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ. قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيْلًا. نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا. أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيْلًا. إِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا. إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْءًا وَ أَقْوَمُ قِيْلًا. إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا. وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيْلًا. رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا. وَ اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُوْلُوْنَ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا.
AYAT 1-4
“Hai yang berselimut. Bangkitlah di malam hari, kecuali sedikit, seperduanya atau kurangilah dari itu sedikit, atau lebihkan atasnya. Dan bacalah al-Qur’ān dengan perlahan-lahan.”
Pada awal surah al-Jinn – surah yang lalu – demikian pula pada akhir surahnya dikemukakan keagungan al-Qur’ān, antara lain dengan sambutan jin terhadapnya dan juga pemeliharaan Allah atas wahyu yang dicampakkan-Nya kepada para rasul sehingga tidak dapat disentuh oleh siapa pun. Dalam konteks penyampaian wahyu itu dan pemeliharaannya, di sini Nabi s.a.w. diperintahkan untuk mempersiapkan diri menghadapi turunnya wahyu yang berat. Di sini, Allah berfirman: Hai, Nabi Muḥammad, yang berselimut. Kurangilah tidurmu dan bangkitlah secara sempurna untuk shalat dan bermunajat kepada Allah di malam hari, kecuali sedikit dari waktu malam untuk engkau gunakan tidur, yaitu seperduanya malam atau kurangilah dari seperdua itu sedikit hingga mencapai sepertiganya atau lebihkan atasnya, yakni dari seperdua itu, hingga mencapai dua pertiga malam. Dan bacalah al-Qur’ān dengan perlahan-lahan dengan bacaan yang baik dan benar.
Kata (الْمُزَّمِّلُ) al-muzzammil terambil dari kata (الزَّمْلُ) az-zaml yang berarti beban yang berat. Seorang yang kuat dinamai (إِزْمِيْل) izmil karena ia mampu memikul beban yang berat. Ia juga berarti menggandeng. Dari sini, lahir kata (زَمِيْل) zamīl. Yakni teman akrab yang bagaikan bergandengan dan (زِمِل) zimil, yakni sesuatu yang dibonceng.
Kata tersebut juga diartikan sebagai menyembunyikan atau menyelubungi badannya dengan selimut. Kata yang sama digunakan dalam bahasa kiasan dengan arti seorang yang menutupi atau menyembunyikan kelemahan-kelemahannya sehingga ia menjadi penakut, malas, tidak giat, dan takut menghadapi kesulitan. Dari makna-makna kebahasaan tersebut serta dari perbedaan-perbedaan yang berbeda tentang maksud panggilan al-Muzzammil, antara lain:
Pendapat terakhir ini dikemukakan antara lain oleh mufassir az-Zamakhsyarī. Menurutnya: “Pada suatu malam, Rasūlullāh s.a.w. sedang berbaring dalam keadaan berselimut maka turunlah ayat ini menegur beliau. Teguran itu mengandung arti kecaman yang disebabkan oleh karena beliau ketika itu bersiap-siap untuk tidur nyenyak, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang tidak memberi perhatian kepada persoalan-persoalan besar serta malas dan enggan menghadapi kesulitan dan tantangan.” Demikian az-Zamakhsyarī. Memang, boleh jadi Nabi Muḥammad s.a.w. ketika itu sedang resah sehingga berselimut, tetapi makna yang dikemukakan az-Zamakhsyarī ini sungguh jauh dari kebenaran bahkan tidak wajar dinyatakan sebagai sikap Rasūlullāh s.a.w.
Pendapat umum para ulama justru menjadikan seruan “Wahai orang yang berselimut” sebagai panggilan akrab dan mesra dari Allah terhadap Nabi-Nya. Memang, di sisi lain, panggilan itu dapat tertuju kepada setiap orang yang tidur malam agar memerhatikan pesan ayat ini dengan menggunakan waktu malam untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Kata (قُمْ) qum terambil dari kata (قَوَمَ) qawama yang kemudian berubah menjadi (قَامَ) qāma yang secara umum diartikan sebagai melaksanakan sesuatu secara sempurna dalam berbagai seginya. Perintah al-Qur’ān dalam bentuk kata qum hanya ditemukan dua kali dalam al-Qur’ān, masing-masing pada ayat kedua surah ini dan surah al-Muddatstsir.
Sayyid Quthub dalam tafsirnya menulis tentang ayat ini bahwa: “Ini adalah ajakan langit serta suara Yang Maha Besar lagi Maha Tinggi. Bangkitlah, bangkitlah untuk menghadapi persoalan besar yang menantimu. Suatu beban bangkitlah untuk diletakkan di pundakmu. Bangkitlah untuk bekerja keras, letih, dan sungguh-sungguh. Bangkitlah karena telah berlalu masa tidur dan istirahat. Bangkit dan bersiaplah menghadapi persoalan-persoalan berat ini.” Sayyid Quthub selanjutnya menyatakan bahwa Rasūlullāh s.a.w. menyadari benar kandungan perintah ini sehingga beliau berkata kepada istrinya Khadījah: “Telah berlalu masa tidur, wahai Khadījah.”
Kata (اللَّيْل) al-lail pada mulanya dari segi bahasa berarti hitam pekat. Karena itu, malam, rambut (yang hitam) dinamai Lail.
Dalam literatur keagamaan: “malam” diartikan sebagai “waktu terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar”, demikian kesimpulan ulama Sunnī. Sedang, bagi ulama Syī‘ah “malam dimulai setelah terbenamnya matahari yang ditandai dengan hilangnya mega merah di ufuk timur”. Karena itu, waktu berbuka puasa bagi penganut aliran Syī‘ah lebih lambat sedikit dibandingkan dengan penganut aliran Sunnī, walaupun keduanya berpegang kepada firman Allah:
ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ.
“Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam” (QS. al-Baqarah [2]: 187).
Thāhir Ibn ‘Āsyūr memahami kata malam pada ayat al-Baqarah ini dalam arti setelah ‘Isyā’.
Sementara ulama mengartikan kata (قُمْ) qum pada ayat kedua ini dalam arti shalatlah. Menurut mereka, kata qum, apabila terangkai dengan (اللَّيْل) al-lail, ia telah sangat populer dalam arti shalat malam.
Sedang, mereka yang memahaminya dalam arti bangkit, menyatakan bahwa dalam redaksi ayat kedua ini terdapat kata tersirat, yaitu “shalat”, sehingga keseluruhannya diartikan sebagai: “Bangkitlah untuk shalat pada waktu malam.”
Dengan demikian, menjadi jelas bahwa konteks ayat ini tidak berkaitan secara langsung dengan perintah bangkit untuk menghadapi tugas-tugas berat – sebagaimana pendapat Sayyid Quthub di atas – tetapi perintah untuk bangkit melaksanakan Shalāt-ul-Lail. Hal ini akan semakin jelas jika diamati bahwa “kebangkitan” yang dituntut bukannya kebangkitan penuh, padahal yang dituntut dalam konteks penyampaian risalah adalah kebangkitan penuh.
Ayat ini tidak memerintahkan untuk melaksanakan Shalāt-ul-Lail sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, sebagaimana terlihat dari kata (إِلَّا قَلِيْلًا) illā qalīlan/kecuali sedikit dalam arti: “Sedikit dari bagian malam itu, engkau hendaknya tidak melakukan shalat.”
Bagian yang sedikit tersebut dijelaskan oleh ayat 3 dan dengan demikian perintah melakukan Qiyām-ul-Lail adalah selama seperdua malam, atau kurang sedikit atau lebih sedikit dari seperdua malam itu. Dengan kata lain, Nabi Muḥammad s.a.w. diperintahkan untuk shalat lebih kurang lima setengah jam.
Ada ulama juga yang tidak menjadikan ayat 3 dan 4 sebagai penjelasan tentang arti pengecualian pada ayat kedua. Menurut mereka, pengecualian yang dimaksud bukan pada “bagian” malam tetapi “jumlah malam” sehingga keseluruhan ayat-ayat di atas diartikan sebagai: “Bangkitlah untuk melakukan shalat malam sebanyak lebih kurang setengah malam, kecuali pada beberapa malam di mana kamu misalnya sedang sakit, sangat mengantuk, atau menghadapi kesibukan-kesibukan lain yang tidak terelakkan.”
Kata (رَتِّلِ) rattil dan (تَرْتِيْل) tartīl terambil dari kata (رتل) ratala yang antara lain berarti serasi dan indah. Kamus-kamus bahasa merumuskan bahwa segala sesuatu yang baik dan indah dinamai ratl, seperti gigi yang putih dan tersusun rapi, demikian pula benteng yang kuat dan kukuh.
Ucapan-ucapan yang disusun secara rapi dan diucapkan dengan baik dan benar dilukiskan dengan kata-kata Tartīl-ul-Kalām.
Tartīl-ul-Qur’ān adalah: “Membacanya dengan pelahan-lahan sambil memperjelas huruf-huruf berhenti dan memulai (Ibtidā’) sehingga pembaca dan pendengarnya dapat memahami dan menghayati kandungan pesan-pesannya”. Sedang, yang dimaksud dengan al-Qur’ān adalah nama bagi keseluruhan firman Allah yang diterima oleh Nabi Muḥammad s.a.w. melalui malaikat Jibrīl dari ayat pertama al-Fātiḥah sampai dengan ayat terakhir an-Nās. Dalam saat yang sama, al-Qur’ān juga merupakan nama dari bagian-bagiannya yang terkecil. Satu ayat pun dinamai “al-Qur’ān”.
Kalau pendapat yang menyatakan bahwa ayat-ayat di atas merupakan wahyu ketiga, dari segi konteksnya ayat ini berpesan agar Nabi s.a.w. membaca dengan tartīl lima ayat pertama pada surah Iqrā’, awal surah al-Qalam, serta awal surah al-Muddatstsir (jika yang terakhir ini turun sebelum al-Muzzammil).
Di sisi lain, timbul pertanyaan apakah perintah melakukan “Tartīl” dilaksanakan pada saat Qiyām-ul-Lail ataukah ia merupakan perintah tersendiri yang dilaksanakan kapan saja? Dua pendapat yang berbeda, namun penulis cenderung memahaminya sebagai perintah tersendiri yang hendaknya dilaksanakan pada malam atau siang hari.
Kedua perintah di atas adalah dalam rangka menghadapi tugas berat yang akan diemban sebagaimana dijelaskan oleh ayat berikut.
AYAT 5
“Sesungguhnya Kami akan menurunkan atasmu perkataan yang berat.”
Mengapa Allah memerintahkan Nabi s.a.w. untuk bangkit shalat dan bermunajat mendekatkan diri kepada Allah. Itu disebabkan “Sesungguhnya Kami melalui malaikat Jibrīl a.s. dalam waktu singkat ini akan menurunkan atasmu, wahai Nabi Muḥammad, perkataan yang berat, yakni firman-firman Allah berupa al-Qur’ān.”
Kata (سَنُلْقِيْ) sanulqī terambil dari kata (لقِي) laqiya yang pada mulanya berarti bertemunya dua hal dalam bentuk kedekatan. Ia juga biasa diartikan mencampakkan dan ini mengandung arti keras dan cepatnya campakan itu. Al-Qur’ān menggunakan kata tersebut dalam berbagai bentuk dengan makna yang berbeda-beda namun kesemuanya bermuara kepada arti kebahasan di atas. Penggunaan kata tersebut, di samping mengisyaratkan kehadiran wahyu yang demikian cepat, juga kemantapan dan kedekatan wahyu itu kepada diri Nabi Muḥammad s.a.w.
Kata (عَلَيْكَ) ‘alaika, di samping mengandung makna kemantapan, juga mengesankan bahwa wahyu itu akan diterima Nabi s.a.w. dalam keadaan berat dan itu ditegaskan lagi dengan kata (ثَقِيْلًا) tsaqīlan/berat.
Kata (قَوْلًا) qaulan, yakni ucapan, yang diterima Nabi Muḥammad s.a.w. adalah lafal-lafal yang bersumber langsung dari Allah s.w.t. Itu beliau terima bukan berupa inspirasi karena inspirasi atau ilham adalah “pengetahuan yang diperoleh secara langsung menyangkut persoalan-persoalan yang dapat dipikirkan atau telah dipikirkan”. Sedang “wahyu” yang diterima oleh para nabi adalah pengetahuan yang secara langgung menyangkut masalah-masalah yang tidak terpikiran. Di samping itu, inspirasi tidak menimbulkan keyakinan yang bulat dari penerimanya, berbeda halnya dengan wahyu. Di sisi lain, inspirasi tidak mengakibatkan atau tidak disertai gejala-gejala yang tampak pada fisik penerimanya, berbeda halnya dengan wahyu al-Qur’ān.
‘Ā’isyah r.a., istri Nabi Muḥammad s.a.w. (*Missing) menerima wahyu, beliau bercucuran keringat walaupun di musim dingin yang sangat menyekat. Rasūlullāh, dalam sekian riwayat, menyampaikan bahwa pada saat menerima wahyu terkadang penerimaannya disertai dengan bunyi yang demikian keras bagaikan gemerincingan lonceng di teliga atau seperti suara lebah yang menderu, sedemikian “berat” wahyu yang diterima itu sehingga terkadang pula beliau memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk menutup wajah beliau.
Yang memerintahkan untuk menutupnya adalah Nabi Muḥammad sendiri, hal mana menjadi bukti bahwa, ketika menerima wahyu, beliau berada dalam keadaan sadar dan yang ditutup hanya wajah bukan seluruh tubuh. Dua hal di atas dapat menjadi bukti bahwa apa yang beliau alami itu bukan merupakan gejala epilepsi (penyakit ayan).
Demikian gambaran tentang cara penerimaan wahyu serta salah satu arti kata tsaqīlan/berat yang dilukiskan oleh ayat 5 ini.
Ada juga yang memahami kata tsaqīlan/berat sebagai gambaran tentang kandungan wahyu yang akan diterima dan bukan keadaan yang beliau alami ketika menerimanya. Menurut mereka, “beratnya” kandungan al-Qur’ān adalah karena ia merupakan Kalām Ilāhi Yang Maha Agung dan karena ia mengandung petunjuk-petunjuk yang menuntut kesungguhan, ketabahan, dan kesabaran dalam melaksanakannya. Sejarah membuktikan betapa berat perjuangan Nabi dan sahabatnya dalam menegakkan ajaran-ajaran tersebut dan betapa berat pula tantangan yang dihadapi umat untuk mempertahankannya. Sebenarnya, kedua makna tersebut dapat dicakup oleh kata berat, bahkan ditegaskan oleh QS. al-Ḥasyr [59]: 21:
لَوْ أَنْزَلْنَا هذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ.
“Kalau sekiranya Kami menurunkan al-Qur’ān ini kepada sebuah gunung pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah-belah karena takut kepada Allah.”
Masih terdapat pendapat-pendapat lain tentang arti berat, namun pendapat-pendapat tersebut, walaupun kandungannya benar, agak jauh dari konteks ayat ini. Seperti yang menyatakan bahwa al-Qur’ān berat bagi orang kafir dan munafik, atau dalam timbangan ‘amal di hari Kemudian, atau berat dalam arti agung, atau dalam arti mantap (karena sesuatu yang berat pasti mantap). Sehingga, karena kemantapannya, ia tidak akan mengalami perubahan bahkan akan kekal selama-lamanya.”