Surah al-Ikhlash 112 ~ Tafsir al-Mishbah (2/2)
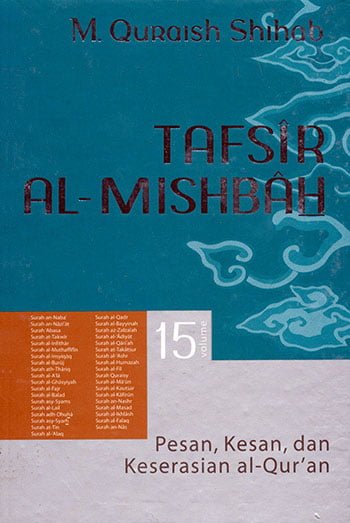
Tafsir al-Mishbāḥ
(Jilid ke-15, Juz ‘Amma)
Oleh: M. Quraish Shihab
Penerbit: Penerbit Lentera Hati
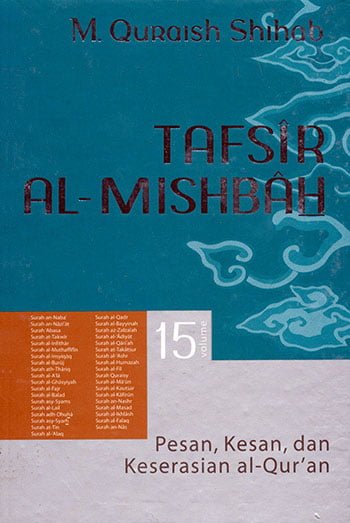
Tafsir al-Mishbāḥ
(Jilid ke-15, Juz ‘Amma)
Oleh: M. Quraish Shihab
Penerbit: Penerbit Lentera Hati
“Allah tumpuan harapan.”
Setelah ayat yang lalu menjelaskan tentang dzāt, shifāt, dan perbuatan Allah Yang Maha Esa, ayat di atas menjelaskan kebutuhan makhluk kepada-Nya, yakni hanya Allah Yang Maha Esa itu adalah tumpuan harapan yang dituju oleh semua makhluk guna memenuhi segala kebutuhan, permintaan mereka, serta bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
Kata (الصَّمَدُ) ash-shamad terambil dari kata kerja (صمد) shamada yang berarti menuju. Ash-Shamad adalah kata jadian yang berarti yang dituju. Bahasa menggunakan kata ini dalam berbagai arti, namun ada dua di antaranya yang sangat populer, yaitu:
Satu riwayat yang disandarkan kepada Ibn ‘Abbās r.a. menyatakan bahwa ash-Shamad berarti: “tokoh yang telah sempurna ketokohannya, mulia dan mencapai puncak keagungan, yang penyantun dan tiada melebihi santunannya, yang mengetahui lagi sempurna pengetahuannya, yang bijaksana dan tiada cacat dalam kebijaksanaannya.”
Ulama-ulama yang memahami kata ash-Shamad dalam pengertian “tidak memiliki rongga” mengembangkan arti tersebut agar sesuai dengan kebesaran dan kesucian Allah. Mereka berkata: “Sesuatu yang tidak memiliki rongga mengandung arti bahwa ia sedemikian padat dan atau bahwa ia tidak membutuhkan sesuatu untuk dimasukkan ke dalam dirinya, seperti makanan atau minuman.” Allah tidak membutuhkan makanan, tidak ada sesuatu yang keluar dari-Nya, tidak beranak dan tidak diperanakkan, sebagaimana ditegaskan oleh ayat berikut.
Ada juga yang mengartikan kata tersebut sebagai menunjuk kepada Allah yang dzāt-Nya tidak dapat terbagi. Menurut mereka, kalau kata aḥad menunjuk kepada dzāt Allah yang tidak tersusun oleh bagian atau unsur apa pun, maka kata ash-Shamad mengandung arti bahwa dalam keesaan-Nya itu, dzāt tersebut tidak dapat dibagi-bagi.
Mayoritas pakar bahasa dan tafsir memahami arti ash-Shamad dalam pengertian kedua yang disebut di atas, yakni bahwa Allah adalah dzāt yang kepada-Nya mengarah semua harapan makhluk, Dia yang didambakan dalam pemenuhan kebutuhan makhluk serta penanggulangan kesulitan mereka.
Kata (الصَّمَدُ) ash-shamad berbentuk ma‘rifah (definite) yakni dihiasi oleh alif dan lām berbeda dengan aḥad berbentuk nakirah (indefinite). Ini menurut Ibn Taimiyyah, karena kata aḥad tidak digunakan dalam kedudukannya sebagai shifāt (adjektif) kecuali terhadap Allah sehingga di sini tidak perlu dihiasi dengan alif dan lām berbeda dengan kata ash-Shamad. Yang digunakan terhadap Allah, manusia, atau apa pun.
Memang, makhluk dapat menjadi tumpuan harapan, tetapi harus disadari bahwa makhluk tersebut – pada saat itu atau pada saat yang lain – juga membutuhkan tumpuan harapan yang dapat menanggulangi kesulitannya. Ini berarti bahwa substansi dari ash-shamadiyyah (tumpuan harapan) tidak dimiliki makhluk secara penuh, berbeda dengan Allah s.w.t. yang menjadi harapan semua makhluk secara penuh sedang Dia sendiri tidak membutuhkan siapa dan apa pun. Dengan demikian, kita dapat berkata bahwa alif dan lām pada kata ini untuk menunjukkan kesempurnaan dan ketergantungan makhluk terhadap-Nya.
Muḥammad ‘Abduh menulis bahwa kata Allāh yang bersifat ma‘rifah (definite) dengan ash-Shamad yang sifatnya juga demikian, menjadikan ayat kedua ini dalam bentuk ḥashr, yakni mengandung arti pengkhususan. ‘Abduh memberi contoh, misalnya jika lawan bicara anda menduga bahwa si Zaid seorang alim (pandai) tetapi ada orang lain yang seperti dia maka, untuk menghapus dugaan itu sambil menyatakan bahwa Zaid satu-satunya yang alim, anda harus berkata: Zaid al-‘ālim. Nah, demikian juga Allahu ash-Shamad. Ayat ini, menurutnya, menegaskan bahwa hanya Allah yang menjadi tumpuan harapan satu-satunya. Kebutuhan segala sesuatu dalam wujud ini tidak tertuju kecuali kepada-Nya dan yang membutuhkan sesuatu tidak boleh mengajukan permohonannya kepada selain-Nya. Segala sebab berakhir pada-Nya dan segala yang terjadi di alam raya ini merupakan hasil ciptaan-Nya. Lebih jauh, ‘Abduh menjelaskan bahwa makhluk yang memiliki kemampuan memilih – seperti manusia – apabila bermaksud mendapat sesuatu, ia berkewajiban untuk mencari cara yang tepat untuk itu, sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, yakni dengan melihat kaitan antara sebab dan akibat. Tetapi, pada akhirnya ia harus mengembalikan sebab terakhir dari segala sesuatu kepada Allah s.w.t. jua.
Dalam ayat kedua ini, kata Allāh diulang sekali lagi, setelah sebelumnya pada ayat pertama telah disebut. Ini untuk memberi isyarat bahwa siapa yang tidak memiliki sifat ash-shamadiyyah atau dengan kata lain tidak menjadi tumpuan harapan secara penuh, ia tidak wajar dipertuhankan.
“Tidak beranak dan tidak diperanakkan.”
Setelah ayat-ayat yang lalu menjelaskan bahwa semua makhluk bergantung kepada-Nya, ayat di atas membantah kepercayaan semetara orang tentang Tuhan dengan menyatakan bahwa Allah Yang Maha Esa itu tidak wajar dan tidap pula pernah beranak dan di samping itu Dia tidak diperanakkan, yakni tidak dilahirkan dari bapak atau ibu.
Dia tidak menciptakan anak dan juga tidak dilahirkan dari bapak atau ibu. Tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai-Nya.
Kata (يَلِد) yalid/beranak dan (يُوْلَد) yūlad/diperanakkan terambil dari kata (وَلَدَ) walada yang digunakan al-Qur’ān untuk menggambarkan hubungan keturunan sehingga kata (وَالِدٌ) wālid, misalnya, berarti ayah dan yang dimaksud adalah ayah kandung, (وَلَدٌ) walad adalah anak kandung, (وَالِدَةٌ) wālidah adalah ibu kandung, demikian seterusnya. Ini berbeda dengan kata (أَبٌ) ab yang bisa berarti ayah kandung atau ayah angkat.
Beranak atau diperanakkan menjadikan adanya sesuatu yang keluar darinya dan ini mengantar kepada terbaginya dzāt Tuhan, bertentangan dengan arti Aḥad serta bertentangan dengan hakikat sifat-sifat Allah. Di sisi lain, anak dan ayah merupakan jenis yang sama, sedangkan Allah tiada sesuatu pun yang seperti-Nya (laisa kamitslihi syai’), baik dalam benak maupun dalam kenyataan, sehingga pasti Dia tidak mungkin melahirkan atau dilahirkan.
Anak dibutuhkan oleh makhluk berakal untuk melanjutkan eksistensinya atau untuk membantunya, sedang Tuhan kekal selama-lamanya dan tidak memerlukan bantuan.
Kata (لَمْ) lam digunakan untuk menafikan sesuatu yang telah lalu, kata tersebut digunakan karena selama ini telah beredar kepercayaan bahwa Tuhan beranak dan diperanakkan. Nah, untuk meluruskan kekeliruan itu, yang paling tepat digunakan adalah redaksi yang menafikan sesuatu yang lalu. Seakan-akan ayat ini menyatakan: “Kepercayaan kalian keliru, Allah tidak pernah beranak atau diperanakkan.”
Yang dinafikan terlebih dahulu adalah lam yalid/tidak beranak baru lam yūlad/tidak diperanakkan. Ini agaknya karena banyak sekali yang percaya bahwa Tuhan beranak sehingga wajar kalau hal tersebut yang terlebih dahulu dinafikan.
Ayat di atas menafikan segala macam kepercayaan menyangkut adanya anak atau ayah bagi Allah s.w.t., baik yang dianut oleh kaum musyrikin, orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, atau sementara filosof, baik anak tersebut berbentuk manusia atau tidak.
“Tidak ada satu pun yang setara dengan-Nya.”
Setelah menjelaskan bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, ayat di atas menafikan sekali lagi segala sesuatu yang menyamai-Nya, baik sebagai anak atau bapak atau selainnya, dengan menyatakan: Tidak ada satu pun, tidak dalam imajinasi apalagi dalam kenyataan, yang setara dengan-Nya dan tidak juga ada sesuatu pun yang menyerupai-Nya.
Kata (كُفُوًا) kufuwan terambil dari kata (كُفُؤٌ) kufu’, yakni sama. Sementara ulama memahami kata ini dalam arti istri. Ayat di atas menurut mereka serupa dengan firman-Nya:
وَ أَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رِبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَ لَا وَلَدًا.
“Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak (pula) beranak” (QS. al-Jinn [72]: 3). Pendapat di atas tidak didukung oleh banyak ulama walau memang Allah tidak memiliki istri. Banyak ulama memahami ayat di atas sebagai menafikan adanya sesuatu – apa pun – yang serupa dengan-Nya. Sementara kaum percaya bahwa ada penguasa selian Allah, misalnya dengan menyatakan bahwa Allah hanya menciptakan kebaikan, sedang syaithan menciptakan kejahatan. Ayat ini menafikan hal tersebut sehingga, dengan demikian, kedua ayat terakhir ini menafikan segala macam kemusyrikan terhadap Allah s.w.t.
Demikian surah al-Ikhlāsh menetapkan keesaan Allah secara murni dan menafikan segala macam kemusyrikan terhadap-Nya. Wajar jika Rasūl s.a.w. menilai surah ini sebagai: “Sepertiga al-Qur’ān” (HR. Mālik, Bukhāri, dan Muslim), dalam arti makna yang dikandungnya memuat seperti al-Qur’ān karena keseluruhan al-Qur’ān mengandung akidah, syariat, dan akhlak, sedang surah ini adalah puncak akidah. Maha Benar Allah dalam segala firman-Nya. Wa Allāhu A‘lam.