Surah al-Ikhlash 112 ~ Tafsir al-Mishbah (1/2)
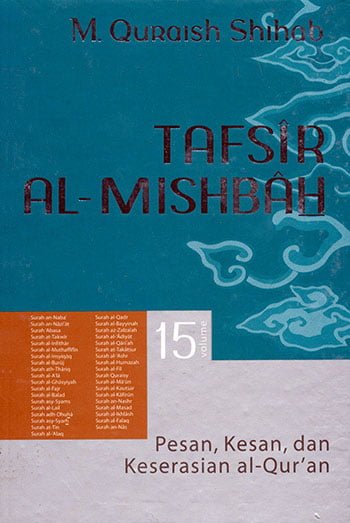
Tafsir al-Mishbāḥ
(Jilid ke-15, Juz ‘Amma)
Oleh: M. Quraish Shihab
Penerbit: Penerbit Lentera Hati
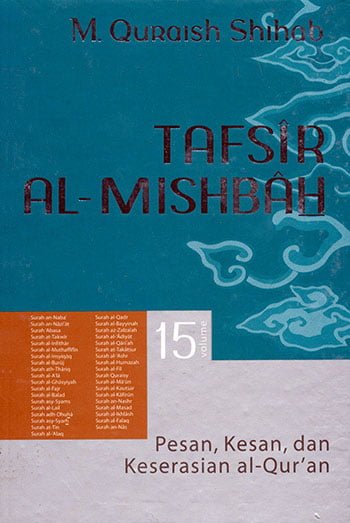
Tafsir al-Mishbāḥ
(Jilid ke-15, Juz ‘Amma)
Oleh: M. Quraish Shihab
Penerbit: Penerbit Lentera Hati
Surah al-Ikhlāsh terdiri dari 4 ayat.
Kata AL-IKHLĀSH, yang berarti “Suci”atau “Murni”
karena surah ini menggambarkan
ke-Esa-an dan kemurnian Allah s.w.t.
Menurut mayoritas ulama, surah ini Makkiyyah. Ia turun sebagai jawaban atas pertanyaan sementara kaum musyrikin yang ingin mengetahui bagaimana Tuhan yang disembah oleh Nabi Muḥammad s.a.w. Ini karena mereka menyangka bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu serupa dengan berhala-berhala mereka.
Ada juga riwayat yang menyatakan bahwa surah ini turun berkenaan dengan pertanyaan orang-orang Yahudi di Madīnah atau dalam riwayat lain berkenaan dengan datangnya ‘Āmir Ibn Thufail dan Arbad Ibn Rabī‘ah yang bertanya kepada Nabi s.a.w. tentang ajakan beliau. Ketika itu, Nabi s.a.w. menjawab: “Aku mengajak kepada Allah”. Kalau mereka meminta agar dilukiskan apakah Allah terbuat dari emas atau perak atau kayu. Peristiwa ini, menurut riwayat tersebut, terjadi di Madīnah. Riwayat ini kalau pun diterima, itu tidak menunjukkan bahwa surah ini turun ketika itu, tetapi Nabi s.a.w. ketika itu membacakan setelah jauh sebelumnya di Makkah beliau telah menerimanya. Memang, pada wahyu-wahyu pertama yang turun, al-Qur’ān menggunakan Rabbuka (Tuhanmu, hai Nabi Muḥammad) untuk menunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perhatikan surah-surah Iqra’, al-Muzzammil, al-Muddatstsir, dan seterusnya. Kalau demikian, wajar jika timbul pertanyaan, baik di kalangan kaum musyrikin maupun orang-orang Yahudi, tentang Tuhan yang disembah Nabi Muḥammad itu. Bagaimana sifatnya, apa nisbahnya, apakah terbuat dari emas atau perak. Demikian beberapa pertanyaan menurut aneka riwayat itu. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, turun ayat-ayat surah ini.
Namanya banyak sekali. Pakar tafsir, Fakhruddīn ar-Rāzī, menyebut sekitar dua puluh nama, antara lain surah at-Tafrīd (Pengesaan Allah), surah at-Tajrīd (Penafian segala sekutu bagi-Nya), surah an-Najāt (Keselamatan, yakni di dunia dan akhirat), surah al-Wilāyah (Kedekatan kepada Allah), surah al-Ma‘rifah (Pengetahuan tentang Allah), surah al-Jamāl (Keindahan karena Allah Maha Indah), surah Qasyqasy (Penyembuhan dari kemusyrikan), surah al-Mudzdzakkirah (Pemberi peringatan), surah ash-Shamad, surah al-Amān, dan masih banyak lainnya. Tetapi, namanya yang paling populer adalah surah al-Ikhlāsh. Kata Ikhlāsh terambil dari kata khālish yang berarti suci atau murni setelah sebelumnya memiliki kekeruhan. Ikhlāsh adalah keberhasilan mengikis dan menghilangkan kekeruhan itu sehingga sesuatu yang tadinya keruh menjadi murni. Dengan nama itu, tecermin bahwa kandungan ayat-ayat ini, bila dipahami dan dihayati oleh seseorang, itu akan menyingkirkan segala kepercayaan, dugaan, dan prasangka kekurangan atau sekutu bagi Allah s.w.t. yang boleh jadi selama ini hinggap di benak dan hatinya sehingga pada akhirnya keyakinannya tentang keesaan Allah benar-benar suci murni tidak lagi dihinggapi oleh kemusyrikan baik yang jelas (mempersekutukan Allah) maupun yang tersembunyi (riyā’ dan pamrih).
Tema utamanya adalah pengenalan tentang Tuhan Yang Maha Esa dan yang menjadi andalan dan harapan semua makhluk. Menurut al-Biqa‘ī, tujuan utamanya adalah penjelasan tentang Dzāt Yang Maha Suci (Allh s.w.t.) serta kewajaran-Nya menyandang puncak semua sifat sempurna serta menghindarkan dari-Nya semua sifat kekurangan.
Surah ini merupakan surah yang ke-19 bagi ulama yang menyatakannya Makkiyyah. Ada juga di antara mereka yang berpendapat surah yang ke-22 yang turun sesudah surah an-Nās dan sebelum an-Najm. Jumlah ayat-ayatnya sebanyak 4 ayat menurut cara perhitungan ulama Madīnah, Kūfah, dan Bashrah, sedang menurut cara perhitungan ulama Makkah dan Syām sebanyak 5 ayat. Mereka menilai lam yalid merupakan satu ayat dan wa lam yūlad ayat yang lain.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
KELOMPOK 1
Ayat 1-4
قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ. اللهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُوْلَدْ. وَ لَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ
AYAT 1
“Katakanlah! Dia Allah Yang Maha Esa.”
Tujuan utama kehadiran al-Qur’ān adalah memperkenalkan Allah dan mengajak manusia untuk mengesakan-Nya serta patuh kepada-Nya. Surah ini memperkenalkan Allah dengan memerintahkan Nabi Muḥammad s.a.w. untuk menyampaikan sekaligus menjawab pertanyaan sementara orang tentang Tuhan yang beliau sembah. Ayat di atas menyatakan: Katakanlah, wahai Nabi Muḥammad, kepada yang bertanya kepadamu bahkan kepada siapa pun bahwa Dia Yang Wajib wujud-Nya dan yang berhak disembah adalah Allah Tuhan Yang Maha Esa.
Kata (قُلْ) qul/katakanlah membuktikan bahwa Nabi Muḥammad s.a.w. menyampaikan segala sesuatu yang diterimanya dari ayat-ayat al-Qur’ān yang disampaikan oleh Malaikat Jibrīl a.s. Seandainya ada sesuatu yang disembunyikan atau tidak disampaikannya, yang paling wajar untuk itu adalah semacam kata qul ini. Rujuklah ke awal surah al-Kāfirūn untuk mengetahui lebih banyak tentang hal ini. (461).
Kata (هُوَ) Huwa biasa diterjemahkan Dia. Kata ini bila digunakan dalam redaksi semacam bunyi ayat pertama ini, ia berfungsi untuk menunjukkan betapa penting kandungan redaksi berikutnya, yakni: Allāhu Aḥad. Kata (هُوَ) Huwa di sini dinamai dhamīr-usy-sya’n atau al-qishshah atau al-ḥāl. Menurut Mutawallī asy-Sya‘rāwī, Allah adalah ghaib, tetapi keghaiban-Nya itu mencapai tingkat syahādat/nyata melalui ciptaan-Nya. Dengan demikian, jika anda berkata Huwa/Dia, ketika itu juga anda bagaikan berkata bahwa al-Ḥāl (keadaan) yang sebenarnya adalah Allah Maha Esa – baik anda mengesakan-Nya maupun tidak. Karena demikian itulah keadaan-Nya. Lebih jauh, asy-Sya‘rāwī menyatakan bahwa kata Huwa menunjuk sesuatu yang tidak hadir di depan anda, dengan kata lain ghaib. Kata Huwa di sini menunjuk Allah yang ghaib itu. Dia ghaib karena Dia cahaya. Dengan cahaya, anda melihat sesuatu, tetapi dia sendiri tidak dilihat sampai ada cahaya yang melebihi-Nya agar dia dapat terlihat, tetapi karena tidak ada yang melebihi Allah maka wajar jika kita tidak melihat-Nya. Memang, seandainya Dia terlihat, hakikat-Nya diketahui dan dengan demikian, Dia terjangkau, dan jika Dia terjangkau maka Dia tidak wajar lagi dipertuhan. Pengetahuan merupakan salah satu bentuk jangkauan. Karena itu, pengetahuan anda bahwa anda tidak tahu merupakan jangkauan anda terhadap Allah. Asy-Sya‘rāwī memberi contoh dengan dua orang yang disodorkan kepada keduanya satu masalah. Yang pertama mengaku tahu dan mencoba lalu terbukti gagal, dan yang kedua mengetahui dan menyadari bahwa dia tidak tahu. Di sini, pengetahuan orang yang kedua ini lebih dalam dan sesuai dengan hakikat yang sebenarnya dibanding dengan yang pertama. Karena yang pertama mengira bahwa ia tahu tetapi terbukti tidak. Ini menunjukkan bahwa ia tidak tahu betapa sulit masalah yang disodorkan kepadanya. Adapun yang kedua, ketika ia berkata saya tidak tahu, sebenarnya ia telah menyadari sulitnya masalah itu dan menyadari pula keterbatasan dirinya. Di sisi lain, orang yang kedua memiliki pengetahuan lebih tinggi daripada yang pertama. Itulah yang dimaksud kesadaran tentang ketidakmampuan meraih sesuatu merupakan pengetahuan tentang sesuatu itu. Demikian jugalah ketika menyatakan bahwa: “Dia yang ghaib itu adalah Allah.”
Pakar tafsir, al-Qāsimī, memahami kata (هُوَ) Huwa sebagai berfungsi menekankan kebenaran dan kepentingan berita itu, yakni apa yang disampaikan itu merupakan berita yang benar yang ḥaqq dan didukung oleh bukti-bukti yang tidak diragukan. Sedang, Abus-Su‘ūd, salah seorang pakar tafsir dan tashawwuf, menulis dalam tafsirnya: Menempatkan kata Huwa untuk menunjuk kepada Allah, padahal sebelumnya tidak pernah disebut dalam susunan redaksi ayat ini kata yang menunjuk kepada-Nya, adalah untuk memberi kesan bahwa Dia Yang Maha Kuasa itu sedemikian terkenal dan nyata sehingga hadir dalam benak setiap orang dan bahwa kepada-Nya selalu tertuju segala isyarat.
Para pengamal tashawwuf biasa menggunakan kata (هُوَ) Huwa dengan men-sukūn-kan huruf kedua yaitu (و) wāwu sehingga terdengar dan terucap (هُوْ) Huw, dan yang mereka maksudkan dengan kata ini adalah Allah s.w.t. Dengan berbuat demikian, mereka ingin berkata bahwa Allah sedemikian jelas kehadiran-Nya sehingga, walaupun dengan menggunakan kata yang menunjuk persona ketiga tanpa terlebih dahulu menyebut nama tertentu, tetap saja dapat diketahui bahwa yang dimaksud adalah Allah. Bukankah jika anda berkata dia, anda tidak dapat mengetahui siapa yang dimaksud kecuali jika sebelumnya telah disebut atau ditunjuk persona yang dimaksud? Nah, bagi Allah, tidak demikian itu halnya. Selama anda menyebut kata Huw, otomatis yang dimaksud adalah Allah karena Dia selalu hadir dalam benak.
Kata (اللهُ) Allah adalah nama bagi suatu Wujud Mutlak, Yang berhak disembah, Pencipta, Pemelihara, dan Pengatur seluruh jagat raya. Dia-lah Tuhan Yang Maha Esa yang disembah dan diikuti segala perintah-Nya. Para pakar bahasa berbeda pendapat tentang kata ini. Ada yang menyatakan bahwa ia adalah nama yang tidak terambil dari satu akar kata tertentu, dan ada juga yang menyatakan bahwa ia terambil dari kata (أَلِهَ) aliha yang berarti mengherankan, menakjubkan karena setiap perbuatan-Nya menakjubkan, sedang dzāt-Nya sendiri, bila akan dibahas hakikat-Nya akan mengherankan pembahasnya. Ada juga yang berpendapat bahwa kata ilāh yang terambil dari akar kata yang berarti ditaati karena Ilāh atau Tuhan selalu ditaati.
Apa pun asal katanya, yang jelas Allah menunjuk kepada Tuhan yang Wajib Wujud-Nya itu, berbeda dengan kata (إِلَاه) ilāh yang menunjuk kepada siapa saja yang dipertuhan, baik itu Allah maupun selain-Nya, seperti matahari yang disembah oleh umat tertentu atau hawa nafsu yang diikuti dan diperturutkan kehendaknya oleh para pendurhaka itu (Baca QS. al-Furqān [25]: 43).
Kata (أَحَد) aḥad/esa terambil dari akar kata (وَحْدَة) waḥdah/kesatuan seperti juga kata (وَاحِد) wāḥid yang berarti satu. Kata (أَحَدٌ) aḥad bisa berfungsi sebagai nama dan bisa juga sebagai sifat bagi sesuatu. Apabila ia berkedudukan sebagai sifat, ia hanya digunakan untuk Allah s.w.t. semata.
Dalam ayat yang ditafsirkan ini, kata (أَحَد) aḥad berfungsi sebagai sifat Allah s.w.t., dalam arti bahwa Allah memiliki sifat tersendiri yang tidak dimiliki oleh selain-Nya.
Dari segi bahasa, kata aḥad, walaupun berakar sama dengan wāḥid, masing-masing memiliki makna dan penggunaan tersendiri. Kata aḥad hanya digunakan untuk sesuatu yang tidak dapat menerima penambahan baik dalam benak apalagi dalam kenyataan. Karena itu, kata ini – ketika berfungsi sebagai sifat – tidak termasuk dalam rentetan bilangan menjadi dua, tiga, dan seterusnya walaupun penambahan itu hanya dalam benak pengucap atau pendengarnya.
Allah memang disifati juga dengan kata Wāḥid seperti antara lain dalam firman-Nya:
وَ إِلهُكُمْ إِلهٌ وَاحِدٌ لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيْمُ.
“Tuhan-mu adalah Tuhan yang Wāḥid, tiada tuhan selain Dia, Dia Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.” (QS. al-Baqarah [2]: 163).
Sementara ulama berpendapat bahwa kata Wāḥid pada ayat al-Baqarah itu menunjuk kepada keesaan dzāt-Nya disertai dengan keragaman sifat-sifatNya, bukankah Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuat, Maha Tahu, dan sebagainya, sedang kata Aḥad seperti dalam surah yang ditafsirkan ini, mengacu kepada keesaan dzāt-Nya saja, tanpa memerhatikan keragaman sifat-sifat tersebut.
Terlepas dari setuju atau tidak dengan pembedaan terkahir ini, namun yang jelas bahwa Allah Maha Esa. Keesaan itu mencakup keesaan dzāt, keesaan sifat, keesaan perbuatan, serta keesaan dalam beribadah kepada-Nya.
Keesaan dzāt mengandung pengertian bahwa seseorang harus percaya bahwa Allah s.w.t. tidak terdiri dari unsur-unsur atau bagian-bagian. Karena bila dzāt Yang Maha Kuasa itu terdiri dari dua unsur atau lebih – betapapun kecilnya unsur atau bagian itu – maka ini berarti Dia membutuhkan unsur atau bagian itu, atau dengan kata lain unsur (bagian) itu merupakan syarat bagi wujud-Nya dan ini bertentangan dengan sifat Ketuhanan yang tidak membutuhkan suatu apa pun. Benak kita tidak dapat membayangkan Tuhan membutuhkan sesuatu dan al-Qur’ān pun menegaskan demikian yakni bahwa:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهِ وَ اللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ.
“Wahai seluruh manusia, kamulah yang butuh kepada Allah dan Allah Maha Kaya tidak membutuhkan sesuatu lagi Maha Terpuji.” (QS. Fāthir [35]: 15).
Keesaan shifāt antara lain berarti bahwa Allah memiliki sifat yang tidak sama dalam substansi dan kapasitas-Nya dengan sifat makhluk, walaupun dari segi bahasa kata yang digunakan menunjuk sifat tersebut sama. Sebagai contoh, kata Raḥīm merupakan sifat bagi Allah, tetapi juga digunakan untuk menunjuk rahmat/kasih-sayang makhluk. Namun, substansi dan kapasitas rahmat dan kasih-sayang Allah berbeda dengan rahmat makhluk-Nya. Allah Maha Esa di dalam sifatnya, sehingga tidak ada yang menyamai substansi dan kapasitas sifat tersebut.
Sementara ulama memahami lebih jauh keesaan sifat-Nya itu dalam arti bahwa dzāt-Nya sendiri merupakan sifat-Nya. Demikian mereka memahami keesaan secara amat murni. Mereka menolak adanya “sifat” bagi Allah, walaupun mereka tetap yakin dan percaya bahwa Allah Maha Mengetahui, Maha Pengampun, Maha Penyantun, dan lain-lain yang secara umum dikenal ada 99 itu. Mereka yakin tentang hal tersebut, tetapi mereka menolak menamainya sifat-sifat. Lebih jauh penganut paham ini berpendapat bahwa “sifat-Nya” merupakan satu kesatuan sehingga kalau dengan Tauḥīd Dzāt dinafikan adanya unsur keterbilangan pada dzāt-Nya, betapapun kecilnya unsur itu, dengan Tauḥīd Shifāt dinafikan segala macam dan bentuk ketersusunan dan keterbilangan bagi sifat-sifat Allah.
Keesaan dalam perbuatan mengandung arti bahwa segala sesuatu yang berada di alam raya ini, baik sistem kerjanya maupun sebab dan wujudnya, kesemuanya adalah hasil perbuatan Allah semata. “Apa yang dikehendaki-Nya terjadi dan apa yang tidak dikehendaki-Nya tidak akan terjadi, tidak ada daya (untuk memperoleh manfaat), tidak pula kekuatan (untuk menolak mudharat) kecuali bersumber dari Allah.” Tetapi, ini bukan berarti bahwa Allah berlaku sewenang-wenang atau “bekerja” tanpa sistem. Keesaan perbuatan-Nya dikaitkan dengan hukum-hukum atau taqdir dan sunnatullah yang ditetapkan-Nya.
Ketiga keesaan di atas merupakan hal-hal yang harus diketahui dan diyakini.
Keesaan beribadah secara tulus kepada-Nya yang merupakan keesaan keempat ini merupakan perwujudan dari ketiga makna keesaan terdahulu.
Ibadah beraneka ragam dan bertingkat-tingkat. Salah satu ragamnya yang paling jelas adalah amalan tertentu yang ditetapkan cara dan atau kadarnya langsung oleh Allah atau melalui Rasūl-Nya, dan yang secara populer dikenal dengan istilah ibadah mahdhah (murni).
Ibadah dalam pengertiannya yang umum mencakup segala macam aktivitas yang dilakukan demi karena Allah. Nah, mengesakan Tuhan dalam beribadah menuntut manusia untuk melaksanakan segala sesuatu demi karena Allah, baik sesuatu itu dalam bentuk ibadah mahdhah maupun selainnya. Alhasil, keesaan Allah dalam beribadah adalah dengan melaksanakan apa yang tergambar dalam firman-Nya:
قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَ نُسُكِيْ وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِيْ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.
“Katakanlah, sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku, kesemuanya demi karena Allah, Pemelihara seluruh alam.” (QS. al-An‘ām [6]: 162).