Surah al-Haqqah 69 ~ Tafsir al-Mishbah (4/6)
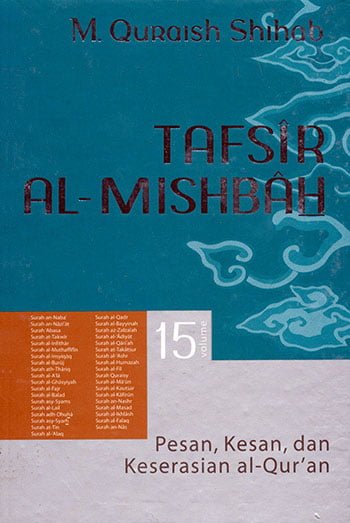
Tafsir al-Mishbāḥ
(Jilid ke-15, Juz ‘Amma)
Oleh: M. Quraish Shihab
Penerbit: Penerbit Lentera Hati
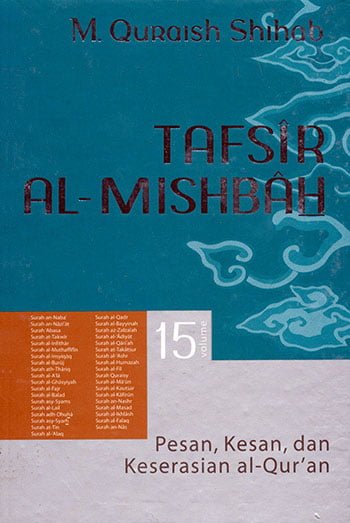
Tafsir al-Mishbāḥ
(Jilid ke-15, Juz ‘Amma)
Oleh: M. Quraish Shihab
Penerbit: Penerbit Lentera Hati
AYAT 25-29.
“Adapun yang diberikan kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata: “Wahai, alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku dan aku tidak mengetahui apa hisabku. Wahai, kiranya dia yang menjadi pemutus. Tidaklah berguna bagiku hartaku. Telah hilang (binasa) kekuasaanku dariku.”
Setelah ayat-ayat yang lalu menjelaskan keadaan orang-orang yang taat kepada Allah, kini ayat-ayat di atas berbicara tentang orang-orang yang durhaka. Seperti diketahui, telah merupakan kebiasaan al-Qur’ān menyandingkan sesuatu dengan lawannya agar menjadi bahan perbandingan oleh mitra bicara dan pendengarnya.
Ayat-ayat di atas menyatakan: Adapun orang yang diberikan kepadanya kitab ‘amal-nya dari sebelah kirinya, maka dia berkata dengan penuh penyesalan setelah menyadari kesengsaraan dan siksa yang akan dihadapinya: “Wahai, alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitab ‘amal-ku ini. Dan alangkah baiknya jika aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diri-ku. Wahai, kiranya dia, ya‘ni kematian, yang telah kualami di dunia itulah yang menjadi pemutus, ya‘ni yang menyelesaikan hidupku, sehingga aku tidak menghadapi segala sesuatu apalagi siksa ukhrawi ini. Tidaklah berguna untuk suatu apa pun bagiku hartaku yang dahulu kukumpul dan tidak aku tunaikan haknya. Telah hilang binasa kekuasaanku dariku ya‘ni kekuasaan yang pernah kugunakan untuk menindas manusia di dunia kini telah tiada dan kini aku menjadi hina tanpa kuasa.”
Kalimat (مَا أَغْنَى عَنِّيْ مَالِيَهْ.) mā aghnā ‘annī māliyah ada juga yang memahaminya dalam arti pertanyaan yang mengandung penyesalan. Ya‘ni, apa (lagi) yang berguna dari hartaku? Tidak ada darinya yang dapat kugunakan untuk meraih sedikit manfaat pun.
Al-Qur’ān tidak menggunakan kata (مَال) māl harta yang dinisbahkan kepada tunggal persona pertama kecuali sekali, yaitu pada ayat 28 di atas. Ini mengisyaratkan bahwa siapa yang menjadikan harta yang berada dalam genggaman tangannya sebagai milik pribadi – tidak melakukan fungsi sosialnya – maka yang bersangkutan akan mengalami nasib seperti yang diuraikan oleh ayat di atas. Al-Qur’ān juga tidak menggunakan kata harta dalam bentuk tunggal persona ketiga (māluhu) kecual enam kali, lima di antaranya dalam konteks kecaman dan hanya sekali pujian, ya‘ni terhadap siapa yang menyerahkan secara tulus hartanya itu kepada yang butuh (baca QS. al-Lail [92]: 17-18).
Kalimat (هَلَكَ عَنِّيْ سُلْطَانِيَهْ) halaka ‘annī sulthāniyah ada juga yang memahaminya dalam arti hilang dan binasalah aneka dalih yang pernah digunakan untuk membendung kebenaran atau meraih manfaat duniawi.
AYAT 30-32.
“Ambillah dia lalu belenggulah dia. Kemudian, ke dalam Jaḥīm masukkanlah dia. Kemudian, di dalam rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta masukkanlah dia.”
Setelah ayat-ayat yang lalu menjelaskan keadaan para pendurhaka ketika menerima kitab ‘amalannya, ayat-ayat di atas menjelaskan apa yang akan mereka alami setelah penyerahan kitab ‘amalan itu. Seakan-akan ada yang bertanya apa yang terjadi pada yang bersangkutan setelah menyampaikan keluhan dan penyesalannya itu. Ayat di atas menjawab bahwa Allah berfirman memerintahkan malaikat-malaikat yang bertugas menyiksa bahwa: Ambillah, ya‘ni pegang dan tangkap, dia lalu belenggulah dia, ya‘ni ikatlah tangannya ke lehernya. Kemudian, lakukan yang lebih buruk lagi yaitu ke dalam Jaḥīm, ya‘ni tingkat tertentu dari neraka – jangan pada tingkat lainnya – masukkanlah dia atau berulang-ulanglah memanggang dia di sana.” Kemudian, dikatakan juga kepada para malaikat itu setelah mereka memasukkannya ke dalam neraka bahwa: “Di dalam rantai sangat besar dan yang panjangnya tujuh puluh hasta, ya‘ni sangat panjang, masukkanlah ya‘ni belitlah, dia atau masukkanlah dia sebagaimana tali masuk di lubang yang kecil.”
Kata (سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا) sab‘ūna dzirā‘an/tujuh puluh hasta dipahami dalam arti rantai yang panjang. Anda jangan duga bahwa rantai itu terulur sedemikian rupa sehingga yang bersangkutan memiliki sedikit kebebasan bergerak. Tidak! Rantainya berat dan lilitannya berulang-ulang akibat panjangnya rantai. Informasi ini mengisyaratkan bahwa yang bersangkutan tidak mati akibat siksaan api itu sehingga terbebaskan dari siksa. Dia tetap hidup, berusaha melepaskan diri dan menghindar, buktinya bahwa dia dibelenggu. Seandainya dia mati, tentu tidak perlu lagi dia dibelenggu.
AYAT 33-37.
“Sesungguhnya dahulu dia tidak beriman kepada Allah Yang Maha Agung dan tidak mendorong untuk memberi makanan (nya) orang miskin. Maka, tiada baginya pada hari ini di sini seorang teman. Dan tiada makanan sedikit pun kecuali berupa ghislīn. Tidak ada yang memakannya kecuali para pendosa.”
Setelah ayat-ayat yang lalu menggambarkan siksa yang akan dialami oleh para pendurhaka, ayat-ayat di atas menjelaskan kedurhakaan yang menjadi sebab utama penyiksaan itu. Allah berfirman: Sesungguhnya dahulu ketika hidup di dunia dia tidak beriman kepada Allah Yang Maha Agung dan tidak juga dia mendorong dirinya dan orang lain untuk memberi makanan (nya) orang miskin. Maka, tiada baginya pada hari ini ya‘ni di akhirat, dan di sini, ya‘ni di neraka, seorang teman atau karib yang dapat menolong atau meringankan siksanya. Dan tiada baginya makanan sedikit pun kecuali makanan berupa ghislīn, ya‘ni darah dan nanah penghuni neraka atau sejenis pohon yang tumbuh di sana. Tidak ada yang memakannya kecuali para pendosa yang senantiasa secara mantap terus-menerus melakukan dosa.
Kata (يَحُضُّ) yaḥudhudhu/mendorong. Penggunaan kata ini di sini, mengisyaratkan bahwa seseorang hendaknya, walalupun dia tidak memiliki sesuatu untuk diberikannya kepada fakir miskin, paling tidak dia harus berupaya untuk mendorong dan menganjurkan orang lain menutupi kebutuhan pokok kaum lemah.
Kalimat (طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ.) tha‘am-il-miskin/makanan(nya) orang miskin mengisyaratkan bahwa fakir miskin pada hakikatnya memiliki makanannya yang merupakan haknya, hanya saja makanan tersebut tidak berada di tangannya, tetapi di tangan orang yang berpunya. Siapa pun yang mampu berkewajiban menyerahkan makanan orang miskin itu yang dititipkan Allah ke tangan mereka. Yang tidak memiliki kemampuan berkewajiban mengingatkan yang mampu menyangkut hak orang miskin itu. Selanjutnya, kalimat itu berpesan kepada siapa pun yang memberi agar tidak menduga pemberiannya itu merupakan “sumbangan” darinya, tetapi itu adalah pengembalian hak kepada pemiliknya.
Kata (غِسْلِيْنٍ.) ghislīn terambil dari kata (غَسَالَةٌ) ghasālah. Sementara ‘ulamā’ berpendapat bahwa ia terambil dari kata ghasala yang berarti mencuci. Atas dasar itu, mereka berpendapat bahwa yang dimaksud adalah cairan yang keluar dari luka apabila luka itu dibersihkan atau dicuci. Cairan itu biasanya bercampur nanah. Al-Biqā‘ī memperoleh kesan bahwa tentulah yang disiksa itu berada pada posisi yang lebih rendah daripada penghuni neraka lainnya yang dicuci lukanya itu karena, kalau tidak, bagaimana cairan tersebut mengalir? Bukankah cairan selalu mencari tempat yang lebih rendah? Ayat ini tidak harus dipertentangkan dengan ayat-ayat yang lain misalnya yang menyebut bahwa makanan penghuni neraka adalah (ضَرِيْعٌ) dharī‘ (al-Ghāsyiyah [88]: 6) atau zaqqūm (QS. ad-Dukhān [44]: 43-44) atau lainnya karena bisa saja siksa tersebut bertingkat-tingkat, ada pendurhakan yang ma‘na ini dan ada juga yang itu.
Kata (الْخَاطِؤُوْنَ) al-khāthi’ūn terambil dari kata (الْخِطْئُ) al-khith’ (dengan kasrah pada huruf khā’), ya‘ni dosa. Ia berbeda dengan (الْمُخْطِئُوْنَ) al-mukhthi’ūn yang terambil dari kata (الْخَطَأُ) al-khatha’ (dengan fatḥah pada huruf khā’ yang berarti keliru). Kekeliruan terjadi karena tidak tahu, lupa, atau tidak sengaja. Sedang, dosa adalah pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja. Al-khāthi’ūn adalah orang-orang yang dengan sengaja lagi berulang-ulang melakukan dosa sehingga dosa telah menjadi ciri kepribadiannya.