Suratu ‘Abasa 80 ~ Tafsir Sayyid Quthb (3/4)
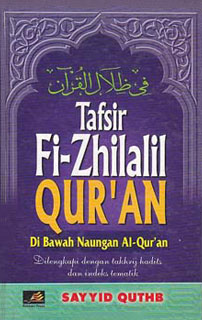
Tafsīr fi Zhilāl-il-Qur’ān
Oleh: Sayyid Quthb Penerbit: Gema Insani
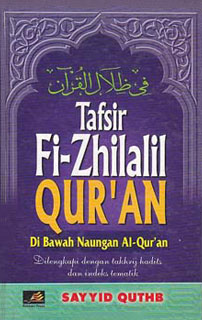
Ḥudzaifah r.a. mengatakan bahwa Rasūlullāh s.a.w. bersabda:
إِنِّيْ لَا أَدْرِيْ مَا بَقَائِيْ فِيْكُمْ، فَاقْتَدُوْا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِيْ – وَ أَشَارَ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ وَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا – وَ اهْتَدُوْا بِهَدْيِ عَمَّارٍ. وَ مَا حَدَّثَكُمُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَصَدِّقُوْهُ.
“Aku tidak mengetahui berapa lama lagi aku tinggal di antara kamu. Karena itu, ikutilah dua orang sesudahku nanti (beliau berisyārat kepada Abū Bakar dan ‘Umar r.a.) dan ikutilah petunjuk ‘Ammār. Apa yang dikatakan Ibnu Mas‘ūd kepadamu, maka percayailah.” (H.R. at-Tirmidzī).
Ibnu Mas‘ūd dikira keluarga Rasūlullāh s.a.w. oleh orang luar Madīnah. Dalam riwayat Bukhārī, Muslim, dan at-Tirmidzī, disebutkan bahwa Abū Mūsā r.a. berkata: “Aku datang dari Yaman bersama saudaraku, kemudian kami tinggal di sana beberapa lama. Maka, kami tidak menganggap Ibnu Mas‘ūd dan ibunya melainkan dari keluarga Rasūlullāh s.a.w. karena seringnya mereka masuk menemui Rasūlullāh s.a.w. dan berada di sana.”
Aḥmad dalam Musnad-nya meriwayatkan bahwa Anas r.a. berkata: “Ketika Rasūlullāh s.a.w. meminang seorang wanita untuk dikawinkan dengan Julaibib, seorang laki-laki mantan budak, maka kedua orang tua anak wanita itu berkata: “Apakah kalian hendak menolak urusan Rasūlullāh s.a.w.? Jika beliau telah merelakannya untuk kalian, maka kawinkanlah dia.” Kedua orang tua wanita itu lantas merelakan, kemudian dikawinkannyalah wanita itu dengan lelaki tersebut.”
Tidak lama setelah perkawinannya itu Rasūlullāh s.a.w. kehilangan Julaibib dalam suatu peperangan karena gugur sebagai syahid. Muslim meriwayatkan bahwa Abū Burzah al-Aslamī r.a. berkata: Rasūlullāh s.a.w. berada dalam suatu peperangan, lalu Allah memberikan rampasan atas kemenangan ini. Kemudian beliau berkata kepada para sahabat: “Apakah kamu kehilangan seseorang?” Mereka menjawab: “Ya, si fulan, si fulan, dan si fulan.” Kemudian bertanya lagi: “Apakah kamu kehilangan seseorang?” Mereka menjawab: “Ya, si fulan, si fulan, dan si fulan.” Kemudian beliau bertanya lagi: “Apakah kamu kehilangan seseorang?” Mereka menjawab: “Tidak.” Lalu beliau bersabda: “Akan tetapi, saya kehilangan Julaibib.”
Mereka lalu mencarinya, dan mereka mendapati Julaibib berada di sisi tujuh orang (musuh) yang telah dibunuhnya. Kemudian Nabi s.a.w. datang dan berdiri di sampingnya, lalu bersabda: “Ia telah membunuh tujuh orang, lalu mereka membunuhnya. Dia ini bagian dariku dan aku bagian darinya.” Kemudian beliau meletakkannya di atas kedua lengan beliau tanpa alas kecuali kedua lengan beliau itu. Kemudian digalikan lubang, lalu beliau memasukkannya ke dalam kuburnya, dan tidak menyebut-nyebut mandi.”
Dengan pengarahan Ilahi dan petunjuk nabawi ini, terjadilah kelahiran baru bagi kemanusiaan dengan cara yang unik ini, dan lahirlah masyarakat Rabbānī (yang patuh kepada Tuhan) yang menerima tata nilai dan tata normanya dari langit, yang lepas dari ikatan-ikatan bumi, meskipun mereka sendiri hidup di atas bumi. Ini merupakan mu‘jizat yang sangat besar bagi Islam. Mu‘jizat yang tidak akan terwujud kecuali dengan iradah Ilahi, dan dengan ‘amal Rasūlullāh s.a.w. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa agama Islam berasal dari sisi Allah dan yang membawanya kepada manusia adalah seorang rasūl.
Di antara skenario Allah dalam mengatur urusan ini adalah diserahkannya tongkat estafet tugas dakwah ini sepeninggal Rasūlullāh s.a.w. kepada sahabat pertama beliau Abū Bakar dan sahabat kedua ‘Umar. Dua orang manusia yang lebih mengerti tabiat urusan ini, yang intens penghayatannya terhadap petunjuk Rasūlullāh s.a.w., yang paling dalam kecintaannya kepada Rasūlullāh s.a.w., dan yang paling antusias mengimplementasikan kecintaannya dan mengikuti jejak langkah beliau.
Abū Bakar r.a. selalu menjaga apa yang dikehendaki oleh sahabatnya, Rasūlullāh s.a.w. mengenai Usāmah. Maka, tindakan pertama yang dilakukannya setelah dia diangkat menjadi khalīfah ialah melaksanakan penugasan Usāmah untuk menjadi pemimpin pasukan sebagaimana yang sudah disiapkan Rasūlullāh s.a.w. Usāmah naik kendaraan, sedang Abū Bakar yang khalīfah itu berjalan kaki. Maka, Usāmah yang masih muda belia itu merasa malu naik kendaraan sedangkan khalīfah berjalan kaki, lalu dia berkata: “Wahai khalīfah Rasūlullāh, silakan engkau naik dan saya akan turun.” Tetapi, Khalīfah Abū Bakar menjawab dengan bersumpah: “Demi Allah, engkau tidak boleh turun, dan demi Allah aku tidak akan naik. Apakah kerugianku seandainya kakiku berlumuran debu di jalan Allah barang sesaat?”
Kemudian Abū Bakar merasa mempunyai keperluan kepada ‘Umar, karena memikul tugas kekhalīfahan yang berat itu. Akan tetapi, ‘Umar hanya seorang anggota pasukan Usāmah, sedang Usāmah adalah komandan. Karena itu, ia meminta idzin kepada Usāmah. Tiba-tiba Khalīfah Abū Bakar berkata: “Jika engkau memandang perlu membantuku dengan ‘Umar, silakan.” Ya Allah, sungguh luar biasa. Khalīfah Abū Bakar berkata kepada Usāmah: “Jika engkau memandang perlu membantuku dengan ‘Umar, silakan.” Sungguh sangat luas cakrawala hati dan pikiran Abū Bakar. Sungguh ini adalah ufuk tinggi yang tidak mungkin dicapai oleh manusia kecuali dengan iradah dan bimbingan dari Allah, di bawah bimbingan tangan Rasūlullāh.
Kemudian roda zaman pun terus berputar. Maka, kita lihat ‘Umar ibn-ul-Khaththāb yang menjadi khalīfah (kedua) itu mengangkat ‘Ammār bin Yāsir menjadi gubernur di Kūfah.
Di depan pintu ‘Umar, telah berdiri Suhail bin ‘Amr bin al-Ḥārits bin Hisyām, Abū Sufyān bin Ḥarb, dan sejumlah pembesar Quraisy. Akan tetapi, ‘Umar terlebih dahulu mengidzinkan Suhaib dan Bilāl untuk masuk, karena mereka termasuk orang yang terdahulu memeluk Islam dan termasuk peserta Perang Badar. Maka, tersenyumlah Abū Sufyān, dan ia berkata dengan sensitivitas jahiliah: “Selama ini aku belum pernah melihat kejadian seperti hari ini, di mana budak-budak itu diidzinkan masuk sedangkan kami dibiarkan menunggu di depan pintu.”
Kemudian sahabatnya yang telah merasakan kebenaran Islam, berkata: “Wahai kaum, demi Allah, sesungguhnya saya melihat gejolak yang terjadi pada wajah kalian. Jika kalian marah, maka marahlah kepada diri kalian. Masyarakat telah diseru untuk memeluk Islam, demikian juga kalian, maka mereka segera memeluk Islam sedang kalian enggan melakukannya. Maka bagaimana keadaan kalian apabila mereka telah dipanggil pada hari kiamat sedang kalian dibiarkan saja?” (21)
Dalam riwayat at-Tirmidzī, disebutkan bahwa ‘Umar memberikan bagian kepada Usāmah bin Zaid lebih besar daripada bagian ‘Abdullāh bin ‘Umar, sehingga ‘Abdullāh menanyakan kepada ‘Umar tentang sebab tindakannya itu. Maka, ‘Umar berkata kepadanya: “Wahai anakku, Zaid itu lebih dicintai oleh Rasūlullāh s.a.w. daripada ayahmu, dan Usāmah lebih dicintai Rasūlullāh daripada engkau. Oleh karena itu, aku lebih mengutamakan orang yang dicintai Rasūlullāh dari orang yang kucintai.”
‘Umar mengucapkan perkataan ini karena ia mengetahui bahwa kecintaan Rasūlullāh s.a.w. itu menjadi ukuran timbangan langit.
‘Umar pernah menugaskan ‘Ammār untuk memeriksa Khālid ibn-ul-Walīd, seorang panglima perang yang selalu mendapatkan kemenangan yang gemilang dan memiliki nasab yang terhormat (di kalangan kaumnya). Lalu, ‘Ammār mengikatnya dengan selendangnya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa ‘Ammār mengikatnya dengan kain surbannya hingga selesai pemeriksaan. Maka, setelah terbukti bahwa Khālid tidak bersalah, ‘Ammār lantas melepaskan ikatan itu dengan tangannya. Khālid tidak menganggap apa-apa terhadap semua tindakan ‘Ammār ini. Hal itu karena Khālid (tahu bahwa ‘Ammār) adalah seorang sahabat yang lebih dahulu memeluk Islam sebagaimana dikatakan oleh Rasūlullāh s.a.w.
‘Umar pulalah yang berkata tentang Abū Bakar r.a.: “Dia adalah tuan kita yang telah memerdekakan tuan kita pula ya‘ni Bilāl, yang dahulu adalah budak Umayyah bin Khalaf. Bilāl disiksa dengan siksaan yang pedih, hingga ia dibeli oleh Abū Bakar dan dimerdekakannya.” ‘Umar menyebut Bilāl ini dengan sayyidinā” “tuan kita”.
‘Umar pula yang berkata: “Seandainya Sālim mantan budak Ḥudzaifah itu masih hidup, niscaya kujadikan dia penggantiku.” Ia menggantikannya kepada ‘Utsmān, ‘Alī, Thalḥah, dan az-Zubair. ‘Umar tidak mengangkat seorang pun untuk menggantikannya menjadi khalīfah, tetapi hal itu diserahkan kepada hasil musyāwarah enam orang (formatur) sepeninggalnya.
Dalam riwayat Bukhārī disebutkan bahwa ‘Alī bin Abī Thālib mengutus ‘Ammār dan Ḥasan bin ‘Alī r.a. kepada penduduk Kūfah untuk meminta bantuan kepada mereka mengenai urusan yang terjadi antara dia dan ‘Ā’isyah r.a. Lalu, ‘Ammār berkata: “Sesungguhnya aku mengetahui bahwa ia (‘Ā’isyah) adalah istri Nabi kamu s.a.w. di dunia dan di akhirat. Hanya saja Allah menguji kamu untuk mengikuti ‘Alī atau mengikuti ‘Ā’isyah.” Maka, orang-orang pun mendengarkannya mengenai urusan ‘Ā’isyah Umm-ul-Mu’minīn dan putri Abū Bakar ash-Shiddīq r.a.
Bilāl bin Rabāḥ diminta oleh saudaranya sesama muslim Abū Ruwaihah al-Khats‘amī untuk menjadi mediator dalam perkawinannya dengan orang Yaman, lalu Bilāl berkata kepada mereka: “Aku adalah Bilāl bin Rabāḥ, dan ini saudaraku Abū Ruwaihah. Ia seorang lelaki yang jelek akhlāq dan agamanya. Jika anda mau mengawinkan dia, silakan mengawinkannya; dan jika hendak meninggalkannya, silakan tinggalkan.”
Bilāl tidak memanipulasi dan menutup-nutupi kekurangan saudaranya itu. Ia tidak menyebut dirinya sebagai mediator dan tidak melupakan bahwa dirinya akan ditanya di hadapan Allah tentang apa yang dikatakannya. Maka mereka merasa tenteram dengan kejujurannya itu, dan mereka kawinkan saudara Bilāl ini. Mereka merasa tersanjung, padahal mereka dari kalangan bangsawan ‘Arab, karena Bilāl yang mantan budak ini menjadi mediatornya.
Hakikat besar itu telah mantap di kalangan masyarakat Islam, dan sesudah itu ia tetap mantap dalam masa yang panjang meskipun banyak keburukan. “ ‘Abdullāh bin ‘Abbās sangat populer, demikian pula mantan budaknya, ‘Ikrimah. ‘Abdullāh Ibnu ‘Umar juga sangat populer, demikian pula mantan budaknya, Nāfi‘. Begitu juga Anas bin Mālik dan mantan budaknya, Ibnu Sīrīn. Abū Hurairah bersama mantan budaknya, ‘Abd-ur-Raḥmān bin Hurmūz. Di Bashrah terdapat al-Ḥasan al-Bashrī, di Makkah terdapat Mujāhid bin Jabar, ‘Athā’ bin Rabāḥ, dan Thāwūs bin Kīsān sebagai fuqahā’-fuqahā’ ternama. Di Mesir yang memiliki wewenang memberi fatwa adalah Yazīd bin Abī Ḥabīb, pada masa pemerintahan ‘Umar bin ‘Abd-il-‘Azīz, padahal Yazīd ini adalah mantan budak Aswad dari Danqilah.” (32).
Timbangan langit menguatkan ahli taqwā, meskipun mereka terlepas dari nilai-nilai (kedudukan) bumi (duniawi) menurut anggapan mereka sendiri dan menurut orang-orang di sekitar mereka. Timbangan ini tidak pernah naik dari bumi kecuali hanya sebentar sesudah kejahiliahan merajalela di seluruh penjuru dunia, dan orang-orang mengintai dolar Amerika yang menjadi pemimpin negara-negara Barat, serta seluruh manusia tidak lebih dari sekadar alat dalam madzhab materialisme yang dominan di Rusia sebagai pemimpin bangsa-bangsa Timur. Sedangkan, tanah air kaum Muslimīn sendiri sudah dikuasai oleh kejahiliahan kuno yang dulu Islam datang untuk menghapuskan dan menghancurkannya, dan dalam beberapa masa Islam memang dapat melibasnya. Tata nilai Ilahi sudah dihancurkan, dan mereka kembali kepada nilai-nilai jahiliah yang tidak berharga dan tidak ada hubungan sama sekali dengan iman dan taqwā.
Nah, di sana tidak ada sesuatu lagi kecuali harapan terhadap dakwah Islam untuk menyelamatkan kemanusiaan pada kali lain dari kejahiliahan. Juga untuk membidani lahirnya kembali kemanusiaan seperti kelahirannya yang sudah disaksikannya pada kali pertama. Ya‘ni, kelahiran pertama yang untuk itu datanglah peristiwa yang diceritakan oleh bermulaan surah ini, untuk diumumkan lewat ayat-ayat yang sedikit jumlahnya, penuh kepastian, dan agung ini.
Setelah menetapkan hakikat yang besar di tengah-tengah komentarnya terhadap peristiwa tersebut pada segmen pertama surah ini, maka ayat-ayat berikutnya pada segmen kedua ini menunjukkan keheranan terhadap sikap orang-orang yang berpaling dari petunjuk, tidak mau beriman, dan menyombongi dakwah ke jalan Tuhannya. Segmen ini menunjukkan keheranan terhadap sikap orang itu dan kekafirannya, yang tidak mau mengingat sumber keberadaannya dan asal-usul kejadiannya. Juga yang tidak mau memperhatikan pemeliharaan dan perlindungan Allah kepada dirinya dalam setiap tahapan pertumbunhan dan perkembangan dirinya sejak pertama hingga terakhir, dan tidak mau menunaikan kewajibannya terhadap Penciptanya, Penjaminnya, dan Penghisabnya:
قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ. مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ. مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ. ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهُ. ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ. ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ. كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ.
“Binasalah manusia; alangkah amat sangat kekafirannya? Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya. Kemudian Dia memudahkan jalannya. Lalu Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur, Apabila Dia menghendaki, Dia membangkitkannya kembali. Sekali-kali jangan; manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya.” (‘Abasa: 17-23).
“Binasalah manusia!” Karena dia benar-benar layak mendapatkan kebinasaan dan kecelakaan, karena tindakan dan sikapnya yang mengherankan itu. Perkataan ini adalah untuk menjelek-jelekkan dan mencela dengan keras sikapnya, dan untuk menunjukkan bahwa dia melakukan sesuatu yang pantas mendapatkan kebinasaan karena buruk dan jeleknya apa yang dilakukannya itu.
“Alangkah amat sangat kekafirannya?” (‘Abasa: 17).
Alangkah kafir dan ingkarnya dia terhadap masalah kejadian dan penciptaan dirinya. Kalau dia mau memikirkan masalah-masalah ini, niscaya dia akan bersyukur kepada Penciptanya, akan tawādhu‘ di dalam urusan dunianya, dan akan sadar terhadap akhiratnya.
Nah, kalau tidak begitu, maka mengapakah dia sombong, congkak, dan berpaling? Siapakah dan apakah dia itu? Dari mana asalnya, dan apa bahan penciptaan dirinya?
“Dari apakah Allah menciptakannya?” (‘Abasa: 18).
Ia berasal dari sesuatu yang hina dan tak berharga. Kemudian nilainya menjadi meningkat karena karunia, ni‘mat, penentuan, dan pengaturan-Nya:
“Dari setetes mani, Allah menciptakan dan menentukannya.” (‘Abasa: 19).
Dari sesuatu yang tidak ada harganya sama sekali, dari bahan pokok yang tidak ada nilainya. Akan tetapi, Penciptanyalah yang menentukannya dengan menciptakan dan mengaturnya. Dia menentukannya dengan memberinya harga dan nilai, menjadikannya makhlūq yang sempurna, dan menjadikannya makhlūq yang mulia, serta mengangkatnya dari asal-usul yang hina dan rendah ke tempat dan kedudukan tinggi yang untuknyalah bumi dengan segala sesuatunya diciptakan:
“Kemudian Dia memudahkan jalannya.” (‘Abasa: 20).
Direntangkan untuknya jalan kehidupan, atau dibentangkan untuknya jalan petunjuk, dan dimudahkan baginya untuk menempuhnya dengan peralatan-peralatan dan potensi-potensi yang diberikan-Nya, baik untuk menempuh kehidupan maupun menempuh hidāyah tersebut.
Hingga apabila perjalanan hidup sudah berakhir, maka berkesudahanlah kehidupan dan aktivitasnya sebagaimana yang dialami oleh semua makhlūq hidup, tanpa ada pilihan lain dan tanpa dapat menghindar:
“Kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur.” (‘Abasa: 21).
Maka, urusan kesudahannya ini seperti urusannya dalam permulaannya, berada di tangan Dzāt yang telah mengeluarkannya kepada kehidupan dan menyudahi kehidupannya manakala Dia menghendaki. Juga menjadikan tempat tinggalnya di perut bumi, sebagai penghormatan baginya dan untuk memeliharanya. Dia tidak menyunnahkan untuk memeliharanya. Dia tidak menyunnahkan untuk membiarkan tubuhnya dan anggota-anggotanya berserakan di muka bumi. Bahkan, Dia menjadikan insting manusia berkeinginan menutup dan mengubur mayat. Maka, semua itu termasuk pengaturan dan penataan-Nya.
Sehingga, apabila telah tiba waktu yang dikehendaki-Nya, maka dikembalikanlah manusia itu kepada kehidupan untuk menghadapi urusan yang dikehendaki-Nya:
“Kemudian bila Dia menghendaki, Dia membangkitkannya kembali.” (‘Abasa: 22).