Suratu ‘Abasa 80 ~ Tafsir Sayyid Quthb (2/4)
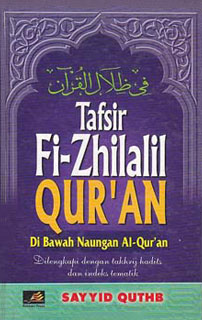
Tafsīr fi Zhilāl-il-Qur’ān
Oleh: Sayyid Quthb Penerbit: Gema Insani
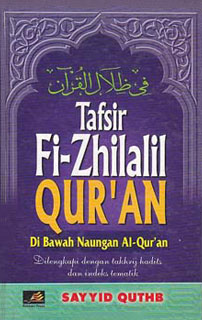
Datanglah celaan dari Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Luhur kepada Nabi-Nya yang mulia, pemilik akhlāq yang luhur, dengan uslub yang keras dan tegas. Hanya satu kali ini saja di dalam seluruh al-Qur’ān dikatakan kepada Rasūl tercinta dan dekat dengan Allah perkata: (كَلَّا) “sekali-kali jangan demikian”, yaitu perkataan untuk membentak. Hal itu disebabkan besarnya urusan yang menjadi bertumpunya agama ini.
Uslub yang dipergunakan al-Qur’ān di dalam menyampaikan celaan Ilahi ini merupakan uslub yang unik, yang tidak mungkin dapat diterjemahkan ke dalam bahasa tulis manusia. Karena, bahasa tulis itu memiliki ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan tradisi-tradisi, yang menurunkan suhu pengarahan dalam bentuknya yang hidup secara langsung. Uslub Qur’āni ini juga unik dengan kemampuan pemaparannya dalam bentuk ini dalam sentuhan-sentuhan sekilas, kalimat-kalimat yang terputus-putus, dan ungkapan-ungkapan yang seakan-akan berupa kesan-kesan, dengan intonasi-intonasi, sifat-sifat, dan kilasan-kilasan yang hidup.
“Dia bermasam muka dan berpaling, karena telah datang seorang tunanetra kepadanya.” (‘Abasa: 1-2).
Ayat ini menggunakan bentuk cerita tentang orang ketiga yang bukan lawan bicara. Di dalam uslub “metode” ini terdapat isyārat yang mengesankan bahwa persoalan ini menjadi topik pembicaraan yang disertai ketidaksenangan di sisi Allah. Dia tidak suka mengarahkan secara langsung perkataan ini kepada Nabi-Nya dan kekasih-Nya, karena kasih-sayangnya dan untuk menghormatinya. Sehingga, tidak diucapkan langsung sesuatu yang tidak menyenangkan ini kepadanya.
Kemudian diputarlah pernyataan ini, sesudah ditutupnya perbuatan yang menyebabkan datangnya celaan ini, kepada celaan kepada lawan bicara. Maka, dimulailah celaan ini dengan sedikit tenang:
“Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa), atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya?” (‘Abasa: 3-4).
Tahukah kamu, barangkali akan terealisir kebaikan yang besar ini? Yaitu, lelaki tunanetra yang fakir – yang datang kepadamu karena mengharapkan kebaikan dari sisimu – ini ingin meembersihkan dirinya, menyadarkan hatinya, dan mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu bermanfaat baginya? Tahukah kamu barangkali hatinya akan bersinar dengan secercah cahaya dari Allah, karena tidak mungkin mercusuar di bumi menerima cahaya langit? Ini adalah suatu hal yang dapat terwujud apabila hati sudah terbuka terhadap petunjuk, dan hakikat iman sudah sempurna di dalamnya. Ini adalah persoalan besar dan berat dalam timbangan Allah.
Kemudian intonasi celaannya naik lagi, nadanya keras, dan beralih kepada sikap keheranan terhadap tindakan itu, yang menggantikan celaan:
“Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman). Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), sedang ia takut kepada (Allah), maka kamu mengabaikannya.” (‘Abasa: 5-10).
Tentang orang yang sudah menampakkan ketidakbutuhannya kepada dirimu, agamamu, petunjuk, kebaikan, cahaya, dan kesucian yang ada di sisimu; kamu lanyani dia, perhatikan urusannya, serius untuk menunjukkannya, dan hadapi dia, sedang dia berpaling darimu! “Apakah kerugianmu kalalu dia tidak membersihkan dirinya (beriman)?” Apakah kerugianmu kalau dia tetap di dalam kekotoran dan kejorokannya? Toh kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang dosanya. Kamu tidak dapat ditolong olehnya, dan kamu juga tidak berkewajiban melaksanakan urusannya.
“Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran)” yang datang dengan penuh kepatuhan dan kesadaran: “serta takut (kepada Allah)” dan berusaha menjaga dirinya, “maka kamu mengabaikannya.” Sikap mengabaikan orang yang beriman dan menginginkan kebaikan serta bertaqwā itu, disebut dengan “talahhiy” sebagai sifat yang keras dan kasar.
Kemudian tekanan celaan ditinggikan lagi hingga menjadi bentakan dan gertakan, (كَلَّا) “sekali-kali jangan demkian”. Jangan sekali-kali begitu! Suatu pernyataan yang menarik perhatian dalam hal ini.
Lalu dijelaskanlah hakikat dakwah ini beserta kemuliaan, keagungan, ketinggiannya, dan ketidakbutuhannya kepada seorang pun dan sandaran apa pun. Juga pemfokusan perhatiannya kepada orang yang menginginkan dakwah itu, apa pun kedudukan dan timbangannya dalam timbagan-timbangan dunia:
“Sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya, di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, dan ditinggikan lagi disucikan, di tangan para penulis (malaikat), yang mulia lagi berbakti. (‘Abasa: 1-16).
Peringatan itu sangat mulia kalimat dan lembarannya (kitabnya), ditinggikan, disucikan, dan diserahkan kepada para utusan dari kalangan makhlūq tertinggi untuk menyampaikannya kepada orang-orang pilihan di muka bumi, agar disampaikan lagi kepada umat manusia. Di samping itu para utusan (malaikat) tersebut adalah mulia dan sangat berbakti. Karena itu, peringatan (wahyu Allah) itu adalah mulia dan suci mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengannya, dan sesuatu yang bersentuhan dengannya, dari dekat ataupun jauh. Ia adalah terhormat, tidak pantas digunakan melayani orang-orang yang berpaling dan menampakkan ketidakbutuhannya kepadanya. Maka, peringatan (dakwah, al-Qur’ān) ini hanya untuk orang yang mengenal kemuliaannya dan mencari penyucian diri dengannya.
Inilah timbangan Allah, yang dipergunakan untuk menimbang semua tata nilai dan pemikiran, untuk mengukur manusia dan semua peraturan. Inilah kalimat Allah yang menjadi muara semua perkataan, hukum dan keputusan.
Di manakah dia berada? Kapan? Di Makkah, dakwah dilakukan dengan mengendap-endap, dan jumlah kaum Muslimīn minoritas. Adapun melayani pembesar-pembesar Quraisy yang dilakukan Nabi s.a.w. itu bukan didorong oleh kepentingan pribadi, dan sikap tidak menghiraukan lelaki tunanetra yang fakir itu juga tidak dimotivasi oleh pertimbangan pribadi, melainkan untuk kepentingan dakwah sejak awal hingga akhir. Akan tetapi, dakwah ini sendiri merupakan timbangan dan nilai. Ia datang untuk menetapkan timbangan dan nilai ini di dalam kehidupan manusia. Maka, ia tidak akan menjadi kokoh dan kuat, serta memperoleh kemenangan kecuali dengan ditetapkannya timbangan dan nilai-nilai ini.
Sesungguhnya urusan ini, sebagimana sudah dikemukakan, lebih agung dan lebih kompleks daripada peristiwa personal dan persoalan langsungnya. Akan tetapi, ia hendak menyampaikan kepada manusia timbagan-timbangan dan nilai-nilai serta kalimat-kalimat langit, bukan dari bumi. Yaitu: “Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwā”.
Orang yang paling bertaqwā di sisi Allah ialah orang yang berhak mendapatkan perlindungan dan perhatian, meskipun ia lepas dari semua unsur dan pemikiran-pemikiran lain, yang dikenal manusia di bawah tekanan realitas bumi (duniawi) dan kesepakatan-kesepakatan mereka. Nasab (keturunan), kekuatan, harta, dan semua tata nilai tidak ada bobotnya apabila lepas dari iman dan taqwā. Satu-satunya hal yang layak mendapatkan timbangan dan penilaian ialah apabila diperhitungkan dengan perhitungan iman dan taqwa.
Inilah hakikat besar yang menjadi sasaran pengarahan Ilahi yang ditetapkan dalam konteks ini. Pengarahan itu berdasarkan metode al-Qur’ān dalam menjadikan peristiwa personal dan dalam konteks terbatas, sebagai saran untuk menetapkan hakikat yang mutlak dan manhaj yang berlaku.
Jiwa Rasūlullāh s.a.w. sangat terkesan oleh pengarahan dan celaan ini. Ia memperoleh kesan yang kuat dan hangat. Juga termotivasi untuk menetapkan hakikat ini di dalam seluruh kehidupan beliau dan kehidupan masyarakat Islam, dengan menyifatinya sebagai hakikat Islam yang pertama.
Maka, aktivitas pertama yang dilakukan Rasūlullāh s.a.w. ialah mengumumkan pengarahan dan celaan yang turun berkenaan dengan perisitwa tersebut. Pengumuman ini merupakan sesuatu yang besar dan luar biasa serta tidak dapat dilakukan kecuali oleh seorang Rasūlullāh, dari sisi mana pun kita melihatnya.
Ya, tidak ada seorang pun yang mampu kecuali Rasūlullāh untuk mengumumkan kepada manusia bahwa dia dicela demikian keras dengan bentuk yang unik ini karena suatu kekeliruan yang dilakukannya. Cukuplah bagi orang besar mana pun, selain Rasūlullāh, untuk mengakui kesalahan ini dan memperbaikinya pada masa yang akan datang. Akan tetapi, ini adalah persoalan nubuwwah “kenabian”, persoalan yang lain, dan ufuk yang lain pula.
Tidak ada yang mampu selain Rasūlullāh untuk menyampaikan hal ini sedemikian rupa di hadapan pembesar-pembesar Quraisy dalam kondisi seperti itu. Ya‘ni, dalam rangka dakwah terhadap orang-orang yang membangga-banggakan nasab, harta, dan kekuatannya, dalam suatu lingkungan yang tidak ada tempat padanya selain pemikiran-pemikiran ini. Sehingga, pada batas di mana mengenai Muḥammad bin ‘Abdillāh bin ‘Abd-il-Muththalib bin Hāsyim ini mereka mengatakan:
“Mengapa al-Qur’ān ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri (Makkah dan Thā’if) ini?” (az-Zukhruf: 31).
Itulah nasab beliau di antara mereka. Secara pribadi, beliau tidak memiliki kedudukan apa-apa di kalangan mereka sebelum menjadi rasūl.
Kemudian, tidak mungkin hal ini terjadi di lingkungan seperti ini kecuali karena wahyu dari langit. Ia tidak mungkin bersumber dari bumi ini, apalagi pada masa itu.
Ini adalah kekuatan langit yang mendorong urusan seperti itu berjalan di jalannya. Ia tembus dari celah-celah jiwa Rasūlullāh s.a.w. kepada lingkungan di sekitarnya. Kemudian ia menetap padanya secara mendalam, kuat, dan mantap, serta berlaku sepanjang masa di dalam kehidupan umat Islam.
Sungguh ini merupakan kelahiran baru bagi kemanusiaan seperti lahirnya manusia dengan tabiatnya. Adapun yang lebih besar lagi nilainya ialah terbebasnya manusia secara hakiki, dalam perasaan dan realitas, dari semua tata nilai yang sudah dikenal dan diberlakukan di muka bumi. Mereka beralih kepada nilai-nilai lain yang turun dari langit dengan terlepas dari semua tata nilai, pertimbangan-pertimbangan, pandangan, pola pikir, lingkungan kerja, ikatan-ikatan realitas yang memiliki daya tekan yang berat, dan hubungan-hubungan daging, darah, urat saraf, dan perasaan yang ada di bumi.
Kemudian nilai-nilai baru itu dipahami dan diterima oleh semua orang. Maka, berubahlah urusan besar yang untuk menyampaikannya ini jiwa Nabi Muḥammad s.a.w. memerlukan peringatan dan pengarahan. Berubahlah sesuatu yang besar ini menjadi terang-benderang di dalam hati nurani orang Muslim, menjadi syarī‘at masyarakat Islam, dan menjadi hakikat kehidupan yang utama di dalam kehidupan masyarakat Islam sepanjang masa.
Sesungguhnya kita hampir tidak mengerti hakikat kelahiran baru itu. Karena, kita tidak pernah membayangkan di dalam hati kita hakikat keterbebasan dari semua tata nilai, timbangan-timbangan, dan norma-norma serta pemikiran-pemikiran yang dilahirkan oleh tatanan dunia dan hubungan-hubungannya yang memiliki daya tekan yang berat. Sehingga, menimbulkan persepsi sebagian pengikut madzhab “progersif” bahwa salah satu sisi sistem duniawi – yaitu kembalinya manusia beserta ‘aqīdah, kebudayaan, peradaban, perundang-undangan, tradisi, dan pandangannya terhadap kehidupan.
Sungguh apa yang diwahyukan Allah kepada Rasūlullāh ini suatu mu‘jizat kelahiran baru bagi manusia di tangan Islam pada masa itu.
Sejak kelahiran itu dominanlah nilai-nilai yang menyertai peristiwa besar dunia. Akan tetapi, masalahnya tidak ringan dan tidak mudah di lingkungan bangsa ‘Arab, bahkan di dalam jiwa kaum Muslimīn sendiri. Hanya saja Rasūlullāh s.a.w. dengan irādah Allah beserta tindakan-tindakan dan pengarahan-pengarahanNya yang menimbulkan respons yang hangat dari jiwa Rasūlullāh, dapat menanamkan hakikat ini di dalam hati nurani dan di dalam kehidupan. Beliau mampu menjaga dan memeliharanya, hingga akar-akarnya kuat, cabang-cabangnya berkembang, dan menaungi kehidupan umat Islam dalam kurun waktu yang panjang, meskipun golongan-golongan lain menentangnya.
Setelah peristiwa ini, Rasūlullāh s.a.w. senantiasa bersikap lunak kepada Ibnu Ummi Maktūm. Setiap kali berjumpa dengannya, beliau berkata: “Selamat jumpa orang yang karenanya aku dicela oleh Tuhanku.” Bahkan, beliau menjadikannya pengganti beliau dua kali setelah hijrah di Madīnah.
Untuk menggugurkan timbangan-timbangan lingkungan dan tata nilainya yang besumber dari pemikiran dan tradisi-tradisi dunia. Rasūlullāh s.a.w. mengawinkan putri bibi beliau Zainab binti Jaḥsy al-Asadiyyah dengan mantan budak beliau yang bernama Zaid bin Ḥāritsah. Masalah perkawainan dan persemendaan (periparan) merupakan masalah yang sangat sensitif di lingkungan bangsa ‘Arab khususnya.
Sebelumnya, ketika Rasūlullāh s.a.w. saudarakan antarkaum Muslimīn pada masa-masa permulaan hijrah, beliau mempersaudarakan paman beliau Ḥamzah dengan mantan budak beliau Zaid. Juga mempersaudarakan Khālid bin Ruwaihah al-Khats‘amī dengan Bilāl bin Rabāḥ.
Rasūlullāh s.a.w. mengangkat Zaid sebagai panglima Perang Mu’tah, yaitu sebagai panglima pertama disusul dengan Ja‘far bin Abī Thālib dan ‘Abdullāh bin Rawāḥah, untuk memimpin tiga ribu pasukan Muhajirīn dan Anshār, termasuk di antaranya Khālid bin Walīd.
Rasūlullāh s.a.w. sendiri juga keluar mengiringkan mereka. Dalam perang ini, ketiga panglima tersebut gugur sebagai syuhadā’. Mudah-mudahan Allah meridhāi mereka.
Tindakan terakhir yang dilakukan Rasūlullāh s.a.w. ialah mengangkat Usāmah bin Zaid menjadi panglima perang dalam menghadapi pasukan Romawi. Dalam pasukan Islam ini, banyak kalangan Muhājirīn dan Anshār yang ikut. Di antaranya Abū Bakar dan ‘Umar yang merupakan dua orang wazīr dan sahabat Rasūl serta khalīfah sepeninggal beliau berdasarkan kesepakatan kaum Muslimīn. Di antaranya lagi adalah Sa‘ad bin Abī Waqqāsh yang merupakan orang dekat Rasūlullāh s.a.w. dan termasuk golongan Quraisy angkatan pemula yang masuk Islam.
Sebagian orang merasa kurang pas dengan kepemimpinan Usāmah karena masih terlalu muda. Mengenai hal ini, dalam riwayat Bukhārī, Muslim, dan at-Tirmidzī disebutkan bahwa Ibnu ‘Umar r.a. berkata: “Rasūlullāh s.a.w. mengirim satu pasukan di bawah pimpinan Usāmah bin Zaid r.a., maka sebagian orang mencela kepemimpinan Usāmah. Kemudian Rasūlullāh bersabda: “Jika kamu mencela kepemimpinannya, maka sesungguhnya kamu telah mencela kepemimpinan bapaknya sebelumnya. Demi Allah, sesungguhnya dia termasuk orang yang paling saya cintai, sesungguhnya dia termasuk orang yang saya cintai.”
Dalam hadits riwayat ath-Thabrānī dan al-Ḥākim disebutkan bahwa ketika banyak orang berceloteh mengenai Salmān al-Fārisī dan mempersoalkan kebangsaan Persia dan kebangsaan ‘Arab, sesuai dengan hukum nasionalisme yang sempit, maka Rasūlullāh s.a.w. membuat pukulan telak dalam persoalan ini seraya bersabda: “Salmān itu termasuk keluarga kami (Ahl-ul-Bait).”
Maka, dilampauilah dengan sabda beliau ini – dengan nilai-nilai langit dan timbangan-timbangannya – semua dataran nasab yang mereka bangga-banggakan, dan semua batas nasionalisme sempit yang mereka agung-agungkan. Beliau menganggap Salmān (yang bukan berkebangsaan ‘Arab) ini sebagai keluarga beliau.
Ketika terjadi peristiwa antara Abū Dzarr al-Ghiffārī r.a. dan Bilāl bin Rabāḥ r.a. sehingga dari mulut Abū Dzarr terlontar perkataan: “Wahai anak wanita hitam”, maka Rasūlullāh s.a.w. sangat marah terhadap ucapan itu. Beliau mengecam Abū Dzarr dengan keras dan menakutkan dengan sabdanya:
يَا أَبَا ذَرٍّ، طُفَّ الصَّاعُ، لَيْسَ لِابْنِ الْبَيْضَاءِ عَلَى ابْنِ السَّوْدَاء فَضْلٌ.
“Hai Abū Dzarr, telah dikurangi takaran! Tidak ada keutamaan bagi anak wanita yang berkulit putih atas anak wanita yang berkulit hitam!” (H.R. Ibn-ul-Mubārak).
Maka, dibedakanlah urusan ini menurut akarnya yang jauh. Adapun Islam adalah nilai-nilai dan timbangan-timbangan langit, sedangkan jahiliah adalah nilai-nilai dan timbagan-timbangan bumi!
Kalimat nabawiyyah dengan segala kehangatannya ini meresap ke dalam hati Abū Dzarr yang sensitif. Ia sangat terkesan olehnya, dan ia letakkan pipinya ke tanah seraya bersumpah bahwa ia tidak akan mengangkatnya sebelum diinjak oleh Bilāl, untuk menebus perkataannya yang besar implikasinya.
Timbangan yang mengangkat derajat Bilāl ialah timbangan langit. Dalam hadits riwayat Bukhārī dan Muslim, disebutkan bahwa Abū Hurairah r.a. berkata: “Rasūlullāh s.a.w. bersabda:
يَا بِلَالُ، حَدِّثْنِيْ بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ مَنْفَعَةً عِنْدَكَ، فَإِنِّيْ سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشْفَ نَعْلِيْكَ بَيْنَ يَدَيْ فِي الْجَنَّةِ. فَقَالَ: مَا عَمِلْتُ فِي الْإِسْلَامِ عَمَلًا أَرْجَى عِنْديْ مَنْفَعَةً مِنْ أَنِّيْ لَا أَتَطَهَّرُ طُهُوْرًا تَامًّا فِيْ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذلِكَ الطُّهُوْرِ مَا كُتِبَ لِيْ أَنْ أُصَلِّيَ.
“Wahai Bilāl, ceritakanlah kepadaku tentang ‘amalan yang engkau kerjakan dalam Islam yang lebih diharapkan manfaatnya bagimu, karena saya mendengar semalam (ketika mi‘rāj) bunyi sandalmu di hadapan saya di surga”. Bilāl menjawab: “Tidaklah saya kerjakan suatu ‘amalan di dalam Islam yang lebih kuharapkan manfaatnya daripada aku bersuci baik pada waktu malam maupun siang. Setelah selesai bersuci itu saya kerjakan shalat (thuhur atau shalat sunnah sesudah berwudhū’) sesuai yang ditentukan untuknya.”
Dalam hadits riwayat at-Tirmidzī, disebutkan bahwa Rasūlullāh s.a.w. bersabda tentang ‘Ammār bin Yāsir yang meminta idzin kepada beliau: “Berilah idzin kepada ‘Ammār. Selamat datang bagi orang dan bagus lagi harum.”
Beliau juga bersabda tentang ‘Ammār ini:
“‘Ammār dipenuhi keimanan hingga ke dalam jiwanya.” (H.R. an-Nasā’ī).