Surah at-Tin 95 ~ Tafsir Sayyid Quthb
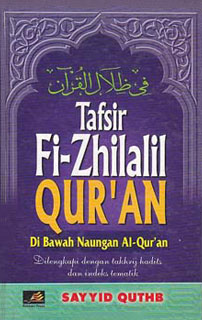
Tafsīr fi Zhilāl-il-Qur’ān
Oleh: Sayyid Quthb Penerbit: Gema Insani
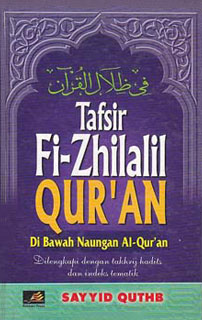
Diturunkan di Makkah
Jumlah Ayat: 8.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ
“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang”
وَ التِّيْنِ وَ الزَّيْتُوْنِ. وَ طُوْرِ سِيْنِيْنَ. وَ هذَا الْبَلَدِ الْأَمِيْنِ. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِيْنَ. إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ. أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ
095:1. Demi (buah) Tīn dan (buah) Zaitūn,
095:2. dan demi bukit Sinai,
095:3. dan demi kota (Makkah) ini yang aman,
095:4. sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
095:5. Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya,
095:6. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan ‘amal shāliḥ; maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.
095:7. Apakah yang menyebabkan kamu mendustakan (hari) pembalasan sesudah (adanya keterangan-keterangan) itu?
095:8. Bukankah Allah Ḥākim yang seadil-adilnya?
Hakikat pokok yang dipaparkan surah ini adalah hakikat fitrah yang lurus yang Allah menciptakan manusia atas fitrah ini. Istiqāmah tabiatnya bersama tabiat iman, dan sampainya fitrah itu bersama iman kepada kesempurnaannya yang ditaqdīrkan untuknya. Hakikat tentang jatuhnya manusia dan kerendahannya ketika ia menyimpang dari fitrah yang benar dan iman yang lurus.
Allah s.w.t. bersumpah atas hakikat ini dengan tīn dan zaitūn, Gunung Sinai, dan kota Makkah yang aman. Sumpah ini, sebagaimana banyak kita jumpai dalam juz ini, merupakan bingkai yang memuat hakikat tersebut. Kita lihat dalam surah-surah yang serupa bahwa bingkai ini selaras dengan hakikat yang dikandungnya.
Gunung Sinai adalah gunung yang Nabi Mūsā a.s. diseru dari sisinya. Sedangkan, kota yang aman adalah kota Makkah Baitullāh al-Ḥarām. Hubungan antara Gunung Sinai dan kota Makkah ini dengan urusan agama dan iman sangat jelas. Adapun hubungan dengan tīn dan zaitūn tidak jelas bagi kita bayangannya.
Banyak sekali pendapat mengenai tīn dan zaitūn ini. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa Tīn itu mengisyaratkan kepada Gunung Zaita di seberang Damsyiq. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah isyārat yang menunjuk kepada pohon Tīn tempat Ādam dan istrinya pergi mengambil daun-daunnya untuk menutup kemaluannya di surga yang mereka tempati sebelum turun ke kehidupan dunia. Ada pula yang mengatakan bahwa ia adalah daerah tempat tumbuhnya pohon Tīn di gunung tempat berhentinya bahtera Nabi Nūḥ a.s.
Mengenai zaitūn ada yang mengatakan bahwa ia adalah isyārat yang menunjuk kepada Gunung Zaita di Bait-ul-Maqdis. Ada yang mengatakan bahwa ia mengisyāratkan kepada Bait-ul-Maqdis itu sendiri. Ada yang mengatakan bahwa ia mengisyāratkan kepada ranting pohon zaitūn yang dibawa pulang kembali oleh burung merpati yang dilepas oleh Nabi Nūḥ dari bahtera untuk memberi pertanda telah surutnya banjir. Maka, ketika burung itu kembali dengan membawa ranting pohon ini, tahulah Nabi Nūḥ bahwa bumi telah surut airnya dan telah menampakkan tumbuhan-tumbuhannya.
Ada yang mengatakan bahwa tīn dan zaitūn adalah dua jenis makanan yang kita tidak mengetahui hakikatnya. Sedangkan, di sana tidak ada isyārat yang menunjukkan sesuatu di belakangnya. Atau, justru keduanya sebagai isyārat yang menunjukkan daerah tempat tumbuhnya di bumi.
Pohon zaitūn yang diisyaratkan di dalam al-Qur’ān berada di suatu tempat di dekat Gunung Sinai. Lalu, dikatakan: “Pohon yang tumbuh dari kawasan Gunung Sinai yang menghasilkan minyak dan dijadikan lauk-pauk bagi orang yang hendak makan”, sebagaimana di dalam al-Qur’ān disebutkan pohon zaitūn dalam firman Allah:
“Zaitūn dan pohon kurma.” (‘Abasa: 29).
Sedangkan, “tīn” hanya disebutkan sekali ini saja di dalam al-Qur’ān.
Oleh karena itu, kita tidak dapat memastikan sesuatu pun dalam persoalan ini. Paling-paling kita hanya dapat mengatakan, dengan bersandar pada persamaan bingkai ini dalam surah-surah al-Qur’ān, bahwa kemungkinan terdekat adalah bahwa penyebutan tīn dan zaitūn mengisyaratkan kepada tempat-tempat atau kenangan-kenangan yang ada hubungannya dengan persoalan agama dan keimanan. Atau, memiliki hubungan dengan pertumbuhan manusia dalam bentuk yang sekaik-baiknya (boleh jadi hal itu terjadi di surga tempat dimulainya kehidupan di sana). Sehinggga, ada relevansi antara isyārat itu dan hakikat pokok yang tampak dalam surah ini, dan selaras pula antara bingkai dan hakikat yang ada di dalamnya. Semuanya disampaikan menurut metode al-Qur’ān.
Adapun hakikat yang terkandung di dalam surah ini adalah:
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِيْنَ. إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ.
“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan ‘amal shāliḥ; maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.” (at-Tīn: 4-6).
Dari ayat-ayat ini, tampak bagaimana perhatian Allah dalam menciptakan manusia di dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Memang Allah s.w.t. menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, tetapi dikhususkannya penyebutan manusia di sini dan di tempat-tempat lain dalam al-Qur’ān dengan susunan yang sebaik-baiknya, bentuk yang sebaik-baiknya, dan keseimbangan yang sebaik-baiknya. Hal ini menunjukkan perhatian yang lebih dari Allah kepada makhlūq yang bernama manusia.
Perhatian Allah terhadap manusia, meskipun pada diri mereka juga terdapat kelemahan dan adakalanya penyimpangan dari fitrah dan kerusakan, mengisyāratkan bahwa mereka memiliki urusan tersendiri di sisi Allah, dan memiliki timbangan sendiri di dalam sistem semesta. Perhatian ini tampak di dalam penciptaannya dan susunan tubuhnya yang bernilai dibandingkan dengan makhlūq lain, baik dalam susunan fisiknya yang sangat cermat dan rumit, susunan akalnya yang unik, maupun susunan ruhnya yang menakjubkan.
Kemudian pembicaraan di sini ditekankan pada khushūshiyyah rūḥiyyahnya. Karena, ialah yang menjadikannya jatuh ke tempat yang serendah-rendahnya ketika menyimpang dari fitrah dan menyeleweng dari iman yang lurus. Karena sudah jelas bahwa wujud badaniyyahnya tidak akan menjatuhkannya ke derajat yang serendah-rendahnya.
Di dalam khushūshiyyah rūḥiyyahnya ini, tampaklah keunggulan wujud manusia. Maka, mereka diberi potensi untuk mencapai tingkatan yang tinggi melebihi kedudukan malaikat muqarrabīn, sebagaimana dibuktikan dengan adanya peristiwa Isrā’ Mi‘rāj. Ketika itu malaikat Jibrīl berhenti pada suatu tempat, sedang Nabi Muḥammad bin ‘Abdillāh – yang manusia itu – terus naik ke tempat yang lebih tinggi.
Akan tetapi, manusia juga potensial untuk mencapai derajat terendah yang tidak ada makhlūq lain mencapai derajat kerendahan seperti itu: “Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya.” Ketika itu makhluq binatang pun masih lebih tinggi dan lebih lurus daripadanya. Karena, binatang masih istiqāmah pada fitrahnya, masih melaksanakan ilham bertasbīḥ menyucikan Tuhannya, dan menunaikan tugasnya di bumi menurut petunjuk yang digariskan Allah. Sedangkan, manusia yang diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, mengingkari Tuhannya dan memperturutkan hawa-nafsunya. Sehingga, ia hingga jatuh ke lembah kehinaan terendah yang binatang pun tidak sampai terjatuh serendah itu.
“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya” dalam fitrah dan potensinya. “Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya” ketika dia sudah menyimpang dengan fitrahnya dari garis yang telah ditunjuki dan dijelaskan oleh Allah. Kemudian dibiarkan-Nya ia untuk memilih salah satu dari dua jalan kehidupan.
“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan ‘amal shāliḥ”. Maka, merekalah yang tetap berada di atas fitrah yang lurus, dan menyempurnakannya dengan iman dan ‘amal shāliḥ, serta meningkatkan derajatnya ke tingkat kesempurnaan sesuai dengan ukuran yang ditetapkan untuknya. Sehingga, mencapai kehidupan yang sempurna di negeri kesempurnaan. “Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya”, yang kekal abadi tidak akan pernah berhenti.
Adapun orang-orang yang terbalik dengan fitrahnya ke tingkatan yang serendah-rendahnya, maka kelak akan menempati tempat paling rendah di akhirat nanti, di neraka Jahannam. Di sana kemanusiaannya tersia-sia, berkubang dalam kehinaan.
Inilah dua akibat yang logis sesuai dengan titik awalnya. Adakalanya bermula dari komitmennya pada fitrah yang lurus dan menyempurnakannya dengan iman, serta meninggalkannya dengan ‘amal shāliḥ. Kemudian pada akhirnya ia akan sampai pada kesempurnaan yang ditetapkan dan berada dalam kehidupan yang penuh keni‘matan. Namun, adakalanya menyimpang dari fitrah yang lurus, terbalik, dan terputus dari tiupan Ilāhiyyah. Sehingga, pada akhirnya ia sampai ke tempat paling rendah, di neraka yang menyala-nyala.
Oleh karena itu, tampak jelaslah nilai iman di dalam kehidupan manusia. Iman inilah yang meningkatkan dan menyampaikan fitrah yang lurus untuk mencapai puncak kesempurnaannya. Ia adalah tali yang membentang antara fitrah dan Penciptanya. Ia adalah cahaya yang menerangi langkah-langkahnya untuk mendaki kepada kehidupan orang-orang dalam kemuliaan yang kekal.
Apabila tali ini putus dan cahaya itu padam, maka hasil yang pasti adalah keterjatuhan ke tempat yang serendah-rendahnya. Sehingga, terabaikan kemanusiaannya secara total, ketika tanah liat berlumuran pada wujud manusia. Dengan demikian, ia menjadi bahan bakar api neraka bersama bebatuan.
Di bawah hakikat ini manusia diseru:
فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ. أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ
“Apakah yang menyebabkan kamu mendustakan (hari) pembalasan sesudah (adanya keterangan-keterangan) itu? Bukankah Allah Ḥākim yang seadil-adilnya?” (at-Tīn: 7-8).
Apakah yang menjadikanmu mendustakan hari pembalasan sesudah dijelaskannya hakikat ini dan sesudah diketahuinya nilai iman di dalam kehidupan manusia? Apa yang menyebabkanmu mendustakannya sesudah dijelaskannya tempat kembali orang-orang yang tidak beriman, tidak menggunakan petunjuk cahaya ini dan tidak berpegang dengan tali Allah yang kuat?
“Bukankah Allah Ḥākim yang seadil-adilnya?”
Bukankah Allah itu Ḥākim yang seadil-adilnya ketika memutuskan urusan makhlūq seperti ini? Atau, bukankah kebijaksanaan Allah itu sangat tinggi di dalam memberikan keputusan yang demikian kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman?
Keadilan-Nya sangat jelas, kebijaksanaan-Nya sangat nyata. Karena itu, diriwayat di dalam hadits marfū‘ dari Abū Hurairah:
إِذَا قَرَأَ أَحَدُكُمْ (وَ التِّيْنِ وَ الزَّيْتُوْنِ) فَأَتَى آخِرَهَا: أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ….. فَلْيَقُلْ: بَلَى وَ أَنَا عَلَى ذلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ.
“Apabila salah seorang dari kamu membaca surah “Wat-Tīni waz-Zaitūn” dan sampai pada ayat terakhir yang berbunyi “Alaisa-Llāhu bi Aḥkam-il-Ḥākimīn”, maka hendaklah ia mengucapkan: “Balā, wa ana ‘alā dzālika min-asy-syāhidīn.” (Ya, saya termasuk orang yang bersaksi atas yang demikian itu).”