Surah an-Nazi’at 79 ~ Tafsir Sayyid Quthb (2/4)
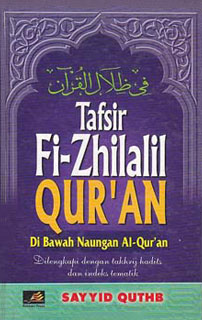
Tafsīr fi Zhilāl-il-Qur’ān
Oleh: Sayyid Quthb Penerbit: Gema Insani
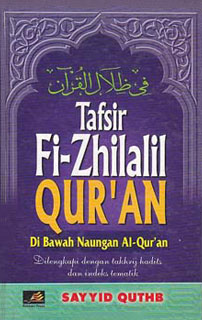
Bagian permulaan yang datang dengan menggunakan bentuk sumpah ini adalah sebagai pengantar terhadap urusan yang digambarkan oleh ayat-ayat berikut ini:
يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ. تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ. قُلُوْبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ. أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ. يَقُوْلُوْنَ أَئِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِي الْحَافِرَةِ. أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً. قَالُوْا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ.
“(Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan) pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam, tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut, pandangannya tunduk. (Orang-orang kafir) berkata: “Apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah (akan dibangkitkan juga) apabila kami telah menjadi tulang-belulang yang hancur lumat?” Mereka berkata: “Kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan”. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi.” (an-Nāzi‘āt: 6-14)
Menurut satu keterangan, yang dimaksud “ar-rājifah” adalah bumi yang bergoncang, didasarkan pada firman Allah dalam ayat lain:
“Pada hari bumi dan gunung-gunung bergoncangan.” (al-Muzzammil: 14).
Sedang “ar-rādifah” adalah langit yang bergoncang. Maksudnya, bumi bergoncang, kemudian diiringi oleh goncangan langit sehingga terbelah dan bintang-gemintangnya berserakan.
Disebutkan juga dalam suatu riwayat bahwa yang dimaksud dengan “ar-rājifah” adalah tiupan pertama yang menggoncangkan bumi beserta isinya seperti gunung-gunung dan semua makhlūq hidup. Maka, pingsanlah semua yang ada di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki Allah. Sedangkan “ar-rādifah” adalah tiupan kedua yang membangunkan mereka lantas dikumpulkan di Padang Maḥsyar, sebagaimana diterangkan dalam surah az-Zumar ayat 68.
Ayat ini menjadikan hati manusia merasakan goncangan besar yang menakutkan dan mengerikan. Hati bergoncang karena takut dan gemetar. Ayat ini memberitahukan apa yang akan menimpa hati manusia pada hari itu, yaitu keterkejutan dan ketergoncangan sehingga tidak ada satu pun hati yang teguh dan mantap. Ia pun mengetahui dan merasakan hakikat firman Allah:
“Hati manusia pada waktu itu sangat takut, pandangannya tunduk.” (an-Nāzi‘āt: 8-9)
Ia bergoncang sangat hebat dan tunduk merendahkan diri. Di dalamnya bercampur-baur antara takut dan sedih, bergoncang dan gemetar. Inilah yang terjadi pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam yang diikuti oleh tiupan kedua, atau pada hari ketika bumi bergoncang sekeras-kerasnya yang diikuti dengan pecah-belah dan hancur berantakannya langit.
Inilah persoalan yang didahului dengan sumpah: “Demi yang mencabut (nyawa) dengan keras, yang mencabut (nyawa) dengan lemah-lembut, yang turun dari langit dengan cepat, yang mendahului dengan kencang, yang mengatur urusan”
Pemandangan yang berupa goncangan dahsyat bumi dan langit, dan bergoncangnya hati karena takut dan sedih ini serasi benar bayang-bayang dan kesannya dengan permulaan surah yang berisi sumpah tersebut.
Selanjutnya, dibicarakanlah tentang ketakutan dan kebingungan mereka ketika bangun dari kubur mereka:
“(Orang-orang kafir) berkata: “Apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah (akan dibangkitkan juga) apabila kami telah menjadi tulang-belulang yang hancur lumat?”” (an-Nāzi‘āt: 10-11)
Mereka bertanya-tanya: “Apakah kami dikembalikan kepada kehidupan yang pernah kami tempuh dahulu?” Dalam ketakutan dan kebingungan mereka bertanya, jika mereka hidup kembali seperti dulu lagi, seraya berdesah: “Bagaimana hal ini bisa terjadi setelah kami menjadi tulang-belulang yang hancur lumat?”
Barangkali mereka sadar dan mengerti bahwa mereka dikembalikan kepada kehidupan, tetapi kehidupan yang lain, Maka, mereka merasa rugi dan menderita dengan pengembalian hidup seperti ini, lalu keluarlah dari mulut mereka kalimat ini:
“Kalau demikian, itu adalah pengembalian yang merugikan.” (an-Nāzi‘āt: 12)
Pengembalian yang tidak pernah mereka perhitungkan, dan tidak pernah mereka menyiapkan bekal untuknya. Sehingga, yang mereka peroleh hanya kerugian semata-mata!
Dalam menghadapi pemandangan ini, al-Qur’ān mengakhirinya dengan mengemukakan hakikat sesuatu yang terjadi:
“Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi.” (an-Nāzi‘āt: 13-14)
“Az-zājirah” berarti suara yang dahsyat (tapi juga diartikan juga dengan tiupan dalam al-Qur’ān dan Terjemahannya). Digunakannya perkataan yang kasar itu sejalan dengan suasana pemandangan ini beserta pemandangan-pemandangan dalam surah ini secara keseluruhan. Adapun kata “as-sāhirah” adalah bumi (tanah) yang putih mengkilat, yaitu Padang Maḥsyar yang kita tidak mengetahui di mana ia berada. Informasi tentang hal ini tidak kita ketahui kecuali dari informasi benar yang kita peroleh. Maka, kita tidak menambahnya dengan sesuatu pun yang tidak dapat dipercaya dan tidak dijamin kebenarannya.
Suara dahsyat satu kali ini maksudnya, bila merujuk kepada nash-nash lain, adalah tiupan yang kedua ya‘ni tiupan kebangkitan dari kubur dan berkumpul ke Maḥsyar. Penggunaan kalimat “sekali tiup” ini mengesankan peristiwa itu begitu cepat. Memang kesan surah secara keseluruhan menunjukkan peristiwa-peristiwanya terjadi dengan begitu cepat dan sepintas kilas. Hati yang ketakutan ini juga terjadi dengan begitu cepat, ya‘ni ia langsung ketakutan. Sehingga, terdapat keserasian dalam setiap gerakan, lintasan, bayang-bayang, dan susunan kalimatnya.
Kemudian nadanya diturunkan sedikit dalam menapaki perjalanan tempo dulu, agar serasi dengan kisah-kisahnya, ketika membeberkan apa yang terjadi antara Mūsā dan Fir‘aun. Diakhiri dengan menceritakan kezhāliman si penguasa tiran (diktator) itu dengan kecongkakannya:
هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ مُوْسَى. إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. اِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى. فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى. وَ أَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى. فَكَذَّبَ وَ عَصَى. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى. فَحَشَرَ فَنَادَى. فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. فَأَخَذَهُ اللهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَ الْأُولَى. إِنَّ فِيْ ذلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَخْشَى.
“Sudahkah sampai kepadamu (ya Muḥammad) kisah Mūsā? Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci iaitu Lembah Thuwā; “Pergilah kamu kepada Fir‘aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas, dan katakanlah (kepada Fir‘aun): “Adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan, dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu supaya kamu takut kepada-Nya?” Lalu Mūsā memperlihatkan kepadanya mu‘jizat yang besar. Tetapi Fir‘aun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian ia berpaling seraya berusaha menantang (Mūsā). Dia mengumpulkan (pembesar-pembesarnya) lalu berseru memanggil kaumnya, (seraya) berkata: “Akulah tuhanmu yang paling tinggi”. Maka Allah meng‘adzābnya dengan ‘adzāb di akhirat dan ‘adzāb di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut (kepada Tuhannya).” (an-Nāzi‘āt: 15-26)
Kisah Mūsā ini merupakan kisah yang paling banyak disebutkan dalam al-Qur’ān dan paling terperinci. Sebelumnya sudah banyak disebutkan pada beberapa surah dalam konteks yang bercama-macam dengan menggunakan metode yang berbeda-beda pula. Masing-masing sesuai dengan konteks surah, dan seiring pula dengan tujuan atau sasaran yang ditonjolkan dalam surah tersebut, menurut metode al-Qur’ān di dalam menyampaikan cerita. (11)
Di sini, kisah ini dipaparkan secara ringkas dan ditampilkan dalam pemandangan sepintas kilas. Dimulai sejak dipanggilnya Mūsā di lembah suci, hingga dihukumnya Fir‘aun dengan hukuman di dunia dan di akhirat. Sehingga, bertemulah dengan tema pokok surah ini, yaitu hakikat akhirat.
Kisah panjang ini disebutkan di sini dalam beberapa ayat pendek dan sepintas lalu saja, sesuai dengan tabiat surah dan kesan-kesannya. Adapun ayat-ayat yang pendek dan sepintas lalu ini mengandung beberapa poin dan pemandangan dari kisah ini sebagai berikut:
Dimulai dengan menunjukkan khithāb “perkataan” kepada Rasūlullāh s.a.w.:
“Sudahkah sampai kepadamu (ya Muḥammad) kisah Mūsā.” (an-Nāzi‘āt: 15).
Ini adalah pertanyaan pendahuluan untuk menyiapkan hati dan telinga guna menerima kisah ini.
Kemudian pemaparan kisah sebagai narasi dengan membeberkan peistiwa-peristiwanya. Penceritaan ini dimulai dengan menggambarkan pemandangan ketika Mūsā dipanggil Tuhannya dan bermunājat kepada-Nya:
“Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci, yaitu Lembah Thuwā” (an-Nāzi‘āt: 16)
Thuwā, menurut pendapat yang lebih kuat, adalah nama sebuah lembah yang terletak di sebelah kanan Gunung Sina bagi orang yang datang dari Madyān di sebelah utara Ḥijāz.
Saat pemanggilan itu adalah saat yang menakutkan dan agung, sekaligus menakjubkan. Pemanggilan Allah s.w.t. Sendiri kepada salah seorang hamba-Nya itu adalah suatu hal yang luar-biasa besarnya, yang perkataan manusia tidak dapat mengungkapkan besarnya urusan itu. Ini merupakan salah satu dari rahasia-rahasia Ilahi yang agung, seperti halnya rahasia penciptaan manusia yang diberi-Nya potensi untuk menerima panggilan itu. Inilah puncak sesuatu yang dapat anda katakan dalam hal ini. Pengetahuan manusia tidak mampu mengetahui hakikatnya yang sebenarnya. Sehingga, ia harus berhenti pada bingkainya, sampai Allah menyingkapkannya untuknya lantas dia dapat merasakannya dengan perasaannya.
Di tempat-tempat (surah-surah) lain terdapat perincian dialog Mūsā denan Tuhannnya dalam hal ini. Adapun di sini hanya disebutkan secara ringkas untuk memberikan kesan-kesan sepintas. Karena itulah, dalam konteks ini segera diceritakan penugasan Ilahi kepada Mūsā, sesudah disebutkannya pemanggilan di lembah suci Thuwā:
“Pergilah kamu kepada Fir‘aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas.” (an-Nāzi‘āt: 17)
“Thaghā” “melampaui batas” adalah suatu hal yang tidak boleh terjadi dan tidak boleh dibiarkan. Ia adalah sesuatu yang sangat dibenci, menimbulkan kerusakan di muka bumi, berlawanan dengan apa yang dicintai Allah, dan menyebabkan kebencian-Nya. Maka, untuk mencegahnya, Allah memberi tugas dengan berbicara secara langsung kepada salah seorang hamba pilihan-Nya untuk berusaha menghentikan kejahatan, mencegah kerusakan, dan menghentikan tindakan melampaui batas ini. Sungguh tindakan melampaui batas ini sangat dibenci oleh Allah sehingga Dia berbicara langsung kepada salah seorang hamba pilihan-Nya agar pergi menghadapi penguasa tiran yang sewenang-wenang dan melampaui batas itu, untuk berusaha mencegahnya dari tindakan-tindakannya dan menyampaikan argumentasi-argumentasi kepadanya sebelum Allah menghukumnya di akhirat dan di dunia!
Kemudian Allah mengajarkan kepada Mūsā bagaimana berbicara kepada thāghiyah “diktator/tiran” itu dengan cara yang sangat simpatik dan menarik hati, barangkali Fir‘aun mau menghentikan perbuatannya dan takut atas murka dan hukuman Tuhannya:
“….. dan katakanlah (kepada Fir‘aun): “Adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri.” (an-Nāzi‘āt: 18)
Adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kotornya perbuatan melampaui batas dan kemaksiatan? Maukah kamu menempuh jalan kesucian dan keberkahan?
“….. dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar kamu takut kepada-Nya?” (an-Nāzi‘āt: 19)
Maukah kutunjukkan kepadamu jalan Tuhanmu? Apabila kamu sudah mengetahuinya, niscaya akan timbul di dalam hatimu rasa takut kepada-Nya. Karena tidaklah seseorang bersikap dan berbuat melampaui batas serta melakukan kemaksiatan dan pelanggaran melainkan ketika jauh dari Tuhannya dan ketika ia tersesat jalan menuju kepada-Nya. Lalu, hatinya menjadi keras dan rusak, sehingga ia suka melampaui batas dan berbuat durhaka.
Semua ini terlukis dalam pemandangan yang berupa pemanggilan dan penugasan. Sesudahnya adalah pemandangan di mana Mūsā berhadapan dengan Fir‘aun dan menyampaikan ajakan, tetapi tablīgh (penyampaian) ini tidak diulang lagi di sini, karena dianggap cukup ditampilkan dan disebutkan di sana. Maka, dilipatlah apa yang terjadi sesudah dibentangkannya pemandangan tablīgh, dan diringkaslah pengungkapan tablīgh itu dalam pemandangan tablīgh. Kemudian diturunkanlah layar di sini untuk diangkat kembali pada akhir pemandangan ketika menghadapi Fir‘aun:
“Lalu Mūsā memperlihatkan kepadanya mu‘jizat yang besar. Tetapi, Fir‘aun mendustakan dan mendurhakai.” (an-Nāzi‘āt: 20-21)
Mūsā telah menyampaikan apa yang ia ditugaskan untuk menyampaikannya, dengan metode sebagaimana yang diajarkan dan diberitahukan Tuhannya kepadanya. Akan tetapi, cara yang simpatik ini tidak berhasil melunakkan hati diktator yang kosong dari pengetahuan tentang Tuhannya. Karena itu, Mūsā menunjukkan kepadanya mu‘jizat yang sangat besar, yaitu mu‘jizat yang berupa tongkat dan tangan yang putih cemerlang sebagaimana diceritakan di tempat-tempat lain: “Tetapi, Fir‘aun mendustakan dan mendurhakai.”
Berakhirlah pemandangan pertemuan dan tablīgh ketika Fir‘aun mendustakan dan mendurhakai. Pemandangan ini ditampilkan hanya sepintas kilas saja.
Selanjutnya ditampilkanlah pemandangan lain. Yaitu, pemandangan ketika Fir‘aun berpaling dari Mūsā, dan dia berusaha mengumpulkan tukang-tukang sihirnya untuk memperlombakan antara sihir dan kebenaran, ketika ia merasa keberatan untuk menerima kebenaran dan petunjuk itu:
“Kemudian ia berpaling seraya berusaha menantang (Mūsā). Dia mengumpulkan (pembesar-pembesarnya) lalu berseru memanggil kaumnya, seraya berkata: “Akulah tuhanmu yang paling tinggi”.” (an-Nāzi‘āt: 22-24)
Ayat-ayat ini segera menampilkan celotehan diktator kafir itu, dengan menggambarkan secara garis besar mengenai pemandangan-pemandangan dan perincian-perincian ketika ia berusaha menantang Mūsā dan mengumpulkan tukang-tukang sihirnya. Ia berpaling dan seraya berusaha melakukan daya upaya untuk mengumpulkan tukang-tukang sihir dan para pembesar. Kemudian meluncurlah dari mulutnya perkataan yang sangat jelek dan memalukan, penuh dengan ketertipuan dan kebodohan: “Akulah tuhanmu yang paling tinggi”.
Perkataan ini diucapkan oleh si diktator yang tertipu oleh kelengahan, ketundukan, dan kepatuhan pembesar-pembesarnya. Maka, tidaklah seorang tiran atau diktator dapat tertipu seperti tertipunya oleh kelengahan, sikap merendahkan diri, kepatuhan, dan ketundukan pembesar-pembesarnya. Padahal, si tiran itu tidak lain hanyalah seorang manusia yang pada hakikatnya tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan apa-apa. Kekuatannya hanyalah pembesar-pembesarnya yang lalai dan penurut itu. Mereka membentangkan punggung untuk dinaikinya, mengulurkan lehernya kepadanya untuk ditarik, menundukkan kepala kepadanya lantas dia naik ke atasnya, dan melucuti hak kemuliaan dan kehormatannya sehingga ia bersikap sewenang-wenang.
Para pembesar berbuat demikian karena pada satu sisi mereka tertipu dan pada sisi lain karena takut. Sedangkan, rasa takut ini tidak akan timbul kecuali karena kekeliruan persepsi. Seorang tiran – seorang diri – tidak mungkin lebih kuat dari beribu-ribu dan berjuta-juta manusia, seandainya mereka menyadari kemanusiaan, kemuliaan, kehormatan, dan kemerdekaannya. Setiap orang dari mereka sepadan dengan si tiran itu dilihat dari segi kekuatannya, tetapi si tiran itu menipu dan memperdayakan mereka seakan-akan ia memiliki kekuatan dan kekuasaan terhadap mereka.
Tidak mungkin seorang individu bertindak melampaui batas terhadap umat yang terhormat. Tidak mungkin seorang individu bersikap diktator terhadap umat yang lurus dan benar. Juga tidak mungkin seorang individu bertindak sewenang-wenang terhadap umat yang mengenal Tuhannya, beriman kepada-Nya, dan tidak mau menyembah seorang pun dari makhlūq-Nya yang tidak memiliki kekuasaan untuk memberikan mudharat dan manfaat kepada mereka!
Fir‘aun menjumpai adanya kelengahan, kehinaan, dan kekosongan hati dari iman di kalangan kaumnya, sehingga menjadikannya berani mengucapkan perkataan kufur dan durhaka ini: “Akulah tuhanmu yang paling tinggi”. Ia tidak mungkin berani mengucapkann perkataan ini seandainya umat ini pandai, terhormat, dan beriman. Umat yang mengerti bahwa Fir‘aun itu hanyalah seorang hamba yang lemah dan tidak memiliki kekuasaan apa-apa, yang jika dihampiri lalat pun dia tidak akan mampu mengusirnya.
Di depan kecongkakan yang tak tahu malu, dan sesudah memaparkan kesombongan yang amat buruk ini, maka bergeraklah kekuatan yang amat dahsyat:
“…..Maka, Allah meng‘adzābnya dengan ‘adzāb di akhirat dan di dunia…..” (an-Nāzi‘āt: 25)
Didahulukannya penyebutan ‘adzāb akhirat daripada ‘adzāb dunia di sini karena ‘adzāb akhirat itu lebih dahsyat dan lebih kekal, serta karena ia adalah ‘adzāb hakiki (sebenarnya) yang akan menimpa orang-orang yang melampaui batas dan suka berbuat maksiat dengan kedahsyatan siksa itu dan kekekalannya. Juga karena penyebutan ini lebih cocok dalam membicarakan konteks akhirat yang menjadi tema sentralnya, dan karena secara lafal penyebutan ini serasi dengan nuansa musikal dalam persajakannya setelah terdapat keserasian ma‘na beserta tema sentral dan hakikat aslinya.
‘Adzāb dunia itu pun sangat keras dan pedih, maka bagaimana lagi dengan ‘adzāb akhirat yang lebih dahsyat dan lebih menyakitkan? Fir‘aun itu dahulu (sewaktu di dunia) memiliki kekuatan, kekuasaan, dan kedudukan yang diwariskan kepada penguasa yang sejenisnya, maka bagaimana dengan orang-orang selain Fir‘aun yang mendustakan ayat-ayat Allah? Bagaimana dengan orang-orang musyrik yang menentang dakwah itu?
“Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut (kepada Tuhannya).” (an-Nāzi‘āt: 26)
Maka, orang yang mengenal Tuhannya dan takut kepada-Nya itulah orang yang dapat mengambil pelajaran dari cerita Fir‘aun tersebut. Adapun orang yang hatinya tidak mengenal taqwā, maka antara dia dan pelajaran ini terdapat dinding penghalang, antara dia dan nasihat terdapat tembok penyekat. Sehingga, ia akan membentur akibatnya, dan Allah meng‘adzābnya dengan ‘adzāb akhirat dan ‘adzāb dunia. Setiap orang dimudahkan menempuh jalan hidupnya, dan menuai akibatnya, sedangkan pelajaran itu hanyalah bagi orang yang takut kepada Tuhannya.