Surah al-Muthaffifin 83 ~ Tafsir Syaikh Fadhlallah (1/2)
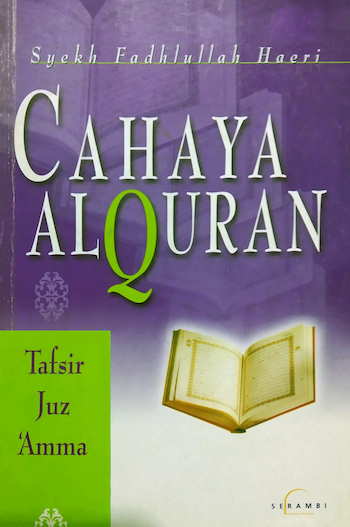
Tafsir Juz ‘Amma
(Judul Asli: Beams of Illumination)
Oleh: Syaikh Fadhlallah Haeri
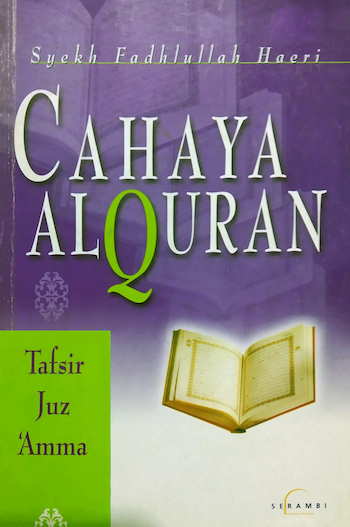
Tafsir Juz ‘Amma
(Judul Asli: Beams of Illumination)
Oleh: Syaikh Fadhlallah Haeri
“ORANG YANG MENGURANGI TAKARAN”
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ
Dengan Nama Allah, Yang Maha Pengasih, Lagi Maha Penyayang
وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ
Akar kata muthaffifīn adalah thaffafa, yang berarti ‘membuat kurang, memberikan takaran kurang, bakhil’. Artinya, sengaja melakukan ketidakadilan dalam suatu transaksi. Tathfīf berarti ‘kekikiran, hemat’, dan thafīf berarti ‘kurang, sedikit, kecil, tidak berarti’.
Ini adalah gambaran tentang kecenderungan alamiah manusia dalam jual-beli dan perdagangan untuk mencoba memanipulasi timbangan demi keuntungannya sendiri, sering kali tidak jujur. Para pedagang Makkah dan Madinah tidak berbeda dengan pebisnis lain di sepanjang sejarah.
الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ
Bentuk akar kata yastawfūn adalah istawfā yang berarti ‘menerima sepenuhnya, lengkap, sampai nilai penuhnya, memenuhi’. Akar kata asalnya adalah wafā berarti ‘sempurna, memenuhi, ketaatan, kesetiaan’. Dalam kisah Nabi Ibrāhīm yang kadang-kadang disebut Ibrāhīm wafā’ (wafā’ di sini artinya iman dia), dikatakan bahwa ketika dimasukkan ke dalam api beliau berteriak, ‘Ḥasbiy Allāh’ (cukup Allah bagiku) dan ia tetap tidak terluka oleh api. Itulah arti wafā’.
وَ إِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ
Kāla artinya ‘menakar’. Yukhsirūn berasal dari kata kerja khasira, ‘membuat rugi, kehilangan, tidak sampai, binasa’. Ketika muthaffifīn (orang yang mengurangi takaran) berada dalam keadaan mampu memberi dan menerima secara adil, yang mereka lakukan dalam transaksi malah merugikan pihak lain dan menguntungkan diri mereka sendiri.
Tiga ayat ini bermakna sama: muthaffifīn, yastawfūn, dan yukhsirūn, saling menguatkan satu sama lain dalam hal kecenderungan manusia untuk ingin selalu menang. Ayat-ayat tersebut menggambarkan bagaimana kita berusaha untuk cerdik dalam transaksi. Itulah sifat dasar kita yang ingin menang dan untung dalam segala situasi. Sementara, sifat mukmin, atau muslim, adalah selalu ingin mengetahui kecenderungan ini dan berusaha memperbaikinya ketika dirinya bertransaksi dengan orang lain yang memiliki potensi sama dengan dirinya. Inflasi terjadi bila kita berusaha mengambil lebih banyak dan memberi lebih sedikit. Ini berlaku bagi situasi sekarang, persis seperti terjadi di Madinah selama periode turunnya al-Qur’an. Jika kita berhubungan dengan suatu komunitas atau masyarakat, maka kita memperhatikan kecenderungan manusia untuk mengambil lebih banyak dan memberi lebih sedikit, dan jika seseorang menyadarinya selagi dia mengerjakannya, maka peluang dia untuk tidak terlalu rakus lebih besar, dan ia akan ingat untuk lebih berlaku adil dalam transaksinya. Kesadaran terhadap ketidakseimbangan kemungkinan besar akan menghasilkan keadilan. Jika kita sadar akan ketidakadilan, maka mungkin kita akan menyadari sifat bawaan manusia yang rendah dalam diri kita.
Ayat pertama mengatakan: Wayl, artinya, ‘Celakalah’ bagi orang-orang yang menipu. Suatu tindakan yang tidak seimbang adalah penipuan. Imām Ghazalī mengatakan bahwa kita harus mengakui bahwa jual-beli tidak bisa terjadi kecuali kalau ada ketidakseimbangan, yakni, selalu ada unsur laba. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi pedagang yang jujur, kita harus selalu mengetahui kecenderungan bawaan ini dan memahami bahwa salah satu pihak akan memiliki tangan di atas. Keadaan yang paling baik terjadi bila kedua belah pihak merasa telah mengambil kesepakatan yang memuaskan dan perasaan tersebut tidak berubah begitu salah satu pihak meninggalkan tempat jual-beli. Jual-beli yang jujur harus bertahan terhadap ujian waktu. Jual-beli itu harus mencapai keseimbangan yang paling adil, agar terjadi inflasi yang paling kecil.
Untuk menjelaskan hal ini, mari kita tengok seorang tābi‘īn (generasi muslim kedua, murid para sahabat Nabi) yang mempunyai toko emas. Satu hari ia meninggalkan tokonya untuk pergi salat ke mesjid, dan mempercayakan kepada kemenakan laki-lakinya untuk menjaga toko sampai ia kembali. Ketika si penjaga toko kembali usai salat, ia berpapasan dengan seorang laki-laki, seorang pedagang yang jelas kaya, yang membawa beberapa gelang emas, dan ia tahu gelang tersebut berasal dari tokonya. Ia menghampiri laki-laki tersebut dan bertanya, “Apakah Anda senang dengan yang Anda beli?” Orang itu menjawab, “Ya, saya sangat-sangat senang”. Lalu si penjaga toko bertanya dengan harga berapa ia membelinya. Si laki-laki menjawab, “Saya membayar 200 dirham untuk yang ini, dan 400 dirham untuk yang itu. Saya dapat menjualnya di tempat saya seharga dua kali lipatnya, karena itu saya sangat gembira.” Tapi si penjaga toko berkata, “Tidak. Saya tidak senang karena bajingan kemenakan ini telah menipu Anda. Saya sudah memberitahu dia tentang harga barang-barang ini. Tolong, saya mohon kepada Anda, kembalilah ke toko bersama saya.” Maka si penjaga toko menarik kembali laki-laki itu, memberinya sebagian uang selisihnya, dan mengusir kemenakannya. Si penjaga toko telah memasang harga untuk barang-barangnya dan puas dengan harga itu. Nabi berkata, “Jual, dan ambillah keuntungan, sekalipun keuntungannya sedikit saja.” Dengan cara ini ada dinamisme dan perputaran, dan orang tidak terikat pada apa yang dimilikinya.
Muthaffifīn menunjuk kepada kita semua, karena potensi untuk melakukan penipuan ada pada kita semua. Jika potensi untuk menjadi penjahat tidak ada pada diri kita, maka kita tidak akan mampu memahami kriminalitas. Jika potensi kekasaran, atau potensi rasa takut, tidak ada dalam diri kita, maka kita tidak akan memahami maknanya. Jika ketuhanan tidak ada dalam diri kita, bagaimana kita dapat berbicara tentang Samudera Ilahi? Semua itu ada dalam diri kita, dan karena itu kita tidak akan mengatakan bahwa kemenakan si tukang emas suka mementingkan diri sendiri. Jika kisah ini bersifat historis belaka dan ditujukan hanya kepada penduduk Madinah, maka kita tidak perlu mengindahkannya. Namun, yang benar adalah bahwa kita selalu memiliki potensi ini, karena memang begitulah kisah umat manusia.
أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ
Ayat ini menunjukkan jalan keluar dari penjara dan rantai kecenderungan kita pada kesukaan untuk mementingkan diri sendiri dan ketamakan.
Ba‘atsa berarti ‘bangkit, bangun, mengirimkan, menyebabkan’. Di sini maksudnya bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban kepada siapa? Kita semua akan dimintai pertanggungjawaban kita sendiri. Ini tentu saja menunjuk kepada alam akhirat, dan tentunya juga berkenaan dengan kehidupan ini. Dengan jalan apa pun, perhitungan ini akan terjadi baik kita suka atau tidak. Jika kita membuka sebuah keran, apa pun yang ada dalam pipa akan memancar; dan semakin lebar kita membukanya, semakin banyak mengalir. Jadi, kita hanya akan membangun lebih banyak ketamakan, kebencian, atau apa pun yang ada dalam diri kita, karena sistem penciptaan terletak dalam pertambahan. Itulah sebabnya mengapa Allah mengatakan, “Kasih-sayang-Ku meliputi segala sesuatu“ (Q.S.7:156).
لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ
Secara eksplisit, ayat ini merupakan penjelasan tentang hari ketika yang tertinggal adalah roh kita, di mana niat dan amal kita telah distempel. Hari Besar ini bisa juga merupakan hari di mana kita siap untuk memperhitungkan diri kita secara utuh, hari kepasrahan total kita, hari islām kita (ketundukkan kepada Realitas). Jika kita ingin terbebas dari rantai-rantai yang membelenggu diri kita, kita harus mampu menyelesaikan semua perhitungan kapan saja. Bahkan, sebenarnya kita harus siap menyelesaikan perhitungan kita sebelum kita membuat perhitungan. Kita dapat melakukan hal ini dengan mempertanyakan niat. Dengan mengetahui niat kita sebelum melaksanakan suatu perbuatan, perhitungan kita akan selalu tetap bersih.
يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ
Yawma yaqūmu adalah Hari di mana kita akan berdiri di hadapan Tuhan semesta alam dan menghadapi catatan-catatan amal kita. Jika kita sungguh-sungguh dalam Islām sepanjang waktu, maka kita selalu menghadapi Rabb-ul-‘Ālamīn (Tuhan semesta alam). Qāma berarti, di antaranya, ‘berdiri, bangkit dari kematian’, dan menunjukkan bahwa si pelaku dipersiapkan untuk berinteraksi dengan apa yang menjadi tujuan dibangkitkannya dia.
Ayat ini berkenaan dengan akhir zaman untuk menyentak kita dari kelesuan kita saat ini. Ia mengingatkan kita bahwa ada suatu akhir, dan bahwa pada akhimya kita akan dibiarkan tanpa dibekali apa pun selain buah dari niat-niat kita.
كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ
Buku catatan kaum fujjār (orang-orang yang jahat, berakhlak rendah, sesat jalan) berada dalam sijjīn. Fujjār berasal dari fajara, yang berarti ‘membelah, mengakhiri, bertindak secara tak bermoral, turut dalam penyimpangan moral’. Subuh disebut fajr, karena ia mengakhiri malam. Seseorang disebut fājir jika ia sesat jalan. Ini berarti bahwa ia menyeleweng, merosot, keluar jalur. Kita semua adalah mutiara dalam untaian yang sama, dan sebutir mutiara hanya akan berarti jika ia dirangkai dalam sebuah untaian.
Akar kata sijjīn, daftar setiap perbuatan yang tidak bermoral, adalah sajana, yang berarti ‘memenjarakan’. Sijjīn adalah suatu pemenjaraan yang berlebih-lebihan, lebih permanen dan kekal. Dalam beberapa tafsir al-Qur’an, kata ini dijelaskan sebagai nama lain dari jahannam (neraka). ‘Kitab’ adalah apa yang sedang ditulis oleh orang yang telah melakukan kejahatan tentang kehidupannya. Ia adalah penulis biografinya sendiri, tentang segala perbuatannya, yang dihasut oleh niat-niatnya. Si pesakitan sendirilah yang menentukan berapa banyak lagi rantai dan belenggu yang akan dimilikinya.
Kitab adalah apa yang ditulis, dan tulisan itu diwujudkan oleh setiap orang di antara kita melalui amal-amalnya. Jika biografi kita penuh dengan ketamakan dan kekikiran, sebagaimana disebutkan dalam ayat kedua dan ketiga, dan kita beramal tapi demi keuntungan pribadi dan untuk menguasai orang lain, maka kita akan dipenjarakan oleh amal-amal kita. Seseorang bisa saja berkeinginan untuk memimpin seluruh kerajaan, karena mengira itu akan membawakan kebahagiaan. Tapi, begitu keinginannya terpenuhi dia pun ingin merangsak kerajaan tetangganya juga. Apakah keinginan ini bukan belenggu? Karena terbelenggu maka kita tidak mau berurusan dengan objek itu sendiri, melainkan dengan perasaan kita terhadap objek tersebut. Sijjīn, hukuman penjara, menunjuk kepada keadaan mental kita dan berkenaan dengan kebahagiaan kita, kebebasan batin kita, dan pemenuhan kita, yang merupakan hasil sampingan dari keluasan dan ketulusan islām (penyerahan) dan keterbebasan kita.
وَ مَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّيْنٌ
Kata kerja adrāka berarti ‘mencapai, mendekati, merenggut, merasakan, menyadari, matang’. Ia menunjukkan suatu pengetahuan yang lebih dalam dan lebih halus dibanding ketajaman buatan. Melalui perenungan yang dalam, maka realisasi dan pemahaman akan datang. Kita semua tahu apa itu belenggu, dan tahu akan seperti apa berada di bawah beratnya pengharapan dan kekecewaan. Kita harus bertanya kepada hati kita sendiri. Bagaimana sijjīn, atau penjara kita, muncul, dan mengapa penjara seseorang berbeda dengan penjara orang lainnya? Itu karena kita menentukan situasi-situasi tertentu untuk kita sendiri.
كِتَابٌ مَّرْقُوْمٌ
Akar kata marqūm (tertulis) adalah raqama, yang berarti ‘menulisi, menandai dengan hal-hal yang bersifat pengenal, membubuhi cap, menomori’. Ia juga bermakna ditetapkan dan dituliskan. Raqam berarti ‘nomor’. Maka kitab, atau apa yang dibicarakan, dapat diukur, ditulis dengan persis, dan tidak hanya dapat diukur.
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ
Pengertiannya di sini adalah bahwa jika seseorang menyangkal realitas eksistensi dan penciptaan, maka ia adalah seorang mukadzdzib (pendusta). Mukadzdzib berarti perbuatan seseorang yang bertentangan dengan ucapannya, ada pemisahan antara ucapan dan perbuatan. Kidzb adalah dusta, penipuan, kebohongan atau ketidakjujuran. Kecelakaan akan menimpanya pada hari ketika ia tak bisa lagi mengubah diri dan menyaksikan realitas terakhir, yakni hari kematiannya. Barangsiapa menyangkal ḥaqq (kebenaran), yang menjelma sebagai keadilan, berarti telah menyangkal bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan ḥaqq, dengan keadilan dan keseimbangan. Jika seseorang berbuat tidak seimbang, maka ia sedang berbohong. Seseorang yang mengaku bahwa dirinya tidak menyangkal kebenaran tapi menegakkannya namun berbuat dengan cara yang berlawanan, maka ia berada dalam keadaan kufr (menutup, menyangkal realitas). Pengakuannya sebagai orang yang mengesakan Tuhan (muwaḥḥid) ternyata palsu karena ia berbuat sebagai penipu (muthaffif) dan tidak memperhatikan keadilan dari perbuatannya sendiri.
الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ
Hari Pengadilan, hari dīn, adalah hari ketika kita membayar penuh utang-utang kita. Itulah Hari Perhitungan, hari ketika bentuk kita yang sesungguhnya, yakni roh, membentang terbuka. Bentuk ini tidak dapat dilihat sekarang, karena ia merupakan energi halus yang mempertahankan kita hidup. Pemahaman kita tentang roh hanya bisa sejauh ini saja dan tak lebih, karena kemampuan untuk memahaminya muncul dari apa yang disebut ‘Aku’, yang akan terputus sudah sampai di situ.
وَ مَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيْمٍ
I‘tadā, akar dari mu‘tadin artinya ‘menyeberang, melebihi, bertindak sangat keterlaluan’. Sekaitan dengan kata ini adalah kata ‘aduw, yang berarti ‘musuh, lawan’, dan ‘adā, yang berarti ‘permusuhan, kebencian, antagonisme, agresi’. Pelanggaran terjadi karena kita tidak merasakan adanya tauhid di dalam diri kita.
Kata ‘aduw (musuh) tentu saja tidak berarti permusuhan di antara dua pihak tapi mengindikasikan bahwa mereka asing atau berbeda satu sama lain: tidak ada kesatuan di antara mereka. Itu tidak berarti bahwa mereka saling membenci, tetapi yang pasti mereka tidak saling mengenal. Maka kebodohan (ketidaktahuan) adalah juga musuh; kita menentang apa yang tidak kita ketahui. Dari kata i‘tadā, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pelanggaran dan penyangkalan kita adalah akibat kebodohan kita, maka kita bisa melihat betapa kita bisa menjadi musuh diri kita sendiri. Ketika kita telah melanggar (melampaui batas) jatidiri kita sendiri, maka kita atsīm (berdosa). Atsima berarti ‘melakukan dosa atau kejahatan’, dan ini dilakukan karena kebodohan dan kebencian kita yang menyebabkan kita terputus dan berdusta. Atsima termasuk melakukan apa yang tidak boleh kita lakukan. Itsm artinya ‘berjudi’; perjudian dianggap pelanggaran karena dengan terlibat di dalamnya kita melakukan ketidakadilan. Kita menyebutkan suatu sistem selain dari apa yang ditetapkan oleh realitas—yakni kasih sayang dan keadilan—dan, karena itu, kita melakukan kejahatan. Dengan kembali ke sistem yang tidak adil maka kita menjadikan diri kita bagian dari itu.
إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ
Ini berkenaan dengan situasi yang berulangkali terjadi bahkan hingga sekarang, di mana orang mengatakan bahwa karena al-Qur’an diturunkan beberapa ratus tahun lampau maka ia tidak bisa berlaku pada kondisi sekarang; ia hanyalah dongengan masa lampau.
كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ
Rāna berarti ‘mengambil hati’, dan juga ‘menangkap, mengatasi, merendahkan diri, berlaku’. Yang mereka usahakan akan dimudahkan bagi hati mereka. Seperti dikatakan sebelumnya, jalan mana pun yang kita pilih akan dijadikan mudah bagi kita. Jika kita seorang penjahat, jalan ini akan dimudahkan bagi kita karena bagaimana pun juga kita akan selalu berusaha membenarkan perbuatan kita. Apa pun amal-amal seseorang, semuanya akan dibuat kelihatan nampak-wajar baginya. Dia akan terus membenarkannya kalau dia tidak senantiasa mengembalikan kepada standar perilaku kenabian. Maka dari itu dikatakan bahwa kalau kita terus bersama orang-orang tertentu selama empat puluh hari, kita akan menjadi seperti mereka. Bagi orang yang mudah dipengaruhi mungkin hanya perlu dua jam saja untuk menjadi seperti orang-orang yang mereka gauli.
كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ
Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa dalam kehidupan mendatang para pelanggar tertutup oleh suatu hijab dari pengenalan terhadap ketuhanan secara total dan final. Ini berarti bahwa mereka belum memperoleh cukup pengetahuan untuk mempersiapkan diri sebagaimana mestinya di kehidupan ini guna menjalani proses pengungkapan dan penyucian tambahan lainnya yang akan berlangsung di kehidupan selanjutnya. Mereka belum mempersiapkan jalan bagi dirinya untuk berpindah ke alam kehidupan selanjutnya. Al-Qur’an mengatakan bahwa kehidupan kita selanjutnya akan sesuai dengan ilmu dan amal kita dalam kehidupan ini. Maka orang-orang yang telah mengingkari, yang terus-menerus berbuat tidak adil dan tidak seimbang di sini, mereka akan berada dalam keadaan terpisah di kehidupan selanjutnya karena mereka sudah berada dalam keadaan seperti itu di sini. Pengingkaran yang mereka jalani dan mereka hidupkan di sini akan mencegah mereka untuk lebur kembali ke dalam sumbernya (tauḥīd).
ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ
Shāla berarti ‘memanggang, membakar’ atau ‘dihadapkan pada lautan api’. Akar kata jaḥīm adalah jaḥama, yang berarti ‘menyalakan api’ dan ia digunakan karena api yang akan mereka masuki adalah api yang telah mereka nyalakan dalam kehidupan ini. Jaḥīm di sini menunjuk kepada neraka yang diancamkan kepada kita pada hari kiamat, dan juga neraka yang kita pahami sebagai manusia biasa. Ketika hati kita berkecamuk, ketika darah kita mendidih oleh kemarahan atau kegusaran, atau ketika kita terbakar oleh hasrat, maka kita mengalami berbagai aspek neraka dunia. Tapi maksudnya di sini adalah bahwa orang-orang tersebut pasti akan mencapai api abadi karena perbuatannya sendiri.
ثُمَّ يُقَالُ هذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُوْنَ
Kemudian mereka akan menyadari bahwa inilah kebenaran yang mereka dustakan, karena jika kebenaran tidak disadari pada saat sekarang, maka ia akan disadari pada saat kematian. Ini berarti bahwa kebenaran itu sudah ada tapi didustakan. Api agitasi, kemarahan, kebencian sudah ada di sini, tapi mereka menyangkalnya. Kebenaran hidup sepanjang masa, ia tidak tunduk pada waktu. Yang berubah karena waktu hanyalah ketamakan, rasa lapar, atau hasrat-hasrat pribadi dan individu. Umpamanya, yang kita inginkan di masa kanak-kanak dulu bukanlah yang kita inginkan sekarang. Semua hasrat duniawi bersifat relatif, berlalu sepintas, mengikuti peredaran dan tidak menentu. Yang benar dari hasrat adalah ketidakmenentuannya itu, sifatnya yang sementara. Yang benar dari manusia adalah bahwa dalam hati manusia senantiasa hidup potensi untuk ragu. Turunnya Surah al-‘Ashr (‘Demi waktu, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi’ Q.S.103:1-2) tidak untuk merendahkan manusia. Memang begitulah faktanya. Kita harus menyadari kebenaran tersebut agar dapat memasuki Kebenaran Tunggal yang mencakup kebenaran tersebut.