Surah al-Ma’un107 ~ Tafsir Sayyid Quthb
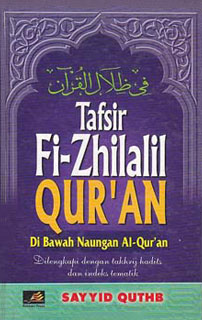
Tafsīr fi Zhilāl-il-Qur’ān
Oleh: Sayyid Quthb Penerbit: Gema Insani
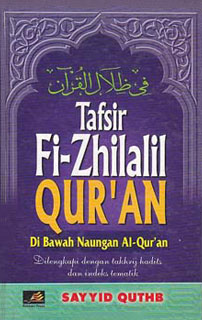
Diturunkan di Makkah
Jumlah Ayat: 7.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ
“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang”
أَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ. فَذلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ. وَ لَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاؤُوْنَ. وَ يَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ
107:1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan Agama?
107:2. Itulah orang yang menghardik anak yatim,
107:3. dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin,
107:4. Maka, kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat,
107:5. (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya,
107:6. orang-orang yang berbuat riyā’.
107:7. dan enggan (menolong dengan) barang berguna.
Surah ini adalah surah Makkiyyah menurut beberapa riwayat, dan menurut beberapa yang lain adalah surah Makkiyyah dan Madaniyyah (yaitu tiga ayat pertama adalah Makkiyyah sedang sisanya adalah Madaniyyah). Pendapat terakhir inilah yang lebih kuat, meskipun surah ini secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dengan arahan yang sama, ya‘ni untuk menetapkan hakikat global dari hakikat-hakikat agama Islam, yang hampir-hampir membawa kita untuk berkecenderungan menganggapnya sebagai surah Madaniyyah secara keseluruhan. Karena, tema yang dibahasnya adalah tema-tema al-Qur’ān Madanī yang secara garis besar membeberkan masalah nifāq dan riyā’ yang belum terkenal di kalangan kaum Muslimīn di Makkah. Akan tetapi, menerima riwayat yang mengatakannya sebagai surah Makkiyyah-Madaniyyah tidak menutup kemungkinan diturunkannya keempat ayat terakhir di Madīnah dan disambung dengan ketiga ayat pertama, karena adanya kesesuaian dan keserupaan temanya. Persoalan ini kami anggap cukup untuk selanjutnya, kita bicarakan secara ringkas tema surah dan hakikat persoalan besar yang dipecahkannya.
Surah kecil dengan tujuh ayatnya yang pendek ini memecahkan hakikat besar yang hampir mendominasi pengertian iman dan kufur secara total. Lebih dari itu, ia mengungkapkan hakikat besar dan terang tentang tabiat ‘aqīdah ini. Juga tentang kebaikan besar dan agung yang tersimpan di dalamnya bagi manusia, dan tentang rahmat yang besar yang dikehendaki Allah untuk manusia, yaitu dengan diutusnya Rasūlullāh s.a.w. dengan membawa risālah terakhir ini.
Sesungguhnya, agama Islam bukanlah agama simbol dan lambang semata-mata. Tidak cukup beragama dengan simbol-simbol dan syiar-syiar ‘ibādah saja kalau tidak bersumber dari keikhlasan dan ketulusan hati karena Allah, ya‘ni keikhlasan yang mendorong dilakukannya ‘amal shāliḥ dan tercermin di dalam perilaku untuk memperbaiki dan meningkatkan kehidupan umat manusia di muka bumi.
Agama Islam juga bukan aturan-aturan parsial, terpilah-pilah, terbagi-bagi, dan lepas atau sama lain yang dapat saja manusia menunaikan dan meninggalkan apa yang dikehendakinya. Tetapi, agama Islam adalah manhaj “sistem” yang saling melengkapi, yang berinteraksi antara ‘ibādah dan syiar-syiarnya dengan tugas-tugas individual dan sosialnya. Semuanya bermuara untuk kepentingan umat manusia dengan tujuan untuk menyucikan hati, memperbaiki kehidupan, dan tolong-menolong antarsesama manusia dan bantu-membantu untuk kebaikan, keshāliḥan, dan perkembangan mereka. Pada masa itu, tercerminlah rahmat yang besar dari Allah kepada hamba-hambaNya.
Kadang-kadang ada orang yang mengatakan bahwa dia adalah Muslim dan membenarkan agama ini dengan segala ketetapannya. Kadang-kadang dia melakukan shalat dan melaksanakan syiar-syiar lain selain shalat. Tetapi, hakikat iman dan hakikat membenarkan agama masih jauh darinya. Karena, hakikat ini memiliki indikasi yang menunjukkan eksistensi dan kenyataannya. Kalau indikasi-indikasi ini tidak ada, tidak ada keimanan dan pembenaran itu, meskipun lisan telah mengucapkan dan orang itu melaksanakan simbol-simbol ‘ibādah.
Sesungguhnya, hakikat iman itu apabila sudah meresap di dalam hati, ia akan bergerak merefleksikan dirinya dalam ‘amal shāliḥ (sebagaimana kami katakan pada waktu menafsirkan surah al-‘Ashr). Apabila tidak ada gerakan ber‘amal shāliḥ, ini menunjukkan bahwa hakikat iman itu tidak ada wujūdnya. Demikianlah yang ditetapkan surah ini dengan nashnya.
أَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ. فَذلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ. وَ لَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ.
“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan Agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.” (al-Mā‘ūn: 1-3).
Surah ini dimulai dengan pertanyaan yang dihadapkan kepada setiap orang yang dapat berpikir: “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan Agama?”, dan orang yang dapat mendengar pertanyaan ini, untuk mengetahui ke mana arah isyārat ini dan kepada siapa ia ditujukan? Untuk mengetahui siapa gerangan orang yang mendustakan agama dan orang yang ditetapkan oleh al-Qur’ān sebagai pendusta agama, maka jawabannya ialah: “Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin”.
Boleh jadi, hal ini sebagai sesuatu yang mengejutkan bila dibandingkan dengan definisi iman secara tradisional. Akan tetapi, inilah inti persoalan dan hakikatnya. Bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim dengan keras, ya‘ni menghina anak yatim dan menyakitinya. Juga tidak menganjurkan memberi makan orang miskin dan tidak suka memberi anjuran untuk memelihara orang miskin. Kalau hakikat pembenaran agama itu sudah mantap di dalam hatinya niscaya dia tidak akan membiarkan anak-anak yatim dan tidak akan berhenti menganjurkan memberi makan orang miskin.
Hakikat tashdīq “membenarkan” agama bukanlah pernyataan yang diucapkan oleh lisan, tetapi ia bercokol di dalam hati dan mendorong yang bersangkutan untuk berbuat kebaikan dan kebajikan kepada saudara-saudaranya sesama manusia yang membutuhkan pertolongan dan pemeliharaan. Allah tidak hanya menghendaki pernyataan-pernyataan dari manusia, tetapi menghendaki pernyataan itu disertai dengan ‘amalan-‘amalan sebagai pembuktiannya. Kalau tidak, pernyataannya itu hanyalah debu yang tidak ada bobot dan nilainya di sisi Allah.
Tidak ada yang lebih jelas dan lebih tegas daripada ketiga ayat ini di dalam menetapkan hakikat yang mencerminkan ruh ‘aqīdah dan tabiat agama ini dengan cerminan yang lebih tepat.
Di sini, kami tidak ingin memasuki perdebatan fiqhiyyah tentang batas-batas iman dan Islam, karena batasan-batasan fiqhiyyah itu hanya didasarkan pada persoalan mu‘āmalah syar‘iyyah sedangkan surah ini menetapkan hakikat persoalan dalam penilaian dan timbangan Allah. Ini merupakan persoalan lain selain lambang-lambang lahiriah yang menjadi objek mu‘āmalah.
Kemudian, hakikat pertama ini diiringi dengan pemaparan salah satu gambaran praktisnya:
فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاؤُوْنَ. وَ يَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ
“Maka, kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riyā’, dan enggan (menolong dengan) barang berguna”. (al-Mā‘ūn: 4-7).
Ini adalah doa atau ancaman kebinasaan bagi orang-orang shalat yang lalai dari shalatnya. Siapakah gerangan orang-orang yang lalai dari shalatnya itu? Mereka adalah: “Orang-orang yang berbuat riyā’, dan enggan (menolong dengan) barang berguna”.
Mereka mengerjakan shalat, tetapi tidak menegakkan shalat. Mereka menunaikan gerakan-gerakan shalat dan mengucapkan doa-doanya, tetapi hati mereka tidak hidup bersama shalat, tidak hidup dengannya. Ruh-ruh mereka tidak menghadirkan hakikat shalat dan hakikat bacaan-bacaan, doa-doa, dan dzikir-dzikir yang ada di dalam shalat. Mereka melakukan shalat hanya ingin dipuji orang lain, bukan ikhlas karena Allah. Karena itu, mereka melalaikan shalat, meskipun mereka mengerjakannya. Mereka lalai dari shalat dan tidak menegakkannya, padahal yang dituntut adalah menegakkan shalat, bukan sekadar mengerjakannya. Selain itu, menegakkan shalat itu adalah dengan menghadirkan hakikatnya dan melakukannya hanya karena Allah semata-mata.
Oleh karena itu, shalat semacam ini tidak memberi bekas di dalam jiwa orang-orang yang mengerjakan shalat, tetapi lalai dari shalatnya itu. Karena itu, mereka enggan memberi bantuan dengan barang-barang yang berguna. Mereka enggan memberi pertolongan, dan enggan berbuat kebaikan dan kebajikan kepada saudara-saudaranya sesama manusia. Mereka enggan memberikan bantuan dengan barang-barang yang berguna kepada sesama hamba Allah. Seandainya mereka menegakkan shalat dengan sebenar-benarnya karena Allah niscaya mereka tidak akan enggan memberikan bantuan kepada hamba-hamba Allah. Karena demikianlah sumbu ‘ibādah yang benar dan diterima di sisi Allah.
Demikianlah kita dapati diri kita pada kali lain di depan hakikat ‘aqīdah dan tabiat agama ini. Kita dapati nash Qur’ān mengancam orang-orang yang shalat dengan wail, kecelakaan yang besar, karena mereka tidak menegakkan shalat dengan sebenarnya. Mereka hanya melakukan gerakan-gerakan yang tidak ada ruhnya. Lagipula mereka tidak tulus karena Allah di dalam melakukannya, melainkan hanya karena riyā’, supaya dipuji orang lain. Shalatnya tidak meninggalkan bekas di dalam hati dan ‘amal perbuatan mereka. Karena itu, shalat mereka menjadi debu yang berhamburan, bahkan sebagai kemaksiatan yang menunggu pembalasan yang buruk!
Di balik semua ini, kita melihat hakikat sesuatu yang dikehendaki Allah terhadap hamba-hambaNya, ketika Dia mengutus Rasūl dengan membawa risālah-Nya supaya mereka beriman dan ber‘ibādah kepada-Nya.
Dia tidak menghendaki sesuatu pun dari mereka untuk diri-Nya Yang Maha Suci karena Dia Maha Kaya, tidak membutuhkan sesuatu pun. Tetapi, Dia hanya menghendaki kemaslahatan diri mereka sendiri, menghendaki kebaikan untuk mereka, menghendaki kesucian hati dan kebahagiaan hidup mereka. Dia menghendaki bagi mereka kehidupan yang tinggi dan terhormat, yang berlandaskan perasaan yang suci, memiliki rasa kesetiakawanan sosial yang bagus, dermawan dan murah hati, cinta, bersaudara, dan bersih hati dan perilakunya.
Maka, hendak pergi ke manakah manusia kalau menjauh dari kebaikan ini; menjauh dari rahmat; menjauh dari kehidupan yang tinggi, indah, bermutu, dan terhormat? Mengapa mereka berkelana dalam kebingungan jahiliyyah yang gelap-gulita padahal di depannya ada cahaya yang dapat menunjukkan persimpangan jalan?