Surah al-Ma’arij 70 ~ Tafsir Sayyid Quthb (4/5)
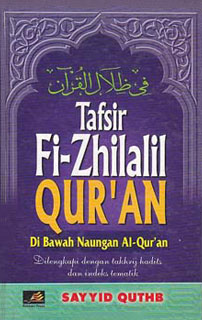
Tafsīr fi Zhilāl-il-Qur’ān
Oleh: Sayyid Quthb Penerbit: Gema Insani
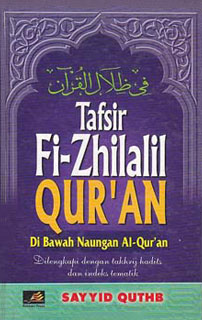
Sifat-sifat orang-orang mu’min yang dikecualikan dari sifat-sifat umum manusia itu dijelaskan batasan-batasannya dalam rangkaian ayat berikutnya:
“Kecuali orang-orang yang mengerjakan shalāt, mereka tetap mengerjakan shalātnya” (al-Ma‘ārij: 22-23.)
Shalāt itu lebih dari sekadar rukun Islām dan simbol iman. Ia adalah sarana berhubungan dengan Allah dan tindak lanjut dari pengintaian (kesadaran bāthinnya) itu. Shalāt adalah lambang ‘ubūdiyyah yang tulus, sebagai implementasi maqām rubūbiyyah dan maqām ‘ubūdiyyah dalam bentuk tertentu. Adapun sifat kekekalan yang dikhususkan untuk shalāt di sini, “mereka tetap mengerjakan shalātnya”, memberikan gambaran tentang keajegan dan keberlangsungannya. Maka, shalātnya ini adalah shalāt yang tidak pernah terputus dengan ditinggalkannya karena sembrono atau malas. Dengan keajegannya menunaikan shalāt ini, berarti dia terus-menerus berhubungan kepada Allah tanpa pernah terputus. Rasūlullāh s.a.w. selalu melakukan suatu ‘ibādah dengan mantap, ya‘ni konstan (ajeg). Beliau bersabda:
وَ إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى مَا دَاوَمَ وَ إِنْ قَلَّ.
“‘Amalan yang paling disenangi Allah ialah apa yang dilakukan secara ajeg (rutin) meskipun hanya sedikit.”
Hal ini untuk menunjukkan perhatian terhadap sifat kemantapan, keseriusan, dan kesungguhan dalam berhubungan dengan Allah, sebagaimana hubungan ini pun harus dihormati. Hubungan ini bukanlah permaianan yang dengan begitu saja boleh disambung dan diputuskan sesuai selera!
“Orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)” (al-Ma‘ārij: 24-25.)
Yaitu zakat secara khusus, dan sedekah-sedekah yang dimaklumi ukurannya, yang merupakan hak pada harta orang-orang mu’min. Atau, mungkin ma‘nanya lebih lengkap dan lebih besar daripada ini. Ya‘ni, mereka menjadikan bagian tertentu pada hartanya, karena mereka merasa bahwa itu adalah hak orang miskin baik yang meminta-minta maupun tidak. Tindakannya ini membuktikan terlepasnya dari sifat kikir dan kebebasannya dari sifat rakus. Hal ini juga menunjukkan adanya kewajiban orang yang mampu terhadap yang tidak mampu, di kalangan umat yang saling menjamin dan saling menanggung.
Si miskin yang meminta-minta dan si papa yang tidak meminta-minta, tanpa menyatakan apa kebutuhannya, melainkan ia tetap tidak mau meminta-minta. Atau, barangkali ia adalah orang yang tertimpa bencana, lantas menjadi miskin papa, namun ia tetap tidak mau meminta-minta.
Perasaan dan kesadaran tentang adanya hak di dalam hartanya bagi orang miskin yang meminta-minta dan yang tidak meminta-minta, adalah kesadaran tentang adanya karunia Allah pada satu sisi, dan adanya unsur perikemanusiaan pada sisi lain, yang melebihi keterbebasan perasaannya dari belenggu kekikiran dan kerakusan. Pada waktu yang sama, hal itu menunjukkan adanya rasa kesetiakawanan sosial dan ras senasib sepenanggungan dengan umatnya. Maka, ini adalah kefardhuan yang memiliki implikasi yang luas dan beraneka macam, baik dalam hati sanubari maupun dalam dunia realita.
Al-Qur’ān menyebutnya di sini, lebih dari sekadar melukiskan sifat dan ciri-ciri jiwa yang beriman. Akan tetapi, ia adalah salah satu mata rantai pengobatan penyakit kikir dan tamak dalam surah ini.
“Orang-orang yang mempercayai hari pembalasan.” (al-Ma‘ārij: 26.)
Sifat ini berhubungan langsung dengan tema sentral surah, dan pada waktu yang sama ia melukiskan garis pokok ciri-ciri jiwa yang beriman. Maka, mempercayai hari pembalasan adalah separo dari iman, dan ia memiliki pengaruh yang pasti terhadap manhaj kehidupan, baik dalam perasaan maupun dalam perilaku. Timbangan di tangan orang yang mempercayai hari pembalasan itu berbeda dengan timbangan yang ada di tangan orang yang mendustakan atau meragukannya. Yaitu, timbangan kehidupan, timbangan nilai, timbangan ‘amal, dan timbangan peristiwa-peristiwa.
Orang yang percaya kepada hari pembalasan ber‘amal dengan memperhatikan timbangan langit, bukan timbangan bumi; dan hisab (perhitungan) akhirat, bukan hisab dunia. Ia terima semua peristiwa yang baik dan yang buruk dengan memperhitungkannya sebagai pendahuluan yang kelak akan diperoleh balasannya di sana nanti. Maka, ia akan menyandarkan kepadanya semua hasil yang dinantikan ketika ia menimbang dan menakarnya.
Sedangkan, orang yang mendustakan hari pembalasan, menghitung segala sesuatu dengan perhitungan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan dunia yang singkat dan terbatas. Ia bergerak dan beraktivitas untuk sesuatu yang terbatas di bumi yang terbatas dan dalam masa yang terbatas oleh usia ini pula. Karena itu, hisabnya sering berubah-ubah, berbeda antara akibat dan pertimbangannya, dan berakhir pada akibat fatal yang melebihi keterbatasan ruang dan waktu yang memang terbatas ini. Akibatnya, ia sengsara, miskin, tersiksa, dan goncang hatinya. Karena, apa yang terjadi pada bagian kehidupan yang dipenuhi dengan angan-angan, perhitungan-perhitungan, dan perkiraan-perkiraannya ini sering tidak menenangkan hati, tidak menyenangkan, tidak adil, dan tidak rasional, selama tidak disadarkan pada bagian lain yang lebih besar dan lebih panjang ya‘ni iman kepada hari pembalasan.
Maka, celakalah orang yang tidak menghitung dengan perhitungan akhirat, atau mungkin juga akan dapat tegak lurus kehidupannya yang tinggi dan tidak dijumpai balasannya di dunia ini. Karena itu, percaya kepada hari pembalasan merupakan bagian iman yang dapat menegakkan manhaj kehidupan dalam Islām.
“Orang-orang yang takut terhadap ‘adzāb Tuhannya, karena sesungguhnya ‘adzāb Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman (dari kedatangannya)” (al-Ma‘ārij: 27-28.)
Ini adalah tingkatan yang lain di balik kepercayaan terhadap hari pembalasan. Yaitu, tingkat sensitivitas yang menggetarkan, kewaspadaan yang penuh kesadaran, dan perasaan mengenai kekurangan dirinya di sisi Allah padahal dia banyak dan rajin ber‘ibādah. Ia takut sewaktu-waktu hatinya berpaling dan ia layak mendapatkan ‘adzāb. Karena takut, ia lantas menghadapkan diri kepada Allah untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan.
Rasūlullāh s.a.w., orang yang tiada bandingnya tentang kedekatannya kepada Allah dan mengetahui bahwa Allah telah memilih dan memeliharanya, selalu merasa takut terhadap ‘adzāb Allah. Beliau yakin bahwa ‘amalan beliau saja tidak dapat melindunginya dan memasukkannya ke surga kecuali dengan karunia dan rahmat Allah. Beliau bersabda kepada sahabat-sahabatnya:
لَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ أَحَدًا عَمَلَهُ. قَالُوْا: وَ لَا أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: وَ لَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِرَحْمَتِهِ.
“‘Amal seseorang tidak akan dapat memasukkannya ke surga.” Para sahabat bertanya: “Tidak juga engkau wahai Rasūlullāh?” Beliau menjawab: “Tidak juga aku, kecuali karena Allah meliputiku dengan rahmat-Nya.” (HR. Bukhārī, Muslim, dan an-Nisā’ī).
Di dalam firman Allah: “Sesungguhnya ‘adzāb Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman (dari kedatangannya)”, terdapat isyārat yang menunjukan sensitivitas terus-menerus yang tidak pernah teralpakan sedetik pun. Karena, hal-hal yang mewajibkan ‘adzāb dapat saja datang sewaktu-waktu sehingga yang bersangkutan lantas layak mendapatkan ‘adzāb. Allah tidak menuntut kepada manusia melainkan sensitivitas dan kesadaran ini. Apabila mereka dikalahkan oleh kelemahannya, maka rahmat Allah itu luas dan ampunan-Nya senantiasa siap, sedang pintu tobat-Nya tidak pernah tertutup.
Demikianlah penegakan perkara dalam Islām, antara kelalaian dan kegoncangan, dan Islām bukanlah kelalaian dan kegoncangan ini. Sedangkan, hati yang selalu berhubungan dengan Allah akan senantiasa merasa takut dan berharap serta merasa tenang bersama rahmat Allah dalam kondisi apa pun.
“Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki. Maka, sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.” (al-Ma‘ārij: 29-31.)
Yang dimaksudkan oleh ayat-ayat ini adalah kesucian pribadi dan masyarakat. Karena, Islām menghendaki masyarakat yang suci bersih, indah, dan transparan. Masyarakat yang siap menunaikan tugas-tugas hidupnya, dan memenuhi panggilan fitrahnya. Akan tetapi, tanpa melakukan demoralisasi yang menghilangkan rasa malu yang indah, dan tanpa kebandelan yang mematikan transparansi yang bersih. Masyarakat yang ditegakkan di atas sendi kekeluargaan syar‘iyyah yang kuat dan tegak, dan rumah-tangga yang transparan dan jelas tanda-tandanya. Masyarakat yang setiap anak mengetahui siapa bapaknya, dan kelahirannya tidak memalukan, bukan masyarakat yang perasaan malunya telah sirna dari wajah dan jiwanya. Namun, hubungan biologis itu harus dilakukan berdasarkan prinsip yang suci dan transparan untuk jangka panjang dengan sasaran jelas, yang membangkitkan semangat untuk menunaikan tugas kemanusiaan dan sosial, bukan semata-mata memenuhi naluri kehidupan dan hasrat biologis.
Karena itulah, di sini al-Qur’ān menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang beriman: “Dan, orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki. Maka, sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”
Al-Qur’ān menetapkan kesucian hubungan biologis dengan istri dan budak yang diperoleh dengan jalan yang dibenarkan syara‘ dan diakui Islām. Yaitu, budak yang diperoleh sebagai tawanan di dalam perang fī sabīlillāh. Hanya jalan peperangan inilah satu-satunya yang diakui oleh Islām, dan sebagai dasar hukum tawanan ini ialah ayat al-Qur’ān yang tersebut dalam surah Muḥammad:
“Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang), maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga, apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti.” (Muḥammad: 4).
Tetapi, adakalanya terdapat tawanan yang tidak dibebaskan dan tidak ditebus karena kondisi tertentu. Dengan demikian, ia menjadi budak apabila si tentara memperbudak tawanan kaum Muslimīn dalam bentuk perbudakan apa pun, walaupun disebut dengan istilah lain. Nah, ketika itulah Islām memperbolehkan bagi pemiliknya saja untuk menggauli budak tersebut. Sedangkan, masalah pembebasannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan berbagai cara yang disyarī‘atkan oleh Islām untuk mengalirkan sumber ini.
Islām menegakkan prinsip-prinsipnya dengan jelas dan bersih. Ia tidak memberi peluang kepada tawanan-tawanan wanita itu untuk melakukan hubungan seks yang kotor sebagaimana yang biasa terjadi dalam peperangan-peperangan zaman dahulu maupun sekarang. Ia tidak pula memanipulasi dengan menyebut mereka sebagai orang merdeka padahal hakikatnya adalah budak.
“Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”
Dengan demikian, tertutuplah semua pintu hubungan seks yang kotor. Yaitu, hubungan seks yang tidak melalui dua pintu yang jelas dan terang ini (yaitu perkawinan dan perbudakan yang diperoleh dari peperangan). Islām tidak memperbolehkan manusia memenuhi fungsi naluriahnya dengan cara yang kotor, melalui penyimpangan-penyimpangan. Islām itu bersih, jelas, dan lurus.
“Juga orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya” (al-Ma‘ārij: 32.)
Ini termasuk standar akhlāq yang di atasnya Islām menegakkan tatanan kemasyarakatannya.
Memelihara amanat dan janji di dalam Islām dimulai dengan memelihara amanat terbesar yang telah ditawarkan Allah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi, karena mereka menolak untuk memikulnya dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, maka dipikullah amanat itu oleh manusia. Hal ini sebagaimana tersebut dalam surah al-Aḥzāb ayat 72.
Amanat terbesar adalah amanat ‘aqīdah dan komitmen padanya secara sukarela tanpa ada paksaan. Adapun perjanjian pertama yang ditetapkan atas fitrah manusia ketika mereka di dalam sulbi adalah bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan mereka, dan mereka naik saksi atas penciptaan mereka pada perjanjian ini.
Dari amanat dan perjanjian ini timbullah semua amanat dan perjanjian di dalam pergaulan dunia. Islām sangat ketat terhadap masalah amanat dan janji ini. Ia menyebutkannya secara berulang-ulang dan dipertegasnya, supaya masyarakat ditegakkan di atas landasan yang kokoh dari akhlāq kepercayaan, dan kemantapan. Juga menjadikan penunaian amanat dan perjanjian ini sebagai ciri jiwa yang beriman, sebagaimana ia menjadikan pengkhianatan terhadap amanat dan perjanjian ini sebagai ciri jiwa yang munāfiq dan kafir. Masalah ini disebutkan dalam banyak tempat di dalam al-Qur’ān dan as-Sunnah sehingga tidak dapat disangsikan lagi betapa pentingnya masalah ini dalam tradisi Islām.
“Orang-orang yang memberikan kesaksiannya.” (al-Ma‘ārij: 33.)
Allah menggantungkan banyak hak kepada penunaian kesaksian ini. Bahkan, pelaksanaan ḥudūd (hukum ḥadd) pun digantungkan pada adanya kesaksian ini. Karena itulah, Allah mempertegas penunaian kesaksian ini dan tidak dibolehkan mengabaikan kesaksian sama sekali, serta tidak dibolehkan menyembunyikan kesaksian di dalam sidang peradilan. Di antara bentuk pemberian kesaksian itu adalah menyampaikannya secara benar tanpa ada kecenderungan kepada salah satu pihak. Bahkan, Allah menghubungkan penunaian kesaksian ini dengan ketaatan kepada-Nya sebagaimana firman-Nya:
“Tegakkanlah kesaksian karena Allah.” (ath-Thalāq: 2).
Di sini Allah menjadikan penunaian kesaksian sebagai sifat orang-orang beriman yang merupakan salah satu dari sekian bentuk amanat, yang disebutkan sendiri di sini untuk menunjukkan betapa pentingnya hal ini.
Sebagaimana dimulainya penyebutan ciri-ciri jiiwa yang beriman dengan shalāt, maka penyebutan ini juga diakhiri dengan shalāt:
“Dan, orang-orang yang memelihara shalātnya.” (al-Ma‘ārij: 34.)
Ini adalah sifat yang berbeda dengan sifat kekekalan yang disebutkan pada permulaan tadi. Sifat ini terwujūd dengan memelihara shalāt pada waktunya, sesuai dengan kefardhuan-kefardhuannya, memenuhi sunnah-sunnahnya, sesuai dengan aturannya, dan ditunaikan dengan ruhnya. Maka, mereka tidak meninggalkannya karena mengabaikannya atau malas, dan tidak menyia-nyiakannya tanpa menyesuaikannya dengan aturan-aturannya. Disebutnya shalāt pada permulaan dan penutupan tema ini menunjukkan betapa pentingnya shalāt itu, dan dengan penyebutan shalat tersebut diakhirilah semua sifat dan ciri-ciri orang-orang yang beriman.
Setelah itu ditetapkanlah tempat kembali golongan manusia beriman setelah sebelumnya ditetapkan tempat kembalinya golongan lain (yang tidak beriman):
“Mereka itu (kekal) di surga lagi dimuliakan.” (al-Ma‘ārij: 35.)
Kalimat singkat dalam nash ini menghimpun antara jenis keni‘matan indrawi dengan jenis keni‘matan spiritual. Mereka berada di dalam surga, dan mereka mendapatkan kemuliaan di sana. Maka, terkumpullah bagi mereka kelezatan dengan keni‘matan disertai dengan kemuliaan, sebagai balasan atas akhlāqnya yang mulia, yang menjadi ciri khas orang-orang yang beriman.