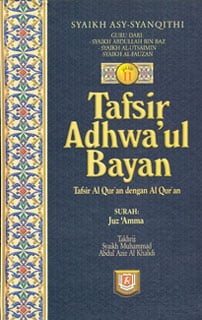Pembahasan Kelima
Dalam hal penuh sesaknya masjid dan shaf memanjang hingga keluar masjid di jalan atau lapangan, apakah shaf yang belakang tersebut mendapatkan pelipat-gandaan itu?
Keutamaan jama‘ah bisa didapatkan tanpa perselisihan pendapat. Tentang kelipatan hingga seribu, saya tidak menemukan nashnya, dan saya telah menanyakan masalah tersebut kepada Syaikh sebanyak dua kali. Pada kali yang pertama ia cenderung mengkhususkan hal itu kepada masjid, sedangkan pada kali yang kedua dan di antara keduanya, sekitar sepuluh tahun, ia cenderung memberlakukan keumuman pahala.
Ia mengatakan yang semakna, bahwa perluasaan bangunan adalah keutamaan dari Allah s.w.t., dan ini adalah karunia untuk hamba-hambaNya bagi orang yang menginginkan keluasan keutamaan Allah s.w.t., karena tidak ada dua orang dalam shaf yang berdekataan, yang salah satunya berada dalam ambang pintu masjid sampai keluar, sedangkan yang lain berada di luar sampai ke dalam, sehingga seribu ini diberikan kepada salah satunya, dan yang satunya diberikan pahala satu. Punggung keduanya saling berdekatan, dan ini jelas, wal-ḥamdulillāh.
Saya melihat dalam masalah Jum‘at menurut Mālikiyyah sebuah nash. Demikian juga menurut yang selainnya di antara yang mensyaratkan masjid untuk shalat Jum‘at, mereka sepakat bahwa jika barisan memanjang hingga ke jalan dan lapangan di luar masjid, maka Jum‘atnya sah, padahal mereka menunaikannya di luar masjid. Akan tetapi, karena shaf memanjang hingga keluar masjid, maka baginya ditarik hukum masjid dan sah Jum‘atnya.
Di sini kami katakan: Demikian juga ketika shaf keluar dari masjid Nabi, maka ditarik baginya hukum masjid, in syā’ Allāh. Wallāhu a‘lam.
Juga apabila dilakukan istidlāl secara kebiasaan, yakni bahwa jika saya bertanya kepada orang yang shalat dalam keadaan demikian, yakni apakah kamu telah shalat di masjid Nabi? Atau apakah kamu shalat di Qubā’? Maka ia akan menjawab: “Ya, di masjid Nabi”, karena posisi itu tidak keluar dari apa yang disebut masjid berdasarkan kebiasaan.
Pembahasan Keenam
Ketika penuh berdesakan di masjid Nabi khususnya, dan di masjid-masjid lainnya secara umum, ketika tempat menjadi sempit dan orang-orang terpaksa shalat di luar masjid dan di depan Imām beberapa kaki dengan banyak shaf, maka bagaimana hukum shalat mereka?
An-Nawawī menyebutkan dalam al-Majmū‘ tentang perbedaan pendapat dari asy-Syāfi‘ī, bahwa yang benar dari madzhab adalah sah, meski makruh.
Mālikiyyah menyebutkan sahnya keadaan demikian. Mereka ber-istidlāl untuk itu dengan shalatnya Ibnu ‘Abbās r.a. suatu malam di rumah Maimūnah dengan shalat Nabi s.a.w. Ibnu ‘Abbās pada waktu itu masih anak-anak, dan ia berdiri di sebelah kiri Nabi s.a.w., sehingga Rasūlullāh s.a.w. berada di sisi kanannya sebagai bentuk memuliakan Rasūlullāh s.a.w. Ketika Rasūlullāh s.a.w. merasakan itu, dan setelah ia telah dewasa dan harus mengerjakan shalat, Nabi s.a.w. meraih tangannya dan memindahkannya dari belakangnya dan menjadikannya berada di sisi kanan Nabi s.a.w. dengan kaki berada di satu tempat, sebagaimana telah maklum dari hukum shalat sendirian dengan imam. (233).
Posisi istidlāl dalam hal itu bahwa terdapat empat arah dalam kaitannya dengan imam shalat.
Di belakangannya, yakni bagi dua orang makmum atau lebih. Sisi kanan, yakni untuk posisi makmum sendirian. Sisi kirinya dan sisi depan. Adapun sisi kiri, Ibnu ‘Abbās pernah melakukannya dan itu bukan merupakan posisi yang tepat, maka Nabi s.a.w. memindahkannya hingga berada di sisi kanan beliau. Akan tetapi ketika ia telah masuk dalam shalat dan melakukan sebagian shalat pada tempat itu (sisi kiri), maka shalatnya tetap sah, sekalipun ia memulai shalatnya pada posisi yang tidak dibenarkan karena darurat ketidak-tahuan mengenai posisi yang tepat. Adapun arah depan, maka itu bukan posisi yang tepat, akan tetapi ketika ada darurat karena penuh sesak, maka maju melebihi imam tidak apa-apa, boleh, atau dapat dikatakan shalatnya tetap sah karena adanya faktor darurat, sebagaimana sahnya shalat di sebelah kiri Nabi s.a.w. Wallāhu a‘lam.
Istidlāl ini menjadi kuat jika seseorang mendatangi shalat jama‘ah dan tidak menemukan tempat selain di samping imam, maka ia berdiri di sisi kanannya, sebagaimana jika ia sendirian, padahal ada banyak shaf, akan tetapi posisinya sah karena keadaan darurat.
Pembahasan Ketujuh
Tentang shalat arba‘īn yakni yang khusus di masjid Nabi, dan secara umum di semua masjid, akan tetapi yang dimaksud arba‘īn (empat puluh) bukan berarti shalat empat puluh kali, melainkan shalat 40 hari. Adapun pengkhususan yang terdapat pada masjid Nabi adalah hadis Anas r.a. dari Nabi s.a.w., bahwa beliau bersabda:
مَنْ صَلَّى فِيْ مَسْجِدِيْ أَرْبَعِيْنَ صَلَاةً لَا تَفُوْتُهُ صَلَاةٌ كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ وَ نَجَاةٌ مِنَ الْعَذَابِ وَ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ.
“Barang siapa shalat di masjidku 40 shalat yang tidak tertinggal satu shalat pun, maka ditetapkan baginya pembebasan dan keselamatan dari adzab, serta bebas dari sifat kemunafikan.”
Dalam at-Targhību wat-Tarhīb al-Mundzirī berkata: “Para rawinya shaḥīḥ. Diriwayatkan oleh Aḥmad dalam Musnad-nya (234) dan ath-Thabrānī dalam al-Ausath.” (235).
Dalam Majma‘-uz-Zawā’id dikatakan: “Rijāl-nya tsiqah.”
Dalam at-Tirmidzī lafazhnya:
مَنْ صَلَّى للهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِيْ جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيْرَةَ الْأُوْلَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَ بَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ.
“Barang siapa shalat 40 hari secara berjama‘ah, yang ia mendapati takbir pertama, maka ditetapkan baginya dua pembebasan/keselamatan; keselamatan dari neraka dan keselamatan daari kemunafikan.” (236).
At-Tirmidzī berkata: “Hadits ini mauqūf pada Anas, dan aku tidak mengetahui seorang pun me-marfū‘-kannya.”
Mulla ‘Alī al-Qārī berkata: Riwayat seperti ini tidak dinyatakan melalui pendapat pribadi, karena sebagian orang menyatakan dalam masalah ini melalui hadits dengan dua riwayat:
Pertama, karena Nubaith bin ‘Umar.
Kedua, dari segi ke-marfū‘-an dan ke-mauqūf-an.
Terhadap dua hadits tersebut sebagian ulama telah terus-menerus meneliti sanad-nya dan menetapkan keabsahan yang pertama dan hukum marfū‘ untuk yang kedua.
Syaikh Ḥammād al-Anshārī membahas keduanya secara khusus dalam risalah yang di dalamnya terdapat penolakan kepada perkataan sebagian kalangan Muta’akhkhirīn tentang keduanya, dan kami mengutip pernyataannya sebagai berikut:
“Al-Ḥāfizh Ibnu Ḥajar dalam menyegerakan manfaat dalam Zawā’id-ul-Arba‘ah berkata: Nubaith bin ‘Umar, disebutkan oleh Ibnu Ḥibbān dalam ats-Tsiqāt, sehingga terpadu anggapan tsiqat terhadap Nubaith dari Ibnu Ḥibbān, al-Mundzirī, al-Baihaqī, dan Ibnu Ḥajar. Juga tidak dianggap cela oleh seorang pun dari kalangan ulama terkait. Oleh karena itu, tidak boleh seorang pun mencela dan menganggap dha‘īf orang yang dianggap tsiqah oleh para Imām terkemuka, dan tidak ditentang oleh seorang Imām pun dari kalangan ahli jarḥ wa ta‘dīl. Cukup dari para ulama ahli di bidang ini sebagai teladan.”
Demikianlah, meski seandainya terdapat perdebatan mengenai sanad dalam riwayat ini, maka para Imām hadits tidak melarangnya selama hadits tersebut tidak menyangkut perkara halal, haram, atau akidah. Melainkan hanya dalam masalah keutamaan amal, dan pembahasan tentang keutamaan amal tidak ditekankan sekeras pembahasan tentang hukum halal, haram, atau menyakut aqidah.
As-Suyūthī mengutip yang seperti ini dari Aḥmad dan Ibnu Mubārak.
Adapun hadits yang menyatakan menemukan takbīrat-ul-iḥrām di masjid manapun, maka lebih umum daripada tema masjid Nabi (Masjid Nabawi) yang sedang dibicarakan tersebut, dan semua sanad-nya dha‘īf, tetapi al-Ḥāfizh Ibnu Ḥajar berkata: “Termasuk dalam kandungan apa yang diamalkan dari keutamaan-keutamaan amal.” Pembahasan secara singkat selesai.
Anjuran kepada shalat arba‘īn di masjid Nabi, mungkin termasuk dalam masalah membiasakan diri dan membekali diri, karena melakukan amal tersebut adalah melanggengkan dan menjaga pelaksanaan shalat lima waktu selama delapan hari dalam keadaan berjama‘ah, dan kesibukannya yang terus-menerus serta pemeliharaannya tehadap shalat hingga ia tidak tertinggal dari hal yang menggantungkan hatinya kepada masjid, maka jama‘ah menjadi kebiasaan dan menjadi orang yang puas karena sering mendatangi masjid dan menjaga seluruh shalat di semua harinya sehingga tidak ketinggalan jama‘ah kecuali ‘udzur.
Jika ia sedang berkunjung dan kembali ke negerinya, maka ia kembali dalam tabiat yang terpuji, dan mungkin dalam hal kelipatan shalat dengan seribu menjadi obat yang dipadatkan yang sangat manjur, yang bekerja cepat, lebih banyak daripada yang datang pada masjid umum dengan 40 hari yang tidak ketinggalan takbīrat-ul-iḥrām, karena 40 shalat di masjid Nabi sama dengan 40.000 shalat di tempat lain, yakni sama dengan sekitar shalat selama 72 tahun.
Jika kita memperhatikan pahala jama‘ah yang 25 derajat, maka akan sama dengan shalat sendirian 550 tahun, yakni dalam hal pahala, bukan dalam hal hitungan, yakni kualitas bukan kuantitas, dan karunia Allah itu agung.
Hendaknya diketahui bahwa tujuan dari 40 ini adalah sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam hal membiasakan diri dan menjaga shalat jama‘ah.
Adapun jika ia kembali dan meninggalkan jama‘ah serta melengahkan masalah shalat, maka hendaknya ia meminta perlindungan kepada Allah s.w.t., karena itu menjadi puncak kemunduran. Kita meminta kesehatan kepada Allah s.w.t., sebagaimana kita ketahui bahwa 40 shalat tidak ada kaitannya dengan haji dan ziarah, sebagaimana dipaparkan oleh Syaikh dalam pembahasan tentang tatakarma ziarah dalam surah al-Ḥujurāt.
Ziarah menjadi sempurna dengan shalat dua rakaat tahiyyat-ul-masjid dan mengucapkan salam kepada Rasūlullāh s.a.w., kemudian berdoa untuk dirinya sendiri dan kaum muslim untuk kebaikan, kemudian jika ia ingin ia boleh kembali ke keluarganya, dan jika ia ingin maka ia boleh duduk yang bisa membuatnya senang.
Catatan: