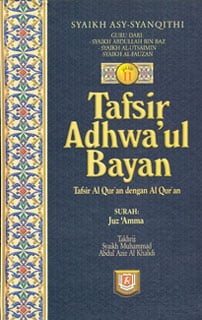Pembahasan Kedua
Manakah yang lebih utama bagi perempuan, shalat di rumah atau di masjid Nabi?
Masalah ini telah dibahas oleh syaikh pada pembahasan firman Allah: (فِيْ بُيُوْتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَ الْأَصَالِ، رِجَالٌ) “Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang, laki-laki (yang)…..” (Qs. an-Nūr [24]: 36-37).
Mafhūm (رِجَالٌ) “Laki-laki” adalah mafhūm shifat dalam masalah ini, bukan mafhūm laqab, maka bagi perempuan bertasbih di rumah.
Pembahasan telah diberikan secara memadai pada keumuman masjid dan kekhususan Masjid Nabi, maka tidak perlu dibahas secara lebih luas lagi.
Pembahasan Ketiga
Apakah kelipatan itu khusus di Masjid Nabi yang beliau bangun, dan yang ada pada masa beliau hidup? Atau juga bisa diperoleh setelah dilakukan perluasan bangunan?
Pembahasan ini berkisar pada nash yang terdapat dalam hadits yang berkaitan, yaitu isim isyārah yang terdapat pada lafazh (فِيْ مَسْجِدِيْ هذَا) “di masjidku ini”. Sebagian ulama berpendapat bahwa isim isyārah adalah objek untuk menentukan. Para ulama yang lain berpendapat bahwa ia adalah objek untuk posisi umum pada tempat yang khusus, maka dikhususkan dalam penggunaan dengan mufrad tertentu, yang sesuai dengan petunjuk inderawi, dan itu adalah yang sebenarnya ada pada zaman Nabi s.a.w.
Telah maklum bahwa isyarat tidak menerima penambahan yang ada setelah isyarat tersebut, maka dari sinilah timbul perbedaan pendapat dan pertanyaan.
Pertanyaan ini muncul pada zaman ‘Umar r.a. ketika awal penambahan yang ia lakukan pada Masjid Nabawi. Oleh karena itu, sebagian sahabat menghindari shalat pada penamabahan itu dan lebih senang pada bagian yang lama. Itulah sebabnya ‘Umar r.a. berkata kepada mereka: “Seandainya aku tidak mendengar Rasūlullāh s.a.w. berkeinginan memperluas masjid, maka aku tidak akan memperluasnya, dan demi Allah itu adalah masjid Rasūlullāh s.a.w., dan meski akan meluas hingga Dzul-Ḥulaifah atau hingga Shan‘ā’.” Pertanyaan inilah yang menjadi motif dan sebab pembahasan.
Akan tetapi, jika dikatakan bahwa dalam hadits yang sama terdapat pembahasan lughawiyyah (kebahasaan) lain, yakni bahwa sabda Nabi s.a.w. (فِيْ مَسْجِدِيْ) yang di-idhāfah-kan kepada beliau, maka idhāfah itu berfungsi men-takhshīsh atau ta‘rīf.
Di dalamnya juga terdapat makna keumuman dan pencakupan, dan sekarang dengan tambahan yang terjadi setiap masa dan sepanjang masa, maka itu masih tetap masjid Rasūlullāh s.a.w.
Dalam riwayat tersebut juga terdapat penegasan dari ‘Umar r.a. bahwa itu adalah masjid Rasūlullāh s.a.w.
Pendapat para ulama: “Jumhur mengatakan bahwa penggandaan pahala shalat pada semua bagiannya meliputi tambahan yang ada, dan dikutip dari an-Nawawī dalam Syarḥ Muslim, bahwa penggandaan itu khusus pada Masjid Nabi saja.”
Pendapat pertama, sebelum adanya penambahan, dan ada yang mengatakan bahwa pendapat itu telah ditarik kembali. Penarikan pendapat ini terdapat dalam al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzab, dengan demikian tidak ada lagi perbedaan pendapat dalam masalah tersebut.
Ibnu Farhum berkata: Aku memperhatikan jawaban Mālik ketika ditanya tentang hal itu, ia menjawab: “Aku tidak melihat Nabi s.a.w. mengisyaratkan dengan sabda beliau “di masjidku ini” melainkan meliputi perubahan yang akan terjadi setelahnya (dengan pemugaran dan perluasan), dan Allah s.w.t. telah memperlihatkan hal itu kepada beliau.
Telah dipaparkan isyarat bahwa ‘Umar r.a. tidak menambahkan masjid kecuali setelah mendengar dari Rasūlullāh s.a.w. tentang keinginan beliau untuk memperluasnya, dan itu menjadi penguat bagi pendapat Mālik.
Diriwayatkan juga bahwa Nabi s.a.w. bersabda – ketika beliau berada di tempat shalatnya di masjid – : (لَوْ زِدْنَا فِيْ مَسْجِدِنَا) “Seandainya kita memperluas masjid kita” dan beliau memberikan isyarat dengan tangannya ke arah qiblat.
Dalam satu riwayat dikatakan: (إِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ أَزِيْدَ فِيْ قِبْلَةِ مَسْجِدِنَا) “Aku ingin menambahkan di qiblat masjid kita” yang menunjukkan bahwa penambahan telah diperhitungkan oleh Rasūlullāh s.a.w.
Dengan adanya keinginan untuk membuat tambahan, namun tidak ada isyarat yang merubah hukum shalat pada tambahan yang ditunggu-tunggu itu (direncanakan) tersebut. Keutamaan shalat di masjid Nabi itu juga tidak dikatakan untuk sebelum adanya tambahan dan tambahan yang akan ada tidak berkaitan dengan hukum yang telah ditetapkan, karena kita menyaksikan bahwa Rasūlullāh s.a.w. telah menetapkan hukum-hukum atas masalah-masalah yang belum ada, seperti miqat-miqat untuk penduduk Mesir, Syām, dan ‘Irāq, dan seperti sabda beliau: (سَتُفْتَحُ الْيَمَنُ وَ سَتُفْتَحُ الشَّامُ وَ سَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ.) “Yaman akan ditaklukkan, Syām akan ditaklukkan dan ‘Irāq akan ditaklukkan.” (232).
Selain itu juga beliau bersabda: “Akan didatangkan kaum-kaum yang menyeru, marilah menuju kemakmuran dan kelapangan sehingga mereka membawa keluarga dan orang-orang yang patuh kepada mereka, padahal Madīnah lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahui.”
Sebagian ulama mengatakan bahwa sabda beliau: “Di masjidku ini”, untuk menolak keraguan masuknya seluruh masjid yang dinisbatkan kepada beliau di Madīnah selain masjid ini. Dan bukan untuk mengeluarkan perluasan yang akan ditambahkan ke dalam masjid Nabi. Ini dikatakan oleh as-Samhudī. Pembahasan selesai.
Akan tetapi, tidak diketahui bahwa terdapat banyak masjid Nabi, maka tidak ada selain masjid serta mushalla, dan semua masjid disebutkan dengannya sesuai pengertian istilah.
Terdapat ulasan Syaikhu Islām Ibnu Taimiyyah yang mencukupi tentang hal tersebut, yakni penambahan adalah pada masa ‘Umar r.a. dan ‘Utsmān r.a.
Terjadi penambahan dari keduanya dari arah qiblat dan selain itu, maka masing-masing dari keduanya jika shalat dengan orang-orang maka berdiri di qiblat yang terletak di bagian bangunan penambahan tersebut, sehingga jika dikatakan bahwa keduanya terhalang dari mendapatkan keutamaan masjid, tidaklah benar, karena dalam kondisi demikian ‘Umar r.a. dan ‘Utsmān r.a. wajib shalat bersama dengan orang-orang di bangunan tambahan tersebut.
Shalat orang-orang bersama mereka pada shaf pertama di tempat yang diutamakan dengan meninggalkan yang lebih utama. Pembahasan selesai.
Dari semua yang telah kami paparkan, jelas bahwa hukum bangunan tambahan pada masjid Nabi adalah seperti hukum bangunan asal dalam hal kelipatan pahala hingga seribu.
Saya mendengar syaikh mengisyaratkan hal itu, dan uraiannya akan diberikan dalam pembahasan shalat arba‘īn, dan shalatnya orang di shaf, di luar masjid.
Peringatan
Mengenai pelipat-gandaan yang mereka sepakati ini adalah dalam hal kualitas, bukan kuantitas. Seandainya seseorang terlewat satu dari lima waktu shalat dan menunaikan satu shalat yang lebih baik daripada seribu shalat, maka itu tidak berarti menggugurkan sedikit pun dari shalat yang terlewat tersebut. Ini menurut pandangan saya dalam kaitannya dengan satu baju dengan baju lainnya yang salah satunya berharga 1000 dirham dan lainnya berharga satu dirham, maka masing-masing dari keduanya adalah baju dalam hal arti pentingnya, dan baju bersebut tidak dapat dipakai oleh lebih dari satu orang dalam satu waktu meski harganya lebih mahal.
Demikian juga pena, meski satu pena harganya mahal, namun pena tersebut tidak dapat dipakai oleh dua orang dalam waktu yang bersamaan.
Peringatan lain
Dari hal yang tidak diragukan lagi bahwa masjid yang asal memiliki kekhususan yang tidak terdapat pada lain di bagian tambahan masjid, seperti taman dari surga (raudhah), mimbar yang merupakan salah satu dari pintu surga, dan sebagian tiang yang memiliki nilai sejarah.
An-Nawawī berkata: “Jika seseorang hendak shalat sendirian atau shalat sunnah, maka yang lebih utama hendaklah di raudhah, dan jika tidak maka di masjid yang pertama, dan jika tidak maka di tempat manapun di masjid, dan inilah makna yang logis, alḥamdulillāh.”
Pembahasan Keempat
Setelah perluasan ini dan pindahnya shaf pertama dari raudhah, maka manakah yang lebih utama, shalat berjamaah di shaf pertama atau shalat berjamaah di raudhah dengan tidak menempati yang pertama? Untuk menggambarkan masalah ini kami mengajukan yang berikut ini:
Orang yang shalat di masjid ini menghadapi dua hal, yang pertama raudhah, dengan keutamaannya sebagai salah satu dari taman surga. Yang kedua adalah menempati shaf pertama (terdepan), dengan keutamaannya sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi s.a.w.: “Kalau saja mereka mengetahui keutamaan yang terdapat pada shaf pertama, tentu mereka akan melakukan undian untuk mendapatkannya.” Lalu manakah yang lebih utama di antara keduanya?
Telah maklum bahwa sebelum diadakan perluasan, siapapun mungkin mendapatkan dua keutamaan itu, karena shaf pertama terletak di raudhah.
Sekarang, setelah dilakukan perluasan, shaf pertama terpisah dari raudhah, selama imam shalat di bagian depan masjid, dan saya tidak memperincikan masalah ini.
Hanya saja keumuman-keumuman menurut an-Nawawī dan Syaikh Ibnu Taimiyyah sebagaimana yang telah kami paparkan dalam pembahasan pencakupan pelipat-gandaan pahala pada bangunan tambahan setelah perluasan. Juga adanya permasalahan yang mungkin diambil jawaban darinya, yaitu bahwa sebelum dilakukan perluasan, shaf pertama memiliki sisi kanan dan sisi kiri, dan sisi kanan memiliki keutamaan daripada yang sebelah kiri. Telah maklum bahwa shaf pertama sisi kanan sebelum perluasaan berada di sebelah barat mimbar, yakni di luar raudhah, shaf pertama sisi kiri seluruhnya berada di dalam raudhah. Padahal mereka lebih mengutamakan sisi kanan daripada sisi kiri itu karena keberadaannya yang sebelah kanan, demikian pula dengan keutamaan shalat di dalam raudhah. Jika shaf sisi kanan berada di luar raudhah lebih diutamakan oleh mereka daripada di dalam raudhah, maka tentu lebih diutamakan juga shalat di shaf yang pertama.
Di situ terdapat hakikat fikih yang disebutkan oleh an-Nawawī, yakni mendahulukan sifat dzat daripada sifat bukan dzat. Di sini sifat pertama adalah sifat dzat untuk jama‘ah, dan keutamaan raudhah adalah keutamaan sifat untuk sebuah tempat, yakni untuk semua keadaan berupa dzikir, shalat fardhu atau sunnah, maka mendadulukan shaf pertama karena adanya sebagai dzat dalam kaitannya dengan jama‘ah lebih utama daripada mendahulukan raudhah karena adanya adalah sebagai sifat yang bukan dzat.
An-Nawawī memberikan contoh untuk kaidah ini dengan menyatakan bahwa jika seseorang dalam perjalanannya menuju shalat di masjid Nabi, kemudian menemukan masjid lain, yang ia dapat melaksanakan shalat secara berjama‘ah di dalamnya. Manakah yang lebih utama antara ikut shalat jama‘ah bersama mereka atau tetap melanjutkan perjalanan hingga sampai di masjid Nabi, namun di tertinggal shalat berjama‘ah dan hanya dapat melakukan shalat sendirian dengan keutamaan seribu shalat? Maka ia menjawab: Shalat di masjid itu secara berjama‘ah lebih utama baginya, karena keutamaan shalat berjama‘ah merupakan shifāt dzāti untuk shalat (yang melekat pada dzatnya), dan keutamaan seribu shalat adalah sifat yang bukan dzāti, melainkan karena keutamaan masjid Nabi itu sendiri. Pembahasan selesai secara ringkas.
Dikatakan juga bahwa seorang hamba dibebankan untuk yang menunaikan shalat berjama‘ah di masjid Nabi. Demikian pula dengan keutamaan mendapatkan shaf pertama secara mutlak, kemudian sebagai tambahan juga dibebankan untuk mendapat keutamaan shalat di dalam raudhah.