Surah al-Ikhlash 112 ~ Tafsir al-Azhar
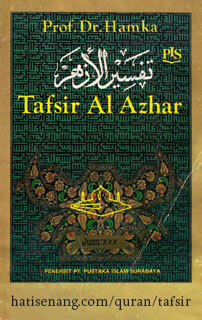
Dari Buku:
Tafsir al-Azhar
Oleh: Prof. Dr. HAMKA
Penerbit: PT. Pustaka Islam Surabaya
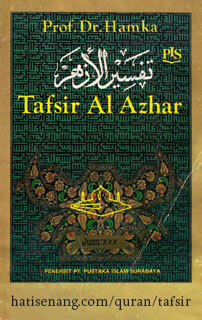
Dari Buku:
Tafsir al-Azhar
Oleh: Prof. Dr. HAMKA
Penerbit: PT. Pustaka Islam Surabaya
112
Sūrat-ul-Ikhlāsh, Ayat: 1-6.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ
Dengan Nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang
قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ. اللهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُوْلَدْ. وَ لَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ
112:1. Katakanlah: “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa.
112:2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
112:3. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan,
112:4. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.
(al-Ikhlāsh [112]: 1-4).
“Katakanlah” – Hai Utusan-Ku- “Dia adalah Allah, Maha Esa.” (ayat 1). Inilah pokok pangkal akidah, puncak dari kepercayaan. Mengakui bahwa yang dipertuhan itu ALLAH nama-Nya. Dan itu adalah nama dari Satu saja. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia Maha Esa, mutlak Esa, tunggal, tidak bersekutu yang lain dengan Dia.
Pengakuan atas Kesatuan, atau Keesaan, atau tunggal-Nya Tuhan dan nama-Nya ialah Allah, kepercayaan itulah yang dinamai TAUHID. Berarti menyusun fikiran yang suci murni, tulus ikhlas bahwa tidak mungkin Tuhan itu lebih dari satu. Sebab Pusat Kepercayaan di dalam pertimbangan akal yang sihat dan berfikir teratur hanya sampai kepada SATU.
Tidak ada yang menyamai-Nya, tidak ada yang menyerupai-Nya dan tidak pula ada teman hidup-Nya. Karena mustahillah kalau Dia lebih dari satu. Karena kalau Dia berbilang, terbahagilah kekuasaan-Nya. Kekuasaan yang terbagi, artinya sama-sama kurang berkuasa.
“Allah adalah pergantungan.” (ayat 2). Artinya, bahwa segala sesuatu ini adalah Dia yang menciptakan, sebab itu maka segala sesuatu itu kepada-Nyalah bergantung. Ada atas kehendak-Nya.
Kata Abū Hurairah: “Arti Ash-Shamadu ialah segala sesuatu memerlukan dan berkehendak kepada Allah, berlindung kepada-Nya, sedang Dia tidaklah berlindung kepada sesuatu jua pun.
Ḥusain bin Fadhal mengartikan: “Dia berbuat apa yang Dia mau dan menetapkan apa yang Dia kehendaki.”
Muqātil mengartikan: “Yang Maha Sempurna, yang tidak ada cacat-Nya.”
“Tidak Dia beranak, dan tidak Dia diperanakkan.” (ayat 3).
Mustahil Dia beranak. Yang memerlukan anak hanyalah makhluk bernyawa yang menghendaki keturunan yang akan melanjutkan hidupnya. Seseorang yang hidup di dunia ini merasa cemas kalau dia tidak mendapat anak keturunan. Karena dengan keturunan itu berarti hidupnya akan bersambung. Orang yang tidak beranak kalau mati, selesailah sejarahnya hingga itu. Tetapi seseorang yang hidup, lalu beranak dan bersambung lagi dengan cucu, besarlah hatinya, karena meskipun dia mesti mati, dia merasa ada yang menyambung hidupnya.
Oleh sebab itu maka Allah subḥānahu wa ta’ālā mustahil memerlukan anak. Sebab Allah hidup terus, tidak akan pernah mati-mati. Dahulunya tidak berpemulaan dan akhirnya tidak berkesudahan. Dia hidup terus dan kekal terus, sehingga tidak memerlukan anak yang akan melanjutkan atau menyambung kekuasaan-Nya sebagai seorang raja yang meninggalkan putera mahkota.
Dan Dia, Allah itu, tidak pula diperanakkan. Tegasnya tidaklah Dia berbapa. Karena kalau dia berbapa, teranglah bahwa si anak kemudian lahir ke dunia dari ayahnya, dan kemudian ayah itu pun mati. Si anak menyambung kuasa. Kalau seperti orang Nasrani yang mengatakan bahwa Allah itu beranak dan anak itu ialah Nabi Isa Almasih, yang menurut susunan kepercayaan mereka sama dahulu tidak bepermulaan dan sama akhir yang tidak berkesudahan di antara sang bapa dengan sang anak, maka bersamaanlah wujud di antara si ayah dengan si anak, sehingga tidak perlu ada yang bernama bapa dan ada pula yang bernama anak. Dan kalau anak itu kemudian baru lahir, nyatalah anak itu suatu kekuasaan atau ketuhanan yang tidak perlu, kalau diakui bahwa si bapa kekal dan tidak mati-mati, sedang si anak tiba kemudian.
“Dan tidak ada bagi-Nya yang setara, seorang jua pun.” (ayat 4).
Keterangan: Kalau diakui Dia beranak, tandanya Allah Tuhan itu mengenal waktu tua. Dia memerlukan anak untuk menyilihkan kekuasaan-Nya.
Kalau diakui diperanakkan, tandanya Allah itu pada mulanya masih muda yaitu sebelum bapa-Nya mati. Kalau diakui bahwa Dia terbilang, ada bapa ada anak, tetapi kedudukannya sama, fikiran sihat yang mana jua pun akan mengatakan bahwa “keduanya” akan sama-sama kurang kekuasaannya. Kalau ada dua yang setara, sekedudukan, sama tinggi pangkatnya, sama kekuasaannya atas alam, tidak ada fikiran sihat yang akan dapat menerima kalau dikatakan bahwa keduanya itu berkuasa mutlak. Dan kalau keduanya sama tarafnya, yang berarti sama-sama kurang kuasa-Nya, yakni masing-masing mendapat separuh, maka tidaklah ada yang sempurna ketuhanan keduanya. Artinya bahwa itu bukanlah tuhan. Itu masih alam, itu masih lemah.
Yang Tuhan itu ialah Mutlak Kuasa-Nya, tiada berbagi, tiada separuh seorang, tiada gandingan, tiada bandingan dan ada tiada tandingan. Dan tidak pula ada tuhan yang nganggur, belum bertugas sebab bapanya masih ada!
Itulah yang diterima oleh perasaan yang bersih murni. Itulah yang dirasakan oleh akal cerdas yang tulus. Kalau tidak demikian, kacaulah dia dan tidak bersih lagi. Itu sebabnya maka Surat ini dinamai pula Sūrat-ul-Ikhlāsh, artinya sesuai dengan jiwa murni manusia, dengan logika, dengan berfikir teratur.
Tersebutlah di dalam beberapa riwayat yang dibawakan oleh ahli tafsir bahwa asal mula Surat ini turun:
صِفْ لَنَا رَبَّكَ.
“Shif lanā rabaka” ialah karena pernah orang musyrikin itu meminta kepada Nabi (Coba jelaskan kepada kami apa macamnya Tuhanmu itu, emaskah dia atau tembaga atau loyangkah?).
Menurut Hadis yang dirawikan oleh Tirmidzī dari Ubay bin Ka’ab, memang ada orang musyrikin meminta kepada Nabi supaya diuraikannya nasab (keturunan atau sejarah) Tuhannya itu. Maka datanglah Surat yang tegas ini tentang Tuhan.
Abus-Su’ūd berkata dalam tafsirnya: “Diulangi nama Allah sampai dua kali (ayat 1 dan ayat 2) dengan kejelasan bahwa Dia adalah Esa, Tunggal, Dia adalah penggantungan segala makhluk, supaya jelaslah bahwa yang tidak mempunyai kedua sifat pokok itu bukanlah Tuhan. Di ayat pertama ditegaskan Keesaan-Nya, untuk menjelaskan bersih-Nya Allah dari berbilang dan bersusun, dan dengan sifat Kesempurnaan.
Dia tempat bergantung, tempat berlindung; bukan Dia yang mencari perlindungan kepada yang lain, Dia tetap ada dan kekal dalam kesempurnaan-Nya, tidak pernah berkurang. Dengan penegasan “Tidak beranak”, ditolaklah kepercayaan setengah manusia bahwa malaikat itu adalah anak Allah atau ‘Īsā al-Masīḥ adalah anak Allah. Tegasnya dari Allah itu tidak ada timbul apa yang dinamai anak, karena tidak ada sesuatu pun yang mendekati jenis Allah itu, untuk jadi jodoh dan “teman hidupnya”, yang dari pergaulan berdua timbullah anak.”
Sekian Abus-Su’ūd.
Imām Ghazalī menulis di dalam kitabnya “Jawāhir-ul-Qur’ān” : “Kepentingan Al-Qur’ān itu ialah untuk ma’rifat terhadap Allah dan ma’rifat terhadap hari akhirat dan ma’rifat terhadap Ash-Shirāth-ul-Mustaqīm. Ketiga ma’rifat inilah yang sangat utama pentingnya. Adapun yang lain adalah pengiring-pengiring dari yang tiga ini. Maka Sūrat-ul-Ikhlāsh adalah mengandung satu daripada ma’rifat yang tiga ini, yaitu Ma’rifatullāh, dengan memberishkan-Nya, mensucikan fikiran terhadap-Nya dengan mentauhidkan-Nya daripada jenis dan macam. Itulah yang dimaksud bahwa Allah bukanlah pula bapa yang menghendaki anak, laksana pohon. Dan bukan diperanakkan, laksana dahan yang berasal dari pohon, dan bukan pula mempunyai tandingan, bandingan dan gandingan.”
Ibnul Qayyim menulis dalam Zād-ul-Ma’ād: “Nabi s.a.w. selalu membaca pada sembahyang Sunnat al-Fajar dan sembahyang al-Witir kedua Sūrat-ul-Ikhlāsh dan al-Kāfirūn. Karena kedua Surat itu mengumpulkan Tauhid, Ilmu dan Amal, Tauhid Ma’rifat dan Iradat, Tauhid I’tiqad dan Tujuan. Sūrat-ul-Ikhlāsh mengandungi Tauhid I’tiqad dan Ma’rifat dan apa yang wajib dipandang tetap teguh pada Allah menurut akal murni, yaitu Esa, Tunggal. Naf’i yang mutlak daripada bersyarikat dan bersekutu, dari segi mana pun. Dia adalah Pergantungan yang tetap, yang pada-Nya terkumpul segala sifat kesempurnaan, tidak pernah berkekurangan dari segi mana pun. Naf’i daripada beranak dan diperanakkan, karena kalau keduanya itu ada, Dia tidak jadi pergantungan lagi dan Keesaan-Nya tidak bersih lagi. Dan Naf’i atau tidaknya kufu’, tandingan, bandingan dan gandingan adalah menafikan perserupaan, perumpamaan ataupun pandangan lain. Sebab itu makna Surat ini mengandung segala kesempurnaan bagi Allah dan menafikan segala kekurangan. Inilah dia Pokok Tauhid menurut ilmiah dan menurut akidah, yang melepaskan orang yang berpegang teguh kepadanya daripada kesesatan dan mempersekutukan.
Itu sebab maka Sūrat-ul-Ikhlāsh dikatakan oleh Nabi Sepertiga Qur’an. Sebab al-Qur’ān berisi Berita (Khabar) dan Insyā. Dan Insyaa mengandung salah satu tiga pokok: (1) perintah, (2) larangan, (3) boleh atau diizinkan. Dan Khabar dua pula: (1) Khabar yang datang dari Allah sebagai Pencipta (Khāliq) dengan nama-nama-Nya dan hukum-hukum-Nya. (2) Khabar dari makhluk-Nya, maka diikhlaskanlah oleh makhluk di dalam Sūrat-ul-Ikhlāsh tentang nama-nama-Nya dan sifat-sifatNya, sehingga jadilah isinya itu mengandung Sepertiga al-Qur’ān. Dan dibersihkannya pula barangsiapa yang membacanya dengan Iman, daripada mempersekutukan Allah secara ilmiah. Sebagaimana Sūrat-ul-Kāfirūn pun telah membersihkan dari syirik secara amali, yang timbul dari kehendak dan kesengajaan.”
Sekian Ibn-ul-Qayyim.
Ibn-ul-Qayyim menyambung lagi: “Menegakkan akidah ialah dengan ilmu. Persediaan ilmu hendaklah sebelum beramal. Sebab ilmu itu adalah Imam, penunjuk jalan, dan hakim yang memberikan keputusan di mana tempatnya dan telah sampai di mana. Maka “Qul Huwallāhu Aḥad” adalah puncak ilmu tentang akidah. Itu sebab maka Nabi mengatakannya sepertiga al-Qur’ān. Hadis-hadis yang mengatakan demikian boleh dikatakan mencapai derajat mutawātir. Dan “Qul Yā Ayyuh-al-Kāfirūna” sama nilainya dengan seperempat al-Qur’ān. Dalam sebuah Hadis dari Tirmidzī, yang dirawikan dari Ibnu ‘Abbās dijelaskan: “Idzā Zulzilat-il-Ardhu” sama nilainya dengan separuh al-Qur’ān. “Qul Huwallāhu Aḥad” sama dengan sepertiga al-Qur’ān dan “Qul Yā Ayyuh-al-Kāfirūna” sama nilainya dengan seperempat al-Qur’ān.
Al-Ḥakīm merawikan juga Hadis ini dalam al-Mustadrik-nya dan beliau berkata bahwa Isnād Hadis ini shaḥīḥ.
Maka tersebutlah dalam sebuah Hadis yang dirawikan oleh Bukhārī dari ‘Ā’isyah, – moga-moga Allah meridhainya – bahwa Nabi s.a.w. pada satu waktu telah mengirim siryah (patroli) ke suatu tempat. Pemimpin patroli itu tiap-tiap sembahyang yang menjahar menutupnya dengan membaca “Qul Huwallāhu Aḥad.” Setelah mereka kembali pulang, mereka khabarkanlah perbuatan pimpinan mereka itu kepada Nabi s.a.w.. Lalu Nabi s.a.w. berkata: “Tanyakan kepadanya apa sebab dia lakukan demikian.” Lalu mereka pun bertanya kepadanya, (mengapa selalu ditutup dengan membaca “Qul Huwallāhu Aḥad”).
Dia menjawab: “Itu adalah sifat dari Tuhan Yang Bersifat ar-Raḥmān, dan saya amat senang membacanya.”
Mendengar keterangan itu bersabdalah Nabi s.a.w.: “Katakanlah kepadanya bahwa Allah pun senang kepadanya.”
Dan terdapatlah juga beberapa sabda Rasul yang lain tentang kelebihan Sūrat-ul-Ikhlāsh ini. Banyak pula Hadis-hadis menerangkan pahala membacanya. Bahkan ada sebuah Hadis yang diterima dari Ubay dan Anas bahwa Nabi s.a.w. pernah bersabda:
أُسِّسَتِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَ الْأَرَضُوْنَ السَّبْعُ عَلَى قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ.
“Diasaskan tujuh petala langit dan tujuh petala bumi atas Qul Huwallāhu Aḥad.”
Betapa pun derajat Hadis ini, namun maknanya memang tepat. Al-Imām az-Zamakhsyarī di dalam Tafsirnya memberi arti Hadis ini: “Yaitu tidaklah semuanya itu dijadikan melainkan untuk menjadi bukti atas mentauhidkan Allah dan mengetahui sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Surat ini.”
رَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: اَقْبَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ (ص) فَسَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: وَجَبَتْ قُلْتُ: مَا وَجَبَتْ؟قَالَ: الْجَنَّةُ.
Diriwayatkan oleh Tirmidzī dari Abū Hurairah, berkata dia: “Aku datang bersama Nabi s.a.w. tiba-tiba beliau dengar seseorang membaca “Qul Huwallāhu Aḥad”. Maka berkatalah beliau s.a.w.: “Wajabat” (Wajiblah). Lalu aku bertanya: “Wajib apa ya Rasul Allah?” Beliau menjawab: “Wajib orang itu masuk syurga.” Kata Tirmidzī Hadis itu ḥasan (bagus) dan shaḥīḥ.