Surah al-Fil 105 ~ Tafsir Sayyid Quthb (2/2)
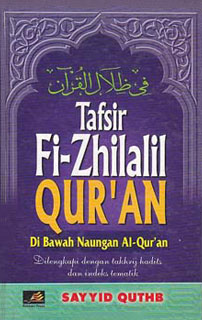
Tafsīr fi Zhilāl-il-Qur’ān
Oleh: Sayyid Quthb Penerbit: Gema Insani
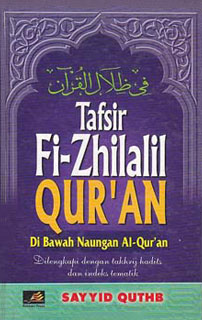
Kemudian ditimpanya tentara tersebut oleh penyakit itu sedangkan bangsa ‘Arab yang berdekatan dengannya tidak tertimpa penyakit tersebut, merupakan suatu peristiwa luar biasa. Pasalnya, burung-burung itu hanya bermaksud menimpakan batu-batu yang dibawanya kepada tentara-tentara bergajah dan komandannya saja. Kalau peristiwa ini adalah peristiwa luar biasa, mengapakah kita harus berpayah-payah membatasinya dengan melukiskannya sebagai perisitwa biasa yang sesuai dengan pemikiran manusia? Padahal, kalau kita memberlakukan peristiwa itu sebagai peristiwa luar biasa, bukankah itu lebih relevan dengan nuansa seluruh peristiwa itu sendiri?!
Saya mengerti dan dapat memperkirakan bahwa yang melatarbelakangi Ustadz Imām Syaikh Muḥammad ‘Abduh berpikiran demikian adalah karena pengaruh lingkungan Madrasah ‘Aqliyyah yang lebih mengedepankan rasio, tempat ia bertugas bahkan sebagai ketuanya. Saya kira itulah yang mendorongnya untuk mempersempit kawasan khawāriq-ul-‘ādah “kejadian luar biasa” dan perkara-perkara ghaib di dalam menafsirkan al-Qur’ān-ul-Karīm dan peristiwa-peristiwa sejarah. Kemudian mencoba mengembalikan semua itu kepada kebiasaan-kebiasaan dan hukum alam yang sudah diketahui.
Memang madrasah (lembaga pendidikan) ini getol memerangi khurafat-khurafat yang sedang berkembang dan mendominasi pikiran masyarakat umum pada waktu itu. Ia juga sedang menghadapi derasnya arus dongeng-dongeng dan cerita-cerita isra’iliyyat yang memenuhi kitab-kitab tafsir dan riwayat-riwayat yang waktu itu sampai dapat menimbulkan fitnah terhadap ‘ilmu pengetahuan baru dan menimbulkan keragu-raguan terhadap apa saja yang dikatakan oleh agama. Maka, madrasah ini berusaha mengembalikan semuanya kepada agama dengan prinsip bahwa apa yang dibawa oleh agama itu sesuai dengan akal.
Karena itu, madrasah ini berusaha keras untuk membersihkan agama dari khurafat-khurafat dan dongeng-dongeng. Ia membangkitkan pemikiran keagamaan untuk memahami hukum-hukum alam, memikirkan keberadaan dan keberlakuannya, dan mengembalikan kepadanya seluruh gerak dan aktivitas manusia. Ia juga mengembalikan kepadanya gerakan-gerakan alam dengan fisik dan materinya berdasarkan rasionalitas al-Qur’ān. Karena al-Qur’ān mengembalikan manusia kepada sunnah Allah pada alam semesta yang dianggap sebagai kaidah (undang-undang) baku yang mengatur semua gerak dan fenomena yang bertebaran.
Akan tetapi, usaha menghadapi tekanan khurafat dari satu sisi dan menghadapi tekanan fitnah terhadap ‘ilmu pengetahuan pada sisi lain meninggalkan dampak tersendiri pada lembaga pendidikan tersebut yang berupa kehati-hatian yang sangat ekstra. Juga kecenderungan untuk menjadikan kebiasaan yang terjadi pada alam semesta sebagai “kaidah umum” bagi sunnatullah. Sehingga, populerlah di dalam penafsiran Ustadz Syaikh Muḥammad ‘Abduh dan muridnya Ustadz Syaikh Rasyīd Ridhā dan Ustadz ‘Abd-ul-Qādir al-Maghrib mudah-mudahan Allah merahmati mereka semuanya kecenderungan yang jelas untuk mengembalikan perkara-perkara khawāriq-ul-‘ādah “luar biasa” kepada sunnatullah (hukum alam) yang biasa-biasa saja. Juga mena’wilkan sebagaimana dengan dicocok-cocokkan dengan apa yang mereka sebut “rasional” dan bersikap sangat ketat di dalam menerima perkara-perkara ghaib.
Di samping faktor-faktor lingkungan yang mendorong munculnya pandangan yang seperti itu, kita juga melihat adanya sikap berlebihan dalam hal ini dan melalaikan aspek lain dari tashawwur qur’ānī yang sempurna, yaitu kemutlakan kehendak Allah dan kekuasaan-Nya di belakang sunnah yang telah dipilih-Nya, baik di dalam kebiasaan manusia maupun di luar kebiasaan. Kemutlakan ini tidak menjadikan akal manusia sebagai pemutus kata terakhir dan tidak menjadikan rasionalitas akal sebagai rujukan semua perkara. Pasalnya, pengutamaan rasionalitas akal berdampak pada keharusan mena’wilkan apa yang dirasa tidak sesuai dengan pikiran, sebagaimana hal ini sering dijumpai dalam penafsiran tokoh-tokoh madrasah tersebut.
Di samping itu, apa yang biasa terjadi pada sunantullāh yang kita ketahui ini, bukanlah sunnatullah secara total. Semua itu hanya sebagian kecil saja yang tidak dapat menafsirkan segala yang terjadi dari sunnah-sunnahNya di alam semesta ini. Semua ini hanya menunjukkan betapa agungnya kekuasaan Allah dan betapa rumitnya ketentuan-ketentuanNya. Namun, sudah tentu kita harus berhati-hati terhadap khurafat dan menolak mitos-mitos dengan seadil-adilnya, tanpa terpengaruh oleh lingkungan tertentu. Juga tanpa terpengaruh oleh tradisi berpikir yang berkembang pada suatu masa.
Sesungguhnya, di sana terdapat kaidah yang terpercaya di dalam menghadapi nash-nash al-Qur’ān, yang mudah-mudahan bisa kita jadikan pedoman untuk membuat ketetapan dalam masalah ini. Yaitu, kita tidak diperbolehkan menghadapkan (mengkonfirmasikan) nash-nash al-Qur’ān kepada ketetapan-ketetapan akal yang telah lalu, ketetapan-ketetapan umum, dan tema-tema tertentu yang tidak sesuai dengan nash.
Akan tetapi, kita harus menjadikan nash sebagai tolok ukur bagi kita untuk menerima atau tidak keputusan-keputusan yang kita buat. Maka, dengan berpijak pada nash-nash inilah, kita terima ketetapan-ketetapan imaniyyah dan kita bangun kaidah-kaidah logika dan semua pola pikir kita. Apabila nash telah menetapkan sesuatu kepada kita, kita terima sebagai suatu ketetapan. Karena apa yang kita sebut “akal” (pikiran) yang hendak kita jadikan sebagai hakim untuk menghakimi ketetapan-ketetapan al-Qur’ān mengenai peristiwa-peristiwa alam, sejarah, kemanusiaan, dan ghaib itu hanyalah realitas-realitas khusus yang terbatas dan pengalaman manusia yang terbatas pula.
Meskipun sebagai kekuatan yang bebas dan terikat oleh pengalaman-pengalaman dan realitas-realitas, bahkan bersifat netral dan mandiri, namun pada ujungnya akal terbatas juga oleh keterbatasan kita sebagai manusia. Apa yang maujud ini tidak mencerminkan kemutlakan sebagaimana yang ada di sisi Allah. Al-Qur’ān yang bersumber dari Yang Maha Mutlak inilah yang membuat ketetapan bagi kita. Keputusan-keputusannyalah yang harus kita jadikan rujukan bagi keputusan dan ketetapan akal kita.
Oleh karena itu, tidak benar kalau dikatakan: “Petunjuk-petunjuk nash yang berbenturan dengan akal harus dita’wilkan,” sebagaimana banyak dilakukan oleh tokoh-tokoh Madrasah ‘Aqliyyah. Ini bukan berarti menyerah kepada khurafat, tetapi ma‘nanya adalah bahwa akal bukanlah untuk menghakimi ketetapan-ketetapan al-Qur’ān. Apabila materi-materi petunjuk dan kalimat-kalimat itu demikian jelas dan lurus, dialah yang menetapkan bagaimana seharusnya akal kita menerima. Juga bagaimana dibentuk kaidah-kaidah berpikir dan berlogika di dalam memahami petunjuk-petunjuknya, dan di dalam menghadapi hakikat-hakikat alam lainnya.
Kita kembali kepada materi surah ini dan petunjuk yang dikandung dalam kisahnya:
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيْلِ.
“Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah.” (al-Fīl: 1).
Ini adalah pertanyaan untuk menunjukkan ketakjuban terhadap peristiwa tersebut dan mengingatkan akan besarnya peristiwa itu. Karena, peristiwa ini sudah terkenal dan sangat populer di kalangan bangsa ‘Arab sehingga mereka jadikan sebagai permulaan sejarah. Mereka biasa berkata: “Peristiwa ini terjadi pada tahun gajah. Peristiwa itu terjadi dua tahun sebelum tahun gajah. Sedangkan, peristiwa yang itu terjadi sepuluh tahun sesudah tahun gajah….” Juga sudah populer di kalangan mereka bahwa kelahiran Rasūlullāh s.a.w. adalah pada tahun gajah. Itu barang kali sudah menjadi ketentuan Ilahi di mana terjadi kesesuaian dengan demikian indah.
Dengan demikian, surah ini tidak menginformasikan cerita yang tidak mereka kenal, namun untuk mengingatkan mereka kepada peristiwa yang sudah mereka kenal, dengan tujuan tertentu di balik peringatan ini.
Kemudian, sesudah permulaan itu disempurnakanlah kisah ini dalam bentuk istifhām taqrīrī “pertanyaan retoris, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban karena sudah merupakan ketetapan”:
أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ.
“Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka (untuk menghancurkan Ka‘bah) itu sia-sia?” (al-Fīl: 2).
Ya‘ni, bukankah telah sia-sia usaha mereka sehingga tidak mencapai sasaran dan tujuannya, seperti halnya orang yang tersesat jalan, lantas tidak sampai kepada apa yang dikehendakinya? Mungkin hal ini juga untuk mengingatkan kaum Quraisy terhadap ni‘mat Allah kepada mereka dengan dipelihara dan dijaga-Nya Bait-ul-Ḥarām, sedang pada waktu itu mereka tidak mampu menghadapi tentara bergajah yang demikian kuat dan perkasa. Barangkali dengan peringatan ini mereka akan merasa malu mengufuri Allah yang telah menolong ketika mereka lemah dan tak berdaya. Lalu, mereka akan menghilangkan sikap mereka yang membanggakan kekuatan mereka sekarang untuk menghadapi dan menentang Nabi Muḥammad s.a.w. dan golongan minoritas mu’min yang bersama beliau. Karena Allah telah meruntuhkan kekuatan tentara-tentara yang perkasa ketika hendak merusak rumah suci-Nya yang terhormat itu. Maka, boleh jadi Dia juga akan meruntuhkan kekuatan orang-orang yang hendak menghalang-halangi Rasūlullāh dan dakwahnya.
Adapun bagaimana cara menjadikan usaha mereka itu tersia-sia, dijelaskan dalam surah ini dalam bentuk keterangan yang indah:
وَ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيْلَ. تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ
“Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang terbakar, lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan (ulat).” (al-Fīl: 3-5).
Abābīl artinya berbondong-bondong. Sijjīl adalah kata Persia yang terdiri dari dua kata yang berarti batu dan tanah atau batu yang dilumuri dengan tanah. Sedangkan, ‘ashf berarti daun-daun pepohonan yang kering. Disifatinya ia dengan ma’kūl “dimakan” ya‘ni rusak karena dimakan dan dirobek-robek oleh ulat atau serangga, atau ketika dimakan oleh binatang lantas dikunyah-kunyah dan dilumatkannya.
Ini adalah gambaran indrawi terhadap badan yang dirobek-robek oleh batu-batu yang dilemparkan oleh kawanan burung itu. Kita tidak perlu mena’wilkannya dengan mengatakan bahwa itu adalah lukisan terhadap keadaan mereka yang ditimpa penyakit cacar atau campak.
Adapun petunjuk dan pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa ini banyak sekali.
Pertama, Allah tidak ingin menyerahkan pemeliharaan rumah suci-Nya itu kepada kaum musyrikīn, meskipun mereka membangga-banggakan, melindungi dan memeliharanya. Ketika Dia hendak melindungi dan menjaganya serta mengumumkan pemeliharaan-Nya kepadanya, dibiarkan-Nya kaum musyrikin kalah atau tak berdaya berhadapan dengan kekuatan musuh. Hanya kekuasaan-Nyalah yang berjalan sendiri untuk melindungi rumah suci-Nya. Sehingga, tangan-tangan kaum musyrikīn tidak ada yang turut serta melindunginya dan mendahului melindunginya, dengan perlindungan cara jahiliyyah.
Barangkali kondisi itu menguatkan asumsi bahwa peristiwa ini terjadi untuk menghancurkan musuh dengan cara yang luar biasa. Hal ini rasanya lebih cocok dan lebih mendekati.
Di antara konsekuensi logis tindakan kekuasaan Ilahi untuk melindungi Bait-ul-Ḥarām inilah maka orang-orang Quraisy dan bangsa ‘Arab segera memeluk agama Allah dengan berbondong-bondong ketika Rasūlullāh s.a.w. datang membawa agama itu kepada mereka. Kebanggaan mereka terhadap Bait-ul-Ḥarām dan kepengurusan mereka terhadapnya serta tata keberhalaan yang mereka bikin tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk masuk Islam.
Peringatan terhadap peristiwa itu dengan cara demikian ini menyadarkan mereka dan menimbulkan keheranan terhadap sikap mereka yang keras kepala.
Kedua, peristiwa ini menunjukkan bahwa Allah tidak menghendaki kaum Ahli Kitab, Abrahah dan tentaranya, untuk menghancurkan Bait-ul-Haram atau menguasai tanah suci. Kehendak-Nya itu, meskipun kesyirikan mengotori rumah suci dan kaum musyrikīn merawatnya, agar rumah ini terjauh dari kekuasaan penjajah, dan terpelihara dari tipu daya orang-orang yang melakukan tipu daya. Karena, Dia hendak memelihara kemerdekaan tanah (wilayah) ini hingga tumbuh padanya ‘aqīdah yang baru, bebas, dan merdeka. Tidak dikuasai oleh penguasa siapa pun, dan tidak mau dibimbing. Ini merupakan rencana Allah terhadap rumah suci dan agama-Nya sebelum ada seseorang yang mengetahui bahwa nabi agama ini dilahirkan pada tahun itu.
Kita merasa senang dan tenang dengan petunjuk ini, di dalam menghadapi ambisi orang-orang durhaka dan penipu daya yang berkeliaran di sekitar tanah suci seperti salibisme internasional dan zionisme internasional, yang menyembunyikan ambisi buruk dan penuh tipu daya. Maka, Allah yang telah melindungi rumah suci-Nya dari kaum Ahli Kitab meskipun pada waktu itu yang merawatnya adalah orang-orang musyrik. Dia tentu akan memeliharanya dan akan memelihara kota Rasūl-Nya dari tipu daya orang-orang yang hendak melakukan tipu daya dan kejahatan.
Ketiga, bangsa ‘Arab tidak memiliki peranan apa-apa di muka bumi dan tidak ada eksistensinya sebelum datangnya Islam. Mereka yang ada di Yaman berada di bawah kekuasaan Persia atau Ḥabasyah. Pemerintahan mereka ketika berdiri, kadang-kadang di bawah protektorat Persia. Di kawasan utara, negeri Syām berada di bawah kekuasaan Romawi baik secara langsung maupun dengan dibentuknya pemerintahan ‘Arab di bawah protektorat Romawi.
Tidak ada yang lepas dari kekuasaan asing kecuali jantung Jazīrah ‘Arab. Akan tetapi, mereka dalam keadaan terbelakang, terpisah-pisah, dan tidak memiliki kekuatan yang signifikan dalam percaturan dunia. Bahkan, pernah terjadi peperangan di antara kabilah-kabilah itu selama empat puluh tahun. Kabilah-kabilah ini tidak berpecah-belah, tetapi tidak juga bersatu, sehingga dipertimbangkan oleh negara-negara yang kuat di sekitarnya. Apa yang terjadi pada tahun gajah menjadi ukuran terhadap kekuatan ini yang sebenarnya sehingga mereka menghadapi serangan bangsa asing.
Di bawah bendera Islam, untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa ‘Arab, mereka memainkan peranan dalam percaturan dunia. Mereka memiliki kedaulatan yang patut diperhitungan dan kekuatan yang menghanyutkan kerajaan-kerajaan dan meruntuhkan singgasana-singgasana. Juga mengendalikan kepemimpinan jahiliyyah yang penuh kepalsuan dan kesesatan.
Akan tetapi, yang menjadikan bangsa ‘Arab layak menyandang predikat ini untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka adalah karena mereka melupakan kebangsaan ‘Arabnya. Mereka lepaskan kesombongan kebangsaannya dan fanatisme golongannya. Mereka menyebut diri mereka sebagai Muslim, ya hanya sebagai Muslim itu saja. Mereka kibarkan bendera Islam, yang hanya bendera Islam itu saja. Mereka usung ‘aqīdah besar dan kuat untuk mereka hadiahkan kepada manusia dan kemanusiaan, tanpa mengusung unsur kesukuan, kebangsaan, fanatisme. Mereka usung pikiran langit untuk mereka ajarkan kepada manusia, bukan dengan madzhab bumi mereka menundukkan manusia kepada kekuasaannya.
Mereka keluar dari negerinya untuk berjihad di jalan Allah saja, bukan untuk membangun imperium ‘Arab yang dengannya mereka akan dapat bersenang-senang dan bersukacita di bawah naungannya, lalu membanggakan dan menyombongkan diri di bawah perlindungannya. Bukan pula mereka keluarkan manusia dari kekuasaan Romawi dan Persia untuk tunduk di bawah kekuasaan bangsa ‘Arab dan kekuasaan diri mereka sendiri. Akan tetapi, mereka lakukan semua itu hanya untuk mengeluarkan dan membebaskan manusia dari menyembah sesama manusia kepada menyembah Allah saja. Hal ini sebagaimana yang dikatakan Ribi‘ī bin ‘Āmir, utusan kaum Muslimīn di majlis Yazdijird: “Allah mengutus kami untuk membebaskan manusia dari menyembah sesama hamba Allah kepada menyembah Allah saja dan dari kesempitan dunia kepada kelapangan akhirat, serta dari kezhāliman agama-agama kepada keadilan Islam.” (241).
Hanya dengan demikian sajalah bangsa ‘Arab eksis, memiliki kekuatan, dan mengendalikan kepemimpinan. Tetapi, semuanya dilakukan karena Allah dan di jalan Allah. Mereka memiliki kekuatan dan menjadi pemimpin selama mereka istiqamah di jalan ini. Sehingga, setelah mereka berpaling dari jalan ini dan menyebut-nyebut kebangsaaan dan fanatisme golongan, serta meninggalkan panji-panji Allah untuk mengibarkan panji-panji fanatisme, maka bumi pun melemparkan mereka dan bangsa-bangsa lain pun menginjak-injak mereka. Karena, Allah telah membiarkan mereka sebagaimana mereka meninggalkan-Nya dan melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan-Nya.
Apakah arti bangsa ‘Arab tanpa Islam? Pemikiran macam apakah yang dapat mereka suguhkan kepada manusia kalau mereka lepas dari pemikiran Islam? Apakah nilai suatu umat yang tidak dapat menyuguhkan pemikiran yang bagus bagi manusia? Sesungguhnya, setiap umat dapat memimpin manusia pada suatu waktu dalam sejarahnya apabila mereka dapat mencerminkan pemikirannya. Bangsa-bangsa yang tidak memiliki pemikiran yang menonjol, seperti bangsa Tartar yang dapat membinasakan bangsa-bangsa Timur dan bangsa Barbar yang pernah mengobrak-abrik Daulat Romawi di kawasan barat, tidak dapat hidup lama. Mereka lebur ke dalam bangsa-bangsa yang menakluqkan mereka.
Satu-satunya fikrah yang dapat disuguhkan bangsa ‘Arab kepada dunia hanyalah ‘aqīdah Islam. ‘Aqīdah ini pulalah yang telah mengangkat mereka ke posisi sebagai pemimpin. Apabila mereka lepas dari ‘aqīdah Islam, mereka tidak berfungsi lagi di muka bumi ini serta tidak diperhitungkan dan tidak memiliki peranan lagi. Inilah yang harus dipikirkan baik-baik oleh bangsa ‘Arab bila mereka menginginkan kehidupan, kekuatan, dan kepemimpinan. Allah-lah yang memberi petunjuk dari kesesatan.