Surah al-Fajr 89 ~ Tafsir Syaikh Fadhlallah (2/2)
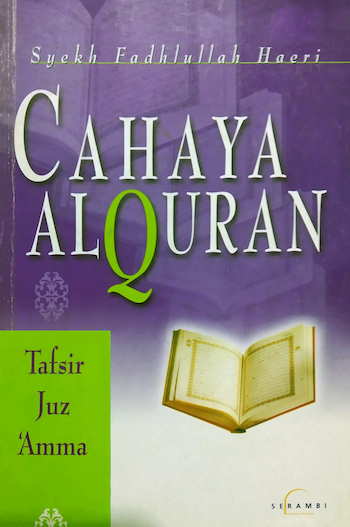
Tafsir Juz ‘Amma
(Judul Asli: Beams of Illumination)
Oleh: Syaikh Fadhlallah Haeri
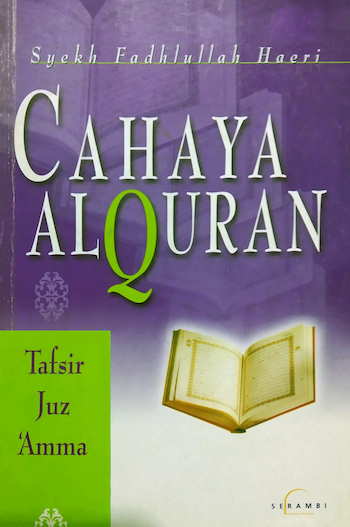
Tafsir Juz ‘Amma
(Judul Asli: Beams of Illumination)
Oleh: Syaikh Fadhlallah Haeri
كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ
Baik dalam keadaan kaya atau miskin, manusia tidak bersyukur dan tidak mengetahui makna dan pengertian dari hikmah di balik kondisinya. Di sini dilambangkan dengan sikapnya yang tidak bermurah hati kepada anak yatim. Karuma berarti ‘bermurah hati’, dan dalam konteks anak yatim, berarti akrama (memuliakan), maksudnya ‘memberikan perhatian yang baik dan kasih sayang yang layak’. Anak yatim adalah orang yang membutuhkan dorongan dan perlindungan, karena ia tidak memiliki pelindung yang nyata. Bapak pertama kita, Adam, adalah seorang yatim. Nabi kita Muḥammad, baginda semua orang, adalah yatim. Dengan mengetahui makna dari yatim yang tidak berdaya, maka kita mengikuti tradisi yang tak berbatas waktu yakni tidak tergantung pada orangtua melainkan kepada Allah.
وَ لَا تَحَاضُّوْنَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ
Akar dari miskīn adalah sakana, yang berarti ‘mendiami’. Sukūn berarti ‘diam, sunyi, damai’. Orang miskin tidak memiliki apa pun dan sama sekali pasrah terhadap keadaan yang sangat tak berdaya. Ini kebalikan dari fakir, yakni orang yang membutuhkan tapi masih bisa aktif: ia bisa mengemis, ia masih bisa mengharapkan seseorang akan memberinya sesuatu, dan menadahkan tangannya. Ayat ini menunjukkan bahwa mayoritas umat manusia berada dalam kerugian, dan tidak mengikuti arus kedermawanan yang bergerak ke depan.
وَ تَأْكُلُوْنَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا
وَ تُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا
Kita semua mencintai harta dari mana pun sumbernya. Manusia biasa akan berteriak memintanya dan sangat mengharapkannya, dan dia mengusahakan keamanan materi yang biasanya justru menimbulkan perasaan tidak aman karena takut kehilangannya. Dengan demikian harta malah menambah kecemasan seseorang. Manusia umumnya ingin menambah kekayaan baik dengan cara yang benar ataupun tidak benar. Manusia bersifat suka mementingkan diri sendiri (egois). Dalam hal ini ia menunjukkan kebalikan dari Penciptanya, Yang Maha Pengasih, sampai ia menyadari bahwa setiap desah napas adalah pemberian yang sangat dibutuhkan dan penting.
Kita telah mengetahui sebutan yang sebanding untuk manusia—kepicikan, pengkhianatan dan ketamakannya. Al-Qur’an mendorong kita agar menggunakan kehidupan ini untuk membuka apa yang ada dalam diri kita agar mengetahui siapa kita, dengan menerima realitas hewaniah dan ilahiah dalam diri kita.
كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا
Maka kini tibalah peringatan. Dakka berarti memukul hingga hancur. Kita biasanya tidak memperhatikan kenyataan bahwa pada akhirnya bumi akan kembali ke ketiadaan.
وَ جَاءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا
Bila ayat ini disampaikan dengan ungkapan lain: ‘Dan tatkala semua kekuatan yang tak terlihat oleh kita datang dengan formasi yang sempurna’. Para malaikat dan kekuatan-kekuatan alam semesta berada dalam tatanan alamiahnya, mereka berbaris-baris. Tidak ada lagi kemungkinan bagi manusia untuk turut campur dan bertindak.
وَ جِيْءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَ أَنَّى لَهُ الذِّكْرَى
Pada waktu itu neraka (jahannam), api abadi, akan mendekat, jelas dan gamblang. Pada waktu itu manusia akan ingat, tapi apa gunanya ingatan dia pada saat itu? Wilayah amal, kemungkinan untuk berperilaku benar dan menyucikan diri di dunia ini, akan berakhir. Ia akan menangis, ‘Andaikan aku beramal saleh selama hidupku’, yang berarti bahwa pada saat itu ia akan mengakui hakikat kehidupan, yang ternyata tidak seperti perkiraannya dulu, tapi sudah terlambat untuk mengubahnya.
يَقُوْلُ يَا لَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ
فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ
وَ لَا يُوْثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ
Tidak seorang pun akan bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Perbuatan seseorang akan menentukan seperti apa kondisi dan keadaan dia di kehidupan mendatang. Tidak ada orang lain yang akan dapat menggantikannya. Setiap orang bertanggung jawab dan akan diberi ganjaran sesuai dengan perbuatannya. Keadaan tersebut memang khas. Pada hari itu—dalam kesadaran baru—kondisi adzab dan penghambaan seseorang akan diukur sesuai dengan perbuatan dia sebelumnya. Kondisinya tidak akan sama dengan kondisi orang lain. Genggaman Allah atasnya akan bersifat khas dan khusus untuk dirinya saja.
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ
ارْجِعِيْ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً
فَادْخُلِيْ فِيْ عِبَادِيْ
وَ ادْخُلِيْ جَنَّتِيْ
Tuhan memanggil jiwa (nafs) yang berada dalam kesentosaan dan kedamaian, an-nafs-ul-muthma’innah. Panggilan ini menandai awal kebangunan rohani. Jika kita tidak mendapatkan kedamaian, bagaimana kita bisa mengingat hal yang jauh di dalam samudera hati kita yang paling dalam? Jika kita gelisah secara lahiriah, terus-menerus dalam kekacauan, bagaimana kita bisa mendengar gaung pengetahuan yang tak berbatas waktu yang tertanam dalam hati kita? Itulah sebabnya maka panggilan dimulai pada nafs yang senang dan tenang.
Tahap berikutnya dari nafs adalah kepuasan hati: rādhiyah berarti ‘puas’, puas terhadap pemahaman dan terhadap pengetahuan bahwa kondisi yang sedang dijalani ini merupakan suatu kesempurnaan dan bukan sebaliknya. Kita mungkin saja tidak menyukai situasi yang sedang kita jalani, tapi kondisi tersebut tidaklah relevan di sini. Pada tahap berikutnya, mardhiyyah (senang), kita akan mengetahui bahwa segala sesuatu yang lain pun puas dengan kita. Secara batiniah kita berada dalam kedamaian yang sejati sedangkan secara lahiriah kita masih sebagai manusia yang suka berbuat karena kita tidak bisa menghindar. Tidak ada jalan untuk menghindar, kita harus berjuang. Dunia ini adalah wilayah percobaan (balwā) baik dalam aspek baik maupun buruk, baik lahir maupun batin. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi: “Apa yang salah dengan hamba-hambaKu? Mereka terus-menerus berdoa kepada-Ku meminta kesenangan di dunia ini, tapi Aku tidak menciptakan dunia ini untuk kesenangan.”
Imām Ḥusein telah menyebutkan tahap-tahap nafs: ‘Nafs yang tenang adalah nafs yang berada dalam tauhid.’ Kita mencapai ketenangan jika kita berada dalam tauhid. ‘Nafs yang bersyukur, adalah nafs yang telah diberkahi rahmat.’ Pada tahap ini kita mengakui bahwa yang ada hanyalah rahmat Allah. Beliau juga mengatakan, ‘nafs yang terpilih adalah nafs yang memiliki hikmah,’ yaitu, nafs yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Realitas. Beliau mengartikan nafs yang berakal dan jiwa yang memahami, sebagai an-nafs-ur-rādhiyah, dan nafs yang menyuruh orang berbuat jahat sebagai an-nafs-ul-jāhilah, nafs yang bodoh.
Klasifikasi nafs secara tradisional berkisar dari keadaan terendah, an-nafs-ul-ammāratu bi-sū’, sampai keadaan tertinggi, an-nafs-ul-kāmilah, yakni meningkat ke atas melalui tujuh maqām (stasiun). Tahap kedua adalah jiwa yang merasa bersalah, an-nafs-ul-lawwāmah, yang kadang-kadang menyadari kecenderungannya terhadap kejahatan. Ini adalah tahap permulaan kesadaran. Lalu berikutnya an-nafs -u-mulhamah, jiwa yang diberi ilham, tidak terikat, tanpa bimbingan, diikuti oleh an-nafs-ul-muthma’innah. Setelah ketenangan muncullah kepuasan disertai pengetahuan, ridha’: an-nafs-ur-rādhiyah memiliki pengetahuan tentang kesempurnaan sang Maharaja. Bila kita puas dengan penciptaan, maka penciptaan pun akan puas dan selaras dengan kita, dan itulah an-nafs-ul-mardhiyyah, tahap keenam. Dari keadaan tersebut muncullah kesempurnaan dan kesatuan, al-kāmilah.
Pada tahap kesempurnaan ini Allah mengatakan, ‘Sekarang masuklah ke dalam arena-Ku, dan bersembunyilah dalam satu-satunya taman tauhid, di dalamnya ada kebahagiaan dan kemeriahan yang luar biasa dan keberlimpahan yang bebas dinikmati!’.