Surah al-Fajr 89 ~ Tafsir Syaikh Fadhlallah (1/2)
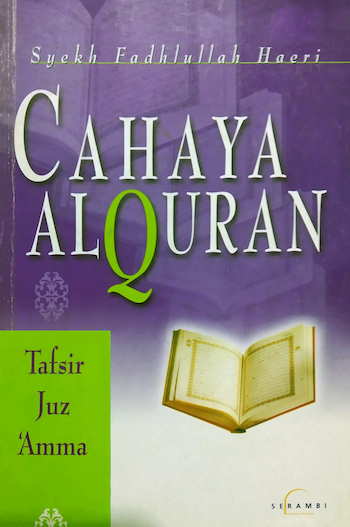
Tafsir Juz ‘Amma
(Judul Asli: Beams of Illumination)
Oleh: Syaikh Fadhlallah Haeri
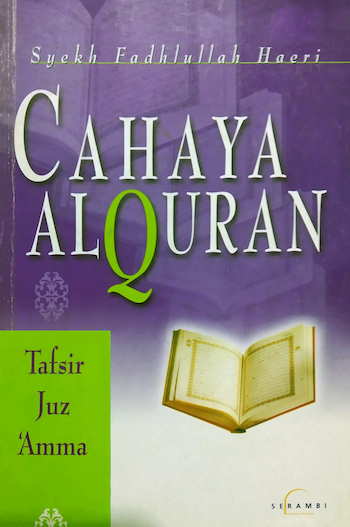
Tafsir Juz ‘Amma
(Judul Asli: Beams of Illumination)
Oleh: Syaikh Fadhlallah Haeri
“WAKTU FAJAR”
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Dengan Nama Allah, Yang Maha Pengasih, Lagi Maha Penyayang.
وَ الْفَجْرِ
Fajar artinya ‘dini hari, subuh’, dan menunjukkan suatu permulaan. Secara tiba-tiba realitas menyinari kita bagaikan pembukaan hari, dan awal bersinarnya cahaya atau pengetahuan adalah bagaikan awal bangunnya fisik.
وَ لَيَالٍ عَشْرٍ
Menurut tradisi, sepuluh malam ini dianggap sebagai sepuluh hari pertama Dzulḥijjah (bulan suci ziarah haji). Hari kesembilan adalah saat para peziarah berdiam di ‘Arafah dari mulai tengah hari hingga matahari terbit, diam menunggu, menantikan pengetahuan yang sudah ada di dalam maupun di luar diri mereka. Penyebutan malam bukannya siang adalah mirip dengan penyebutan empat puluh malam yang ditetapkan oleh Allah untuk nabi Mūsā (Q.S.2:51). Mungkin hal ini berkenaan dengan keuntungan besar dari salat, tafakur dan berdoa kepada Allah selama malam-malam ini ketika semua aktivitas lahir sangat menurun, ketika konsentrasi kita sedang tajam-tajamnya dan, dengan demikian, ada kemungkinan yang lebih besar untuk mencapai mobilitas dan pembukaan batin. Juga, setiap malam ada siangnya, dan perjalanan manusia yang dimulai dari kegelapan dan kebodohan diharapkan akan berakhir dengan persepsi yang jelas tentang pengetahuan.
وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ
Syaf‘a (angka genap) adalah dari syafa’a yang berarti ‘menggandakan, menggenapkan yang ganjil, membubuhkan, menengahi’. Terjemahan umum dari syafā‘ah (dari syafa‘a) adalah ‘perantaraan’, tapi yang dimaksud sesungguhnya adalah kehadiran orang lain yang memiliki kekuatan dan pengetahuan lebih tinggi, dan dengan demikian mampu memberikan bantuan, bimbingan atau keberhasilan. Implikasinya adalah ada keterlibatan dua orang. Jika syafa‘a diterapkan pada seekor unta betina atau biri-biri betina, berarti dengan melahirkan maka unta tersebut jumlahnya menjadi dua. Segala hal yang dapat diamati—semua pengalaman penciptaan—bergantung pada dualitas, meskipun dalam realitasnya ada keesaan di balik itu. Hanya ada satu realitas, namun semua aspek realitas tersebut muncul dua-dua: siang dan malam, pengetahuan dan kebodohan, syariat dan hakikat, taat dan membangkang, roh dan nafsu, dan sebagainya.
Salat malam dimulai dengan beberapa pasang siklus dan diakhiri dengan salat khusus yang terdiri dari satu rakaat, yakni salat witir (salat ganjil). Dengan demikian, dualitas pun akhirnya menjadi satu dalam salat witir.
وَ اللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ
Sāra berarti ‘berangkat, menyuruh pergi, bepergian, pergi, berlalu’. Sayr berarti ‘perjalanan, gerakan, prosesi’. Kemudian muncullah kata sīrah, yang berarti ‘keadaan, kondisi, atau tingkah laku’, khususnya menunjuk kepada perilaku Nabi Muḥammad. Semua penciptaan bergerak secara konstan karena segala sesuatu bergerak dan berubah. Demikian pula malam dan siang, keduanya dalam keadaan bergerak. Dan dengan berlalunya kegelapan malam di akhir perjalanan hidup ini, maka kebodohan pun akan berlalu dan akhimya kita sadar akan Realitas.
هَلْ فِيْ ذلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ
Ḥijr, dalam konteks ini, berarti sama dengan ‘aql, yakni pemahaman dan nalar. Ayat ini menegur kita dengan mengatakan, “Apakah semua fenomena ini tidak cukup menjadi tanda bagi orang-orang yang berpikir?”
Setelah memberitahu kita bahwa di ujung kebodohan akan ada pengetahuan, bahwa di akhir kerugian ada keuntungan, bahwa di ujung malam akan ada siang, bahwa di akhir tidur ada kesadaran, dan bahwa sifat penciptaan selalu berada dalam gerakan konstan dari satu ujung ke ujung lainnya yang berlawanan, suatu gerakan ke arah kesadaran dan, dengan demikian, menuju kepastian—setelah semua hal tersebut disampaikan kepada kita melalui kata-kata kiasan, kemudian Allah memberi kita bukti-bukti historis.
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ
إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ
الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ
Kaum ‘Ād adalah suku yang sangat kuat. Kota-kota, tempat tinggal dan kekuatan mereka dibangun di atas pilar-pilar yang kelihatannya sangat kuat. Meskipun sikap mereka unik, berpengaruh dan arogan namun semua bekas peninggalan mereka telah lenyap. Lihatlah kebudayaan-kebudayaan yang ‘kokoh’ ini yang tidak tahan terhadap ujian waktu. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa hendaknya kita tidak tertipu oleh kekuatan struktur lahiriah.
وَ ثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ
Suku Tsamūd terkenal dengan gedung-gedungnya yang terbuat dari marmer dan batu, yang diperkirakan sangat tahan lama dan tak dapat dihancurkan. Sebagian memang masih ada dan dipahat di atas batu pegunungan yang berkualitas tinggi, dan kelihatannya masih sangat aman. Namun penduduknya lenyap secara misterius, tidak meninggalkan jejak selain tempat tinggal mereka.
وَ فِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ
Ada beberapa tafsiran yang berbeda untuk kata awtād, jama‘ dari watad, artinya ‘pancang atau pasak tenda’. Di beberapa kebudayaan kuno, kekayaan seseorang diukur dengan jumlah pasak yang dimiliki dalam tendanya; semakin besar tenda (semakin banyak jumlah pasaknya— peny.), semakin besar pengaruh pemiliknya. Tapi pasak juga digunakan untuk menyiksa orang. Konon Fir‘aun menyiksa istrinya sampai mati dengan cara mengikatnya pada pasak yang menancap di tanah.
الَّذِيْنَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ
فَأَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ
Di antara ciri-ciri yang lazim pada kaum perusak adalah pelanggaran (perbuatan melampaui batas), korupsi dan dekadensi moral. Mereka menyelewengkan jalan spiritual dan menyesatkan orang lain dari tujuan eksistensinya.
فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ
Adzab tidak terjadi dengan cara yang sembarangan. Ia merupakan akibat dari perbuatan manusia sendiri yang mendatangkan malapetaka. Kesulitannya ada pada si mutrafun sendiri, sebagaimana dengan jelas dinyatakan di tempat lain dalam Alquran (Q.S.56:45). Mutrafin adalah mereka yang hidup dalam keglamoran, dikelilingi oleh kemewahan dan berbagai obyek materi yang tidak perlu. Mereka seakan-akan terlindung dari kehidupan, dan akibatnya tidak hidup dalam kesadaran. Mereka dalam keadaan terpisah, tidak menghubungkan kehidupan dengan kematian, atau pangkal dengan ujungnya. Hidup dengan berlindungkan bantalan palsu ini tentu saja merusak masyarakat. Bilamana terjadi dekadensi, alam akan secara otomatis mengadakan pembaharuan dan regenerasi. Oleh karena itu masyarakat terperosok ke dalam kebusukan disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukannya sendiri. Segala sesuatu mengandung bibit kerusakan di dalam dirinya; jika kita memupuki bibit itu, maka kebusukan akan menyebar dan mengambil-alih.
إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ
Mirshād berasal dari rashada, berarti ‘mengawasi sesuatu, diam menunggu, mengamati’. Ayat ini memberitahu kita bahwa Tuhan kita Yang pekerjaannya menumbuhkan apa yang berada di bawah kekuasaan-Nya hingga mencapai potensi penuhnya, akan mencengkam bangsa-bangsa yang telah melampaui batas.
Pertama-tama kita ditunjukkan pada seluruh penciptaan dalam totalitas kosmiknya, lalu kita disodori dengan beberapa contoh historis tentang nasib kaum yang melampaui batas. Setelah rangkaian ayat-ayat ini bercerita tentang beberapa peristiwa dalam sejarah, kita akhirnya sampai pada manusia masa kini.
فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ فَيَقُوْلُ رَبِّيْ أَكْرَمَنِ
وَ أَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُوْلُ رَبِّيْ أَهَانَنِ
Ibtalā (dari balā), berarti ‘mencoba, memberikan ujian, menimpakan penderitaan’. Tujuan eksistensi manusia adalah untuk menjalani balwā (penderitaan, cobaan) agar beradab dan baik perilakunya sehingga ia berada dalam islam yang sebenarnya: ketundukkan, kepasrahan diri dan kemerdekaan yang sesungguhnya, sebagai hamba sejati dari kemerdekaannya dan dalam kemerdekaan dari penghambaan sejati. Kehidupan dunia ini tak lain hanyalah penderitaan (balwā). Jika seseorang mempunyai harta, maka sulitlah baginya untuk mempertahankan dan memeliharanya, dan, jika ia benar-benar dalam islam, maka ia akan membelanjakannya dengan bijak, karena tahu bahwa penggunaan yang salah akan dimintai pertanggungjawabannya. Jika seseorang tidak mempunyai harta, ia mengalami penderitaan karena ketiadaannya, kuatir akan tidak mampu menghidupi dirinya dan orang lain, dan seterusnya. Jadi setiap orang mengalami ketidakamanan, baik si kaya maupun si miskin.
Barang material memang penting. Manusia tidak bisa berfungsi tanpa adanya barang-barang yang pokok. Jika seseorang tidak diberi makan dan tidak ada atap untuk berlindung, maka akan sulit baginya untuk mempelajari makna batin dari eksistensi ini. Di lain pihak, ingatan seseorang tidak pemah berhenti pada satu tingkat kepuasan: sifatnya menginginkan lebih dan lebih lagi.
Ketika manusia diberikan kesenangan lahiriah, ia duduk-duduk saja sambil berkata, “Tuhanku sayang dan bermurah hati kepadaku.” Di lain pihak, jika perbekalannya terbatas, maka hal itu menguji kesabaran, keuletan dan kesanggupannya untuk tidak terlampau cemas. Manusia mengira bahwa kemiskinan dimaksudkan hanya untuk merendahkannya.
Ada beberapa kata bahasa Arab yang diterjemahkan sebagai ‘kemurahan hati’, meskipun masing-masing sedikit berbeda secara tajam. Karuma berarti ‘memberi apa pun yang diminta’. Sakhā berarti ‘memberi apa yang dibutuhkan dan perlu’, dan jāda berarti ‘memberi tanpa diminta’. Makna dari kata-kata ini merupakan sifat dari Sang Pencipta. Ītsār adalah ‘memberikan kepada orang lain apa yang dia sendiri butuhkan’. Ini adalah perbuatan yang sangat mulia dari sifat sepi ing pamrih (Tidak mengharapkan Pamrih). Hanya manusia yang melakukannya, karena Allah tidak membutuhkan apa pun.