Surah al-Fajr 89 ~ Tafsir Sayyid Quthb (3/4)
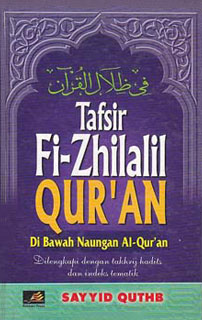
Tafsīr fi Zhilāl-il-Qur’ān
Oleh: Sayyid Quthb Penerbit: Gema Insani
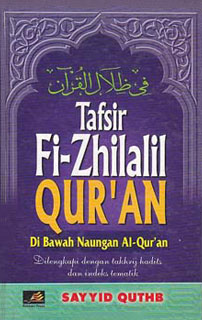
“Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.” (al-Fajr: 14).
Dia melihat, menghitung, memperhitungkan, dan akan memberi balasan, sesuai timbangan yang cermat dan tak pernah salah. Dia tidak pernah dan tidak akan berbuat aniaya. Dia tiak menghukumi sesuatu berdasarkan lahiriahnya, melainkan menurut hakikatnya. Sedangkan manusia, maka pertimbangannya sering keliru, dan ukurannya sering melenceng. Mereka hanya melihat fenomena lahiriah saja, tidak berhubungan dengan timbangan Allah:
فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ فَيَقُوْلُ رَبِّيْ أَكْرَمَنِ. وَ أَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُوْلُ رَبِّيْ أَهَانَنِ.
“Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, maka dia berkata: “Tuhanku telah memuliakanku”. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya maka dia berkata: “Tuhanku menghinakanku”” (al-Fajr: 15-16).
Demikian pandangan manusia terhadap ujian-ujian yang diberikan Allah yang berupa kelapangan dan kesempitan, kekayaan dan kemiskinan. Manusia diuji-Nya dengan keni‘matan dan kemuliaan, dengan harta kekayaan dan atau kedudukan. Akan tetapi, ia tidak mengerti kalau itu ujian, yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Ia mengira bahwa rezeki dan kedudukan ini sebagai indikasi yang menunjukkan bahwa ia berhak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, dan sebagai pertanda bahwa Allah telah memilihnya. Lalu, ia beranggapan bahwa ujian itu sebagai balasan, dan ia mengukur kemuliaan di sisi Allah itu dengan diberikan-Nya kehidupan seperti ini.
Adakalanya Allah menguji manusia dengan menyempitkan rezekinya. Lantas, ia mengira bahwa ujian semacam ini sebagai balasan dan dianggapnya sebagai hukuman. Ia memandang kesempitan rezeki itu sebagai indikasi kehinaan di sisi Allah. Karena, pikirnya, kalau Allah tidak menghinanya, tentu Dia tidak akan menyempitkan rezekinya.
Ternyata pola pikir dan pengukuran semacam ini adalah salah. Karena, kelapangan atau kesempitan rezeki itu hanyalah ujian dari Allah kepada hamba-Nya. Apakah ia mensyukuri ni‘mat itu atau menyombongkan diri, bersabar atas ujian itu atau berkeluh-kesah? Adapun balasannya nanti bergantung pada sikap yang dimunculkannya. Namun, diberikannya kekayaan dunia atau dihalanginya untuk mendapatkannya itu bukan balasan.
Nilai seseorang di sisi Allah tidak berhubungan dengan kekayaan dunia yang dimilikinya. Keridhāan atau kebencian Allah tidak ditunjuki oleh perolehan kekayaan atau keterhalangan mendapatkannya di dunia ini. Karena Dia memberi rezeki kepada orang yang shalih dan yang durhaka. Dia juga menghalanginya dari orang yang shāliḥ dan yang durhaka. Akan tetapi, di belakang semua itu, ada hal yang harus diperhatikan. Yaitu bahwa Dia memberi rezeki adalah untuk menguji dan menghalangi (tidak memberi) itu pun untuk menguji. Adapun yang perlu mendapatkan perhatian di sini adalah hasil ujian tersebut.
Hanya saja, ketika hati manusia kosong dari iman, maka ia tidak mengerti hikmah penghalangan dan pemberian itu, dan tidak mengerti hakikat nilai dalam timbangan Allah. Apabila hatinya penuh dengan Allah dan mengerti apa yang ada di sana. Sehingga, kekayaan dunia yang tak berharga ini terasa rendah nilainya menurut timbangannya. Ia sadar bahwa di belakang ujian ini akan ada balasan. Sehingga, ia akan tetap ber‘amal shāliḥ baik ketika mendapat kelapangan rezeki maupun ketika rezekinya sedang sempit. Hatinya merasa mantap terhadap qadar Allah dalam kedua keadaan itu. Tahu pulalah ia bahwa harga dirinya dalam timbangan Allah bukan dengan nilai-nilai lahiriah yang hampa ini.
Al-Qur’ān periode Makkah berbicara kepada manusia yang banyak didapati orang-orang seperti itu di dalam semua bentuk kejahiliahan yang telah kehilangan hubungannya dengan alam yang lebih tinggi dan lebih luas daripada bumi ini. Yaitu, manusia yang berprasangka seperti itu terhadap Tuhannya dalam masalah kelapangan dan kesempitan rezeki. Begitulah ukuran yang mereka buat di dalam menilai manusia di bumi ini.
Hal itu disebabkan harta dan kedudukan adalah segala-galanya bagi mereka, dan apa yang ada di belakang itu tidak ada nilainya lagi. Karena itu, perhatian mereka terhadap harta sangat besar, dan kecintaan mereka sangat berlebihan. Sehingga, mereka rakus dan serakah, tamak dan kikir. Maka, diungkapkanlah apa yang terkadung dalam hati mereka mengenai lapangan ini. Juga ditetapkanlah bahwa keserakahan dan kekikiran ini yang menjadi biang kekeliruan mereka di dalam memahami ma‘na ujian yang berupa kelapangan dan kesempitan dalam rezeki.
كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ. وَ لَا تَحَاضُّوْنَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ. وَ تَأْكُلُوْنَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا. وَ تُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا.
“Sekali-kali tidak (demikian). Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampurbaurkan (yang halal dan yang bāthil), dan kamu mencintai harta-benda dengan kecintaan berlebihan” (al-Fajr: 17-20).
Tidak! Persoalannya tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang hatinya kosong dari iman. Kelapangan rezeki itu bukan indikasi yang menunjukkan kemuliaan kedudukan orang tersebut di sisi Allah. Kesempitan rezeki juga bukan indikasi yang menunjukkan kehinaan dan ketersia-siaannya. Persoalannya adalah bahwa kamu tidak memenuhi hak harta. Karena itu, kamu tidak memuliakan anak yatim yang kecil yang telah kehilangan pelindung dan penjaminnya ketika ayahnya sudah tiada. Kamu tidak saling menganjurkan satu sama lain untuk memberi makan kepada orang-orang miskin yang tidak mau meminta-minta padahal dia sangat membutuhkan bantuan.
Ketidakmauan saling menganjurkan dan saling berpesan untuk memberi makan kepada orang miskin ini, dianggap sebagai keburukan yang sangat mungkar. Al-Qur’ān memberikan arahan betapa perlunya melakukan kesetiakawanan terhadap jama‘ah, dan dianjurkannya mereka untuk menunaikan kewajiban dan melakukan kebaikan umum. Demikianah di antara sifat ajaran Islam.
Sesungguhnya kamu tidak mengetahui ma‘na ujian. Karena itu, kamu tidak berusaaha untuk dapat lulus dalam ujian ini, dengan memuliakan anak yatim dan saling berpesan untuk memberi makan kepada orang miskin. Bahkan sebaliknya, kamu memakan harta pusaka dengan loba dan rakus, dan kamu mencintai harta-benda secara berlebihan. Sehingga, tidak ada lagi di dalam hatimu rasa kasih-sayang dan penghormatan terhadap orang-orang yang perlu dimuliakan dan diberi makan.
Islam dalam periode Makkah menghadapi kondisi kerakusan dan ketamakan untuk mengumpulkan harta-benda dengan segala cara, yang menimbulkan kekerasan dan kekasaran dalam hati. Anak-anak yatim yang lemah menjadi sasaran perampasan harta. Khususnya anak yatim yang wanita mendapat perlakuan itu dalam berbagai bentuk dan cara, lebih-lebih yang berkaitan dengan warisan (sebagaimana sudah dijelaskan di muka dalam beberapa tempat di dalam tafsir azh-Zhilāl ini). Perampasan harta anak yatim marak dilakukan sebagaimana halnya kecintaan terhadap harta dan pengumpulannya dengan jalan riba dan lain-lainnya dilakukan dengan terbuka dan terang-terangan di kalangan masyarakat Makkah sebelum datangnya Islam. Ini merupakan salah satu jahiliah pada setiap masa dan tempat, hingga sekarang!
Lebih dari sekadar menyingkap sikap bathin mereka, dalam ayat-ayat ini juga terkandung ancaman dan larangan dari tindakan itu. Hal ini tercermin dalam perulangan kata kallā “sekali-kali tidak” yang juga tercermin dalam pengungkapan dan iramanya, yang melukiskan betapa keras dan kuatnya kerakusan dan ketamakan itu.
“Kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampurbaurkan (yang halal dan yang bāthil), dan kamu mencintai harta-benda dengan kecintaan berlebihan” (al-Fajr: 19-20).