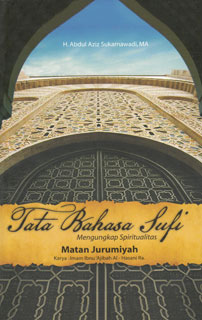بَابُ التَّمْيِيْزِ
Mengenal Titik Netral
بَابُ التَّمْيِيْزِ
التَّمْيِيْزُ هُوَ الْاِسْمُ الْمَنْصُوْبُ الْمُفَسِّرُ لِمَا انْبَهَمَ مِنَ الذَّوَاتِ نَحْوُ قَوْلِكَ تَصَبَّبَ زَيْدٌ عَرَقًا وَ تَفَقَّأَ بَكْرٌ شَحْمًا وَ طَابَ مُحَمَّدٌ نَفْسًا وَ اشْتَرَيْتُ عِشْرِيْنَ غُلَامًا وَ مَلَكْتُ تِسْعِيْنَ نَعْجَةً وَ زَيْدٌ أَكْرَمُ مِنْكَ أَبًا وَ أَجْمَلُ مِنْكَ وَجْهًا وَ لَا يَكُوْنُ إِلَّا نَكِرَةً وَ لَا يَكُوْنُ إِلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْكَلَامِ
Seorang wali tidak akan memperoleh kewaliannya kecuali bila ia telah meraih Tamyīz, yakni kemampuan membedakan dengan cermat dalam satu poin netral antara ketuhanan dan kehambaan, antara ruhani dan jasmani, antara yang halus dan yang kasar, antara kekuasaan dan kebijaksanaan, antara khalq dan amr, antara syariat dan hakikat, antara fanā’ dan baqā’, antara sakr dan shaḥw, dan antara segala sesuatu yang berbeda.
Di antara wali-wali yang telah menemukan titik netral itu seperti Syaikh Ibnu ‘Athā’illāh as-Sakandarī r.a. ketika beliau mengatakan:
سُبْحَانَ مَنْ سَتَرَ سِرَّ الْخُصُوْصِيَّةِ بِظُهُوْرِ الْبَشَرِيَّةِ وَ ظَهَرَ بِعَظَمَةِ الرُّبُوْبِيَّةِ فِيْ إِظْهَارِ الْعُبُوْدِيَّةِ
“Maha Suci Allah yang menutupi rahasia keistimewaan hamba-Nya dengan tampilnya sifat-sifat manusiawinya. Dan Dia Jelas dengan keagungan sifat ketuhanan-Nya di dalam manifestasi sifat-sifat hamba-Nya.”
Begitu juga Syaikh al-Hallāj r.a. ketika mengatakan:
سُبْحَانَ مَنْ أَظْهَرَ نَاسُوْتَهُ سِرَّ سني لَاهُوْته الثَّاقِب ثُمَّ بَدَا فِيْ خَلْقِهِ ظَاهِرًا فِيْ صُوْرَةِ الْآكِلِ وَ الشَّارِبِ حَتَّى لَقَدْ عَايَنَهُ خَلْقَهُ كَلَحْظَةِ الْحَاجِبِ بِالْحَاجِبِ.
“Maha Suci Allah yang penciptaan-Nya menampakkan keyakinan yang tajam, lalu terciptalah makhluk yang dapat minum dan makan, namun ia senantiasa dekat sedekat kedua alis mata yang berpejam.”
Namun karena kata-kata Syaikh al-Hallāj ini tidak dimengerti sama sekali oleh banyak orang, akhirnya beliau dibunuh oleh ahli zhahir. Padahal, ahli batin sangat percaya bahwa apa yang dikatakannya benar.
Untuk membedakan antara jasmani dan ruhani, maka jasmani adalah pusat pengabdian, sedang ruhani adalah pusat penyaksian.
Untuk membedakan antara yang halus dan yang kasar, maka yang kasar adalah yang dapat dirasakan dengan panca indra, sedang yang halus adalah yang dapat diresapi dengan hati yang terpesona. Dan dalam hal ini Syaikh at-Tustarī r.a. berkata:
لَا تَنْظُرْ إِلَى الْأَوَانِيْ وَ خُضْ بَحْرَ الْمَعَانِيْ لَعَلَّكَ تَرَانِيْ.
“Janganlah engkau melihat bejana saja, tapi menyelamlah ke dalam lautan makna, siapa tahu kau dapat menyaksikan-Nya.”
Untuk membedakan antara kekuasaan dan kebijaksanaan, maka kekuasaan selalu dapat disaksikan dengan mudah, sedang kebijaksanaan mesti dijiwai dan diresapi dengan hikmah. Golongan Jabariyyah hanya meyakini kekuasaan, dan Mu‘tazilah hanya mempercayai kebijaksanaan, sedang Ahl-us-Sunnah berkeyakinan bahwa kekuasaan senantiasa memakai jubah kebijaksanaan.
Untuk membedakan antara khalq dan amr, maka khalq adalah penciptaan yang melalui proses, sedang amr adalah penciptaan tanpa proses.
Untuk mebedakan antara syariat dan hakikat, maka syariat adalah etika zhahir, sedang hakikat adalah etika batin.
Dan untuk membedakan antara fanā’ dan baqā’, maka fanā’ adalah meniadakan wujud diri sendiri dan menikmati wujud yang hakiki, sedang baqā’ adalah merasakan keduanya sehingga masing-masing diberikan haknya.
Demikianlah maka tamyīz adalah kemampuan menafsirkan apa yang tersirat dalam segala sesuatu sehingga dapat membedakan yang satu dengan yang lain, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, dan memberikan segala sesuatu apa yang telah menjadi haknya.