001-2 Pengertian Kalam – Ngaji Jurumiyyah
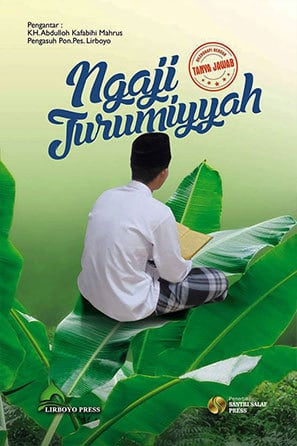
JURUMIYYAH
Kajian & Tanya Jawab
Penyusun: M. Fathu Lillah, M. Muqayyim-ul-Haq
Penerbit: Santri Salaf Press
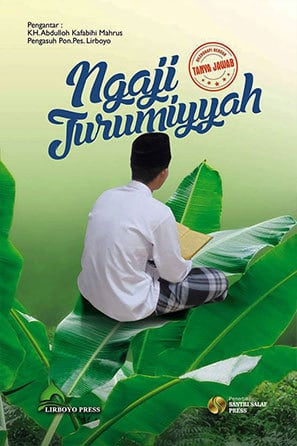
JURUMIYYAH
Kajian & Tanya Jawab
Penyusun: M. Fathu Lillah, M. Muqayyim-ul-Haq
Penerbit: Santri Salaf Press
URAIAN
Pengertian Kalām
Makna dari lafazh adalah suara yang memuat sebagian huruf hijā’iyyah baik secara nyata atau secara hukumnya saja, seperti halnya dhamīr mustatir dalam fi‘il amar, contoh: (قُمْ) dengan pentakdiran lafazh (أَنْتَ) (11), atau dalam fi‘il mudhāri‘, seperti contoh: (نَقُوْمُ) dengan pentakdiran lafazh (نَحْنُ) karena lafazh-lafazh tersebut dihukumi sebagaimana lafazh yang diucapkan, dengan bukti dhamīr yang ada pada lafazh tersebut akan tampak ketika dalam bentuk dhamīr jama‘ ataupun dhamīr tatsniyah (22). Dari qayyid huruf di atas dapat disimpulkan bahwa lafazh haruslah berupa huruf yang diucapkan, maka untuk isyarah ataupun tulisan tidak bisa dikatakan kalām (33). Dan juga harus memuat dari sebagian huruf hijā’iyyah, maka mengecualikan pula suara yang dihasilkan dari suara kendang (44).
Makna dari murakkab adalah tersusunnya kalām dari dua kalimah atau lebih dengan susunan penyandaran (تَرْكِيْبُ إِسْنَادِيّ) (55) contoh: (قَامَ زَيْدٌ). Dengan batasan dua kalimat atau lebih maka satu kalimat seperti halnya (زَيْدٌ) tidak bisa dikatakan kalam. Susunnan kalām tidaklah harus bersifat nyata namun bisa pula berupa susunan yang berbentuk pentakdiran seperti pada contoh ketika ada orang yang bertanya pada mukhāthab (مَنِ الْجَائِي؟) kemudian dijawab (زَيْدٌ), maka contoh ini sudah dianggap sebagai kalām karena ketika ditakdirkan akan ada sebuah susunan dua kalimat (زَيْدٌ الْجَائِي) (66). Selain susunan dari tarkīb isnādī tidak bisa dikatakan kalām seperti tarkib idhāfī, contoh: (عَبْدُ اللهِ), tarkīb mazjī, seperti: (مَعْلَبَك), tarkīb isnādī yang sudah digunakan untuk nama sesuatu, contoh: (تَأَبَّطَ شَرًّا) (77).
Makna dari mufīd adalah sebuah fa’idah yang dirasa baik oleh mutakallim (pembicara) dan sāmi‘ (pendengar) untuk diam dari perbincangan mereka, sekira sāmi‘ tidak menunggu kelanjutan dari kejelasan apa yang diungkapkan oleh mutakallim dengan menunggu secara total (88). Seorang sāmi‘ ketika mendengar dari mutakallim yang mengkhabarkan berdirinya Zaid (قَامَ زَيْدٌ) maka dia akan faham bahwa mutakallim mengkhabarkan berdirinya si Zaid tanpa menunggu lagi kejelasan-kejelasan lain terkait dari berdirinya Zaid. Dalam ungkapan yang menggunakan fi‘il muta‘addī, penyebutan fi‘il dan fā‘ilnya saja sudah bisa dianggap kalām, meskipun sāmi‘ menanti ungkapan dari mutakallim untuk menyebutkan maf‘ūlnya, karena menunggunya sāmi‘ dari penyebutan maf‘ūl dari mutakallim tidaklah lama tidak secara total (99).
Maksud dari wadha‘ adalah menyengajanya mutakallim untuk mengucapkan sebuah lafazh yang bisa memberikan sebuah fa’idah kepada seorang sāmi‘ (1010). Pendapat ini dipelopori oleh beberapa ulama’ yang salah satunya adalah Imām Abū Mālik dalam kitab Tashīl. Jumlah yang menjadi khabar, semisal: (قَامَ أَبُوْهُ) pada contoh: (زَيْدٌ قَامَ أَبُوْهُ) tidak bisa dikatakan kalām, karena tujuan dari mutakallim bukan memberikan khabar berdirinya bapaknya Zaid, namun tujuan dari mutakallim adalah memberikan khabar akan sosok dari seorang yang )bernama( Zaid yang ayahnya sedang berdiri. Dari pengertian ini juga akan mengecualikan kalām (ucapan) yang keluar dari orang yang tidur (ngelindur; Jawa) dan orang yang lupa. Namun sebagian ulama’ mengartikan wadha‘ dengan sebuah lafazh yang dicetak oleh orang ‘Arab dengan memakai bahasa ‘Arab, maka untuk lafazh yang dicetak tidak memakai bahasa ‘Arab (kalām ‘Ajam) seperti kalām Turki, Indonesia, tidak bisa dikatakan sebagai kalām (1111).
Catatan: