Tasbih – Al-Ma’tsurat (3/3)
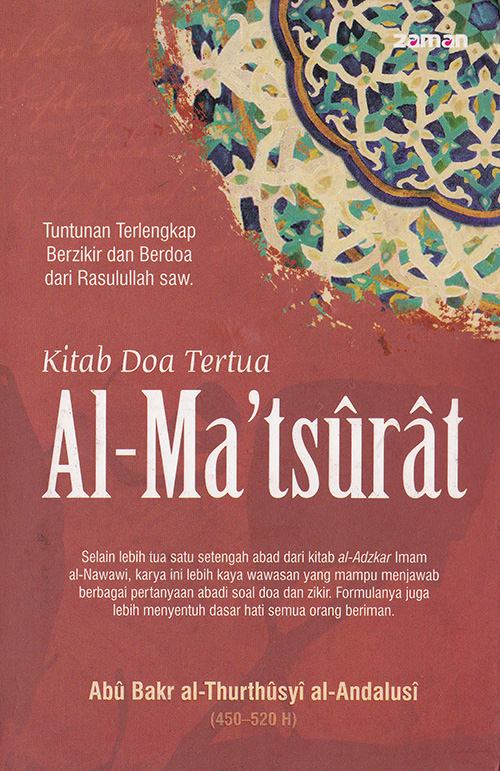
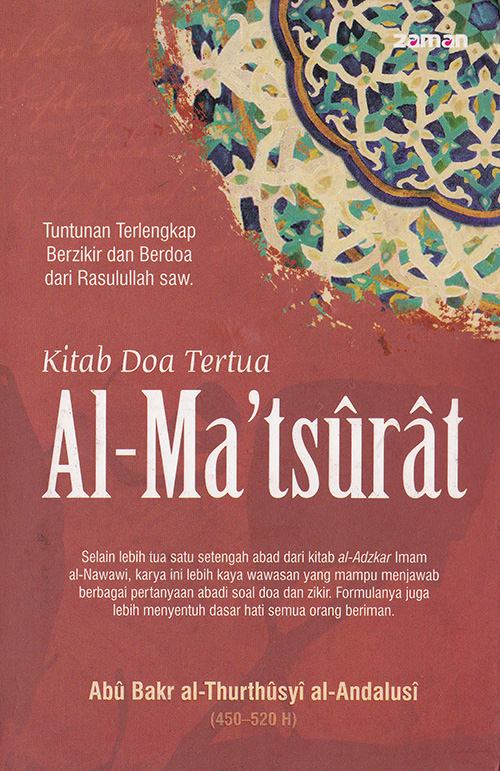
Allah s.w.t. berfirman: “Dan semua bersujūd kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, (dan sujūd pula) bayang-bayang mereka, pada waktu pagi dan petang hari.” (ar-Ra‘d [13]: 15). Bagaimana kalangan Qadariyyah menafsirkan firman ini? Bayangan adalah aksiden-aksiden (‘aradh) yang tidak bisa berdiri sendiri, dan karenanya mustahil ia mempunyai kehidupan alias hidup.
Menurut mereka, orang mu’min sujūd kepada Allah s.w.t. karena kemauannya sendiri, sementara orang kafir akan tunduk ketika sebuah kondisi darurat mengharuskannya untuk melakukan itu.
Allah s.w.t. berfirman: “Bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri, dalam keadaan sujūd kepada Allah, dan mereka (bersikap) rendah hati.” (an-Naḥl [16]: 48). Menurut ‘ulamā’ tafsir (1871), “berbolak-balik” berarti miring atau condong. Jadi, bayang-bayang condong ke satu sisi di waktu pagi dan condong ke sisi lain pada waktu petang. Bagi kalangan Qadariyyah, condongnya bayang-bayang inilah yang dikatakan sujūdnya bayang-bayang tersebut.
Dikatakan: “Keledai itu bersujūd dan disujūdkan.” Ma‘nanya adalah keledai itu dimiringkan agar bisa dinaiki. Dikatakan pula: “Pohon kurma itu bersujūd.” Ma‘nanya adalah pohon kurma itu miring.
Sujūd adalah kiasan dari penyerahan diri dan kepatuhan. Jadi, menurut kalangan Qadariyyah, berbolak-baliknya bayangan dari satu sisi ke sisi lain adalah sujūdnya bayangan tersebut karena ia telah berpasrah diri dan patuh.
Pendapat kalangan Qadariyyah ini bisa kita tanggapi sebagai berikut. Memang benar bahwa bayangan adalah aksiden (‘aradh), yaitu tetapnya substansi-substansi (al-jawāhir) bayangan dan person (syakhsy) pada warna aslinya sebelum matahari terbit. Tetapi, substansi-substansi ini akan berubah ketika diterpa matahari sehingga orang akan melihatnya memiliki warna berbeda. Berubahnya bayangan menjadi aksiden adalah bukti yang memaksa akal untuk menganggapnya sebagai kiasan. Ini berbeda dengan fisik konkrit (al-ajsām) dan substansi-substansi selainnya (selain bayangan) yang salah satu sifat dzātnya adalah menerima aksiden-aksiden. Lalu, kehidupan, akal dan ‘ilmu adalah aksiden-aksiden yang tidak mustahil diciptakan di dalam al-ajsām dan al-jawāhir.
Kita akan kembali ke pembahasan awal seputar tasbīḥ.
Keutamaan tasbīḥ ditunjukkan oleh banyak ayat al-Qur’ān. Ketika Allah s.w.t. memberi tahu Nabi s.a.w. tentang kemenangan agama-Nya di dalam surah an-Nashr, Dia s.w.t. memerintahkan Nabi s.a.w. agar bertasbīḥ dan memohon ampunan kepada-Nya. Dia s.w.t. berfirman: “Maka bertasbīḥlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepada-Nya.” (an-Nashr [110]: 3). Ibnu Mas‘ūd berkata: “Setelah ayat ini turun, Nabi s.a.w. kemudian selalu memperbanyak mengucap: “Maha Suci Engkau, Ya Allah, segala puji hanya milik-Mu, ampunilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Penerima tobat dan Maha Penyayang.”
‘Ā’isyah meriwayatkan bahwa sebelum wafat Nabi s.a.w. memperbanyak mengucap: “Maha Suci Engkau, Ya Allah, segala puji hanya milik-Mu, aku memohon ampunan dan bertobat kepada-Mu.”
‘Ā’isyah berkata: “Ketika surah ini turun, aku tidak pernah melihat Nabi s.a.w. mengerjakan shalat apapun kecuali beliau mengikutinya dengan mengucap: “Mahasuci Engkau, Ya Allah, segala puji hanya milik-Mu, ampunilah aku.”
Ummu Salamah meriwayatkan bahwa Nabi s.a.w. tidak berdiri, tidak duduk, tidak datang dari bepergian, dan tidak bepergian kecuali mengucap: “Maha Suci Allah, segala puji hanya milik-Mu, aku memohon ampunan dan bertobat kepada-Mu.” Beliau bersabda: “Aku disuruh untuk mengucapkan itu.” Beliau lalu membaca ayat: “Apabila telah datang pertolongan Allah s.w.t. dan kemenangan….. sampai akhir ayat.” (an-Nashr [111]: 1-4). (1882).
Apabila dipastikan bahwa tasbīḥ adalah tanzīh (penafian semua sifat tak sempurna pada Allah s.w.t.), sementara Allah s.w.t. juga telah memerintahkan hamba-hambaNya agar bertasbīḥ, maka setiap ucapan yang mengandung tanzīh dan penyucian-Nya dari semua sifat yang tidak boleh disematkan pada-Nya adalah tasbīḥ.
Jika engkau mengucapkan kalimat lā ilāha illlā Allāh, berarti engkau telah menafikan semua sifat yang tidak boleh disematkan pada-Nya, termasuk tidak menjadikan sekutu apa pun bagi-Nya, dan menetapkan bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan. Inilah tasbīḥ yang menempati derajat tertinggi.
Nabi s.a.w. bersabda: “Sebaik-baik yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah kalimat lā ilāha illlā Allāh.”
‘Umar al-Munsatīrī, seorang ahli ibadah di istana Munsatīr, menuturkan: “Aku pernah bermimpi seolah-olah aku bertakbir di atas lautan. Aku bertakbir sebanyak tiga kali. Tiba-tiba seseorang berdiri di depanku dan berkata: “Sempurnakanlah takbir! Semoga Allah s.w.t. menjagamu dari segala hal yang tak diinginkan!” Aku pun bertanya: “Apa yang belum aku ucapkan?” Ia lalu berkata: “Ucapkanlah subḥān-al-‘alīmi bi kaylika (Maha Suci Engkau Yang Maha Mengetahui timbangan-Mu), subḥān-al-‘alīmi bi wazni qathrika (Maha Suci Engkau Yang Maha Mengetahui takaran hujan-Mu), subḥān-al-‘alīmi bi ‘adadi sukkāni qa‘rika (Maha Suci Engkau Yang Maha Mengetahui jumlah penduduk bumi-Mu).”
Diriwayatkan bahwa al-Ashbāgh ibn Yazīd ibn Abī Shālih berkata: “Ku keluar rumah setelah maghrib dan melihat seekor burung berwarna putih nan gemuk mengucapkan subḥānallāh, sementara orang-orang tidak mengetahui dan menyadari hal itu.”
Sa‘īd bin ‘Abd-il-‘Azīz berkata: Aku berkata kepada ‘Umayr ibn Hāni’: “Aku melihat lisanmu tidak henti-hentinya berdzikir kepada Allah. Berapa kali engkau bertasbīḥ setiap hari?” Ia menjawab: “Seribu kali, jika jari-jari (yang aku buat untuk menghitung) ini tidak salah.” (1893).
Demikian penjelasan dan pemaparan kami tentang tasbīḥ.