Sanggahan Terhadap yang Mengharamkan Nyanyian dan Main Musik – Seni Dalam Pandangan Islam (1/2)
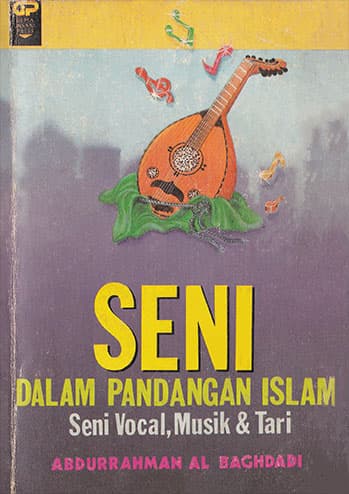
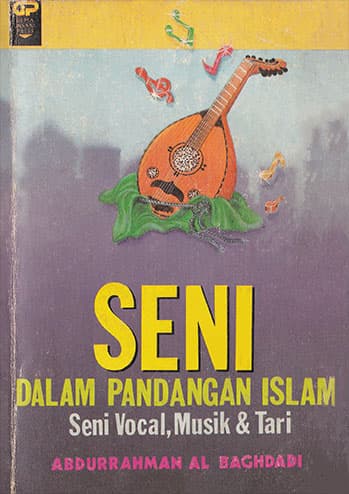
BĀB VI.
Apabila diteliti mendalam dalil-dalil syara‘ maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan manusia seperti melihat, mendengar, bersuara, berjalan, tidur dan menggunakan tangan adalah mubāḥ bila dilihat dari kerumuman pengertian dalil. Sebagai contoh, perhatikanlah firman Allah s.w.t.:
(أَ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَ لِسَانًا وَ شَفَتَيْنِ) (البلد:8,9)
“Bukankah Kami telah berikan kepadamu dua buah mata (untuk melihat), lidah dan dua buah bibir (untuk bersuara, mengecap makanan dan minuman).” (90:8,9).
(هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا…) (الملك: 15)
“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu. Maka, berjalanlah di segala penjurunya….”(67:15).
(وَ جَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا) (النبأ: 9)
“Dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat.” (78:9).
(لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَ مَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ…..) (يس: 35)
“Supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diushakan oleh tangan mereka…..” (36:35).
Dalil-dalil di atas mengajarkan kepada kita bahwa manusia boleh melihat dan mendengar apa saja. Manusia boleh melihat pemandangan, mendengarkan suara wanita dan nyanyiannya kecuali terhadap apa-apa yang telah dilarang syara‘ dalam perbuatan itu (Lihat Saif-ud-Dīn al-Āmidī, AL-IḤKĀM FĪ USHŪL-IL-AḤKĀM, Jilid I, hlm. 130).
Seseorang juga dibolehkan mengeluarkan suara dengan cara apapun, misalnya berbicara, berpidato, berdiskusi, dan bernyanyi, kecuali bila ada suatu dalil syara‘ yang memang melarangnya. Begitu pula tentang gerakan-gerakan lainnya. Sebagai salah satu contoh adalah sabda Rasūlullāh s.a.w. (H.R. Muslim, dari Abū Hurairah : Ḥadīts No.2657):
(كُتِبَ عَلى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنى مُدْرِكٌ ذلِكَ لاَ مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانُ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَ الأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاِسْتِمَاعُ وَ اللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلاَمُ وَ الْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَ الرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَاءُ وَ الْقَلْبُ يَهْوى وَ يَتَمَنّى وَ يُصَدِّقُ ذلِكَ الْفَرْجُ وَ يُكَذِّبُهُ)
“Bani Ādam (manusia) tidak dapat menghindar dari perbuatan (yang menghantarkannya kepada) zina, yang pasti akan menimpanya, yaitu zina mata adalah dengan melihat (aurat wanita), zina telinga adalah dengan mendengar (kata-kata porno, cinta asmara dari wanita/lelaki yang bukan suami/istri), zina mulut adalah dengan rayuan dan kata-kata kotor dan porno), zina tangan adalah dengan bertindak kasar (memperkosa, menjawil wanita), zina kaki adalah dengan berjalan (ke tempat maksiat, misalnya ke kompleks WTS). (Dalam hal ini), hatilah yang punya hajat dan cenderung (kepada perbuatan-perbuatan tersebut), dan farji (kelamin) yang menerima dan menolaknya.”
Menurut riwayat lain yang diriwayatkan oleh ats-Tsa‘labī melalui Ibnu ‘Abbās, ada tambahan lafazh pada ḥadīts tersebut, yakni:
(وَ زِنَى الشَّفَتَيْنِ الْقُبْلَةُ)
“Zina bibir adalah mencium (wanita yang bukan istrinya)”. (Lihat TAFSĪR QURTHUBĪ, Jilid XVII, hal. 106-107).
Bertolak dari dasar hukum inilah maka mendengar atau memainkan alat-alat musik atau menyanyi mubāḥ selama tidak terdapat suatu dalil syar‘i yang menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut ḥarām atau makrūh. Mengenai menyanyi atau memainkan alat musik dengan atau tanpa nyanyian, tidak terdapat satupun nash, baik dari al-Qur’ān maupun sunnah Rasūl yang meng-ḥarām-kannya dengan tegas. Memang ada sebagian dari para sahabat, tābi‘īn dan ‘ulamā’ yang meng-ḥarām-kan sebagian atau seluruhnya karena mengartikannya dari beberapa nash tertentu. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa hal tersebut makrūh, sedangkan yang lain mengatakan hukumnya mubāḥ.
Adapun nash-nash (dalil-dalil) yang dijadikan alasan oleh mereka yang meng-ḥarām-kan seni suara dan musik bukanlah dalil-dalil yang kuat. Sebagaimana telah disebutkan di atas, tidak ada satu dalil pun yang berbicara secara tegas dalam hal ini. Dengan demikian, tidak seorang manusia pun yang wajib diikuti selain daripada Rasūlullāh s.a.w. Beliau sendiri tidak meng-ḥarām-kannya. Seluruh riwayat ḥadīts yang dipakai oleh golongan yang meng-ḥarām-kan alat musik dan nyanyian adalah dha‘īf atau maudhū‘ (palsu dan lemah). Oleh karena itu, Imām Abū Bakar Ibn-ul-‘Arabī berkata: “Tidak terdapat satu dalil pun di dalam al-Qur’ān maupun Sunnah Rasūl yang meng-ḥarām-kan nyanyian. Bahkan ḥadīts Shaḥīḥ (banyak yang) menunjukkan kebolehan nyanyian itu. Setiap ḥadīts yang diriwayatkan maupun ayat yang dipergunakan untuk menunjukkan ke-ḥarām-annya maka ia adalah bāthil dari segi sanad, bāthil juga dari segi i‘tiqād, baik ia bertolak dari nash maupun dari satu penakwilan.” (Lihat Imām Abū Bakar Ibn-ul-‘Arabī, AḤKĀM-UL-QUR’ĀN, Jilid III, hlm. 1053-1054).
Walaupun ada beberapa riwayat yang benar dan bisa diterima tetapi ia tidak dapat dijadikan ḥujjah. Karena itu, patut kita bertanya, siapa yang patut diikuti, Rasūlullāh s.a.w. atau ‘ulamā’?!
Tentang siapa yang harus diikuti, seorang Muslim telah memahami bahwa hanya Rasūlullāh s.a.w. yang patut dijadikan rujukan atas setiap tindakannya. Bahkan pendapat ini telah diperkuat oleh sikap para sahabat dan tābi‘īn. Di kalangan mereka tidak terdapat perbedaan pendapat di antara penduduk Madīnah yang ketika itu merupakan tempat tinggal para sahabat yang sebelumnya mereka bergaul rapat dengan Rasūlullāh s.a.w. Misalnya, seperti apa yang dikutip oleh Imām Ibnu An-Nahawī dalam bukunya AL-‘UMDAH bahwa (Lihat Imām Asy-Syaukānī, NAIL-UL-AUTHĀR, Jilid VIII, hlm. 114-115). telah diriwayatkan tentang halalnya nyanyian dan mendengarkannya dari sekelompok sahabat dan tābi‘īn.
Kemudian Ibnu An-Nahawī mencantumkan nama-nama para sahabat dan tābi‘īn yang membolehkan menyanyikan nyanyian dan mendengarkannya.
Misalnya, di antara para sahabat adalah ‘Umar, ‘Utsmān, ‘Abd-ur-Raḥmān bin ‘Auf, Abū ‘Ubaidah al-Jarrah, Sa‘ad bin Abī Waqqāsh, Bilāl bin Rabbāḥ, Al-Burā’ bin Mālik, ‘Abdullāh bin al-Arqam, Usāmah bin Zaid, Ḥamzah bin ‘Umar, ‘Abdullāh bin ‘Umar, Qurrazhah bin Bakkār, Khawwat bin Jubair, Rabāḥ al-Mu‘tarif, al-Mughīrah bin Syu‘bah, ‘Amru bin al-‘Āsh, ‘Ā’isyah binti Abī Bakar, ar-Rabī‘, dan masih banyak lagi dari kalangan sahabat.
Sedangkan di kalangan tābi‘īn terdapat nama-nama seperti Sa‘īd bin al-Musayyab, Salīm bin ‘Umar, Ibnu Ḥassān, Kharizah bin Zaid, Syuraiḥ al-Qādhī, Sa‘īd bin Jubair, ‘Āmir asy-Sya‘bī, ‘Abdullāh bin Abī ‘Athīq, ‘Athā’ bin Abī Rabāḥ, Muḥammad bin Shahāb az-Zuhrī, ‘Umar bin ‘Abd-ul-‘Azīz, Sa‘ad bin Ibrāhīm az-Zuhrī.
Adapun dari kalangan tābi‘it tābi‘īn jumlahnya sangat banyak, di antaranya Imām yang empat, Ibnu ‘Uyainah, dan jumhur Syāfi‘iyyah. (Lihat Imām Asy-Syaukānī, NAIL-UL-AUTHĀR, Jilid VIII, hlm. 114-115).
Agar tidak timbul keraguan lagi maka di sini akan dibahas seluruh dalil yang dipakai oleh golongan yang meng-ḥarām-kan penggunaan alat-alat musik dan nyanyian.
Ayat ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan nyanyian. Tetapi ayat tersebut berkaitan erat dengan sikap dan perbuatan orang-orang kafir yang berusaha menjadikan ayat-ayat Allah s.w.t. sebagai senda-gurau. Tujuan mereka adalah untuk menghina, merendahkan dan berusaha menyesatkan orang-orang dari jalan-Nya. Mereka bermaksud menjauhkan orang-orang agar tidak mengikuti agama Islam. Sikap dan perbuatan ayat tersebut di atas terang dan jelas.
Dengan demikian, setiap usaha menakwilkan ayat tersebut dengan arti nyanyian adalah penyimpangan dari makna yang telah ditunjukkan oleh ayat itu sendiri.
Dalam menanggapi pengertian pada ayat tersebut di atas, Imām Ibnu Ḥazm telah membantah penggunaan dalil tersebut. Beliau berkata: (Lihat ‘Alī bin Aḥmad bin Sa‘īd Ibnu Ḥazm, AL-MUḤALLĀ, Jilid VI, hlm. 60):
“Teks ayat tersebut cukup untuk membatalkan ḥujjah mereka. Orang-orang yang bertindak demikian, sebagaimana yang diterangkan dalam ayat tersebut, adalah orang-orang yang bila mengerjakannya telah termasuk kafir tanpa ada selisih pendapat (khilāf). Mereka telah menjadikan sabīl (agama Allah s.w.t.) sebagai senda gurau.
Andaikan al-Qur’ān dibeli untuk menyesatkan orang-orang dari Jalan Allah s.w.t. dan dijadikannya sebagai bahan ejekan, maka tentu orang-orang yang melakukan hal tersebut telah menjadi kafir. Inilah yang dicela oleh Allah s.w.t. melalui ayat tersebut. Arti ayat itu bukanlah ditujukan kepada orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan sesuatu untuk menghibur diri tanpa bermaksud menyesatkan orang lain dari jalan Allah s.w.t. Dengan demikian, ḥujjah mereka telah gugur. Begitu pula dengan orang-orang yang sengaja menyibukkan diri dengan maksud tidak melakukan solat walaupun apa yang dilakukannya itu adalah dengan membaca al-Qur’ān, buku-buku Ḥadīts, mencari bahan untuk pengajian, sibuk memandang banyaknya uang, atau menyibukkan diri dengan nyanyian dan yang serupa dengannya, maka orang tersebut adalah fasiq dan telah berbuat maksiat. Adapun yang tidak meninggalkan sesuatu dari apa yang telah diwajibkan walaupun ia sibuk dengan apa yang telah diuraikan di atas, maka orang tersebut adalah muḥsin (orang yang tidak salah melangkah).
Ayat ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan nyanyian. Ia hanya menjelaskan tentang sikap kafir Quraisy yang merasa heran akan Hari Kebangkitan nanti yang sampai kepada kepada mereka. Karenanya, mereka menganggap hal tersebut merupakan kejadian yang mustahil terjadi. Walaupun ayat al-Qur’ān yang disampaikan Rasūlullāh s.a.w. kepada mereka telah memberitahukan tentang adanya Hari Kebangkitan itu, akan tetapi mereka mentertawakan dan merendahkannya. Padahal seharusnya mereka beriman dan menangisi dosa-dosa yang telah mereka perbuat.
Bertolak dari ayat ini, dari manakah para ‘ulamā’ tersebut mengambil pengertian tentang ḥarāmnya nyanyian? Kalau mereka bersandarkan kepada kata “SĀMIDUN” yang mempunyai arti “nyanyian” untuk ayat ini, maka sandaran tersebut tidak tepat sama sekali dan tidak sesuai untuk susunan ayat. Oleh karena itu, sebagian besar ahli tafsir berpendapat, yang dimaksud dengan kata “SĀMIDUN” adalah “MU‘RIDHUN” (menghindari daripadanya), dan atau “GHĀFILUN” (mengabaikan, melupakan). (Lihat TAFSĪR IBNU KATSĪR, Jilid IV, hlm. 261; lihat juga TAFSĪR ATH-THABARĪ, Juz XXVII, hlm. 48-49; TAFSĪR QURTHUBĪ, Juz XVII, hlm. 123-124).
Seperti ayat terdahulu, ayat ini juga tidak ada kaitannya dengan nyanyian. Tetapi ayat tersebut ada kaitannya dengan perbuatan Iblīs yang dibiarkan (hidup dan berbuat apa saja) oleh Allah s.w.t. untuk menggoda dan menyelewengkan manusia dari jalan-Nya, Iblīs dibiarkan leluasa mengajak manusia ke jalan maksiat. Oleh karena itu, kata “SHAUTIKA” pada ayat tersebut tidak dapat ditakwilkan dengan arti “nyanyian”.
Walaupun arti “SHAUTIKA” secara lughawi adalah “suaramu”, tetapi arti tersebut berbentuk kiasan. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat mendengar suara Iblīs. Manusia hanya dapat merasakan bisikan dari Iblīs (rasa was-was) yang berbentuk seruan atau ajakan kepada maksiat. Ini adalah pendapat Ibnu ‘Abbās, Qatādah, dan Ibnu Jarīr ath-Thabarī, serta pendapat ahli tafsir secara umum. (Lihat TAFSIR IBNU KATSĪR, Jilid III, ayat 50).
Pengertian inilah yang sesuai dengan susunan ayat tersebut di atas. Sedangkan hukum penggunaan alat-alat musik dan nyanyian, tidak bisa diambil dari ayat ini walaupun terdapat pendapat dari sebagian ‘ulamā’ tābi‘īn seperti Mujāhid, adh-Dhaḥḥāk, dan lain-lain, yang menafsirkan ayat tersebut dengan arti “nyanyian” dan “alat musik”. Tetapi ajakan atau seruan Iblīs untuk mengajak kepada maksiat kadang-kadang memang dapat saja dikaitkan dengan berbagai jenis hiburan yang kadarnya melebihi takaran (keterlaluan), atau melampaui batas-batas yang dibenarkan syara‘ seperti main musik dan beryanyi pada waktu shalat Jum‘at, atau tatkala kaum Muslimīn hendak berangkat ke medan jihad. Pada jenis pesta yang bercampur antara kaum lelaki dan perempuan adalah suatu peristiwa yang disenangi syaithan, apalagi kalau disertai dengan minuman keras, judi, main perempuan, joget bersama, dan lain-lain. Dengan demikian ayat ini dapat dikaitkan dengan bentuk-bentuk ajakan Iblīs yang sarananya berupa nyanyian atau hiburan lain yang tegas keharamannya.
Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian lima di atas, Ḥadīts ini tidak dapat dipakai sebagai dalil untuk meng-ḥarām-kan nyanyian dan penggunaan alat-alat musik. Di dalam Ḥadīts ini terdapat “QARĪNAH” (tanda penunjukan) bahwa mereka telah berani menghalalkan perzinaan, memakai sutera, menenggak (swallow, gulp down) khamr, dan memainkan alat-alat musik. Mengenai perzinaan dan minum khamr, sudah jelas hukumnya. Adapun mengenai pemakaian sutra dan memainkan alat-alat musik maka syara‘ telah mengaturnya sebagai berikut:
Mengenai sutra, syara‘ telah meng-ḥalāl-kannya bagi kaum wanita tetapi haram bagi kaum lelaki kecuali apabila ada alasan yang membolehkannya. Misalnya, bila seseorang menderita penyakit kulit (semisal eksim), maka ia mendapat “rukhshah” (keringanan) dan ia boleh memakainya. Semua keterangan tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud pemakai sutera dalam Ḥadīts tersebut adalah orang-orang yang meng-ḥalāl-kan pemakaian sutra bagi kaum lelaki secara mutlak tanpa kecuali.
Begitu pula tentang penggunaan alat-alat musik, syara‘ telah membolehkannya dalam acara pesta pernikahan atau pada hari raya dan hari-hari gembira lainnya. Tetapi dalam hal ini, syara‘ telah meng-ḥarām-kan menjadikan nyanyian dan memainkan orkes sebagai profesi kaum wanita. Artinya, mereka tidak dibolehkan menerima imbalan dari profesi (pekerjaan) tersebut.
Rasūlullāh s.a.w. bersabda:
(لاَ يَحِلُّ ثَمَنُ الْمُغَنِّيَةِ وَ لاَ بَيْعُهَا وَ لاَ شِرَاءُهَا وَ لاَ الاِسْتَمَاعُ إِلَيْهَا)
“Penghasilan penyanyi wanita (bayaran) adalah tidak ḥalāl, begitu juga memperjualkan dan mendengarkan suara (nyanyian) nya.”
Dari keterangan di atas dapat kita simpulkan, maksud Ḥadīts Imām Bukhārī tersebut jatuh kepada segolongan orang-orang dari kaum Muslimīn yang berani meng-ḥalāl-kan penggunaan alat-alat musik di luar batas-batas yang telah digariskan syara‘. Misalnya memainkannya di tempat umum (televisi, stadion, atau panggung-panggung pertunjukkan terbuka lainnya), bukan di tempat dan acara khusus, seperti pada acara pesta pernikahan di rumah-rumah. Dengan kata lain, syara‘ membolehkan biduanita budak menyanyi untuk pemilikinya, dan atau untuk para wanita lainnya dalam acara pernikahan. Boleh saja salah seorang di antara anggota keluarga pengantin ikut bernyanyi, tetapi syara‘ tidak membolehkan ada penyanyi wanita bayaran sebagaimana yang umum terjadi sekarang ini.