Menentukan Sikap dan Pendirian – Seni Dalam Pandangan Islam (2/2)
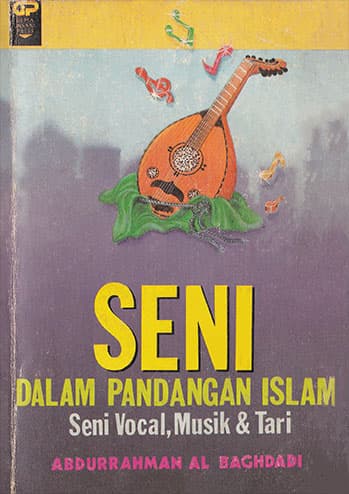
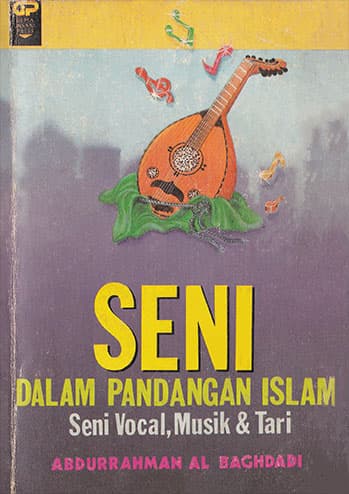
Di atas telah dijelaskan status hukum nyanyian dan menyanyikannya. Adapun hukum mendengarkan nyanyian yang mubāḥ maupun yang ḥarām, jawabnya wallāhu a‘lam!
Mendengarkan sesuatu hukumnya mubāḥ bila orang tersebut hanya sekadar mendengarkan. Tetapi bila ia ikut duduk di tempat-tempat hiburan sambil mendengarkan suara penyanyi lelaki maupun wanita, maka mendengar dalam keadaan demikian hukumnya juga ḥarām karena kita telah dilarang duduk bersama orang-orang yang melakukan maksiat. Ini sesuai dengan firman Allah s.w.t.:
(فَلاَ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ (إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ) (النساء: 140)
“Maka janganlah kamu duduk bersama mereka sampai mereka beralih kepada pembicaraan yang lain. (Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka)….” (4:140).
(فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) (الأنعَام: 68)
“….maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zhalim itu sesudah (mereka) diberi peringatan.” (6:68).
Imām al-Qurthubī dalam menafsirkan surat an-Nisā’ 140 menjelaskan (Lihat: TAFSĪR AL-QURTHUBĪ, Jilid V, hlm. 418) bahwa ayat tersebut menunjukkan wajibnya menjauhi orang-orang yang melakukan maksiat apabila mereka melakukan suatu kemungkaran. Oleh karena itu, setiap orang yang duduk di tempat maksiat dan tidak mengingkari (mengutuk dan mencegahnya), maka ia telah ikut serta bersama mereka dan akan memikul dosa yang sama. Itulah sebabnya seseorang harus mengingkari perbuatan maksiat itu bila mereka membicarakan atau melakukannya. Tetapi bila ia tidak mampu mencegah perbuatan mereka, maka ia harus segera meninggalkan tempat tersebut agar tidak tergolong ke dalam golongan yang disebutkan pada ayat di atas.”
Adapun mengenai surat AL-AN‘ĀM 68, beliau berkata (Lihat: TAFSĪR AL-QURTHUBĪ, Jilid VIII, hlm. 12-13): “Ayat ini menunjukkan apabila seseorang mengetahui atau menyaksikan orang lain sedang melakukan suatu kemungkaran, maka hendaklah ia menjauhinya sekaligus menolaknya dan tidak ingin mendatanginya lagi.”
Berkata pula Ibn-ul-‘Arabī: “Ini merupakan dalil bahwa hidup bersama orang-orang yang mengerjakan dosa besar hukumnya tidak boleh.”
Dengan demikian, seseorang yang berada atau duduk di tempat-tempat hiburan untuk mendengarkan nyanyian berarti mereka telah mengakui kemungkaran atau membiarkannya. Inilah jenis mendengar yang di-ḥarām-kan syara‘
Adapun nyanyian yang boleh (mubāḥ) beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi dan telah disebutkan di atas berbeda hukumnya. Kita boleh duduk di tempat-tempat pertunjukan (misalnya panggung-panggung terbuka) untuk mendengarkan nyanyian yang mendorong umat untuk berjihad fī sabīlillāh, memupuk perasaan halus kaum Muslimīn agar lebih bertaqwa kepada Allah s.w.t., atau membicarakan sifat-sifat orang mu’min dan nilai-nilai keislaman. Juga, nyanyian yang menggambarkan tentang keindahan alam serta nyanyian yang melunakkan hati seseorang fakir miskin dan yatim, nyanyian memuji kebaktian kepada ibu dan bapak, serta kepada keluarganya, atau juga nyanyian yang tujuannya mendidik anak-anak dan sebagainya. Dengan kata lain, nyanyian yang mubāḥ tidak ada kaitannya dengan persoalan cinta dan asmara, kecuali nyanyian dari suami kepada istri dan sebaliknya. Ia tidak disampaikan dengan cara mengeluh yang hal tersebut membangkitkan birahi seksual.
Adapun tentang masalah sya‘ir nyanyian, maka sya‘ir itu harus sebatas kata-kata yang sopan santun, bukan kata-kata yang berupa romantisme atau membicarakan kisah-kisah tentang malam minggu, malam pertama, dan sejenisnya. Dalam hal ini Ibn-ul-‘Arabī berkata (Lihat: Imām Ibn-ul-‘Arabī, AḤKĀM-UL-QUR’ĀN, Jilid III, hlm. 1494): “Hukum mendengarkan nyanyian seorang biduanita telah dijelaskan sebelumnya bahwa seorang lelaki boleh saja mendengarkan nyanyian wanita budaknya. Ini disebabkan karena tidak satu bagian pun yang ḥarām padanya, baik bagian luar maupun dalam. Dengan demikian, bagaimana mungkin ia dicegah untuk menikmati suaranya (nyanyiannya).”
Ada yang mengatakan bahwa yang boleh didengar adalah nyanyian dari lelaki, sedangkan nyanyian wanita ḥarām untuk didengar. Alasannya, suara wanita itu aurat (hal yang tidak boleh ditampilkan). Jawabannya wallāhu a‘lam.
Walaupun nyanyian yang memalukan itu ḥarām dikerjakan bila disertai dengan perbuatan ḥarām atau mungkar namun mendengarkannya tidaklah ḥarām. Ke-ḥarām-annya itu terbatas pada mendengarkannya secara langsung dari penyanyinya di tempat maksiat, bukan karena suara penyanyi wanita itu aurat. Keharaman itu terletak pada sikap berdiam diri terhadap nyanyian yang berisi kata-kata mungkar dan si penyanyi wanita menampilkan kecantikannya dengan membuka auratnya, misalnya rambut, leher, dada, betis, paha dan bagian aurat lainnya. Inilah yang di-ḥarām-kan oleh syara‘, bukan karena masalah mendengarkan nyanyian wanita itu.
Suara wanita bukan aurat karena jika disebut demikian, mengapa Rasūlullāh s.a.w. mengijinkan dua wanita budak bernyanyi di rumahnya? Selain itu, beliau tidak keberatan berbicara dengan kaum wanita, sebagaimana yang terjadi ketika menerima bai‘at dari kaum ibu sebelum dan sesudah hijrah. Bahkan beliau pernah mendengar nyanyian seorang wanita yang bernazar untuk memukul rebana dan bernyanyi di hadapan Rasūlullāh s.a.w. Semua keterangan tersebut dan keterangan serupa lainnya menunjukkan bahwa suara wanita bukan aurat.
Selain itu, syara‘ telah memberikan hak dan wewenang kepada kaum wanita untuk melakukan aktifitas jual beli, berdagang, menyampaikan ceramah atau mengajar, mengaji al-Qur’ān di rumah sendiri, membaca kasidah atau sya‘ir, dan sebagainya. Jika suara mereka dianggap aurat atau ḥarām maka tentu syara‘ akan mencegah mereka melakukan semua aktivitas tersebut. Inilah ḥujjah yang kuat. Hanya memang syara‘ telah melarang wanita menampilkan perhiasannya di hadapan kaum lelaki yang bukan muhrimnya, melenggak-lenggok, atau manja dalam berbicara, sebagaimana firman Allah s.w.t.:
(وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الْطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ) (النور: 31)
” dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islām, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.…” (24:31).
Syara‘ tidak melarang wanita berbicara dengan pria dengan syarat ia tidak menampilkan kecantikan atau perhiasannya kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, mendengar suara wanita tidaklah ḥarām sebab bukan aurat. “Tidak ada larangan wanita berbicara dengan kaum lelaki kecuali dengan suara manja, merayu, atau keluhan yang dapat menimbulkan keinginan kaum lelaki untuk berbuat jahat, serong, dan perbuatan dosa besar lainnya terhadap wanita tersebut. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah s.w.t. dalam firman-Nya:
(فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا) (الأحزاب: 32)
“…maka, janganlah kamu tunduk ketika berbicara (dengan manja, merayu, dan sebagainya). (Sebab), nanti akan timbul keinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya (keinginan nafsu birahinya). Dia ucapkanlah perkataan yang baik (sopan santun).” (33:32).
Apabila wanita sudah melanggar perintah tersebut maka tidak hanya dirinya yang terlibat dalam perbuatan dosa atau haram, tapi juga setiap orang yang membiarkan hal tersebut karena mereka tidak menyeru kepada yang ma‘rūf (wajib, sunnah) terhadap wanita itu, dan tidak pula mencegahnya melakukan yang mungkar (ḥarām).
Rasūlullāh s.a.w. bersabda mengenai hal ini: (Lihat: SHAḤĪḤ MUSLIM, Ḥadīts No. 49,78; SUNAN ABŪ DĀWŪD, Ḥadīts No. 1140; SUNAN TIRMIDZĪ, Ḥadīts No. 2173; SUNAN AN-NASĀ’Ī, Jilid VIII, Ḥadīts 111; dan SUNAN IBNU MĀJAH, Ḥadīts No. 4013):
(مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَ ذلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ)
“Siapa saja di antara kalian yang melihat adanya kemungkaran maka hendaklah ia ubah dengan tangannya. Jika ia tidak mampu melakukannya, maka hendaklah dengan lisannya. Kalau inipun tidak mampu dilakukannya, maka hendaklah dengan menolaknya di dalam hatinya. Tetapi itulah iman yang selemah-lemahnya.” (HR. MUSLIM, ABŪ DĀWŪD, TIRMIDZĪ, AN-NASĀ’Ī, dan IBNU MĀJAH).