Halal atau Haram Nyanyian dan Memainkan Alat Musik – Seni Dalam Pandangan Islam
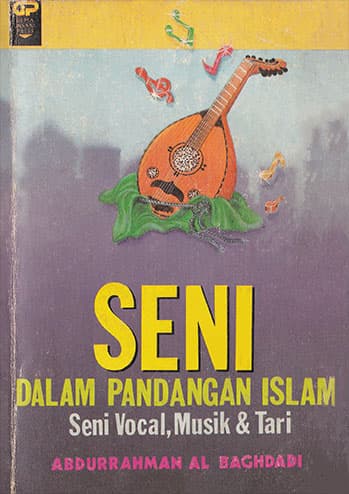
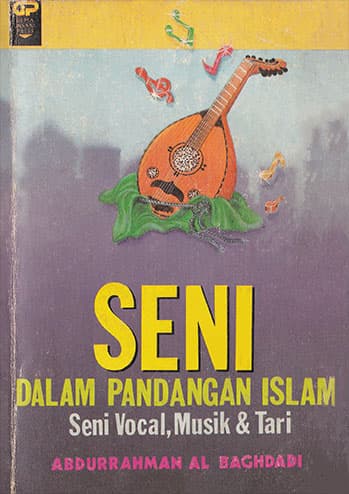
BAB VII.
Nyanyian yang bersifat vokal (suara manusia tanpa instrumen musik) tidak diperselisihkan oleh para fuqahā’. Mereka mengatakan bahwa nyanyian semacam ini ḥalāl atau dibolehkan, sebagaimana yang dikutip oleh Imām asy-Syaukānī dari berbagai kalangan ‘ulamā’ (Lihat: Asy-Syaukānī , NAIL-UL-AUTHĀR, Jilid VIII, hlm. 114-115):
“Nyanyian tanpa instrumen musik, al-Adhfawī dalam kitabnya AL-IMTA menyebutkan bahwa Imām al-Ghazālī dalam berbagai karangan fiqihnya menegaskan kesepakatan ‘ulamā’ tentang ḥalālnya nyanyian jenis ini. Begitu juga Ibnu Thāhir berpendapat ada ijma‘ sahabat dan tābi‘īn tentang ḥalālnya nyanyian vokal ini. At-Tāj-ul-Fazarī dan Ibnu Qutaibah menyebutkan adanya ijma‘ penduduk Makkah dan Madīnah. Ibnu Thāhir dan Ibnu Qutaibah juga menyebutkan adanya ijma‘ penduduk Madīnah dalam hal tersebut. Sedangkan Imām al-Māwardī mengatakan bahwa penduduk Ḥijāz sejak dulu sampai sekarang (abad 5 H) membolehkan nyanyian jenis ini pada hari-hari yang mulia dalam setahun yang (kaum Muslimīn) diperintahkan untuk melakukan nazham-nazham dzikir dan ibadah.”
Imām an-Nawawī dalam kitabnya al-‘Umdah berkata:
“Telah diriwayatkan tentang ḥalālnya nyanyian dan mendengarkannya dari sekelompok sahabat dan tābi‘īn, di antaranya adalah Imām yang empat, Ibnu ‘Uyainah, dan jumhur Syāfi‘iyyah.”
Ini mengenai nyanyian vokal tanpa instrumen musik. Adapun nyanyian yang disertai dengan alat musik maka ‘ulamā’ yang meng-ḥalāl-kannya mengatakan bahwa semua Ḥadīts yang membahas masalah ini nilainya tidak sampai ke tingkat shaḥīḥ maupun ḥasan. Inilah yang dikatakan oleh al-Qādhī Abū Bakar Ibn-ul-‘Arabī (Lihat: Abū Bakar Ibn-ul-‘Arabī, AḤKĀM-UL-QUR’ĀN, Jilid III, hlm. 1053-1054):
“Tidak terdapat satu dalil pun di dalam al-Qur’ān maupun Sunnah Rasūl yang meng-ḥarām-kan nyanyian. Bahkan ada Ḥadīts yang menunjukkan bolehnya nyanyian. Ḥadīts shaḥīḥ itu mengatakan bahwa Abū Bakar pernah masuk ke tempat ‘Ā’isyah yang disampingnya ada dua jāriyah penyanyi dari kalangan Anshār yang sedang menyanyikan tentang hari Bu‘ats. Kemudian Abū Bakar berkata: “Di rumah Nabi s.a.w. ada seruling syaithan?” Mendengar perkataan itu, Rasūlullāh s.a.w. bersabda:
“Biarkanlah keduanya, wahai Abū Bakar, sebab sesungguhnya hari ini adalah hari raya.”
Ibn-ul-‘Arabī berkata: “Jika nyanyian itu ḥarām, tentu di rumah Rasūlullāh s.a.w. tidak akan ada sama sekali hal tersebut. Tetapi alasan yang diberikan beliau (Nabi s.a.w.) untuk membolehkannya adalah karena nyanyian itu dilakukan pada hari raya, yang hal tersebut menunjukkan bahwa bila nyanyian itu dilakukan secara terus-menerus, maka hukumnya makrūh. Sedangkan rukhshah (keringanan) untuk melakukannya terbatas pada saat-saat tertentu seperti hari raya, perkawinan, pulangnya seseorang ke kampung halamannya, dan sebagainya. Berkumpulnya orang-orang (dalam acara tersebut) biasanya untuk menyenangkan hati orang-orang yang sejak lama tidak bertemu atau berkumpul, baik berkumpulnya kalangan kaum wanita maupun pria. Jadi, setiap Ḥadīts yang diriwayatkan maupun ayat dipergunakan untuk menunjukkan ke-ḥarām-an nyanyian merupakan pendapat yang bāthil atau tidak benar dari segi sanad dan ijtihād, baik bertolak dari nash maupun suatu takwilan.”
Imām Ibnu Ḥazm juga memberikan komentar yang melemahkan semua Ḥadīts riwayat tentang nyanyian. Bahkan menurut beliau, sebagian di antaranya adalah maudhū‘ (palsu). Inilah komentarnya. (Lihat: Ibnu Ḥazm, AL-MUḤALLĀ, Jilid VI, hlm. 59):
“Jika belum ada perincian dari Allah s.w.t. maupun Rasūl-Nya tentang ḥarāmnya sesuatu yang kita bincangkan di sini (dalam hal ini adalah nyanyian dan menggunakan alat-alat musik), maka telah terbukti bahwa ia adalah ḥalāl atau boleh secara mutlaq.”
Adapun orang yang bertolak dari pendapat Ibnu Mas‘ūd dan Ibnu ‘Abbās tentang firman Allah s.w.t. surat Luqmān, ayat 6 tentang arti Lahw-ul-ḥadīts dalam ayat tersebut adalah “nyanyian”. Begitu juga pendapat Ibnu ‘Abbās yang mengatakan bahwa memainkan alat musik rebana dan setiap alat musik termasuk seruling, tambur, adalah ḥarām. Maka Ibnu Ḥazm membantah pendapat ini dengan mengatakan (Lihat: Ibnu Ḥazm, AL-MUḤALLĀ, Jilid VI, hlm. 60). bahwa semua pendapat yang semacam ini tidak dapat dijadikan sebagai ḥujjah atau bukti dengan sebab-sebab sebagai berikut:
Kemudian beliau melanjutkan bantahannya terhadap pendapat dari pihak yang menanyakan, apakah nyanyian itu tergolong dalam al-Ḥaqq (sesuatu yang dibenarkan oleh agama) atau tidak? Ini disebabkan karena Allah s.w.t. telah berfirman:
(فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلِ)
“…maka tidak ada sesuatu kebenaran itu melainkan kesesatan.” (10:32), dengan mengatakan (Lihat: Ibnu Ḥazm, AL-MUḤALLĀ, Jilid VI, hlm. 60).
Rasūlullāh s.a.w. telah bersabda:
(إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَ إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوى) (متفق عليه)
“Sesungguhnya ‘amal perbuatan (manusia) itu tergantung niatnya. Bahwasanya apa yang diperoleh oleh seseorang adalah sesuai dengan apa yang diniatkannya….”
Oleh karena itu siapa saja yang niatnya mendengar nyanyian untuk melakukan suatu kemaksiatan kepada Allah, maka ia adalah seorang fāsiq. Begitu pula halnya tiap sesuatu (hiburan) selain nyanyian. Sedangkan orang yang berekreasi di kebun atau duduk-duduk di depan pintu rumah sambil melihat orang-orang yang sedang berjalan, mencelup bajunya dengan warna biru atau hijau, dan warna lainnya, atau ingin meluruskan kaki atau menekuknya (fold s.t., bend s.t. over), begitu pula dengan seluruh perbuatan yang serupa dengannya.
Bertolak dari keterangan di atas maka terbukti dengan pasti bāthilnya pendapat orang-orang yang meributkan masalah tersebut (yang meng-ḥarām-kan nyanyian).
Berdasarkan uraian-uraian di atas, ditambah dengan berbagai keterangan sebelumnya maka dapat kita simpulkan bahwa para ulama memang telah berselisih pendapat terhadap masalah nyanyian. Sebagian dari mereka tidak menganggap Ḥadīts-Ḥadīts yang meng-ḥarām-kan nyanyian adalah shaḥīḥ. Sedangkan yang lain telah menjadikan Ḥadīts-Ḥadīts tersebut sebagai ḥujjah atau bukti untuk meng-ḥarām-kan nyanyian. Masing-masing mengikuti apa yang mereka tentukan sebagai dasar pengambilan hukum sesuai dengan ijtihādnya. Karenanya, siapa saja yang ijtihādnya telah menghasilkan suatu dugaan yang kuat bahwa bernyanyi dan mendengarkannya adalah ḥarām, maka itulah hukum Allah terhadapnya, juga terhadap setiap orang yang mengikutinya.
Sedangkan bagi orang-orang yang belum terbukti baginya ke-shaḥīḥ-an Ḥadīts-Ḥadīts yang mengharamkan nyanyian yang disertai dengan dugaan kuat dan dengan ijtihād yang benar, maka itulah hukum Allah terhadapnya. Juga terhadap setiap orang yang mengikutinya sebab masalah ini adalah masalah khilāfiyyah sebagaimana yang telah kami uraikan pada bab-bab sebelumnya.