Asma’ Allah Teragung dalam Berdoa – Al-Ma’tsurat (3/3)
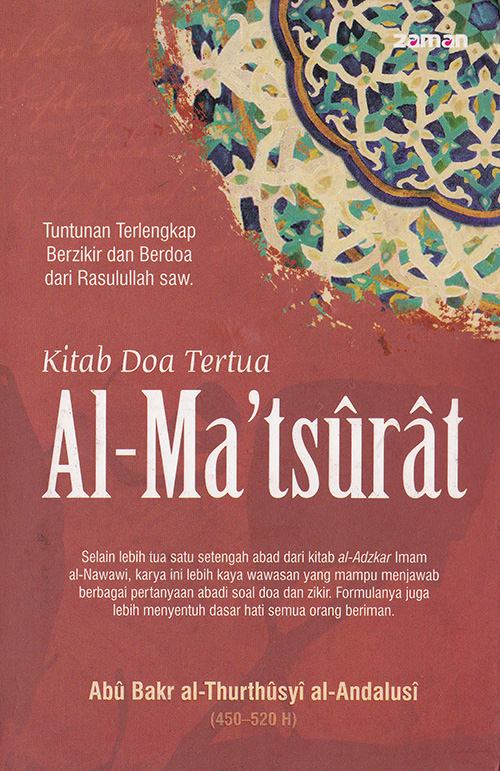
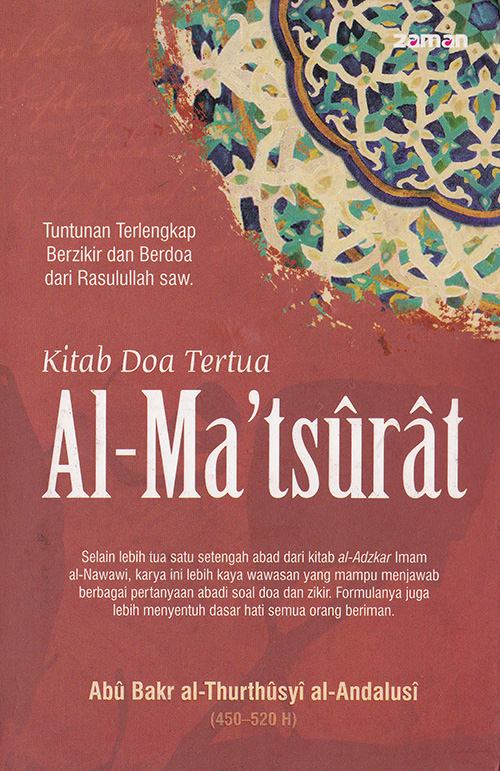
Tidak ada seorang pun yang ditimpa kesusahan atau takut tertimpa musibah kecuali mengucap lafal Yā Allāh. Kalimat inilah yang merupakan kewajiban pertama bagi orang-orang mukallaf di kehidupan dunia, yaitu: Lā ilāha illā Allāh. Kalimat ini juga menjadi kalimat yang pertama didengar saat seseorang memasuki kehidupan dunia untuk kali pertama. Saat rahim mendorong keluar jasad bayi dari kegelapan dunia rahim ke dunia luar, kita semua berteriak: “Allāhu Akbar.” Lalu, lafal ini juga menjadi lafal terakhir saat seseorang berpisah dari kehidupan dunia untuk menyambut kehidupan yang lain.
Dengan lafal yang sama, semua makhluq berinteraksi satu sama lain dan menjadikannya sebagai penghalang untuk saling berbuat kebajikan di antara mereka sampai akhirnya tindakan ini dilarang oleh firman: “Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan.” (al-Baqarah [2]: 244).
Allah s.w.t. telah memberi kebebasan seluas-luasnya bagi makhluq dalam berdoa. Mereka boleh berdoa dengan sesuatu yang paling berkesan dan mengena di hati mereka, yang paling mereka inginkan. Allah s.w.t. berfirman: “….. atau serulah ar-Raḥmān.” (al-Isrā’ [17]: 110). Seolah-olah Allah s.w.t. berfirman: “Jika kalian tidak menyeru-Ku dengan kemanunggalan atau keesaan-Ku (waḥdāniyyah) maka serulah Aku dengan keutamaan dan kerahmatan-Ku.”
Dikatakan: Tidaklah seseorang menyeru Tuhannya dengan salah satu nama-Nya kecuali dirinya memiliki bagian di dalamnya. Tapi, hal ini tidak berlaku jika dirinya menyeru-Nya dengan nama Allāh. Sebab, nama Allah menunjukkan kemanunggalan atau keesaan, dan tak ada sesuatu pun yang berhak menyandangnya selain Dia s.w.t. Atas dasar ini, mereka mengatakan: “Nama itu untuk penggantungan diri kepada-Nya, bukan untuk pengelilingan terhadap-Nya. Ketuhanan adalah kemampuan untuk menciptakan berbagai perubahan. Hanya Allah letak sifat-sifat keutamaan dan keparipurnaan.”
Abū Sa‘īd (681) berkata: “Seruan pertama-Nya kepada hamba-hambaNya adalah menyeru mereka semua pada satu kalimat. Barang siapa yang memahami kalimat itu maka ia telah memahami apa yang ada di baliknya. Kalimat yang dimaksud tak lain adalah Allāh. Tidakkah engkau melihat bagaimana Dia s.w.t. berfirman: “Katakanlah (Muḥammad): “Dialah Allah”. Ini bisa dimengerti oleh kalangan ahli hakikat. Dia s.w.t. kemudian memperjelaskan bagi kalangan khāshsh melalui firman: “Yang Maha Esa;” lalu memperjelas lagi bagi kalangan para kekasih-Nya (awliyā’) melalui firman: “Tempat meminta segala sesuatu”; dan akhirnya memperjelas lagi bagi kalangan biasa (‘amm) melalui firman: “Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, tidak ada sesuatu yang setara dengan-Nya.” (al-Ikhlāsh [112]: 3-4).
Allāhumma sebenarnya berasal dari Yā Allāh. Ketika kata Yā di awal kata dibuang, mereka menambahkan huruf mīm di akhirnya sehingga menjadi Allāhumma – yang memiliki ma‘na serupa dengan ma‘na Yā Allāh. Oleh karena itu, kedua kata (yā dan allāhumma) tidak bisa disatukan. Artinya, tidak bisa dikatakan: Yā Allāhumma, kecuali pada keadaan mendesak di dalam bait syair.
Menurut beberapa orang, ma‘na Yā Allāhumma atau Yā Allāh adalah “Tunjukkan kami dengan kebaikan dan pada kebaikan.”
Dikatakan bahwa huruf mīm pada lafal Allāhumma hanyalah tambahan. Sebab, orang-orang ‘Arab sudah biasa menambahkan huruf mīm di akhir banyak kata, seperti zurqum dan suthum. (692).
Jika ditanyakan: “Apa ma‘na dari pernyataan: “nama Allah s.w.t. yang paling agung?” Apakah terjadi perbandingan di antara nama-nama Allah? Bagaimana konsep perbandingan dan perbedaan di antara nama-nama Allah s.w.t. jika nama-Nya yang paling agung itu memang benar-benar ada?” maka jawabannya adalah sebagai berikut:
Ma‘na dari pernyataan “nama Allah s.w.t. yang paling agung” adalah pendiskusian tentang sabda Nabi s.a.w.: “Jika dibuat untuk berdoa maka Dia s.w.t. pasti akan mengabulkan.”
Jika ditanyakan: “Kenapa terdapat seseorang yang doanya tidak dikabulkan, meskipun dirinya sudah memohon dengan menggunakan nama Allah s.w.t. yang paling agung tersebut?” maka jawabannya adalah sebagai berikut: Nama tersebut belum bisa dipastikan, tapi masih menjadi bahan perdebatan dan memiliki berbagai lafal berbeda.
Jika ditanyakan: “Bagaimana jika seseorang menghimpun semua nama-nama tersebut dalam doanya, tapi doanya tetap belum dikabulkan?” maka jawabannya: “Sampai detik ini, tak ada seorang pun yang mencoba melakukan itu, lalu mengalami kegagalan dan frustrasi.”
Jika ditanyakan: “Apakah mungkin seseorang yang berdoa dengan nama itu tidak dikabulkan doanya?” maka jawabannya: “Apabila Alah s.w.t. berkehendak mendahului apa yang sudah ditetapkan-Nya, doa orang itu akan dikabulkan. Sebab, doa (itu sendiri) tidak akan bisa mengalahkan ketentuan-Nya.”
Jika ditanyakan: “Begitu juga dengan doa-doa lainnya, yang tidak bisa mengalahkan ketentuan Allah s.w.t. dan menghalangi takdir-Nya. Lalu, apa faedah dari nama-Nya yang paling agung tersebut?” (703) maka jawabannya: “Faedahnya bisa berupa bahwa Alla s.w.t. tidak mengilhamkan nama itu kecuali kepada hati dan lisan hamba-Nya, yang sebelumnya sudah ditentukan oleh-Nya bahwa hamba tersebut akan memohon kepada-Nya dengan nama itu. Jika tidak ditentukan oleh-Nya, maka Allah s.w.t. takkan mengilhamkannya pada lisan dan hati orang tersebut.”
Jika ditanyakan: “Apakah ini menandakan adanya tingkatan di dalam doa?” maka jawabanya adalah sebagai berikut: Maksudnya, orang-orang terkadang sudah berdoa dan memohon, tetapi Allah s.w.t. telah menentukan bahwa keinginan mereka takkan terkabulkan. Di lembaran berikutnya, kami akan menjelaskan perihal syarat-syarat dikabulkannya doa dan perkara-perkara yang menghalangi pengabulan suatu doa. In syā’ Allāh.
Apabila Allah s.w.t. sudah menentukan nama teragung-Nya diucapkan oleh seorang hamba yang memohon berdoa kepada-Nya, maka syarat-syarat pengabulan doa sudah terhindari. Inilah ma‘na dari kedudukan nama-Nya yang paling agung. Atas dasar ini, terjadi perbandingan dan perbedaan di antara surah-surah dan ayat-ayat di dalam al-Qur’ān. Orang yang membaca surah atau ayat tertentu dari al-Qur’ān, akan mendapatkan pahala yang lebih banyak ketimbang membaca surah atau ayat lainnya. Nabi s.a.w. pernah bersabda: “Surah Tabārak (al-Mulk) itu akan menjaga pembacanya dari ‘adzab kubur, dan surah Qul Huwa Allāhu Aḥad (al-Ikhlāsh) itu sepadan dengan sepertiga al-Qur’ān.” (714).
Perbedaan dan keragaman bisa dirujukkan pada pemberian nama atau penamaan. Objek yang dinamakan hanya satu dan tunggal, tetapi nama yang diberikan kepadanya itu beragam dan berbeda-beda. Terkadang setiap penamaan diberikan satu nama tertentu. Inilah sebenarnya maksud dari pernyataan tentang nama Allah s.w.t. yang paling agung.
Di awal, di bab tentang doa yang kemungkinan besar dikabulkan, kami telah menyebutkan sabda Nabi s.a.w. tentang nama Allah s.w.t. yang paling agung.
Syaikh Abū Muḥammad ibn Abī Zayd (725) mengingkari nama ini, dan itu dikemukakannya di kitab al-Istizhhār saat mengritik ‘Abd-ur-Raḥmān ibn ash-Shiqillī (736). Ibnu Abī Zayd adalah orang yang sesat, pembuat bid‘ah, menceburkan diri ke kekuasaan, dan melakukan berbagai perbuatan terlarang. Pandangan-pandangannya diikuti oleh ahli fikih Abul-Ḥasan al-Qābisī (747) di risalahnya yang berjudul an-Nashiriyyah. Tetapi, ini semua hanya di fase awal kehidupannya, yaitu saat dirinya mengingkari karamah para wali (kekasih Allah s.w.t.) (758). Ketika mereka menerima pandangan-pandangan ‘ulama’ kami dan membaca kitab karangan Abu Bakar Muhammad ibn ath-Thayyib – yang ditulis untuk menangkal pendapat Syaikh Abu Muhammad ibn Abi Zayd yang mengingkari nama teragung Allah s.w.t. – mereka kembali ke jalur yang benar, menarik kembali pendapat terdahulunya, dan meyakini tentang kekeramtan para wali.