Hakikat Tasawwuf: Wiridnya Kalangan Sufi
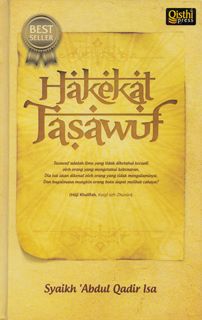
Dari Buku:
Hakikat Tasawwuf
(Judul Asli: Haqa’iq-ut-Tasawwuf)
Oleh: Syaikh ‘Abdul-Qadir ‘Isa
Penerjemah: Khairul Amru Harahap, Lc., MHI dan Afrizal Lubis, Lc.
Penerbit: Qisthi Press
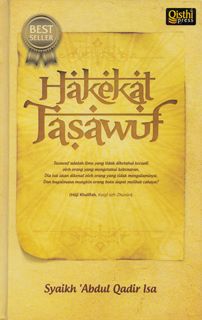
Dari Buku:
Hakikat Tasawwuf
(Judul Asli: Haqa’iq-ut-Tasawwuf)
Oleh: Syaikh ‘Abdul-Qadir ‘Isa
Penerjemah: Khairul Amru Harahap, Lc., MHI dan Afrizal Lubis, Lc.
Penerbit: Qisthi Press
Bab II Bagian ke 4.
Dzikir
Dalam kamus al-Mishbāḥ disebutkan bahwa kata wird berarti penugasan untuk membaca. Bentuk pluralnya adalah aurād. Bagi kalangan sufi, yang dimaksud dengan wirid adalah dzikir-dzikir yang diperintahkan oleh mursyid kepada muridnya untuk dibaca pada waktu pagi setelah sahat Subuh (135) dan pada waktu petang setelah shalat Maghrib.
Secara etimologis, kata wārid berarti orang yang mengetuk pintu atau orang yang datang. Kalimat: “Warada fulān,” berarti: “Fulan datang”. Adapun secara epistimologis, kata ini berarti karunia ilahiah yang dilimpahkan oleh Allah ke dalam hati para wali-Nya (kekasih-Nya), sehingga mereka memperoleh kekuatan penggerak. Kadang hal itu mengagetkan mereka atau menghilangkan kesadaran mereka. Dan itu tidak terjadi kecuali secara mendadak dan sifatnya tidak permanen bagi yang memperolehnya. (1561).
Wirid terdiri dari tiga bentuk dzikir yang diperintahkan oleh syariat. Al-Qur’an telah menganjurkan hal tersebut dan Sunnah telah menjelaskan keutamaan dan pahalanya. Ketiga bentuk dzikir itu adalah:
“Dan kebaikan apa saja yang kalian perbuat untuk diri kalian, niscaya kalian akan mendapatkannya di sisi Allah sebagai sesuatu yang paling baik dan paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (al-Muzzammil: 20).
Rasulullah s.a.w. sendiri melakukan banyak istighfar sebagai pembelajaran dan tuntunan bagi umatnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi s.a.w., beliau bersabda:
“Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar dan bertobat kepada-Nya dalam sehari semalam lebih dari tujuh puluh kali.” (H.R. Bukhari).
Diriwayatkan dari ‘Abdullah ibn Bisr dari Nabi s.a.w., beliau bersabda:
“Berbahagialah orang yang mendapatkan dalam lembaran catatan amalnya (di akhirat) istighfar yang banyak.” (H.R. Ibnu Majah). (1572).
Al-Qur’an telah memerintahkan kita untuk bershalawat keapda Nabi s.a.w., sebagaimana firman Allah:
“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatNya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kalian untuknya dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.” (al-Ahzab: 56).
Rasulullah s.a.w. juga menganjurkan kaum muslimin untuk bershalawat kepadanya, sebagaimana dalam sabda beliau:
“Barang siapa bershalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalasnya dengan sepuluh kali shalawat.” (H.R. Muslim dan Nasa’i).
Diriwayatkan dari Anas ibn Malik dari Nabi s.a.w. beliau bersabda:
“Barang siapa bershalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalasnya dengan sepuluh kali shalawat, dihapus darinya sepuluh kesalahan dan ditinggikan derajatnya sepuluh tingkatan.” (H.R. Nasa’i).
Beliau juga bersabda:
أَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلاَةً
“Sesungguhnya manusia yang paling utama di sisiku pada hari Kiamat adalah orang yang paling banyak bershalawat kepadaku.” (H.R. Tirmidzi).
Oleh sebab itu, Allah mengajak kita semua untuk berakidah dengan tauhid yang murni, sebagaimana firman-Nya:
“Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidka ada Tuhan melainkan Allah.” (Muhammad: 19).
Rasulullah juga telah menganjurkan kita untuk berdzikir dengan kalimat tauhid dan menerangkan keutamaan serta ganjarannya. Beliau bersabda:
“Dzikir yang paling utama adalah kalimat “Lā ilāha illallāh”.” (H.R. Tirmidzi).
Ketika menerangkan tentang hadis ini, Ibnu ‘Allan menyatakan bahwa kalimat “Lā ilāha illallāh” memiliki implikasi yang sangat besar dalam membersihkan hati dari segala sifat tercela yang bersarang di batin orang yang berdzikir. Sebabnya adalah karena kalimat “Lā ilāha” adalah penafian semua bentuk Tuhan, dan kalimat “illallāh” adalah penetapan bagi Dzat Yang Maha Esa, Yang Maha Benar, yang keberadaan-Nya wajib dengan sendirinya, dan yang suci dari segala sesuatu yang tidak layak bagi keagungan-Nya. Kesinambungan dzikir dengan kalimat tauhid ini akan meresapkan dan mengokohkannya di dalam batin orang yang berdzikir, sehingga dzikir ini akan menerangi dan memperbaiki hatinya, menerangi dan memperbaiki seluruh anggota tubuhnya. Oleh sebab itu, seorang murīd sangat dianjurkan untuk memperbanyak dan selalu tekun berdzikir dengan kalimat tauhid ini. (1583).
Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi s.a.w., beliau bersabda:
“Perbaruilah iman kalian.” Rasul s.a.w. ditanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana cara membarui iman itu?” Beliau bersabda: “Perbanyaklah mengucapkan “Lā ilāha illallāh”.” (H.R. Ahmad).
Beliau juga bersabda:
“Barang siapa mengucapkan kalimat “Lā ilāha illallāhu waḥdahu lā syarīka lah, lah-ul-mulku wa lah-ul-ḥamd, wa huwa ‘alā kulli syai’in qadīr,” seratus kali dalam sehari, maka pahalanya sama dengan memerdekakan sepuluh hamba sahaja. Dicatat baginya seratus kebaikan, dihapus darinya seratus kesalahan dan dia akan memiliki tameng dari setan pada hari itu sampai sore hari. Tidak ada yang diganjar lebih baik dari apa yang diperolehnya itu kecuali orang yang mengamalkan lebih banyak darinya.” (H.R. Bukhari, Muslim dan Tirmidzi).
Perlu diperhatikan bahwa ketiga bentuk wirid di atas dibaca pada waktu pagi dan petang dalam khalwat yang dilakukan oleh seorang hamba dengan Tuhannya. Dengan demikian, dia telah menyambut siangnya dengan zikir kepada Allah dan menutupnya dengan zikir serta ketaatan kepada-Nya. Mudah-mudahan dia termasuk orang yang disebut dalam firman Allah:
“Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.” (al-Ahzab: 35).
Model zikir seperti di ataslah yang penulis pelajari dari mursyid penulis, Syaikh Muhammad al-Hasyimi. Dan model itu juga yang beliau peroleh dari mursyid beliau.
Tidak patut bagi seorang sālik yang sedang menapak jalan menuju Allah untuk membatasi wiridnya dengan jumlah yang telah disebutkan di atas. Akan tetapi, dia harus menambah jumlah zikirnya kepada Allah. Sebab, hati seorang sālik yang masih pemula adalah ibarat seorang anak kecil. Setiap kali anak kecil bertambah besar, jumlah makanannya akan bertambah. Begitu juga halnya dengan seorang murīd yang menapak jalan menuju Allah. Semakin tua umurnya, dia harus menambah jumlah zikirnya kepada Allah. Sebab, zikir adalah makanan dan kehidupan bagi hati.
Karena wirid adalah metode bagi para sālik untuk menuju Allah, maka setan merintangi jalan mereka. Setan menghalangi mereka dari zikir kepada Allah dengan beraneka ragam alasan, beraneka ragam bisikan tersembunyi dan beraneka ragam tipuan. Sebagian murid meninggalkan wirid dengan alasan sedang sibuk dengan beraneka ragam aktivitas dan tidak memiliki waktu luang. Ketika itu, setan akan membisikinya dan mengatakan kepadanya bahwa itu adalah alasan yang dapat diterima oleh syariat dan akal sehat.
Akan tetapi, para tokoh sufi mengingatkan para murīd mereka agar tidak melalaikan wirid dan tidak menunggu waktu luang. Sebab, umur kita cepat habis. Sementara kesibukan terus bertambah.
Ibnu ‘Ajibah/‘Ujaibah berkata: “Yang harus dilakukan oleh manusia adalah meninggalkan segala tabir yang menghalangi hatinya dan segera berkhidmat kepada Allah. Jangan sampai dia menunggu waktu kosong. Sebab, seorang sufi adalah anak waktunya sendiri.” (1594)
Kadangkala setan merayu sebagian sālik agar mereka meninggalkan zikir dengan alasan bahwa zikir mereka tidak bersih dari beraneka ragam bisikan dan zikir tidak bermanfaat kecuali dengan hati yang hadir di hadapan Allah.
Akan tetapi, para mursyid sufi mengingatkan para murīd mereka agar berhati-hati terhadap pintu masuk setan yang sangat berbahaya ini. Ibnu ‘Atha’illah as-Sakandari berkata: “Janganlah engkau meninggalkan zikir karena ketidakhadiran hatimu bersama Allah. Sebab, kelalaianmu pada saat engkau tidak berzikir lebih parah daripada kelalaianmu pada saat engkau berzikir. Mudah-mudahan Allah berkenan meningkatkan derajatmu dari zikir yang disertai kelalaian menuju zikir yang disertai keterjagaan hati, dari zikir yang disertai hadirnya hati menuju zikir yang disertai lenyapnya segala sesuatu selain obyek zikir (Allah). Dan hal itu sungguh mudah bagi Allah Yang Maha Perkasa.” (1605).
Kadangkala ada di antara para sālik yang meninggalkan wirid karena merasa cukup dengan karunia Allah. Mereka tidak mengetahui bahwa wirid tetap diperintahkan untuk bertaqarrub kepada Allah. Para pemuka sufi tidak meninggalkan wirid mereka meski mereka telah sampai ke derajat yang sempurna.
Abu Hasan ad-Darraj meriwayatkan bahwa Junaidi pernah menyebutkan tentang ahli makrifat yang terus memelihara wirid dan ibadah mereka setelah mereka memperoleh karamah dari Allah. Dia mengatakan: “Bagi para ahli makrifat, ibadah lebih baik dari mahkota di atas kepala para raja.” Pada suatu ketika, seseorang melihat sebuah tasbih di tangan Junaidi. Lalu orang itu berkata: “Dengan derajatmu yang mulia ini, engkau masih memegang tasbih di tanganmu?” Junaidi menjawab: “Ya. Inilah penyebab kami sampai kepada apa yang kami capai. Dan kami tidak akan meninggalkannya sampai kapanpun.” (1616).
Ibnu ‘Atha’illah berkata: “Tidak akan meremehkan wirid kecuali orang yang bodoh. Wārid (karunia Allah) hanya ada di akhirat. Sedangkan wirid akan berakhir bersama berakhirnya dunia yang fana ini. Wirid itu, Allah yang memintanya darimu. Sedangkan wārid, engkau yang memohonnya dari-Nya.” (1627).
Seorang murīd yang meninggalkan wirid dengan beraneka alasan di atas, lalu dia kembali bangkit dan menekuni wiridnya, hendaknya tidak berputus asa dari rahmat Allah akibat kelalaiannya tersebut. Dia harus segera bertobat dan melunasi wirid-wiridnya yang telah dia tinggalkan. Sebab, wirid dapat dilunasi sebagaimana ibadah dan ketaatan lainnya.
Nawawi berkata: “Seseorang yang mempunyai zikir yang dia baca di waktu siang, malam, sesusai shalat atau dalam kondisi tertentu, lalu dia meninggalkannya, maka dia harus segera menggantinya sebisa mungkin. Dia tidak boleh melalaikannya. Sebab, jika dia sudah terbiasa membacanya, maka dia akan sulit meninggalkannya. Sementara jika dia lalai melunasinya, maka akan mudah baginya untuk meninggalkan pada waktunya.
Diriwayatkan dari ‘Umar ibn Khaththab dari Nabi s.a.w. beliau bersabda:
مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيْمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ صَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ
“Barang siapa tertidur sebelum sempat membaca jatah al-Qur’annya (hizib/wiridnya) atau sebagian darinya, lalu dia membacanya di antara shalat Subuh dan Zuhur, niscaya dicatat baginya seolah dia membacanya pada waktu malam.” (H.R. Muslim). (163[^8]).
Catatan: