Hakikat Tasawwuf: Membacakan dan Mendengarkan Syair di Masjid
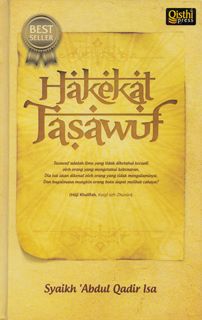
Dari Buku:
Hakikat Tasawwuf
(Judul Asli: Haqa’iq-ut-Tasawwuf)
Oleh: Syaikh ‘Abdul-Qadir ‘Isa
Penerjemah: Khairul Amru Harahap, Lc., MHI dan Afrizal Lubis, Lc.
Penerbit: Qisthi Press
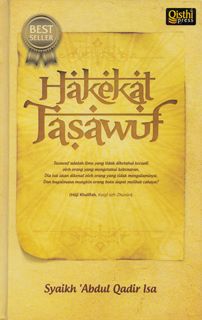
Dari Buku:
Hakikat Tasawwuf
(Judul Asli: Haqa’iq-ut-Tasawwuf)
Oleh: Syaikh ‘Abdul-Qadir ‘Isa
Penerjemah: Khairul Amru Harahap, Lc., MHI dan Afrizal Lubis, Lc.
Penerbit: Qisthi Press
Bab II Bagian ke 4.
Dzikir
Diriwayatkan dari ‘Ubay ibn Ka‘ab bahwa Rasulullah bersabda:
إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةٌ
“Sesungguhnya sebagian syair itu adalah hikmah.” (H.R. Bukhari dan Muslim).
Diriwayatkan dari Anas ibn Malik bahwa tatkala menindahkan batu bata dalam rangka pembangunan masjid Nabawi, Nabi dan para sahabat beliau menyanyikan sajak berikut:
“Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, maka tolonglah orang-orang Anshar dan Muhajirin.” (H.R. Bukhari dan Muslim).
Salamah ibn Akwa menuturkan: “Pada suatu hari, kami keluar bersama Nabi menuju Khaibar. Ketika itu, kami melakukan perjalanan di malam hari. Salah seorang di antara kami berkata kepada ‘Amir ibn Akwa: “Mengapa engkau tidak memperdengarkan kepada kami sebagian dari syair?” Amir memang seorang sahabat Nabi yang terkenal sebagai penyair. Kemudian dia melantunkan syair berikut:
Ya Allah, kalau bukan karena Engkau, kami tidak akan memperoleh petunjuk,
tidak akan menunaikan zakat dan mengerjakan shalat.
Maka ampunilah kami sebagai tebusan, selama kami meminta,
dan kokohkanlah pendirian kami di kala kami menghadapi musuh.
Anugerahkanlah ketenangan dalam hati kami.
Sesungguhnya jika kami diseru, maka kami akan menyambutnya,
Dan dengan seruan mereka meminta bantuan kami.
Mendengar syair itu, Nabi bertanya:
“Siapa yang melantunkan syair itu? Para sahabat menjawab: ‘Amir ibn Akwa.” Nabi s.a.w. berkata: “Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepadanya.” (H.R. Bukhari dan Muslim).
Diriwayatkan dari Sa‘id ibn Musayyab, dia berkata: “Pada suatu hari, ‘Umar ibn Khaththab berjalan dalam masjid Nabawi. Ketika itu, Hasan ibn Tsabit sedang membaca syair. ‘Umar memandangnya dengan pandangan kurang simpatik. Kemudian Hasan berkata kepada ‘Umar: “Aku pernah membacakan syair di hadapan orang-orang yang di antara mereka terdapat orang yang lebih baik darimu (yakni Rasulullah).” Setelah itu Hasan melirik kepadsa Abu Hurairah sambil berkata: “Demi Allah, apakah engkau pernah mendengar Nabi bersabda:
“Ya Allah, kuatkanlah dia (Hasan) dengan roh quddus (Jibril)?” Abu Hurairah menjawab: “Ya, aku pernah mendengarnya.” (H.R. Bukhari dan Muslim).
Diriwayatkan dari ‘A’isyah, dia berkata: “Nabi menyediakan mimbar khusus bagi Hasan ibn Tsabit dalam masjid Nabawi. Di mimbar itu, Hasan berdiri membacakan syair-syairnya yang berisi pujian terhadap Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda:
“Sesungguhnya Allah menguatkan Hasan dengan roh quddus selama dia membela dan mengagungkan Rasulullah.” (H.R. Muslim).
As-Safaraini, komentator kitab Manzhūmat-ul-Ādāb, mengatakan: “Dalam riwayat Abu Bakar ibn al-Anbari disebutkan bahwa tatkala Ka‘ab ibn Zuhair datang kepada Rasulullah s.a.w. untuk bertobat, dia membacakan syairnya:
Su‘ad telah berpisah denganku
Dan hari ini hatiku kacau
Pikiranku melayang
Dan sampai sekarang masih terbelenggu.
Ia meneruskan bacaannya sampai bait berikut:
Sesungguhnya Rasul adalah sebilah pedang yang menyinari
Diasah dengan pedang-pedang India yang sedang dihunus.
Seusai Ka‘ab membacakannya syairnya, Nabi langsung melemparkan kain yang menyelimuti tubuh beliau ke arah Ka‘ab.
Ketika Muawiah berkausa, dia mengeluarkan uang sebanyak 10.000 dirham untuk membeli kain tersebut. Tapi Ka‘ab berkata: “Aku tidak akan mewariskan kain Rasulullah s.a.w. kepada seorang pun.” Lalu ketika Ka‘ab meninggal dunia, Muawiah mengirim seorang utusan untuk membeli kain tersebut dari ahli warisnya dengan harga 20.000 dirham.
Dari peristiwa Ka‘ab ibn Zuhair yang membacakan syairnya di hadapan Rasulullah, lalu Rasulullah memberikan kain beliau kepadanya, dapat ditarik kesimpulan:
1. Diperbolehkan membaca syair.
2. Diperbolehkan mendengarkan syair di dalam masjid.
3. Diperbolehkan memberikan hadiah kepada orang yang membacakan syair.” (1351).
Dalam al-I‘tishām, asy-Syathibi menyatakan: “Abu Hasan al-Qarafi ash-Shufi meriwayatkan dari Hasan Bashri bahwa pada suatu ketika sekelompok orang datang kepada ‘Umar ibn Khaththab. Mereka berkata: “Wahai Amirul-Mukminin, kami mempunyai seorang imam shalat yang selalu bernyanyi seusai mengerjakan shalat.” ‘Umar bertanya: “Siapa dia?” Mereka lalu menyebut nama orang tersebut kepada ‘Umar. Lalu ‘Umar berkata: “Mari kita temui dia.” Mereka berkata: “Jika kami ikut menyertai Amirul-Mukminin, maka dia akan mengira bahwa kami telah mencari-cari kesalahannya.” Kemudian ‘Umar dan beberapa sahabat Nabi menemui orang tersebut di dalam masjid. Tatkala dia melihat ‘Umar, dia berdiri dan berkata: “Wahai Amirul-Mukminin, apa keperluanmu? Apa yang membuatmu datang kemari? Jika kepentingan adalah untuk kami, maka kamilah yang seharusnya datang kepadamu. Dan jika kepentingan tersebut adalah karena Allah, maka orang yang paling berhak untuk kami muliakan adalah khalifah Rasulullah s.a.w.” Umar berkata: “Celakalah engkau! Aku telah mendapat kabar tentang tindakanmu yang menurut pendapatku kurang etis.” Orang itu berkata: “Apa tindakanku itu, wahai Amirul-Mukminin?” ‘Umar berkata: “Apakah engkau bersenda-gurau dalam beribadah?” Orang itu berkata: “Wahai Amirul-Mukminin, aku tidak bersenda-gurau dalam beribadah. Itu hanyalah nasehat yang aku nyanyikan untuk menasehati diriku sendiri.” ‘Umar berkata: “Bacakanlah! Jika itu adalah ucapan yang baik, maka aku akan berpihak kepadamu. Dan jika itu adalah ucapan yang jelek, maka aku akan melarangmu menyanyikannya.” Kemudian orang tersebut membacakan syairnya:
Hatiku, setiap kali aku mencelanya
Tentang jauhnya meninggalkan (agama), dia melelahkanku
Aku tidak melihatnya selamanya kecuali terlena
Dalam keterus-menerusannya, dia menyakitkanku
Wahai teman keburukan, bagaimana dengan masa mudamu?
Habis umurmu dalam permainan seperti ini
Masa mudaku telah tampak lalu sirna
Sebelum aku sempat merealisasikan cita-citaku
Setelah itu, tidak ada pengharapanku kecuali fana
Umurku yang tua telah menyulitkanku untuk mencapainya
Celakalah jiwaku, aku tidak pernah melihatnya
Dalam kebaikan dan tidak pula dalam akhlak
Wahai jiwa, bukan engkau dan bukan pula cinta
Awasilah Tuhanmu dan takutlah kepada-Nya.
‘Umar mengulangi bait terakhir yang dibacakan orang tersebut:
Wahai jiwa, bukan engkau dan bukan pula cinta
Awasilah Tuhanmu dan takutlah kepada-Nya.
Lalu ‘Umar berkata: “Kalau isi syairnya seperti itu, maka siapa saja boleh menyanyikannya.” (1362).
Asy-Syafi‘i berkata: “Syair adalah ucapan. Syair yang baik dianggap baik dan syair yang jelek dianggap jelek.” (1373).
Nawawi menyatakan: “Boleh membaca syair di dalam masjid, asalkan berisi pujian terhadap Nabi dan Islam, atau berisi hikmah dan budi pekerti yang luhur, atau berisi zuhud dan berbagai macam kebaikan lainnya. (1384).
Abu Bakar ibn ‘Arabi al-Maliki, pensyarah Sunan at-Tirmidzi, menyatakan: “Boleh membacakan syair dalam masjid, asalkan berupa pujian terhadap Islam atau penegakan syariat.” (1395).
Tentang ḥidā’ (nyanyian penunggang unta), al-Ghazali berkata: “Bernyanyi di kala menunggangi unta merupakan tradisi yang sudah ada sejak masa Nabi dan para sahabat. Dia tidak lain adalah bait syair yang dilagukan dengan suara merdu dan nada yang teratur. Dan tidak ditemukan satu riwayat pun dari para sahabat yang melarang atau mencelanya.” (1406).
Diriwayatkan dari Anas ibn Malik:
“Pada suatu hari, Nabi melakukan perjalanan bersama seorang anak yang mengendarai untanya sambil bernyanyi. Nama anak itu adalah Anjasyah. Nabi berkata kepadanya: “Wahai Anjasyah, pelan-pelanlah, karena engkau sedang membawa qawārīr.” (H.R. Bukhari).
Qatadah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan qawārīr adalah para wanita yang lemah.
Dalam Fatḥ-ul-Bārī, Ibnu Hajar al-Asqalani berkata: “Ibnu Bathal mengatakan bahwa qawārīr adalah kiasan dari wanita-wanita yang sedang menjadi penumpang unta yang dikendarai ketika itu. Nabi mengingatkan agar Anjasyah pelan-pelan dalam bernyanyi. Sebab, nyanyian yang keras akan mempercepat langkah untanya. Jika langkah unta itu cepat, maka bisa-bisa para penumpang wanita itu terjatuh. Sementara jika jalannya pelan, maka mereka tidak akan terjatuh.”
Ibnu ‘Abdul Barr mengutipkan kesepakatan para ulama tentang bolehnya bernyanyi di kala menunggang unta (ḥidā’). Sedang Hanabilah (para ulama mazhab Hanbali) memiliki pendapat yang berbeda. Akan tetapi, pendapat kalangan yang melarang ḥidā’ terbantah dengan hadis-hadis saḥīh yang membolehkannya.
Yang serupa dengan ḥidā’ adalah nyanyian para jamaah haji yang liriknya memuat kerinduan untuk berhaji dengan menyebut-nyebutkan Ka‘bah dan tempat-tempat lainnya. Begitu juga halnya dengan nyanyian yang mengobarkan semangat para prajurit untuk berjihad.
Ath-Thabari meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dan berkata: “Pada suatu hari aku pernah bertanya kepada ‘Atha’ tentang hukum ḥidā’, syair dan nyanyian. Beliau menjawab: “Semua itu boleh, asalkan bebas dari maksiat.”
Ibnu Bathal berkata: “Jika isi syair dan sajak berupa zikir kepada Allah, pengagungan-Nya, pengesaan-Nya serta dorongan untuk taat dan berserah diri kepada-Nya, maka itu adalah baik dan dianjurkan. Dan itulah yang dimaksud dalam hadis:
“Sesungguhnya sebagian syair itu adalah hikmah.” Namun, jika isinya adalah kebohongan dan maksiat, maka itu adalah tercela.”
Ibnu Bathal juga berkata: “Kesimpulannya, ḥidā’ dengan sajak dan syair pernah dipraktekkan di hadapan Rasulullah. Bahkan, kadang beliau memintanya. Ḥidā’ tidak lain hanyalah bait syair yang dilagukan dengan suara yang merdu dan nada yang teratur.” (1417).
Dan Manzhūmat-ul-Ādāb, as-Safaraini menyatakan: “Dalam kitab al-Iqnā’ dan lainnya disebutkan bahwa lagu yang dinyanyikan di kala menunggang unta dan nasyid yang dinyanyikan para Badui adalah sesuatu yang boleh.”
As-Safaraini juga berkata: “Mazhab kita menyatakan bahwa hal itu boleh dan tidak makruh berdasarkan hadis-hadis dan atsar-atsar yang berkaitan dengan pembacaan syair dan ḥidā’ dalam perjalanan. Sebagian ulama menyebutkan adanya kesepakatan atas diperbolehkannya ḥidā’.” (1428).
Dalam al-Hazhr wal-Ibāḥah, Khalil an-Nahlawi menyatakan: “Hukum lagu adalah hukum mendengarkan.”
Dalam Fatāwā al-Khairiyyah (vol. II, hal. 167), setelah mengutip pendapat dan perselisihan para ulama seputar persoalan simā‘ (mendengarkan syair), Khalil an-Nahlawi menyatakan: “Adapun simā‘ yang dilakukan kalangan sufi harus dipisahkan dari perselisihan para ulama tersebut. Bahkan simā‘ mereka dapat meningkat derajatnya dari boleh ke dianjurkan, sebagaimana diungkapkan beberapa ulama’.” (1439).
Tujuan dari pembacaan syair adalah untuk memberikan bimbingan, nasehat dan faedah. Mendengarkan syair dapat membangkitkan apa yang terpendam di dalam jiwa dan menggerakkan apa yang tersimpan di dalam hati. Di antaranya, kerinduan akan kehadiran Dzat Yang Maha Suci dan nur Muhammad, sebagaimana ditemukan pada kalangan sufi. Mereka tidak tertutupi oleh tabir suara-suara itu, dan mereka tidak berkumpul untuk suatu kesia-siaan. Mereka berada di suatu lembah dan manusia berada di lembah lain. Mereka mendengarkan apa yang tidak didengar manusia. Mereka mengetahui apa yang tidak diketahui manusia. Dan simā‘ mereka membangkitkan mereka untuk meraih keadaan yang lebih baik, menampakkan cinta mereka kepada Allah, menggetarkan kerinduan kepada-Nya dan menggerakkan hati mereka. Karena hati mereka senantiasa tesambung dengan Allah, berdiam di sisi-Nya, dan hadir di hadapan-Nya, maka simā‘ menyirami roh-roh mereka dan mempercepat perjalanannya menuju Allah. Hal ini berbeda dengan simā‘ para pelaku maksiat yang berkumpul untuk melakukan senda gurau dan mendengarkan alat-alat musik. Hal itu membangkitkan maksiat dalam hati mereka dan melupakan mereka dari kewajiban mereka kepada Allah. Dengan demikian, tidak mungkin menyamakan antara para sufi yang senantiasa tulus dengan para pelaku maksiat tersebut, sebagaimana tidak mungkin menyamakan orang-orang saleh dengan orang-orang yang durhaka.
Beriktu ini penulis kemukakan bukti-bukti faedah simā‘ yang diriwayatkan dari para sufi.
Muslim al-Ibadani berkata: “Pada suatu malam, Shalih al-Muri, ‘Utbah al-Ghulam, ‘Abdul-Wahid ibn Zaid dan Muslim al-Aswari datang kepada kami dan tinggal di tepi pantai. Lalu aku menyiapkan makanan dan mengundang mereka. Mereka pun memenuhi undanganku itu. Tatkala aku meletakkan makanan di hadapan mereka, salah seorang di antara mereka melantunkan syair berikut:
Engkau dipalingkan dari akhirat yang abadi oleh makanan,
dan kelezatan nafsu yang sama sekali tidak ada manfaatnya.
Setelah itu, aku melihat ‘Utbah al-Ghulam berteriak sekeras-kerasnya, lalu jatuh pingsan. Kemudian mereka semua menangis. Akhirnya aku mengambil kembali makanan tersebut dari hadapan mereka. Demi Allah mereka sama sekali tidak mencicipinya.” (14410).
Abu ‘Utsman an-Nisaburi menuturkan: “Pada suatu hari, seorang penyanyi bernyanyi di hadapan Haris al-Muhasibi dengan bait syair berikut:
Aku menangis di perantauan
seperti menangisnya orang asing
pada hari aku keluar dari negeriku
Aku salah
Sungguh aneh diriku ini
Aku tinggalkan negeri yang di dalamnya ada kekasihku.
Kemudian penyanyi itu menangis, sehingga semua orang yang hadir bersama al-Muhasibi ketika itu mengasihinya.” (14511)
Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa sewaktu Dzun-Nun al-Mishri tiba di Baghdad, kalangan sufi menemuinya dengan membawa penyanyi mereka. Mereka memohon kepadanya untuk mengizinkan penyanyi itu bernyanyi. Setelah mendapat izin, penyanyi itu melantunkan syair berikut:
Cintamu yang secuil telah menyiksaku
Bagaimana seandainya dia sempurna
Engkau kumpulkan dalam hatiku
cinta yang sebelumnya tercerai-berai
Tidakkah engkau meratapi orang yang malang ini
Jika orang yang tak beristri tertawa
maka dia menangis.
Kemudian Dzun-Nun berdiri dan terjatuh di hadapan penyanyi itu. (14612).
Diriwayatkan bahwa Abu Husain an-Nuri pernah bergabung bersama rombongan dalam rangka misi dakwah. Pada suatu ketika, rombongan itu mendiskusikan suatu masalah. Abu Husain diam dan tidak mengomentari apa yang sedang mereka diskusikan. Tidak lama kemudian beliau berdiri dan melantunkan syair berikut:
Berapa banyak pohon kecil yang berbisik di pagi hari
yang diselimuti duka, bersedih di dahan
Dia sebut sahabat karib dan masa baik
Dia menangis sedih, sehingga kesedihanku bangkit
Mungkin saja tangisanku meluluhkan hatiku
Dan mungkin juga tangisannya meluluhkan hatiku
Aku mengadu dan dia tidak memahamiku
Dia juga mengadu dan aku tidak memahaminya
Namun aku tahu dia sedang diselimuti rindu membara
Dan dia tahu aku sedang diselimuti rindu membara.
Kemudian semua rombongan dakwah itu berdiri dan merasakan wajd (cinta). Wajd yang mereka alami itu tidak mereka capai dengan ilmu yang mereka larut di dalamnya, meskipun ilmu adalah kesungguhan dan kebenaran. (14713).
Dalam Ghidzā’-ul-Albāb, as-Safaraini menyatakan bahwa simā‘ dapat membangkitkan dan menggerakkan apa yang ada dalam hati. Hati para sufi dipenuhi dengan zikir kepada Allah, bersih dari kotoran hawa nafsu, diselimuti cinta yang membara kepada-Nya, dan tidak ada sesuatu pun di dalamnya selain Dia. Rasa rindu, cinta, dahaga dan khawatir tersimpan dalam hati mereka seperti tersimpannya api dalam zinād (batang kayu untuk mengeluarkan api). Api tidak akan tampak kecuali zinād dibenturkan dengan sejenisnya. Yang diinginkan oleh para sufi dengan apa yang mereka dengarkan adalah membenturkan apa yang ada dalam hati mereka dengan kekuatan dan kekuasaan Allah. Hati mereka menjadi lemah ketika benturan itu menjadi, sehingga anggota tubuh mereka bergetar. Mereka berteriak atau pingsan, karena letusan yang ada dalam hati mereka, dan bukan karena simā‘ telah menimbulkan sesuatu dalam hati mereka.
Oleh karena itu, Abu Qasim Junaidi berkata: “Pada dasarnya, simā‘ tidak menimbulkan sesuatu pun dalam hati, tapi dia membangkitkan apa yang ada di dalamnya. Engkau melihat mereka (para sufi) bergerak karena cinta mereka kepada Allah, mengucapkan apa yang mereka maksudkan, dan menampakkan cinta yang terpendam dalam hati mereka. Mereka berlaku seperti itu bukan karena apa yang diucapkan penyair. Perhatian mereka tidak mengarah pada lafal-lafal syair, sebab pemahaman telah ada sebelumnya dalam benak mereka.”
Bukti yang memperkuat pernyataan ini adalah riwayat yang menceritakan bahwa Abu Hukman ash-Shufi mendengar seorang laki-laki yang sedang tawaf di Ka‘bah sambil mengatakan: “Yā sa‘tar birrī (Wahai, Yang Mulia).” Tiba-tiba Abu Hukman jatuh dan pingsan. Ketika dia siuman, dia ditanya mengapa dia sampai pingsan. Dia menjawab: “Aku mendengar orang itu mengatakan “Is‘ā tara birrī (Berusahalah, niscaya engkau akan melihat kebaikan-Ku).”
Dengan demikian, jelaslah bahwa getaran cinta Abu Hukman datang dari hatinya, bukan dari ucapan orang yang tawaf tersebut atau dari maksud ucapannya itu.
Bagi orang yang cintanya kepada Allah membara, lafal-lafal syair yang buruk tidak menghalanginya untuk memahami makna-makna yang indah. Sebab, dia tidak memperhatikan alunan irama atau lirik syair. Barang siapa beranggapan bahwa simā‘ didasarkan pada kelembutan makna dan bagusnya irama, maka sebenarnya dia jauh dari simā‘ yang hakiki.
Para sufi mengatakan bahwa simā‘ adalah hakikat ketuhanan dan kelembutan rohani. Yang Maha Mendengar menuntun hati yang mendengarnya kepada rahasia-rahasia karunia-Nya dan nur-Nya, sehingga semua yang ada dalam hati terhapus dan yang tersisa hanyalah Dia. Inilah yang disebut dengan simā‘ yang benar yang datang dari al-Ḥaqq.
Mereka mengatakan bahwa kondisi yang dialami seorang sufi yang sedang dimabuk cinta bersumber dari kelemahannya untuk menanggung apa yang terjadi. Hal ini disebabkan karena banyaknya cahaya kelembutan yang masuk ke dalam hatinya, sehingga dia terpukau, sekujur tubuhnya bergetar, bahkan dia sampai pingsan, berteriak atau menangis. Kondisi seperti ini biasanya dialami para sufi pemula. Sedangkan para sufi yang sudah sampai pada maqam puncak, biasanya mereka adalah gerak dan duduk mereka adalah goyangan. Suatu ketika, ditanyakan kepada Abu Qasim Junaid: “Mengapa kami tidak pernah melihatmu bergerak saat simā‘?” Dia menjawab dengan firman Allah:
“Dan engkau lihat gunung-gunung itu, engkau sangka dia tetap di tempatnya, padahal dia berjalan sebagaimana berjalannya awan.” (an-Naml: 88) (14814).
Catatan: