3 Manusia Hanya Perantara, Bukan Pemberi Rezeki – Rezeki Para Wali & Nabi
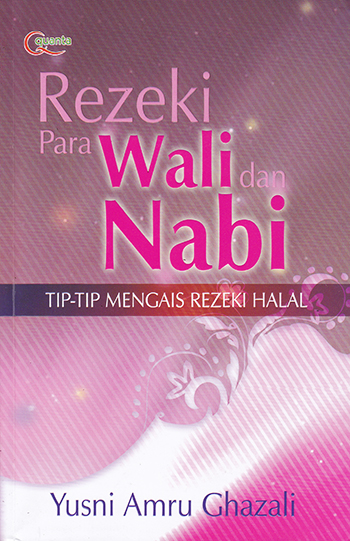
Rezeki Para Nabi dan Wali
TIP-TIP MENGAIS REZEKI HALAL
Oleh: Yusni Amru Ghazali
Penerbit: PT Elex Media Komputindo
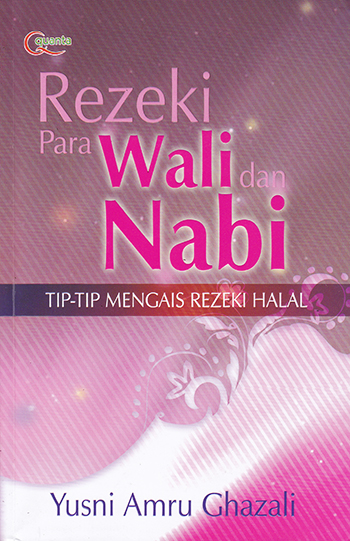
Rezeki Para Nabi dan Wali
TIP-TIP MENGAIS REZEKI HALAL
Oleh: Yusni Amru Ghazali
Penerbit: PT Elex Media Komputindo
“Maka Dia (Allah) menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakariyyā. Setiap kali Zakariyyā masuk menemuinya di mihrab (kamar khusus ibadah), dia dapat makanan di sisinya. Dia berkata: “Wahai Maryam! Dari mana ini engkau peroleh?” Dia (Maryam) menjawab: “Itu dari Allah”. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa diduga-duga”.” (QS. Āli ‘Imrān [3]: 37).
Berangkat dari dialog antara Maryam a.s. dan Zakariyyā a.s. di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kita ini hakikatnya adalah manusia yang juga memiliki peran seperti halnya Zakariyya a.s. Kita adalah “pemilihara” yang bertanggung-jawab atas kebutuhan rezeki beberapa orang di sekitar kita. Kita adalah Zakariyyā-Zakariyyā masa kini dalam konteks sebagai “tumpuan” rezeki orang lain. Oleh karena itu, orang kaya, pejabat tinggi, bos, direktur, General Manajer, manajer dan CEO dalam sebuah perusahaan adalah orang-orang yang lebih dekat untuk dapat merasakan dirinya sebagai “pemelihara” bagi bawahannya.
Sebenarnya, ketika Maryam a.s. menjawab bahwa rezeki yang dia dapatkan itu datang dari Allah, adalah untuk menunjukkan pada Zakariyyā a.s. – dan umat Islam yang mana kitab sucinya adalah al-Qur’ān – tentang siapa Pemelihara dirinya yang sejati. Pada jawabannya itu pula, secara tersirat Maryam a.s. berpesan agar manusia tidak bergantung sepenuhnya pada manusia. Itu karena, menggantungkan diri pada selain Allah disertai iman adalah syirik. Sikap semacam itu pada dasarnya adalah bentuk berhala yang bersemayam dalam hati. Bahkan, sikap itu terkadang membuat jiwa seseorang menjadi tak berdaya dalam “genggaman” orang lain yang memiliki derajat sama sebagai hamba. Berhala semacam ini, biasanya muncul dalam hati karyawan, anak buah dan bawahan lainnya.
Adapun berhala dalam hati para bos, berupa rasa berjasa atas keberlangsungan hidup orang lain, rasa berkuasa atas rezeki orang lain, rasa paling berperan atas rezeki orang lain, rasa menjadi pengendali atas rezeki orang lain dan rasa-rasa lain yang menguatkan bahwa dirinya adalah sang “pemelihara”. Seolah, rasa ini secara berlebihan ingin menggeser tauhid rububiyyah yang dida‘wahkan Maryam a.s. Orang-orang yang mengidap penyakit ini, biasanya sering bersingkap adigang, adigung, adiguna. Dan, sikap itu menginspirasi bawahannya untuk berkeyakinan bahwa dialah (baca: bos) sumber rezeki itu.
Hati kita harus bersih dari berhala-berhala kecil semacam itu karena sekecil apa pun bentuk pengabdian pada dzat selain Allah adalah syirik. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:
“Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyala berhala-berhala, dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu; maka mintalah rezeki dari Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada-Nya, Hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan.” (QS. al-‘Ankabūt [29]: 17).
Ayat tersebut mampu menyentuh realitas budaya masa kini, terutama budaya lekas tunduk di hadapan atasan. Padahal sebesar dan sepenting apa pun peran seseorang atas rezeki yang diterima orang lain, dia sama sekali bukan sumber rezeki yang sebenarnya. Dia bukan pemelihara sejati. Oleh sebab itu, jauh-jauh hari Maryam a.s., telah menegur manusia sekaligus menegaskan bahwa langsung maupun tidak langsung, rezeki itu datangnya dari Allah karena Dia adalah Tuhan pemelihara alam raya. Oleh sebab itu, kepatuhan pada atasan adalah penting dalam perusahaan, tapi harus sesuai porsi dan kebutuhan.
Jadi, setiap rezeki yang dimakan dan yang dinikmati seseorang, pada hakikatnya bukan karena jasa dan andil orang lain. Bahkan, nasi yang disuapkan ibu pada anaknya, tetap merupakan rezeki yang datang dari Allah, bukan rezeki yang datang dari ibu.
Ini mungkin hal kecil, tapi akan berdampak besar jika terlupakan oleh kesadaran tauhid kita. Oleh karena itu, Allah beberapa kali menegaskan dalam al-Qur’ān mengenai peran-Nya sebagai Sang Maha Pemberi rezeki (ar-Razzāq), agar manusia selalu ingat siapa sejatinya Sang Maha Pemelihara itu. Dalam firman-Nya Allah s.w.t. menegaskan:
“Katakanlah (Muḥammad): “Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi?” Katakanlah: “Allah,” dan sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.” (QS. as-Saba’ [34]: 24).
Pada ayat yang lain Allah s.w.t. berfirman:
“Sungguh Allah, Dialah Pemberi rezeki Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh.” (QS. adz-Dzāriyāt [51]: 58).
Allah s.w.t. juga berfirman:
“Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang sama sekali tidak dapat memberikan rezeki kepada mereka, dari langit dan bumi, dan tidak akan sanggup (berbuat apa pun).” (QS. an-Naḥl [16]: 73).
Maka, tak pantas sekejap pun terbesit dalam hati yang suci ini untuk menggantungkan rezeki pada manusia yang hakikatnya tak mampu memberi apa-apa. Hanya Allah s.w.t., dan tidak ada selain Dia, yang mampu memberi manfaat dan mudarat pada makhluk di dunia ini. Manusia hanya berperan sebagai perantara saja. Tidak lebih.
Para Bos dan Masalah Perilaku
Seorang trainer ternama di Barat yakni Marshall Goldsmith, dalam bukunya yang berjudul, What Got You Here Won’t Get You There, menyatakan bahwa semakin tinggi karier seseorang, kebanyakan masalah yang menimpanya adalah seputar perilaku atau akhlak. (121) Artinya, dalam struktur organisasi perusahaan, seseorang yang jabatannya tinggi bisa dipastikan secara keahlian ia jauh terlatih dari orang lain yang ada “di bawahnya”. Dalam hal keahlian mereka sudah di atas rata-rata. Mereka adalah orang-orang cerdas yang memiliki teknik-teknik bekerja yang inovatif dan maju. Sehingga, seseorang menjadi CEO atau pimpinan perusahaan, lebih banyak dilihat bukan lagi karena keahliannya dalam bekerja, melainkan karena sosok dan kepribadiannya. Seberapa baik dirinya, seberapa ramah dirinya dan penilaian-penilaian lain yang mengarah pada perilaku atau akhlak. Dan, orang-orang sukses yang menduduki jabatan tinggi di perusahaan, bukan sebab ia cerdas saja, melainkan karena faktor-faktor lain yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan keahlian.
Marshall dalam bukunya juga mengisahkan tentang seseorang, Jack Welch. Seorang yang memiliki gelar Ph.D dalam rekayasa kimia. Tapi, Marshall tidak yakin kalau masalah yang dialami Jack Welch selama puluhan tahun sebagai CEO di General Electric adalah keahliannya. Marshall yakin bahwa masalah-masalah yang dihadapinya adalah seputar perilaku, seperti kata-kata yang kasar, gengsi terkesan bodoh dan sebagainya. (132).
Jika masalah perilaku sangat urgent untuk diperhatikan CEO, maka sikap adigang, adigung, adiguna, seharusnya menjadi bagian dari masalah yang harus segera dipecahkan. Tapi, pada kenyataannya banyak CEO yang tidak menyadari bahwa sikap tersebut adalah masalah perilaku yang sangat berbahaya. Secara lahiriah, sikap tersebut memang tak separah dengan marah, sombong atau yang lain. Tapi, hampir setiap orang, dapat dengan jelas merasakan sikap adigang, adigung, adiguna dari seseorang. Apalagi, dari seorang atasan yang tiap hari bertemu selama jam kerja.
Ilmu etika mungkin tidak terlalu banyak menjelaskan sikap buruk adigang, adigung, adiguna ini. Tapi, dalam Islam sikap adigang, adigung, adiguna – dalam konteks ini berarti merasa berkuasa atas rezeki orang lain adalah dosa besar – adalah “penyelewengan akidah”. Sebab, secara prinsip Dzāt yang menguasai rezeki orang dan semua makhluk yang ada itu hanyalah Allah atau yang dipahami dengan tauḥīd rubūbiyyah. Jadi, adigang, adigung, adiguna, tidak hanya masalah bagi akhlak atau perilaku, tapi juga masalah bagi tauhid.