25 Tawakkal Bukan Berarti Tak Berusaha – Rezeki Para Wali & Nabi
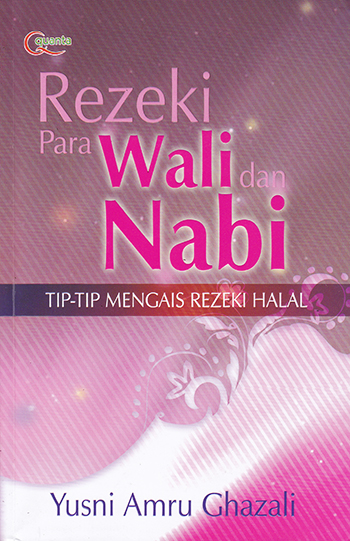
Rezeki Para Nabi dan Wali
TIP-TIP MENGAIS REZEKI HALAL
Oleh: Yusni Amru Ghazali
Penerbit: PT Elex Media Komputindo
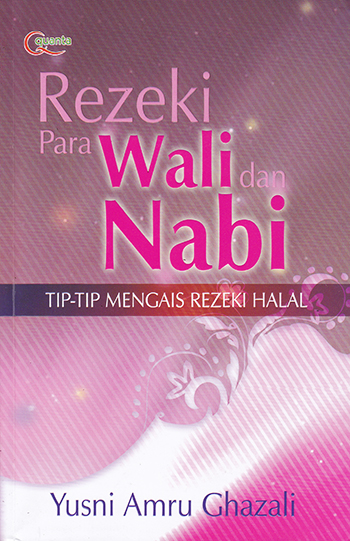
Rezeki Para Nabi dan Wali
TIP-TIP MENGAIS REZEKI HALAL
Oleh: Yusni Amru Ghazali
Penerbit: PT Elex Media Komputindo
Tawakkal adalah wujud iman dalam hati seseorang, dan adanya setelah ia berusaha dan berikhtiar. Semakin tinggi kebergantungan seseorang pada Allah, pertanda bahwa iman dalam hatinya juga semakin kuat.
Sudah menjadi sunnatullāh bahwa rezeki hanya dapat dikais dengan bekerja dan berusaha. Maka, tawakkal adalah kepatuhan nalar untuk mengikuti sunnah tersebut dan sepenuhnya menyandarkan hati pada Allah terkait hasil usaha dan nilai akhir yang bakal dicapai. Adapun kebalikannya adalah menggantungkan hasil dan nilai pencapaian hanya sebatas pada kekuatan kerja dan usaha tanpa pernah memperhitungkan kuasa dan “campur tangan” Allah.
Rasa bergantung, sejatinya bukanlah “barang baru” bagi hati setiap manusia. Rasa itu, merupakan fitrah yang disematkan Allah dalam ciptaannya sejak manusia pertama. Maka, setiap orang yang berusaha pasti dalam harapnya menggantungkan hati pada sesuatu.
Hanya saja, Islam mengikat rasa ini dengan istilah tawakkal, untuk menjelaskan kepada siapa kita berhak menyandarkan diri secara total. Tentu pada Dzāt yang tak pernah membuat kecewa, yang kuasa atas segalanya, yang di “tangan-Nya” semua bisa terjadi semudah membalik telapak yaitu Allah.
Allah berfirman:
“Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu, tetapi jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mu’min bertawakkal.” (QS. Āli ‘Imrān [3]: 160).
Ayat ini, berisi sindiran, terutama pada mereka yang dalam bekerjanya hanya mengandalkan keahlian, kecanggihan sistem, kekuatan modal, tanpa pernah memperhitungkan kuasa Allah pada setiap usaha.
Tapi, orang yang beriman tak pernah meninggalkan tawakkal dalam setiap usahanya. Itu karena, telah terpatri kuat dalam hatinya satu keyakinan bahwa Allah, tanpa bantuan siapa pun, mampu mencukupi kebutuhan dirinya, bahkan kebutuhan seluruh makhluk di alam semesta. Meskipun keyakinan ini tidak mudah diterima oleh orang yang hatinya keras, atau bagi yang tak percaya akan “keterlibatan” Allah dalam setiap usaha manusia.
Padahal dalam firman-Nya Allah mengatakan:
“Dan barang siapa bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.” (QS. ath-Thalāq [65]: 3).
Namun, tawakkal tak bisa langsung diucapkan begitu saja. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, tawakkal ada setelah usaha. Dan, tentu saja bukan usaha asal-asalan untuk kemudian menuntut kekuatan tawakkal dalam mencapai hasil yang maksimal. Bagaimanapun, hukum sunnatullāh tetap berlaku bagi semua ciptaan-Nya, bahwa yang bekerja dan berusaha secara keras dan cerdas berhak mendapatkan hasil memuaskan dan yang bekerja malas serta asal-asalan, mendapatkannya hasil yang biasa saja atau bahkan mengecewakan.
Jadi, dengan kerja keras dan cerdas saja, menurut sunnatullāh kita berhak mendapat hasil yang memuaskan, lantas apa fungsi tawakkal? Sunnatullāh itu, pada tahap selanjutnya akan bertemu dengan sifat Allah bahwa Dialah yang menentukan ending segala sesuatu, tanpa bisa diganggu gugat. Maka, di sinilah, letak pentingnya tawakkal, doa dan permohonan.
Jadi, meskipun kita memiliki kemampuan yang menakjubkan dan dianggap berhak mendapatkan hasil maksimal, tapi jika Allah berkehendak lain maka semuanya menjadi berubah 180 derajat. Dan, Allah dalam keputusan-Nya tak pernah melakukan kezhaliman untuk menyakiti atau membuat kecewa hamba-Nya.
Artinya, meskipun usaha sudah dikerjakan secara maksimal, tapi jika hasilnya tetap mengecewakan maka hal itu bukan kehendak Allah untuk membuatnya kecewa. Karena pada prinsipnya, semua kebaikan itu datangnya dari Allah dan keburukan itu datang akibat ulah kita sendiri.
Terdapat kisah yang menarik terkait tawakkal ini. Diriwayatkan dari Jābir bin ‘Abdullāh:
“Ketika kami bersama Rasūlullāh s.a.w., dalam Perang Dzāt-ur-Riqā’, (511) kami tiba di sebuah pohon yang rindang. Tapi, kemudian pohon itu sengaja kami tinggalkan agar dapat digunakan berteduh oleh Rasūlullāh s.a.w. Tak lama (setelah sejenak Rasūlullāh s.a.w. bersandar), tiba-tiba datang seorang lelaki musyrik (Ghaurats bin Ḥārits) dan merampas pedang Rasūlullāh s.a.w. yang menyandar di pangkal pohon. Kemudian, Ghaurats mengacungkan pedang dan mengarahkannya kepada Rasūlullāh s.a.w. seraya berkata:
“Sekarang kau ketakutan bukan?”
“Tidak” Jawab Rasūlullāh.
“Memang, siapa yang akan melindungimu?” gertak Ghaurats.
“Allah,” jawab Rasūlullāh.
Seketika, pedang yang berada di tangan Ghaurats pun terjatuh. Dan, Rasūlullāh s.a.w., balik mengambil pedang itu lantas menggertak Ghaurats.
“Sekarang, siapa yang akan melindungimu dari ancamanku?”
“Jadilah engkau pembalas yang baik,” Ghaurats memohon.
“Apakah engkau mau mengucapkan syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan-Nya?” tanya Rasūlullāh pada Ghaurats.
“Tidak. Tapi aku berjanji, tidak akan pernah memerangimu dan tidak akan pernah bergabung dengan orang-orang yang memerangimu,” jawab Ghaurats.
Setelah berkata demikian, Ghaurats pergi meninggalkan Rasūlullāh s.a.w., kembali menemui para sahabatnya dan berkata: “Aku baru saja datang dari menemui manusia yang paling baik.” (HR. al-Bukhārī).
Persis, seperti Rasūlullāh dan Ghaurats, itulah gambaran antara orang yang bertawakkal dan orang yang tak punya sandaran hati. Meskipun, dengan pedang terhunusnya Ghaurats yakin dapat menghabisi Rasūlullāh, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ghaurats yang menyandarkan diri pada kekuatan pedang akhirnya tak berdaya menghadapi kuasa Allah, yang telah menjadi sandaran Rasūlullāh sepanjang hidupnya.
Kisah tersebut juga mengajarkan pada kita bahwa semua ada taqdīrnya. Dan, Allah-lah penentu segala kejadian di alam raya ini, karena di “Tangan-Nya” semua kekuasaan bermuara. Sebab taqdīr ada di tangan-Nya, maka tawakkal adalah penenang hati saat cemas berharap.
Pada hadits lain Rasūlullāh s.a.w. bersabda:
“Seandainya kalian bertawakkal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana halnya burung yang pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, kemudian kembali di sore hari dalam keadaan kenyang.” (HR. at-Tirmidzī).
Berkenaan dengan tawakkal ini, pada hadits lain riwayat Imām at-Tirmidzī, Anas r.a. berkata: “Tersebutlah dua orang bersaudara pada masa Rasūlullāh s.a.w. Salah seorang di antara mereka mendatangi Rasūlullāh s.a.w., ketika saudaranya yang lain sibuk bekerja. Beberapa saat kemudian, datanglah lelaki yang bekerja itu kepada Rasūlullāh s.a.w.. Kepada beliau, ia mengeluhkan ihwal saudaranya yang tidak bekerja. Rasūlullāh s.a.w., lalu berkata kepada lelaki yang bekerja itu: “Semoga saja engkau mendapatkan rezeki disebabkan saudaramu itu”.”
Dari hadits di atas dapat kita pahami bahwa dalam tawakkal dan ikhtiar yang kita lakukan, sebenarnya ada etika untuk tidak menghina atau mengeluhkan orang lain yang tak memiliki kesepahaman dengan kita. Tawakkal dan ikhtiar kita, tidak menuntut orang lain agar berlaku hal yang sama. Sebab, ini adalah masalah pribadi yang sifatnya khusus, hanya antara kita dan Allah. Orang yang kita pandang kurang ikhtiar atau kurang tawakkal, bisa jadi kualitas tawakkal dan ikhtiarnya lebih unggul dari yang kita punya.