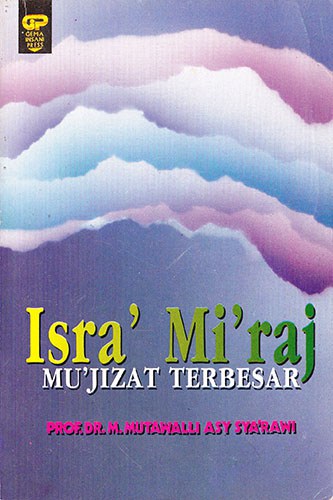3. Hakikat Penggunaan Kata “‘Abdihi” dalam Surat al-Isrā’.
Dalam surat al-Isrā’ ayat satu Allah ta‘ala berfirman: “Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya”. Allah tidak mengatakan rasul-Nya karena memang semua yang selain dari Allah, yang ada di dalam alam-Nya adalah hamba-Nya. Kita semua adalah hamba-Nya, baik yang taat maupun yang tidak taat, yang mu’min maupun yang kafir. Namun dalam ayat-ayatNya biasanya yang Allah katakan hamba-Nya adalah hamba-Nya yang ikhlas, pilihan dan yang senantiasa menyatu dengan metode Ilahi. Segala sesuatu yang diperintahkan Allah segera dilaksanakan dan segala yang dilarang-Nya dijauhi dan dihindari, sami‘nā wa atha‘nā! Karena itulah dalam al-Qur’ān yang ikhlas dan berakhlak, Allah tidak menamakannya “‘abīd”, tetapi ‘ibād, seperti dalam firman-Nya:
“Dan hamba-hamba yang baik dari Rabb yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan.”
Namun dalam surat al-Isrā’ Allah menggunakan kata ‘abdihi (yang sepadan dengan kata ‘ibād). Ini dimaksudkan untuk menarik perhatian kita pada dua hakikat penting yaitu:
PERTAMA. Peritstiwa Isrā’ terjadi dengan rohani dan jasmani, bukan sekedar suatu mimpi dalam tidur. Isrā’ merupakan suatu peristiwa hakiki yang dialami Rasūlullāh s.a.w. dalam keadaan sadar, terjaga, dan dapat diinderanya. Kata ‘abdun dalam istilah bahasa hanya digunakan pada rohani dan jasmani secara bersamaan.
Telah terjadi perdebatan sengit antara orang-orang yang mendengarkan kisah Rasūlullāh s.a.w. Namun justru hal ini lebih memperkuat lagi. Ini menandakan bahwa Rasūlullāh s.a.w. perjalanan Isra’ dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidur atau bermimpi. Kalau perjalanan itu suatu mimpi, siapa yang akan memperdebatkannya? Apa ada orang yang memperdebatkan mimpi orang tidur? Jelas tidak ada!
Kalau anda berkata: “Saya pergi ke Amerika dan kembali ke Mesir dalam 20X semalam”, apakah ada orang yang akan mendustakan mimpi anda itu? Jelas tidak juga! Apa yang terjadi dalam mimpi tidak bisa ditundukkan oleh akal dan disesuaikan dengan hukum logika, seperti mimpi raja di zaman Nabi Yūsuf a.s. yang diuraikan dalam al-Qur’ān-ul-Karīm:
“Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): “Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dari tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering. Hai orang-orang yang terkemuka, terangkan kepadaku tentang ta‘bir mimpiku itu jika kamu dapat mena‘birkan mimpi.” (Yūsuf: 43).
Apakah mimpi yang diucapkan raja itu sesuai dengan akal dan logika? Adakah sapi makan sapi? Siapa di antara kita yang pernah melihat sapi memakan sapi lainnya? Jelas tidak ada! Kalau sekiranya memang ada, mungkinkah sapi yang kurus memakan sapi yang gemuk, atau sebaliknya yang lebih sesuai dengan logika?
Tidak seorang pun yang pernah melihat sapi makan sapi. Akan tetapi, ketika Raja (dalam ayat di atas) menceritakan mimpinya kepada para wazir dan hulubalangnya, dan ketika dia meminta untuk menta’wilkan mimpinya itu, apakah orang yang mendebatnya? Tidak ada, karena mimpi tidak bisa didebat dengan akal dan logika. Lagi pula mimpi tidak tunduk pada hukum kausalitas manusia. Karenanya para wazir dan hulubalang hanya berkata: “(Itu) adalah mimpi-mimpi yang kosong dan kami sekali-kali tidak tahu menta‘birkan mimpi itu.” (Yūsuf: 44).
Mereka sama sekali tidak mendebat mimpi raja tersebut. Begitu pula halnya orang dalam menilai mimpi siapapun. Namun dalam menilai mu‘jizat Isrā’ terjadi perdebatan. Mereka mempertanyakan, bagaimana mungkin Rasūlullāh s.a.w. menempuhnya dalam semalam, padahal kami menempuh perjalanan itu dengan unta dalam jangka waktu sebulan.
Terjadinya perdebatan itu menandakan bahwa perjalanan Isra’ dilakukan Rasūlullāh s.a.w. dengan rohani dan jasmaninya, seperti yang dinyatakan dalam firman-Nya: “Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya”. Firman-Nya ini dipaparkan Allah untuk mengukuhkan bahwa peristiwa Isra’ terjadi dengan ruh dan jasad Rasūlullāh s.a.w.
KEDUA. Hakikat penting kedua yang tersirat dari kata ‘abdihi adalah Allah ta‘ālā ingin menyatakan kepada kita bahwa pengabdian kepada-Nya merupakan kelas tertinggi yang bisa dicapai manusia. Pengabdian kepada Allah merupakan suatu kemuliaan yang tiada tara, dan suatu karunia yang tiada duanya. Apabila kita membaca surat al-Kahfi maka kita akan menemukan firman-Nya yang mengungkapkan pertemuan Mūsā dan pembantunya dengan Khidhir:
“Lalu mereka (Mūsā dan pembantunya) bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba Kami yang telah Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi Kami, dan yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami. Mūsā berkata kepada Khidhir: “Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?” (al-Khafi: 65-66).
Kita tahu, Mūsā adalah Rasūlullāh s.a.w. dan kalim-Nya. Allah telah berbicara dengan Mūsā. Sungguhpun begitu masih ada seorang hamba Allah yang jauh lebih berilmu dari Mūsā a.s. sehingga Mūsā merasa perlu mengikutinya dan berguru kepadanya. Di sini Allah ta‘ālā ingin menarik perhatian kita bahwa pengabdian kepada-Nya merupakan kelas tertinggi di hadapan-Nya. Buktinya, Allah s.w.t. menguraikan kepada kita dalam surat al-Kahfi tentang kisah Mūsā dan Khidhir a.s. Khidhir bukan seorang rasul, tapi hanya seorang hamba-Nya. Namun ia telah mencapai derajat yang tinggi di sisi-Nya, dan Allah memberikan berbagai ilmu dan hikmah kepadanya, yang tidak diberikan-Nya kepada Mūsā sehingga Mūsā berguru kepadanya.
Kalau pengabdian kepada Allah ta‘ālā bisa mengangkat ketinggian martabat seseorang di sisi-Nya maka pengabdian terhadap manusia kebalikan dari itu, yakni akan merupakan suatu kehinaan dan kenistaan. Pada umumnya bila manusia menjadi majikan maka dia cenderung memeras hambanya dan menanggalkan semua hak-hak hambanya sebagai manusia, sedangkan pengabdian kepada Allah akan memberikan segala-galanya, baik di dunia maupun di akhirat. Allah akan memberikan rahmat, karunia dan kemuliaan.
Allah s.w.t. ingin agar kita mengetahui bahwa martabat yang tinggi dan mulia sudah diberikan juga kepada Muḥammad s.a.w. sebagai hamba-Nya, yakni dengan diisrā’kannya ruh dan jasad beliau. Kalau Isrā’ terjadi dalam bentuk mimpi atau hanya dengan ruhnya saja (seperti yang diyakini sementara orang yang lemah iman) maka tentu kaumnya tidak akan mempermasalahkan dan mengatakan dengan rasa kagum dan tidak percaya. Tentu tidak akan ada kaumnya yang berkata: “Bagaimana anda dapat mengatakan menempuh perjalanan itu dalam semalam saja, sedangkan kami tidak bisa kurang dari sebulan untuk menempuh perjalanan tersebut, dan itupun dengan mengendarai unta?”
Dengan demikian jelaslah, perjalanan Isrā’ dan Mi‘rāj terjadi dengan mu‘jizat, dengan kekuatan Allah ta‘ālā yang berlaku di atas perhitungan akal manusia. Peristiwa Isrā’ dan Mi‘rāj diberikan khusus kepada hamba-Nya (yang terdiri dari ruh dan jasad) sebagai makhluk tertinggi dan terdekat-Nya agar dia dapat melihat ayat-ayat dan kekuasaan-Nya di seluruh kawasan kerajaan-Nya.
Kini timbul pertanyaan, kepada Isrā’ terjadi di malam hari, kenapa tidak di siang hari agar bisa dilihat dan diyakini orang? Kalau mu‘jizat itu terjadi dengan kekuatan Allah, kenapa terjadi dalam semalam, bukan sekejap mata? Bukankah Allah Maha Kuat memperjalankan hamba-Nya dari Makkah ke Bait-ul-Maqdis pergi-pulang dalam sekejap mata? Bukankah peristiwa itu terjadi dengan kekuasaan Allah? Mengapa memakai waktu segala, bukan seketika saja agar lebih kuat kemu‘jizatan-Nya?
Biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu diajukan oleh para orientalis. Mereka mengira pertanyaan-pertanyaan itu bisa menghancurkan mu‘jizat-Nya, akan tetapi malah sebaliknya. Pertanyaan-pertanyaan seperti di atas justru menambah kekhasan segi-segi mu‘jizat Isrā’ dan Mi‘rāj. Kalau saja para orientalis tidak membangkitkan kecurigaan orang terhadap Islam, segi-segi tersebut mungkin tidak banyak diperhatikan orang. Akan tetapi, sudah menjadi suratan takdir, terkadang Allah ta‘ālā memperalat orang non-mu’min untuk kepentingan ad-Dīn-Nya agar orang lebih mengenal keagungan dan kebenaran-Nya.