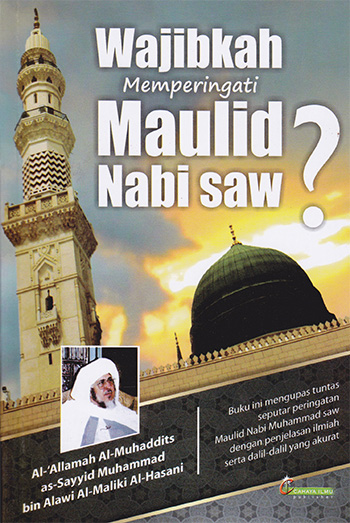Kesebelas
Peringatan maulid Nabi adalah hal yang dinilai baik oleh para ulama dan seluruh kaum muslimin di seluruh negeri dan dilaksanakan di setiap wilayah negeri. Oleh karena itu Maulid tersebut termasuk yang dianjurkan oleh syari‘at berdasar suatu kaidah hukum Islam yang bersumber dari hadits mauqūf (12) riwayat Ibnu ‘Abbās:
مَا رَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنًا وَ مَا رَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ قَبِيْحًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ قَبِيْحًا.
Artinya: “Apa yang dipandang orang-orang muslim baik maka itu adalah baik di sisi Allah. Dan apa yang dipandang buruk oleh orang-orang muslim maka itu adalah buruk di sisi Allah.” (HR. Aḥmad).
Keduabelas
Peringatan Maulid meliputi perkumpulan sesama ikhwan, zikir, sedekah, puji-pujian dan pemuliaan kehadirat Nabi s.a.w. dan itu adalah sunnah, dan perkara-perkara itu adalah perkara yang dianjurkan dan terpuji dalam syari‘at, yang mana hal itu telah dijelaskan dan dianjurkan oleh atsar-atsar (hadits atau perkataan sahabat atau tabi‘in).
Ketigabelas
Allah Yang Maha Tinggi berfirman:
وَ كُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ.
Artinya: “Dan semua kisah dari rasūl-rasūl Kami ceritakan kepadamu (wahai Muḥammad), ialah kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu….” (QS. Hūd: 120).
Dari sini tampak bahwa hikmah pemaparan kisah para nabi a.s. adalah untuk meneguhkan hati beliau yang mulia. Dan tak diragukan lagi bahwa sekarang kita lebih membutuhkan peneguhan hati dengan kisah beliau s.a.w., lebih dari beliau s.a.w. sendiri.
Keempatbelas
Tidak semua perkara yang tak dilakukan oleh salaf (generasi terdahulu, yakni generasi para sahabat, tābi‘īn, dan tābi‘it tābi‘īn) dan ditemui pada masa-masa awal Islam adalah bid‘ah yang munkar dan buruk, haram untuk dilakukan dan wajib diingkari. Tetapi yang harus dilakukan adalah menghadapkan setiap perkara tersebut kepada dalil-dalil syar‘i, jika menurut syari‘at terdapat kemaslahatan maka perkara tersebut hukumnya wajib, dan jika mengandung sesuatu yang haram maka hukumnya haram, dan jika mengandung sesuatu yang makruh maka hukumnya makruh, jika mubah maka mubah, dan jika sunnah maka sunnah. Dan hukum suatu perantara adalah sama dengan hukum tujuannya. Kemudian ulama membagi bid‘ah itu menjadi lima bagian:
– Wājib, seperti: membantah pernyataan-pernyataan orang-orang yang menyimpang (sesat) dari syari‘at agama Islam, dan mempelajari ilmu nahwu (tata bahasa ‘Arab).
– Mandūb (Sunnah): membuat pondok pesantren dan madrasah, adzan di menara, dan melakukan perbuatan baik yang belum ada pada masa awal Islam.
– Makrūh: menghias masjid secara berlebihan, dan juga menghias mushḥaf.
– Mubāḥ: menggunakan ayakan (untuk menghaluskan tepung), dan memakan makanan yang lezat.
– Ḥarām: melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sunnah dan tidak terkandung dalam makna hadits secara luas, serta sesuatu yang tidak mengandung kemaslahatan secara syar‘i.
Kelimabelas
Tidak semua bid‘ah itu haram. Andaikata itu benar maka haramlah hukumnya Abū Bakar ash-Shiddīq. ‘Umar bin Khaththāb, dan Zaid bin Tsābit – semoga Allah meridhai mereka – dalam penulisan al-Qur’ān pada sebuah Mushḥaf karena takut akan hilangnya al-Qur’ān karena banyak di antara para penghafal al-Qur’ān dari kalangan sahabat r.a. yang meninggal dunia. Dan jika demikian maka haram pula hukumnya ‘Umar r.a. mengumpulkan orang-orang di bawah kepemimpinan seorang imam dalam shalat tarāwīḥ, yang mana ketika itu beliau mengatakan: “Sungguh ini adalah sebaik-baiknnya bid‘ah”. Dan niscaya haram pula penyusunan kitab-kitab yang berisi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan wajib pula bagi kita untuk memerangi orang-orang kafir dengan menggunakan anak panah dan busur, sedangkan mereka menyerang kita dengan pistol, meriam-meriam, tank-tank, pesawat-pesawat tempur, kapal-kapal selam dan beberapa kapal laut. Dan haram pula adzan di atas menara, serta haram pula membuat pondok pesantren, madrasah (sekolah), rumah sakit, ambulan, rumah-rumah yatim, dan penjara. Oleh karena itu para ulama r.a. memaknai kata “bid‘ah” dalam hadits “semua bid‘ah adalah sesat” dengan bid‘ah yang sesat saja, yang bertentangan atau menyimpang dari syari‘at. Hal ini dikuatkan dengan perkara-perkara yang dilakukan oleh para sahabat besar, dan tābi‘īn yang semuanya itu tidak didapati pada masa Rasūlullāh s.a.w. Sedangkan kita sekarang telah melakukan banyak hal yang baru yang belum pernah dilakukan oleh salaf, seperti: mengumpulkan orang untuk berjama‘ah dengan satu imam pada shalat malam (tahajjud) setelah melakukan shalat tarāwīḥ, mengkhatamkan al-Qur’ān di dalam shalat malam atau shalat tarāwīḥ itu, khutbah yang dilakukan oleh imam pada malam ke-27 bulan Ramadhān dalam pelaksanaan shalat tahajjud, dan seperti seruan mu’adzdzin:
صَلَاةُ الْقِيَامِ أَثَابَكُمُ اللهُ (صَلَاةُ التَّرَاوِيْحِ آجَرَكُمُ اللهُ)
Artinya: “Bersiaplah untuk shalat tarawih semoga Allah memberimu pahala.”
Kesemuanya itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi s.a.w. dan tidak pula dilakukan oleh para salaf. Lalu apakah perbuatan kita itu bid‘ah?