Tujuh Aspek Cinta Allah Bagi Kaum Muslim – Kitab Cinta (3/3)
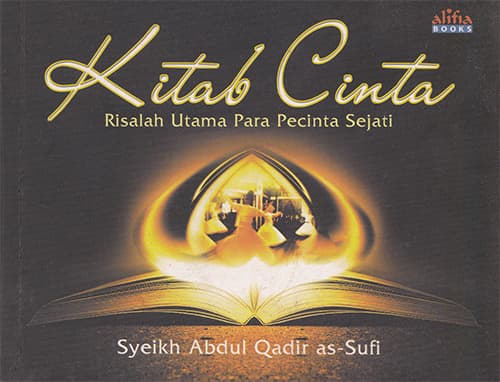
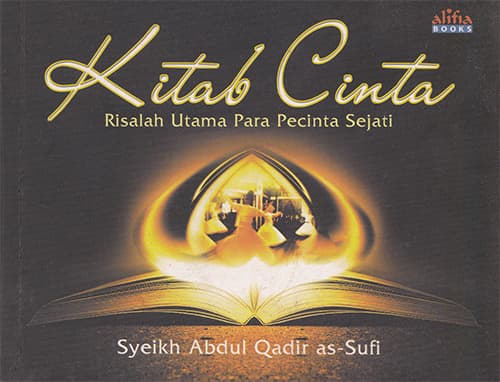
Aspek keempat cinta Allah s.w.t. diperuntukkan bagi ash-Shābirūn – orang-orang yang sabar. Kita menjumpainya dalam Surat Shād (38), di bagian akhir ayat 44:
إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ
“Sesungguhnya kami dapati dia (Ayyūb) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhannya).”
Kita menjumpai kecintaan Allah pada ash-shābirūn, orang-orang yang sabar. Ḥajj ‘Abd-ul-Ḥaqq lebih senang mengartikan kata ash-shabirun dengan “tabah”, meski saya lebih suka mengartikannya “sabar”. Tapi tentu saja ciri orang-orang yang sabar adalah mereka tabah, dan dalam pengertian ini beliau tidaklah keliru. “Kami mendapatinya tabah” – kita menjumpainya sabar, kami menjumpai dia tabah.” “Betapa dia adalah sebaik-baik hamba! Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan.” Jadi, inilah orang-orang yang dicintai Allah. Orang yang tabah, orang yang sabar, dan orang yang taat kepada Tuhannya.
Aspek kelima cinta Allah bagi makhlūq-Nya termaktub dalam Surat Ibrāhīm (14: 7):
وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيْدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ
“Dan (tatkala Tuhanmu memaklumkan: Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya ‘adzāb-Ku sangat pedih.”
Di sini kita mengetahui bahwa Allah mencintai orang-orang yang bersyukur, asy-syākirūn. Dalam ayat ini Allah telah menunjukkan bahwa pahala bagi rasa syukur ini adalah bertambahnya nikmat yang merupakan hadiah dari sang Kekasih kepada sang Pecinta.
Aspek keenam cinta Allah s.w.t. adalah untuk orang-orang yang iḥsān – al-muḥsinūn. Kita akan melihatnya dalam Surat al-Baqarah (2: 195):
وَ أَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَ لاَ تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَ أَحْسِنُوْا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ
“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”
Jadi, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, al-muḥsinūn. Menarik untuk dicermati, si penerjemah mengartikannya sebagai “orang-orang yang berbuat baik”, tapi mari kita melihat pada muḥsin ini. Muḥsin adalah orang yang memiliki ihsan. Dalam hadis pertama kitab hadis Imām Muslim, malaikat Jibrīl bertanya pada Rasūlullāh s.a.w. tentang ad-Dīn: “Apakah Islām itu?” “Apakah Īmān itu?” Kemudian malaikat Jibrīl melanjutkan: “Apakah iḥsān itu?” dan Rasūlullāh s.a.w. sebagaimana anda sekalian ketahui, menjawab: “Menyembah Allah seolah-olah kamu melihat-Nya, dan sekalipun kamu tidak melihat-Nya, kamu tahu bahwa Dia melihatmu.” Jadi, iḥsān adalah pengetahuan bahwa Allah melihat anda.
Iḥsān ini membuka pintu masuk pada sulūk tashawwuf, melalui Wird as-Sahl. Wird as-Sahl diambil dari al-Qur’ān:
اللهُ مَعِيْ، اللهُ نَاظِرٌ إِلَيَّ، اللهُ شَاهِدٌ عَلَيَّ.
“Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah adalah saksi atas perbuatan-perbuatanku.”
Jadi, orang yang memiliki iḥsān adalah orang yang sangat menyadari bahwa Allah sedang melihatnya. Mengetahui bahwa dia sedang dilihat oleh Allah mengubah subyek menjadi obyek, dan inilah jalan tengah sesungguhnya bagi shūfī. Dia bukan lagi orang yang mengamati, tapi orang yang diamati. Inilah wird yang telah diberikan pada Sahl at-Tustarī yang memberinya fātiḥah (pembukaan) untuk fanā’-nya. Allah s.w.t. menyaksikan anda. Inilah muḥsīn.
Aspek ketujuh dan terakhir dari cinta ini terdapat dalam Surat ash-Shaff (61: 4). Aspek ini sangat menarik karena inilah golongan terakhir yang dicintai Allah:
إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ
“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”
Kita harus benar-benar mencamkan hal ini, karena saat ini banyak sekali orang melakukan sesuatu yang kita tahu bertentangan dengan syarī‘at, namun demikian mereka dianggap “para syahīd yang mati di jalan Allah.” Padahal mereka bukanlah para syahīd karena mereka tidak memenuhi apa yang Allah perintahkan pada mereka dalam al-Qur’ān: “Allah menyukai orang-orang yang berperang.” – kata ‘Arab bagi berperang berasal dari kata kerja qatala yang sama sekali bukanlah sesuatu yang puitis, seperti halnya para modernis yang ingin menganggap segala hal berkenaan dengan jihad sebagai sesuatu yang bersifat psikologis – qatala bermakna membunuh, ia berma‘na berperang.
إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ
“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”
Jadi, Allah mencintai mereka yang berperang dalam sabīl-Nya, di jalan-Nya. Dalam ayat-ayat yang lain, anda akan menemui kalimat “Jihād fī sabīlillāh” – jihad di jalan Allah. Namun demikian, Allah memberitahu kita bahwa jihad haruslah dalam “barisan yang teratur”. Apakah gerangan maksudnya? Ini berarti, Jihad mestilah dilakukan oleh sebuah pasukan. Jihad bukanlah seorang pria dengan sebuah bom di tubuhnya, kemudian berjalan menuju kegelapan dan meledakkan dirinya.
Jihad adalah orang-orang yang memperoleh kekuatan mereka dari orang yang berada di sisi mereka. Mereka laksana “bangunan yang tersusun kokoh”, dan bangunan yang kokoh terbuat dari bebatuan yang memperoleh kekuatannya dari bebatuan lain yang ada di sisinya. Jihad adalah berperang di jalan Allah dan karena alasan Allah – bukan untuk menaklukkan sebuah negeri, bukan untuk merebut kembali suatu wilayah, tapi di jalan Allah, dan jalan Allah itu adalah menegakkan ad-Dīn.
Anda tidak bisa menegakkan ad-Dīn kecuali anda membawanya bersama anda. Inilah ad-Dīn. Orang yang berperang di jalan ini berarti sedang membawa ad-Dīn. Sayyidinā ‘Umar bin Khaththāb r.a. bersama pasukannya menyebar ke segala penjuru wilayah di masa hidupnya. Inilah cara beliau melakukan jihad, dengan para pria yang berperang dalam pasukan. Ketika mereka memasuki tempat itu, anda akan menyaksikan kekuatan dari sang Amīr ini dan kekuatan kaum Muslim. Jadi, ke mana saja mereka pergi orang-orang pasti menerima Islam. Mereka tidak memeluk Islam sebab sejumlah ulama datang dengan penjelasan rasional tentang segala hal yang masuk akal. Mereka menerima Islam karena pasukan ini jauh lebih kuat dari mereka, mereka terus bergerak, mereka datang dengan kehidupan, mereka datang dengan ibadah, mereka datang dengan obat, mereka datang dengan ‘ilmu pengetahuan – mereka datang dengan segala macam pengetahuan. Mereka juga berjuang dengan cara demikian karena mereka berjuang melalui ilmu pengetahuan.
Jihād fī sabīlillāh memiliki aturan-aturan, dan salah satu aturan pertamanya yang bahkan tidak diketahui orang-orang “bodoh” ini, yaitu para sahabat dilarang berperang jika mereka unggul 2:1 dari sisi jumlah. Jadi, bagaimana bisa orang-orang bodoh ini menyatakan perang pada Amerikan, seolah-olah itu hal yang sepatutnya dilakukan kaum Muslim? Mereka sepenuhnya unggul dalam jumlah. Seorang sahabat pernah mengatakan: “Benar kita memiliki kenangan indah saat Perang Badar, ketika jumlah kita kalah jauh! Perintah telah turun bahwa kita tidak boleh berperang jika jumlah kita 2:1 lebih banyak, dan karenanya kita tidak akan berperang seperti dulu lagi.”
Orang-orang modern itu tidak tahu tentang ini karena mereka tidak tahu ad-Dīn. Andaipun mereka menang, siapa yang berhak atas kemenangan itu? Apakah orang yang mengatakan: “Karena anak saya yang telah mati meledakkan diri maka sayalah yang berkuasa sekarang!?” Sementara jika kemenangan itu adalah kemenangan fī sabīlillāh, si orang itu akan berkata: “Ayah saya telah berjuang dan mati fī sabīlillāh, dan sekarang saya ingin menegakkan ad-Dīn. Dan beginilah cara saya akan melakukannya.”
Inilah aspek terakhir dari ketujuh aspek cinta Allah s.w.t. bagi kaum Muslim. In sya Allah, dalam kesempatan yang lain kita akan mulai membahas ajaran-ajaran Syeikh Nashīr-ud-Dīn, sang shūfī dari Delhi.