Tuduhan Tarekat Shufi Bid’ah – Tarekat dalam Timbangan Syariat
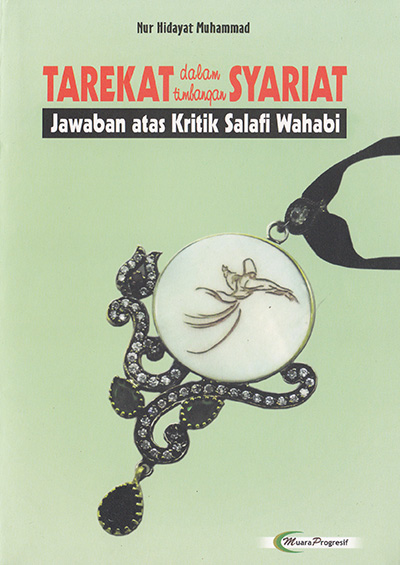
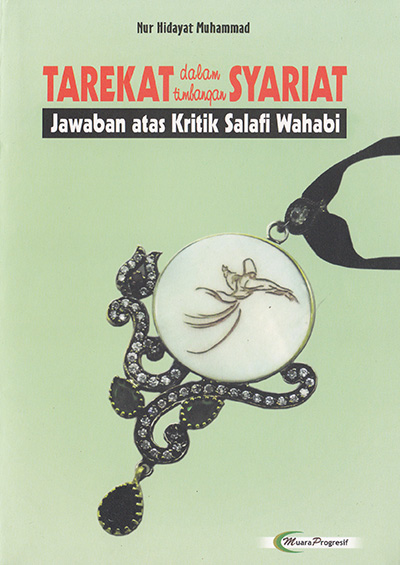
Tuduhan bahwa tarekat (tharīqah) tidak pernah dilakukan oleh Rasūlullāh s.a.w. dan para sahabatnya dan sesat adalah klaim sepihak dan cenderung tidak ilmiah. Kami tak membantah jika tarekat seperti Qādiriyyah, Naqsyābandiyyah, Syādziliyyah dan lain-lain memang tidak ada di zaman Rasūlullāh. Tarekat hanyalah sebuah insititusi pendidikan tazkiyat-un-nafs atau madrasah yang bergerak di bidang suluk ruhani, terdiri dari guru pembimbing dan murid. Lalu apa dipermasalahkan? Bukankah yang demikian tidak bisa dianggap bid‘ah yang sesat. Bahkan, meminjam istilah Imām asy-Syāthibī dalam al-I‘tishām hal pembentukan tarekat termasuk dari kaidah mashalih mursalah, karena di dalamnya terdapat bimbingan dzikir (talqin dzikir) yang merupakan pelajaran dari Rasūlullāh s.a.w., meski saat itu belum ada nama atau label.
Oleh karena itu, stigma bahwa institusi tarekat, sebagaimana tafsir di atas, adalah bid‘ah sesat lantaran tidak ada di era Rasūlullāh s.a.w., kami balik bertanya: “Apakah sulūk tarekat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan membersihkan diri dari akhlāq tercela adalah bid‘ah?”
Jika mereka mengklaim bahwa mengkodifikasikan ilmu nahwu dan sharaf, membuat pondok pesantren atau madrasah dan lain-lain adalah bagian dari mashalih mursalah, maka kenapa tarekat shūfī tidak bisa dimasukkan di dalamnya sehingga tidak ada lagi vonis bid‘ah? Ini sesuatu yang aneh!
Imām Ibnu Taimiyyah berkata: “Tatkala orang yang berfikir dalil bingung tentang hukum suatu masalah, apakah halal atau haram, maka ia bisa mempertimbangkan mafsadah dan maslahahnya”. (431) Nah kenapa kita tidak berfikir, bahwa keberadaan tarekat juga ada maslahahnya, yakni menjadi sentra pembersihan jiwa dengan bimbingan mursyid?
Bukankah juga Rasūlullāh s.a.w. pernah bersabda:
مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا.
“Siapa membuat perilaku baik (sunnah) dalam Islam, maka dia mendapatkan pahala dari itu dan pahala orang-orang yang melakukannya dengan tanpa ada pengurangan sama sakali.” (HR. Muslim).
Baiklah, mari kita kaji secara ilmiah tentang bid‘ah atau tidaknya eksisitensi tarekat dalam percaturan Islam. Yang harapannya tidak ada lagi justifikasi menyeramkan seperti di atas.
Ketetapan hukum haram dan sesat melalui alasan bahwa salaf tidak melakukannya (selanjutnya disebut dalīl tarkī) adalah tidak benar, karena:
وَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا.
“Apa yang dibawa oleh Rasūl kepada kalian, maka ambillah, dan apa yang dilarang atas diri kalian maka hentikanlah.” (QS. al-Ḥasyr: 7)
Lihatlah, Allah menyebutkan kata Nahā (Rasūlullāh melarang) dan bukan Taraka (Rasūlullāh meninggalkan). Artinya yang ditinggalkan beliau tidak bisa langsung diklaim haram.
مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوْهُ وَ مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.
“Apa yang aku larang atas kalian, maka jauhilah. Dan apa yang aku perintahkan, maka lakukanlah semampu kalian.” (HR. Muslim dan Ibnu Mājah).
Rasūlullāh s.a.w. menggunakan kata Nahaitu (aku melarang) dan bukan Taraktu (aku meninggalkan).
Jadi, yang semestinya dipermasalahkan bukan apakah mereka bertarekat atau tidak, tapi cara dzikir yang diajarkan dalam tarekat shufi apakah dari Rasūlullāh s.a.w., atau tidak, kontra dengan kaidah agama atau tidak. Itulah debat ilmiah dan logis untuk ditanyakan. Sebab, tharīqah hanyalah sebuah nama yang tidak mempengaruhi sesuatu. Seperti halnya nama madzhab Ḥanafī dan madzhab-madzhab lain. Apakah dulu para sahabat Rasūlullāh s.a.w. juga bermadzhab Ḥanafī, bermadzhab Ḥanbalī dan lain-lain? Tentu tidak. Tetapi, semestinya yang ditanyakan apakah madzhab mereka keluar dari jalur yang diajarkan Rasūlullāh s.a.w. dan sahabatnya atau tidak.
Dr. ‘Alī Jum‘ah menuturkan, tarekat adalah sebuah organisasi pendidikan ruhani (madrasah) sebagai penyempurnaan dari maksud tujuan pembersihan jiwa. Dan Syaikh adalah yang bertindak sebagai ustadz yang akan mendidik murid dan para pencari ridha Allah.
Tarekat shūfiyyah memang harus berpondasi kepada beberapa hal. Di antaranya adalah harus berpedoman dengan al-Qur’ān dan as-Sunnah dan setiap yang menyelisih keduanya bukanlah tarekat shūfī. Tarekat bukanlah organisasi yang berdiri lepas dari pengajaran syarī‘at. Bahkan dalam tarekat pendidikan syarī‘at itulah intisari ajarannya.” (442).
Sedangkan bantahan sebagian kelompok bahwa agama ini sudah sempurna, tidak perlu ditambah-tambahi, termasuk dengan membuat organisasi tarekat, dan kemudian berdalih dengan firman Allah:
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا
“Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.”. (QS. al-Mā’idah: 3)
Maka sebagaimana yang dikatakan ‘ulamā’, bahwa yang telah disempurnakan Allah adalah kaidah dan dasar-dasar agama Islam, dan bukan juz’iyyah (masalah-masalah)-nya. Dan dengan sedikit berfikir mereka akan memahami ini.
Lebih lucu lagi, mereka mengatakan bahwa qiyās tidak boleh digunakan dalam ibadah (ta‘abbudi). Maka saran kami, mereka perlu mengkaji kembali ilmu ushūl fiqh dengan lebih matang dan mendalam. Karena sungguh di sana mereka akan disuguhkan banyak fakta ilmiah yang tidak mereka pahami sebelumnya.
Sedangkan terkait dengan ucapan Ibnu Katsīr:
وَ أَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ فَيَقُوْلُوْنَ فِيْ كُلِّ فِعْلٍ وَ قَوْلٍ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ الصَّحَابَة: هُوَ بِدْعَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُوْنَا إِلَيْهِ.
“Adapun ahl-us-sunnah wal-jamā‘ah berkata dalam setiap pekerjaan dan ucapan yang tidak ada dari sahabat adalah bid‘ah, lantaran andai itu baik tentu mereka akan mendahului kita melakukannya.”
Maka jawabnya adalah: Pertama, ucapan tersebut bukan hujjah dalam menetapkan sesat dan tidaknya sebuah perilaku lantaran bukan sabda Rasūlullāh s.a.w. Kedua, ucapan tersebut dimaksudkan bid‘ah yang tidak ada dasarnya dalam agama. Membuat organisasi tarekat bertujuan sebagai wahana menggapai ridha Allah dan sebagai riyadhah pembersihan jiwa dari sifat-sifat tercela. Sama halnya dengan mendirikan madrasah atau pesantren yang tidak ada di zaman sahabat Rasūlullāh s.a.w.
Lalu kenapa di zaman sahabat tidak ada tarekat? Jawabannya adalah karena di zaman tersebut (salaf) masih steril dari berbagai virus syahwat duniawi, kemewahan hidup penguasa dan kecenderungan orientasi hidup masyarakat pada materialisme yang berimbas pada degradasi moral sebagaimana yang mulai menjamur di era setelahnya.
Sayyid Ibrāhīm ad-Dasūqī pernah berbicara tentang wajibnya mengikuti tarekat di zaman sekarang, beliau berkata: “Andai para ahli fiqh melakukan ibadah dan perintah-perintah syar‘iyyah tanpa ada penyakit (hati) serta sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, maka mereka tidak akan membutuhkan guru pembimbing (mursyid). Namun, karena mereka melakukan ibadah selalu dibarengi dengan penyakit-penyakit hati, maka mereka butuh seorang dokter yang mampu mengobatinya agar dia sembuh dari penyakit yang dideritanya tersebut. Karena itu, para tabi‘in tidak membutuhkan khalwat (menyendiri berdzikir kepada Allah) dan riyādhah (pelatihan jiwa untuk membersihkan sifat-sifat tercela) sebagaimana yang dilakukan oleh para murid dalam tarekat. Dan, juga tidak pernah ada keterangan bahwa para tabi‘in mengkodifikasikan (tadwīn) kitab-kitab tentang penawar penyakit jiwa, karena penyakit-penyakit tersebut bisa dibilang tidak ada di masa itu (sebagai qurun terbaik setelah qurun Rasūlullāh dan sahabat). Atau ada, namun bisa dibilang relatif sedikit sekali, sehingga dianggap seperti tidak ada. Perhatian besar mereka adalah menghimpun hadits-hadits syari‘at dan dicocokkan dengan al-Qur’ān. Hal ini dianggap lebih penting daripada mengobati penyakit jiwa, karena minimnya penyakit-penyakit jiwa di masa itu.
Dan di antara anugerah Allah kepada seorang hamba adalah jika batinnya selamat dari berbagai penyakit batin, seperti para imam mujtahid dan pengikut-pengikutnya yang memang tidak membutuhkan guru mursyid dalam bertarekat, lantaran mereka telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Dan itulah hakikat dari seorang shūfī. Syaikh ‘Abdullāh al-Ḥararī juga mengatakan bahwa tarekat shūfī termasuk bid‘ah ḥasanah. (453).
Imām al-Qusyairī berkata: “Awal kali muncul penyakit-penyakit batin di hati manusia adalah pada kisaran tahun (Hijriyyah) 300-an. Hal ini terkait mafhūm sabda Rasūlullāh s.a.w.:
خَيْرُكُمْ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ.
“Qurun yang terbaik adalah qurunku, kemudian qurun berikutnya dan kemudian qurun berikutnya.” (HR. Bukhārī Muslim).
Sayyidī ‘Alī al-Khawwāsh berkata: “Qurun awal adalah qurun kesempurnaan iman, qurun kedua adalah kesempurnaan ilmu, qurun ketiga adalah kesempurnaan amal dan kemudian kondisi zaman berubah.”
Adapun kecaman Ibnu Taimiyyah dan Salafī Wahhābī terhadap masyayikh tarekat Rifā‘iyyah yang didirikan oleh Syaikh Aḥmad ar-Rifā‘ī, maka semua telah dijawab oleh Syaikh ‘Abdullāh al-Ḥararī dalam al-Maqālāt-us-Sunniyyah. Dalam jawabannya dikatakan, bahwa Syaikh Aḥmad ar-Rifā‘ī yang dicela adalah seorang yang tak layak dicela, karena beliau sangat dipuji keunggulan ilmunya oleh Imām ar-Rāfi‘ī asy-Syāfi‘ī dan bahkan diakui kewaliannya oleh al-Ḥāfizh Jalāl-ud-Dīn as-Suyūthī dan al-Ḥāfizh Ibnu Mulaqqīn. (464).