Teknik Melakukan Rabithah (Merabit) & sebagai Penghalau Iblis – Unsur-unsur Tarekat – Sabil-us-Salikin
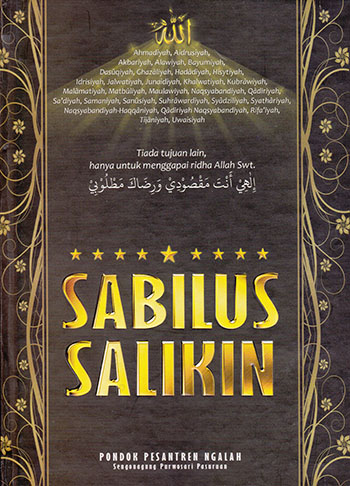
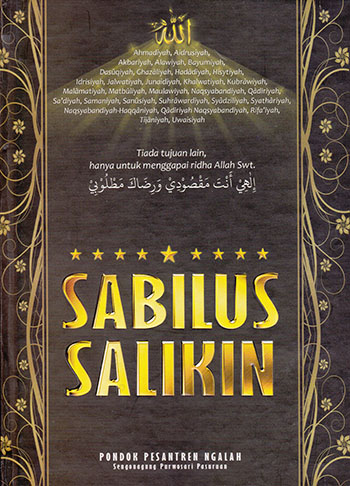
Di dalam shalat, ketika melakukan tasyahhud, kita diperintahkan mengucapkan salam kepada Nabi s.a.w., Assalāmu ‘alaika ayyuh-an-nabiyyu wa raḥmatullāhi wa barakātuh (salam dan Rahmat serta barakah Allāh untukmu wahai Nabi s.a.w.). Perintah ini harus dilakukan secara lahir dan bathin, secara lahir dengan mengucapkan salam itu sendiri, sedangkan secara bathin adalah menghubungkan rohani kita dengan rohani Rasūl s.a.w., agar kita bisa bersama dengan Beliau s.a.w.
Bersama dengan Rasūl s.a.w. sekaligus mengandung makna bersama dengan Allāh s.w.t. karena Rasūl s.a.w. tidak pernah berpisah sedetik-pun dari-Nya. Kenyataan bahwa di dalam rohani Beliau s.a.w. tersimpan Nūr Allāh s.w.t., dan bahwa Beliau s.a.w. sebagaimana ditegaskan oleh ‘Ā’isyah r.a. selalu berdzikir kepada Allāh s.w.t.:
حدثنا هارون بن معروف حدثنا اسحاق الأزرق حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة : عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم كَانَ يَذْكُرُ اللهَ فِيْ كُلِّ أَحْيَانِهِ، (مسند أبى يعلى، ج 8، ص: 355)
Hārūn bin Ma‘rūf menceritakan kepada kami, Isḥāq al-Azrāq menceritakan kepada kami, Zakiriyyā bin Abī Zā’idah dari Khālid bin Salamah, dari al-Bahīy, dari ‘Urwah: dari ‘Ā’isyah r.a. bahwa Nabi s.a.w. senantiasa berdzikir kepada Allah pada setiap waktu.” (Musnad Abī Ya‘lā, juz 8, halaman: 355).
Dalam kaitan inilah mengapa sebagian Kaum ‘Ārifīn yaitu orang-orang yang sudah mengenal Allāh s.w.t. secara taḥqīq berkata: “Bersamalah engkau selalu dengan Allāh, dan jika engkau belum bisa, maka bersamalah engkau selalu dengan orang yang sudah bersama dengan Allāh.” (Tanwīr-ul-Qulūb, halaman: 512).
Namun begitu, karena kita tidak mengenal Rasūl s.a.w. secara jasmani, maka yang dapat kita lakukan adalah menghubungkan rohani kita dengan rohani ‘ulamā’ yang kita kenal secara jasmani, yaitu ‘ulamā’ yang benar-benar berkapasitas sebagai Waratsat-ul-Anbiyā’ (Ahli Waris Para Nabi), yang kepada mereka beliau mewariskan isi rohani beliau dengan idzin Allāh s.w.t.
Hamba-hamba Allāh s.w.t. seperti itu dalam al-Qur’ān disebut antara lain dengan ash-Shādiqūn, dan Allāh memerintahkan kita agar selalu bersama dengan mereka (secara jasmani dan rohani).
يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ ﴿١١٩﴾
“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allāh s.w.t. dan hendaklah kamu selalu bersama orang-orang yang benar.” (at-Taubah [9]: 119).
Bahkan, bersama atau berjamaah secara rohani jauh lebih mungkin direalisasikan daripada berjamā‘ah secara jasmani, sebab tidak mungkin kita dapat berjamā‘ah dengan mereka secara jasmani dalam semua keadaan. Maka ash-Shādiqūn yaitu orang-orang yang benar, dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang benar dalam keimanan mereka kepada Allāh, sehingga sebutan lain yang dikemukakan al-Qur’ān untuk mereka adalah al-Mu’minūna Ḥaqqan, orang-orang mu’min sejati (hak), yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allāh s.w.t., hati mereka bergetar dan apabila dibacakan ayat-ayat Allāh s.w.t. kepada mereka keimanan mereka semakin bertambah, dan hanya kepada Allāh s.w.t. mereka bertawakkal, menegakkan shalat dan menginfakkan sebagian harta yang dikaruniakan kepada mereka.
الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣﴾
“(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS. al-Anfāl [8]: 3).
Bukan orang-orang yang beriman tetapi di dalam hatinya tumbuh subur sifat-sifat nifāq (munafik) yang diantara ciri-ciri utama mereka adalah bahwa mereka tidak berdzikir kepada Allāh kecuali sedikit.
إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ يُخَادِعُوْنَ اللهَ وَ هُوَ خَادِعُهُمْ وَ إِذَا قَامُوْا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوْا كُسَالَى يُرَآؤُوْنَ النَّاسَ وَ لَا يَذْكُرُوْنَ اللهَ إِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٤٢﴾
“Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allāh, dan Allāh akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riyā’ (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allāh kecuali sedikit sekali.” (al-Nisā’ [4]: 142).
Mereka tiada lain adalah wali-wali Allāh yang oleh Nabi sebagaimana disinggung sebelumnya disebut dengan Mafātīḥ-udz-Dzikr ‘kunci-kunci dzikir’, dan yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan kaum sufi, dan oleh Ibn Taimiyah disebut sebagai golongan yang paling baik setelah Nabi, (Majmū‘-ul-Fatāwā, juz 11, halaman: 17). Memandang mereka melahirkan dzikir kata Nabi dalam riwayat Imām al-Thabrānī ketika menggambarkan keberadaan mereka, (al-Mu‘jam-ul-Kabīr, juz 10, halaman: 205). Memandang mereka, terutama yang dilakukan secara rohani, mewujudkan apa yang dimaksud dengan Rābithah di sini.
Melakukan Rābithah pada dasarnya dimaksudkan sebagai realisasi atas perintah berjamā‘ah yang dalam nash diungkapkan dengan berbagai redaksi. Imām al-Bukhārī dalam at-Tārīkh-ul-Kabīr-nya mengutip sebuah Hadits Nabi s.a.w., Kalian harus berjamā‘ah, (at-Tarikh-ul-Kabīr, juz 8, halaman: 447). sementara Imām Aḥmad dalam Musnad-nya meriwayatkan sebuah Hadits bahwa Nabi s.a.w. bersabda:
عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، و إِيَّاكُمْ وَ الفُرْقَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ. (أخرجه الترمذي)
“Wahai manusia, kalian harus berjamā‘ah dan hindarilah bercerai-berai.” (Jāmi’u Ushūli fī Aḥādits-ir-Rasūl juz 6, halaman: 669).
Imām-ut-Tirmidzī dan an-Nasā’ī meriwayatkan dari Ibn ‘Umar bahwa ‘Umar berkhutbah menyampaikan sabda-sabda Nabi yang di dalamnya antara lain beliau bersabda: “Kalian harus berjamā‘ah dan hindarilah bercerai (dari jamā‘ah), karena syaithan bersama orang yang sendirian.”(Sunan-ut-Tirmidzī, juz 4, halaman: 465, as-Sunan-ul-Kubrā, juz 5, halaman: 388).
Dalam riwayat Imām al-Baihāqī Hadits tersebut diungkapkan dengan redaksi:
أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظِ ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوْبَ ثَنَا عَبَّاسُ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّوْرِيْ ثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيْ الْعُمْيَاءِ عَنِ السَّائِبِ بْنِ مَهْجَانِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ أَهْلِ إِيْلِيَاءِ وَ كَانَ قَدْ أَدْرَكَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ فِيْ حَدِيْثٍ ذَكَرَهُ قَالَ: لَمَّا دَخَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الشَّامَ حَمِدَ اللهُ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ وَعَظَ وَ ذَكَرَ وَ أَمَرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَامَ فِيْنَا خَطِيْبًا كَقِيَامِيْ فِيْكُمْ فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ وَ صِلَةِ الرَّحْمِ وَ صِلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ وَ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ يَدَ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَ إِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ
“Kalian harus berjamā‘ah, karena tangan Allāh ada di atas jamā‘ah dan syaithan bersama orang yang sendirian.” (Syu‘ab-ul-Īmān, juz 7, halaman: 488).
Hadits-Hadits di atas semuanya mengisyaratkan pentingnya berjamā‘ah sebagai ajaran agama yang sangat fundamental, baik dalam urusan ibadah maupun dalam urusan mu‘āmalah, baik secara jasmani maupun secara rohani.
Dalam shalat kita dianjurkan berjamā‘ah; bahkan setengah ‘ulamā’ menghukumi shalat berjamā‘ah itu wajib berdasarkan hadits-hadits Nabi yang antara lain mengancam akan membakar rumah-rumah penduduk yang dekat dengan masjid tetapi penghuninya tidak mau shalat berjamā‘ah, (Shaḥīḥu Muslim, juz 1, halaman: 451; Syarḥ-un-Nawawī ‘alā Shaḥīḥu Muslim, juz 5, halaman: 153).
Tujuan paling pokok dari berjamā‘ah adalah melindungi diri dari gangguan Iblīs yang selalu mencari celah untuk memalingkan manusia dari kebenaran menuju kesesatan, dan mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan.
Kalau yang dimaksud berjamā‘ah hanya semata-mata berjamā‘ah secara jasmani, maka efektivitas perlindungan diri tidak akan tercapai secara maksimal, sebab yang menjadi sarang Iblīs adalah qalbu manusia, sehingga qalbu pun harus dikondisikan agar juga berjamā‘ah, yaitu dengan melakukan rābithah (merabit mursyid).
Rābithah yang dilakukan secara berkesinambungan melahirkan berbagai fenomena positif sebagai karunia Tuhan yang jenisnya bergantung kepada kehendak-Nya, antara lain yang paling utama adalah mengalami atau merasakan kehadiran Tuhan. Apa yang dialami Nabi Yūsuf a.s. ketika nyaris terjerumus dalam kemesuman merupakan salah satu indikasi atas kenyataan ini.
Di dalam al-Qur’ān diceritakan bahwa Yūsuf sudah nyaris melakukan perbuatan mesum bersama Zulaikha andai kata ia tidak melihat dan mengalami bukti Tuhannya. Ibn ‘Abbās r.a. menjelaskan, yang dikutip oleh Imām ath-Thabarī dalam Tafsīr-nya, bahwa ungkapan andai kata Yūsuf tidak melihat bukti Tuhannya dalam surah Yūsuf ayat ke-24 tersebut adalah andaikata ia tidak melihat bayangan bentuk wajah ayahnya, (Tafsīr-ut-Thabarī, juz 16, halaman: 34, nomor 19013). Dari penjelasan Ibn ‘Abbās ini semakin jelas bahwa Yūsuf mengalami rābithah secara otomatis dengan idzin Allāh s.w.t.:
وَ غَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ، وَ ذَهَبَ لِيَحِلَّ سَرَاوِيْلَهُ، فَإِذَا هُوَ بِصُوْرَةِ يَعْقُوْبَ قَائِمًا فِي الْبَيْتِ، (تفسير الطبري، ج 16، ص: 34، رقم 19013)
[“Zulaikha mengunci pintu-pintu kamarnya, lalu mulai (mencoba) melepaskan celananya (Yūsuf). Sekonyong-konyong terlihatlah sosok Ya‘qūb berdiri di dalam kamar itu.” (Tafsīr-uth-Thabarī, Juz 16, halaman 34, no: 19013). – SH.]
Dalam hal berdzikir kepada Allāh khususnya, melakukan rābithah merupakan keharusan, karena jalan yang ditempuh dalam berdzikir adalah jalan rohani yang sangat halus dan penuh dengan ranjau-ranjau Iblīs yang selalu berusaha memalingkannya dari jalan Allāh untuk kemudian menjerumuskannya ke dalam kesesatan.
Dalam kaitan inilah Imām an-Nawawī al-Jawī menegaskan dalam kitabnya Nihāyat-uz-Zain, Orang yang berdzikir wajib mengikuti salah seorang Imām dari Imām-imām tashawwuf, (Nihāyat-uz-Zain (Bairut: Dār-ul-Fikr, t.t. halaman: 7).