Surat-Surat Sang Sufi | Surat Pertama (4/7)
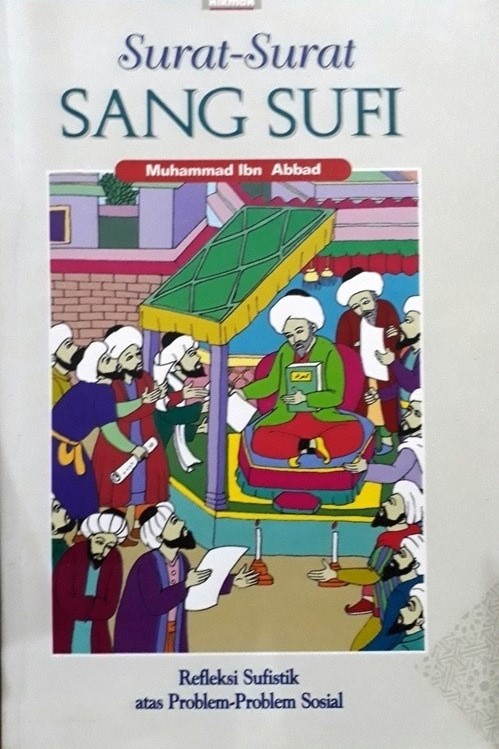
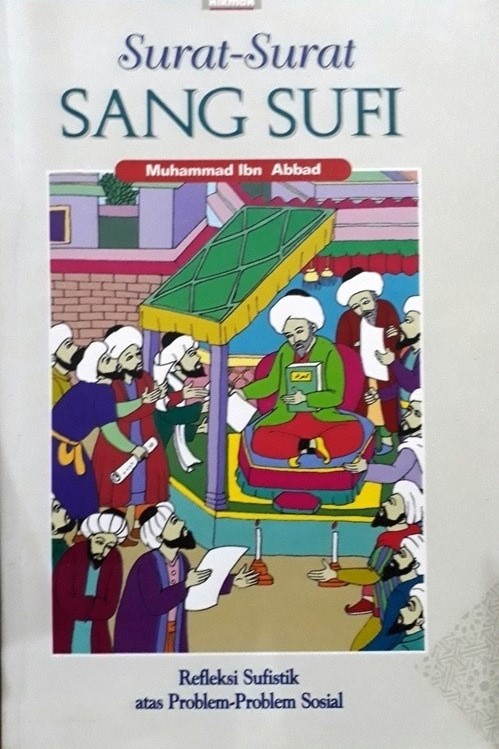
(lanjutan)
Janji pengukuhan dari Allah sungguh masuk akal. Tapi bagaimana melihat nuansa-nuansa itu? Selain itu, dalam pengalaman Muhammad dan Jibril ada sesuatu yang menunjukkan kebergantungan penuh mereka kepada Tuhan mereka yang Mahakuasa dan Mahatinggi. Tingkatan (maqam) ini-Allah mengangkat Nabi-Nya ke tingkatan ini-dalam sebagian besar keadaannya, adalah tingkatan yang tinggi dan mulia. Hal ini lebih sempurna ketimbang memperlihatkan ketidakbergantungan. Kefakiran lebih tepat bagi kondisi penghambaan ketimbang ketidakbergantungan; sebab seperti dilukiskan oleh para pemimpin sufi, ketidakbergantungan adalah salah satu hak istimewa Allah. Masalahnya adalah bahwa kedua makhluk terkasih itu (Muhammad dan Jibril-penerj.) bisa memahami, lewat penyingkapan sifat ketidakbergantungan dan pengalaman tentang kebesaran dan keagungannya dalam keadaan ini. Bahwa apa yang dikehendaki Allah dari mereka pada saat itu adalah mengakui kefakiran dan menyadari kerendahan dan kelemahan. Itulah sebabnya dia berurusan dan berbicara dengan mereka seperti dilakukan-Nya.
Lebih jauh Abu Thalib (Al-Makki-ed.) mengatakan bahwa Allah Swt. tidaklah dipaksa oleh aturan-aturan apa pun, dan tidak ada kecaman-kecaman manusia berlaku atas-Nya. Ini mengacu kepada aspek lain dari transendensi esensi Ilahi atas batasan-batasan kemakhlukan. Dia bertindak dan memiliki keagungan sempurna secara mutlak. Tak ada ketentuan apapun yang mengikat-Nya, sebab Dialah yang mengeluarkan berbagai ketentuan. Lalu bagaimana mungkin Dia terikat oleh ketentuan atau terkena batasan, dan dengan demikian tak mampu membuktikan secara penuh kebenarannya dalam kata dan tindakan? Sebab Dialah yang menyatakan setiap orang tulus memiliki ketulusan, dan Dia-lah yang memberikan kesadaran penuh tentang Kebenaran kepada setiap orang yang memiliki kebenaran. Setiap perkataan-Nya adalah Kebenaran itu sendiri, Kebenaran Mistik yang mengartikulasiannya melampaui sekadar ungkapan lahiriah. Karena itu, karena maknanya tersembunyi dari kita dan maksudnya tak bisa dipahami, maka Allah Swt.-kalau begitu-pasti bukan Tuhan. Ini meruntuhkan keberatan-keberatan terhadap apa yang dikatakan syaikh Abu Thalib. Allah tidak mungkin bisa dilukiskan tidak berwatak benar. Dengan demikian, yang kita dapatkan di sini hanyalah kesulitan dalam memahami gaya ungkapan-Nya.
Abu Thalib selanjutnya mengatakan: “Jika kata-kata berubah, maka Dia sendiri adalah pengganti kata-kata itu,” dan sebagainya. Ini adalah pernyataan logis dan luar biasa tentang makna keesaan Ilahi yang tak mampu dipahami secara rasional. Allah tak perlu, seperti dibayangkan sebagian orang, minta izin untuk membatalkan apa yang telah dikatakan-Nya.241
Aku tidak yakin akan kesahihan hadits yang dikutip Abu Thalib. Aku juga tak tahu ahli-ahli hadits mana yang meriwayatkannya. Akan tetapi Abu Thalib menguatkan dengan pandangannya bahwa karena hadits mutawatir tidak bertentangan dengan Kitab Allah dan Sunnah Nabi, maka ia bisa dipakai dan sahih, sekalipun ada keraguan tidak rantai-periwayatannya (sanad)-yakni, tentang integritas proses periwayatan dan orang yang meriwayatkannya. Baik Ahmad Ibn Hambal maupun ‘Abd Al-Rahman Ibn Mahdi dan lainnya tidak menyebutkan hadis ini dalam “Bab Ilmu”252
Betapapun juga, aku-Ibn Abbad-ed. berpendapat bahwa tak perlu ada bukti penguat guna menjelaskan hadits itu serta menghilangkan keraguan tentangnya. Sungguh mengherankan bahwa adalah orang yang tak mau menerima hadits ini atas dasar karena dia tak memahaminya serta yakin bahwa hadits itu tak masuk akal dan berasal dari rantai periwayatan yang tidak sahih. Sesungguhnya, keimanan dan keyakinan yang dipatrikan oleh Allah Swt. pada Muhammad dan Jibril tidak bisa diragukan lagi. Kedudukan tinggi dan kemuliaan mereka, dan diangkatnya mereka ke tempat yang amat mulia, cukuplah membuktikan hal itu.