Mursyid sebagai Pemandu Jalan – Tugas Mursyid – Unsur-unsur Tarekat – Sabil-us-Salikin (1/2)
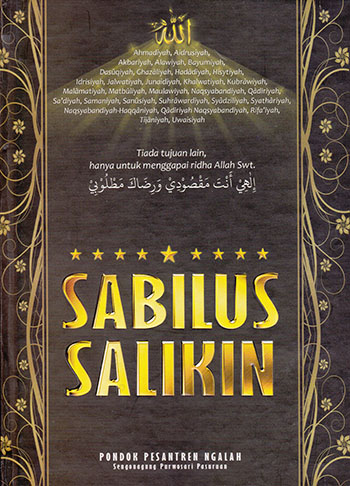
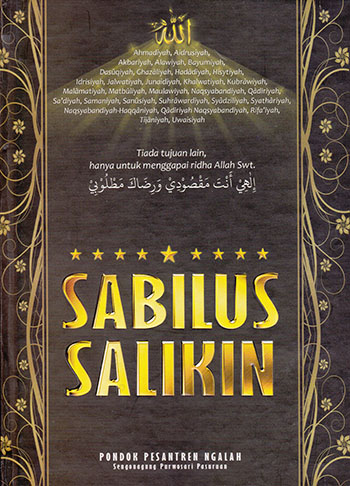
a). Mursyid sebagai Pemandu Jalan
Mursyid dalam tharīqah adalah seorang wali yang layak diikuti sebagai imam dalam perjalanan menuju Tuhan. Ia adalah wali Allāh s.w.t. yang ciri khasnya sebagaimana disebutkan di atas. Jalan menuju Tuhan bukan jalan yang mulus melainkan jalan yang berliku-liku dan penuh dengan rintangan-rintangan berupa ranjau-ranjau Iblīs sehingga diperlukan pemandu yang ‘ārif untuk bisa selamat dari semua rintangan itu. Seorang sālik, orang yang menempuh perjalanan (menuju Tuhan) atau yang biasa disebut dengan murīd, yang telah membulatkan kehendaknya untuk menempuh perjalanan (menuju Tuhan) tidak boleh tidak harus didampingi mursyid sebagai pemandu jalan yang menuntun dan sekaligus memperingatkannya apabila ada bahaya yang mengancam. Keberadaan seorang mursyid dengan fungsi ini sangat mutlak.
Barang siapa berjalan tanpa pemandu, ia memerlukan dua ratus tahun untuk perjalanan dua hari, kata Jalāluddīn Rumi dalam Matsnawī yang dikutip oleh Annemarie Schimmel (Dimensi Mistik dalam Islam, halaman:106), untuk menggambarkan betapa sulitnya perjalanan itu dan betapa pentingnya keberadaan seorang pemandu (mursyid).
Di antara syarat tarekat mu‘tabarah adalah tharīqah tersebut bersambung sampai Rasūlullāh dan diakui keberadaannya. Hal ini disebabkan karena jika seorang yang sanadnya terputus, atau tidak diberi idzin untuk mem-bai‘at para murīd tharīqah, maka bagi seorang sālik tidak boleh untuk mengambil sanad atau mempelajari tharīqah dari guru tersebut. Bahkan, lebih berbahaya lagi jika seorang sālik belajar tharīqah hanya melalui bacaan atau buku-buku tanpa melalui bai‘at dan bimbingan seorang mursyid yang telah memiliki wewenang untuk mengajarkan tharīqah tersebut. Karena jika sudah demikian, maka yang menjadi pembimbingnya adalah syaithan.
Syaikh Amīn al-Qurdhī mengatakan: “Wajib bagi orang yang menempuh tharīqah yang sempurna perjalanannya kepada Allāh dan suluknya atas kuasa seorang mursyid yang sampai pada maqām-maqām yang luhur itu, yang bersambung sampai Rasūlullāh s.a.w., juga mendapatkan idzin (wewenang) dari gurunya untuk memberi arahan dan petunjuk kepada Allāh, bukan didasarkan pada ketidaktahuan atau berdasarkan nafsu. Oleh karena itu, guru yang ‘ārif yang telah sampai (pada maqām-maqām itu) menjadi perantara bagi murīd menuju Allāh, yang menjadi pintu bagi murīd untuk masuk menuju Allāh. Barang siapa tidak mempunyai guru yang menunjukkannya, maka yang menjadi penunjuknya adalah syaithan.” (Tanwīr-ul-Qulūb, halaman: 524-525)
Posisi mursyid atau syaikh sufi menurut Ibn Taimiyah tidak ubahnya seperti imam dalam shalat dan pemandu haji (dalīl-ul-ḥajj); imam shalat diikuti oleh ma’mum, mereka shalat sesuai dengan shalatnya imam (yushallūna bi shalātihi), sedangkan pemandu haji menunjukkan kepada jamā‘ah jalan menuju baitullāh (yadullū-l-wafd ‘alā tharīq-il-bait), (Minhāju Sunnat-in-Nabawiyyah, juz 8, halaman: 38).
Dalam peristiwa Isrā’ dan Mi‘rāj (perjalanan Nabi menuju Tuhan), Nabi s.a.w. dipandu oleh Jibrīl a.s. yang berfungsi sebagai mursyid, imam atau guide, yaitu pemandu jalan yang menuntun dan membimbing beliau hingga sampai di hadirat Allāh ‘azza wa jalla.
فَقَالَ: مَا هذِهِ يَا جِبْرَائِيْلُ؟ قَالَ: سِرْ يَا مُحَمَّدْ، فَسَارَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسِيْرَ، فَإِذَا شَيْءٌ يَدْعُوْهُ مُتَنَحِّيًا عَنِ الطَّرِيْقِ يَقُوْلُ: هَلُمَّ يَا مُحَمَّدُ، قَالَ جِبْرَائِيْلُ: سِرْ يَا مُحَمَّدُ، فَسَارَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسِيْرَ، قَالَ: ثُمَّ لَقِيَهُ خَلْقٌ مِنَ الْخَلَائِقَ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَوَّلُ، وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا آخِرُ، وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَاشِرُ، فَقَالَ لَهُ جِبْرَائِيْلُ: اُرْدُدِ السَّلَامَ يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: فَرَدُّ السَّلَامَ، ثُمَّ لَقِيَهُ الثَّانِيْ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَقَالَةِ الْأَوَّلِيْنَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ، فَعُرِضَ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَ اللَّبَنُ وَ الْخَمْرُ، فَتَنَاوَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّبَنَ، فَقَالَ لَهُ جِبْرَائِيْلُ: أَصَبْتُ يَا مُحَمَّد الْفِطْرَةَ، وَ لَوْ شَرِبْتَ الْمَاءَ لَغَرَقْتَ وَ غَرَقَتْ أُمَّتُكَ، وَ لَوْ شَرِبْتَ الْخَمْرَ لَغَوَيْتَ وَ غَوَتْ أُمَّتُكَ، ثُمَّ بُعِثَ لَهُ آدَمُ فَمَنْ دُوْنَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَأَمَّهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ. ثُمَّ قَالَ لَهُ جِبْرَائِيْلُ: أَمَّا الْعَجُوْزُ الَّتِيْ رَأَيْتَ عَلَى جَانِبِ الطَّرِيْقِ، فَلَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا بِقَدْرِ مَا بَقِيَ مِنْ عَمْرِ تِلْكَ الْعَجُوْزِ، وَ أَمَّا الَّذِيْ أَرَادَ أَنْ تَمِيْلَ إِلَيْهِ، فَذَاكَ عَدُوُّ اللهِ إِبْلِيْسُ، أَرَادَ أَنْ تَمِيْلَ إِلَيْهِ، وَ أَمَّا الَّذِيْنَ سَلَّمُوْا عَلَيْكَ، فَذَاكَ إِبْرَاهِيْمَ وَ مُوْسَى وَ عِيْسَى. (تفسير الطبري ج 17، ص: 336)
Dalam Tafsīr ath-Thabarī disebutkan bahwa dalam Mi‘raj itu, Nabi s.a.w. bertemu dengan seorang tua renta di sisi jalan, dan ketika beliau bertanya siapa orang itu, Jibrīl a.s. berkata: Teruslah berjalan, wahai Muḥammad (sir yā muḥammad)! Beliau juga mendengar sebuah suara yang menyeru beliau agar menyingkir dari jalan, “Halumma yā muḥammad (ke sinilah Muḥammad)!, sebelum Nabi s.a.w. sempat menoleh Jibrīl sudah langsung memperingatkan, Teruslah berjalan, wahai Muḥammad (sir yā muḥammad)! Beberapa saat kemudian Jibrīl memberikan penjelasan. Orang tua yang engkau lihat di sisi jalan tadi menunjukkan bahwa tidak tersisa dari dunia ini kecuali sekadar sisi umur orang tua itu, sedangkan suara yang hendak memalingkanmu adalah Iblīs.” (Tafsīr-uth-Thabarī, juz 17, halaman: 336, Tafsīru Ibni Katsīr, juz 3, halaman: 6, Al-Aḥādits-ul-Mukhtarah, juz 6, halaman: 258).
Peristiwa Isrā’ dan Mi‘rāj Nabi s.a.w. memang menjadi rujukan utama para sufi, terutama yang berkenaan dengan unsur Jibrīl a.s. yang berfungsi sebagai mursyid, sang pemandu.
Keberadaan unsur Jibrīl a.s. sangat mutlak sedemikian rupa sehingga andai kata unsur ini tidak ada, maka Nabi s.a.w. akan terperangkap oleh jebakan Iblīs. Lalu bagaimana dengan umat beliau? Apakah mereka juga memerlukan unsur Jibrīl ini? Jawabannya pasti: ya, tidak boleh tidak. Posisi dan fungsi unsur Jibrīl a.s. ini justru diduduki dan dilaksanakan oleh Nabi sendiri.
Urgensi unsur Jibrīl sangat jelas terutama mengingat pernyataan Nabi s.a.w. bahwa shalat adalah mi‘rāj-nya orang mukmin, (Syarḥu Sunani Ibni Mājah, halaman: 313). Artinya, orang-orang mu’min juga dimungkinkan mengalami mi‘rāj dengan idzin dan kehendak Tuhan. Sebagai sarana mi‘rāj, dalam shalat seorang mukmin harus melibatkan unsur Jibrīl, kalau tidak, maka shalatnya akan didominasi oleh unsur syaithan, sehingga shalat itu menjadi shalat yang tanpa makna, gersang, dan jauh dari nilai-nilai khusyū‘, yang pada gilirannya tidak dapat berfungsi sebagai tanhā ‘an-il-faḥsyā’i wal-munkar mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, (Q.S. al-‘Ankabūt, 29:45).
Shalat semacam ini kata Nabi s.a.w. dalam riwayat ath-Thabranī dengan perawi-perawi shaḥīḥ (Majma‘-uz-Zawā’id, juz 2: 258), adalah shalat yang hanya akan menjauhkan pelakunya dari Allāh s.w.t. (man lam tanhāhu shalātuhu ‘an-il-faḥsyā’i wal-munkari lam yazdad minallāhi illā bu‘dan), (al-Mu‘jam-ul-Kabīr, juz 11, halaman: 54). Berbagai kasus dalam kehidupan orang-orang mu’min menjadi bukti tak terbantah atas pernyataan ini.