Mencari yang Halal – Kitab-ush-Shidq (3/3)
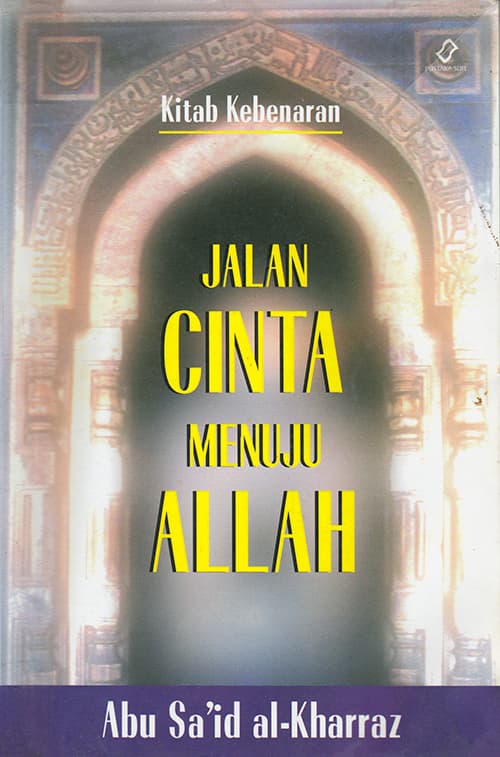
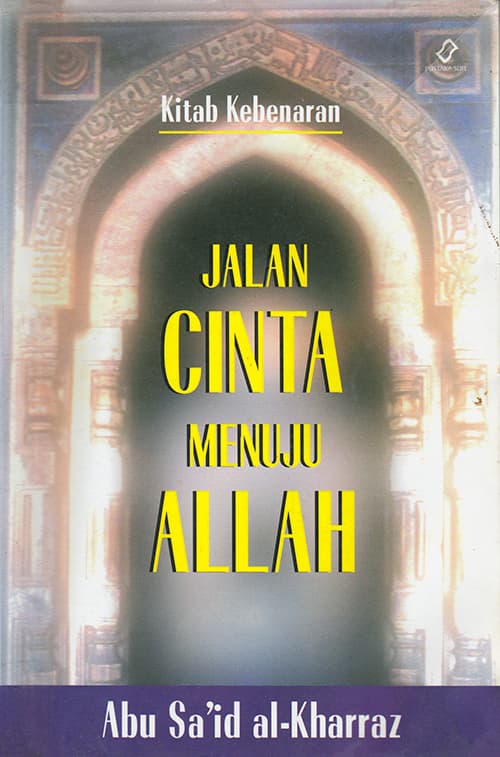
Cukup banyak orang-orang yang berperilaku seperti itu, di mana mereka adalah orang-orang yang mempunyai pikiran yang jernih dan cukup mempunyai pengetahuan yang memadai tentang contoh-contoh tauladan di masa lalu. Misalnya, kala Nabi Muḥammad s.a.w. menganjurkan para sahabatnya untuk bersedekah, maka Abū Bakar menyambut anjuran tersebut dengan membawa semua harta kekayaannya untuk disedekahkan. Dan ketika ditanya oleh Nabi Muhammad s.a.w.: “Apa yang engkau tinggalkan untuk anak-anakmu kelak?” Beliau menjawab: “Allah dan Rasūl-Nya Mahatahu. Sebab, Allah niscaya akan membalasku dengan berlipat ganda.”
Dengan demikian, bukankah Abū Bakar r.a. telah mementingkan Akhirat daripada dunia, sebab betapa kuat hatinya menjunjung perintah Allah s.w.t. dan batinnya selalu tertuju kepada-Nya, bukan kepada selain-Nya. Oleh karena itu, segala harta dunia tidak berharga baginya, karena balasan yang dijanjikan Allah s.w.t. jauh lebih berharga. Sehingga, kala beliau melihat kebesaran-Nya, maka tidak ada sedikit pun harta yang ditinggalkan, semuanya disedekahkan, seraya berujar: “Aku serahkan nasibku kepada Allah dan Rasūl-Nya.”
Sesudah itu, datang ‘Umar Ibn al-Khaththāb r.a. yang membawa setengah harta kekayaannya. Ketika ditanya oleh Nabi s.a.w.: “Apa yang engkau tinggalkan untuk anak-anakmu?” Beliau menjawab: “Separuh dari hartaku, dan Allah akan menambahkannya lagi.” Kemudian datang pula ‘Utsmān Ibn ‘Affān r.a. yang membiayai seluruh amunasi militer bagi para tentara miskin (jaysy al-usrah), di samping juga mendanai penggalian sungai yang disebut “Bi‘r al-Bayt”.
Dari contoh-contoh di atas dapat disimpulkan bahwa para sahabat telah menjadikan harta dan kekayaan mereka untuk disedekahkan di jalan Allah s.w.t., dan mereka tidak pernah sedikit pun terpengaruh oleh harta yang mereka miliki. Dan sebaliknya, mereka justru menjadikannya sebagai sarana untuk memperoleh rida Allah s.w.t.
Di samping itu, pernah juga diriwayatkan bahwasanya Rasūlullāh s.a.w. telah bersabda: “Segala yang kami, para nabi miliki tidak bisa diwariskan. Semuanya harus disedekahkan bagi kaum Muslimin.” Oleh sebab itu, tidak pernah diceritakan adanya seorang nabi yang menahan harta miliknya untuk dibelanjakan di jalan Allah s.w.t., bahkan semua harta peninggalan mereka tidak diwarisi keluarganya, namun disedekahkan di jalan Allah s.w.t. Mereka tidak pernah menyalahgunakan harta titipan Allah tersebut, dan tidak mewariskannya setelah mereka meninggal, namun dibaktikan semata kepada Allah, layaknya hidup mereka sendiri. Ini semua akan menjadi pegangan bagi orang-orang yang berpikiran sehat agar selalu menjunjung perintah Allah s.w.t.
Oleh karena itu, marilah kita ikuti akhlāq agung para sahabat nabi. Abū Bakar r.a., misalnya, adalah salah satu pilar utama Islam sesudah wafatnya Nabi Muḥammad s.a.w., menjadi anutan dan tauladan serta memegang kekuasaan pemerintahan. Bahkan, kala itu, dunia dengan segala kemewahannya datang menghinakan diri di hadapannya, namun beliau tidak pernah sekali pun menyombongkan diri dan bersikap takabbur. Justru dalam kesehariannya beliau hanya mengenakan pakaian yang banyak tambalan, sehingga digelari “Bapak orang berbaju robek.”
Kemudian, hayati pula akhlāq ‘Umar Ibn al-Khaththāb r.a. yang menggantikan Abū Bakar r.a. Beliau dikelilingi kemewahan dunia dari seluruh pelosok negeri, namun makanan beliau tetap saja roti kering dan minyak biasa, dan pada pakaian yang dikenakannya pun terdapat seribu tampalan dan setengahnya terbuat dari kain kasar, pada hal kala ini, negara-negara Romawi dan Persia telah ditaklukkan oleh pemerintahan Islam berikut harta kekayaannya.
Setelah itu, pemerintahan Islam berada dalam kepemimpinan ‘Utsmān Ibn ‘Affān r.a. Saat itu, keadaan beliau tidak jauh berbeda dengan dua orang pendahulunya, baik pakaian maupun sikapnya. Pernah diriwayatkan bahwa pada suatu hari beliau keluar dari kebunnya sambil memikul seikat kayu kering. Melihat hal itu, masyarakat bertanya: “Mengapa sampai sedemikian rupa menyiksa diri?” Beliau menjawab: “Aku ingin menguji diri, apakah sanggup menanggung kesulitan hidup.” Karena itu, renungkanlah sikap beliau tersebut yang tidak pernah lupa mendidik jiwa serta memaksanya dengan pekerjaan yang berat.
Di samping itu, renungkan pula akhlāq ‘Alī Ibn Abī Thālib r.a. yang menggantikan ‘Utsmān r.a. Diceritakan, beliau pernah membeli sehelai kain seharga empat dirham dan membeli baju seharga lima dirham. Setelah dicoba, ternyata lengan bajunya kepanjangan. Karena itu, beliau segera pergi ke tukang jahit dan meminjam gunting untuk memotong bagian bajunya yang kepanjangan dengan tangannya sendiri, pada hal kala itu segala kemewahan dunia berada dalam kekuasaannya.
Selain itu, perhatikan pula akhlak Zubair r.a., di mana ketika wafat, beliau meninggalkan hutang lebih dari dua ratus ribu dirham. Semua uang hasil pinjamannya tersebut disedekahkan dan diberikan kepada orang-orang yang memerlukannya. Perhatikan pula pribadi Talḥah Ibn ‘Ubaidillāh r.a., yang memberikan barang kesayangan istrinya kepada seorang pengemis.
Semua riwayat di atas menunjukkan bahwa para sahabat adalah orang-orang yang telah menepati perintah Allah s.w.t. yang terkandung dalam firman-Nya:
وَ أَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ
“Dan infaqkanlah sebagian harta yang telah Allah kuasakan kepadamu.” (al-Ḥadīd 57: 7).
Namun yang sungguh mengherankan adalah situasi yang terjadi pada zaman sekarang ini. Sebab banyak hamba-hamba Allah yang memiliki harta yang berlimpah berasal dan diperoleh dengan cara syubhat, pada hal mereka menyadari bahwa Allah s.w.t. mengetahui bagaimana harta tersebut mereka peroleh, dari mana asalnya, seberapa jauh hati mereka tertambat padanya, dan seberapa besar prioritas kepentingan yang mereka berikan padanya daripada kepada Allah s.w.t., serta lain-lain sebagainya. Semuanya ada dalam benak mereka dan dalam segala tingkah laku perbuatannya. (151)
Bahkan ada pula di antara mereka yang mengaku memiliki sifat-sifat yang mulia, seperti yang dipunyai oleh orang-orang terdahulu yang shāliḥ (as-Salaf-ush-Shāliḥ). Ia lalu berdalih dengan berbagai argumentasi untuk membenarkan kehendak nafsunya, meski pun sebenarnya menyalahi tradisi orang-orang terdahulu. Pada hal jika seorang hamba mengakui kelalaiannya terhadap Allah s.w.t., niscaya ia akan lebih selamat dari murka-Nya, dibandingkan dengan memohon kepada Allah s.w.t. untuk menonjolkan dirinya, sebagaimana yang sudah dilakukan Allah kepada orang-orang terdahulu. Dan hanya kepada Allah s.w.t. semata kita memohon taufīq dan petunjuk.