Cahaya-cahaya Hati – Biarkan Hatimu Bicara! (2/4)
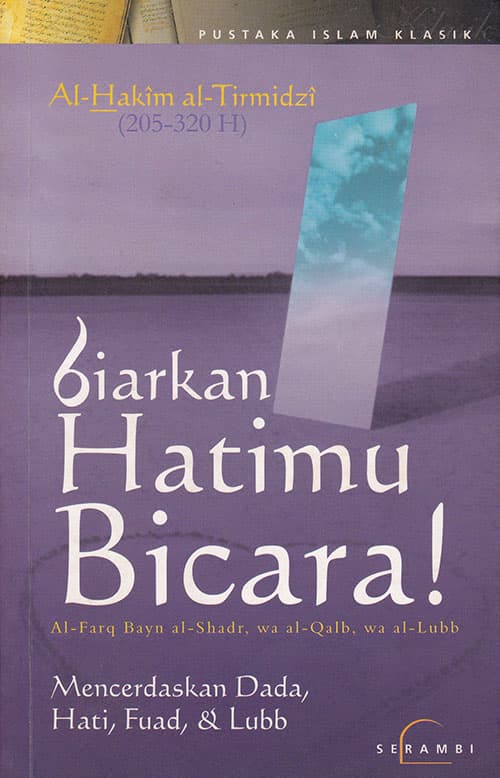
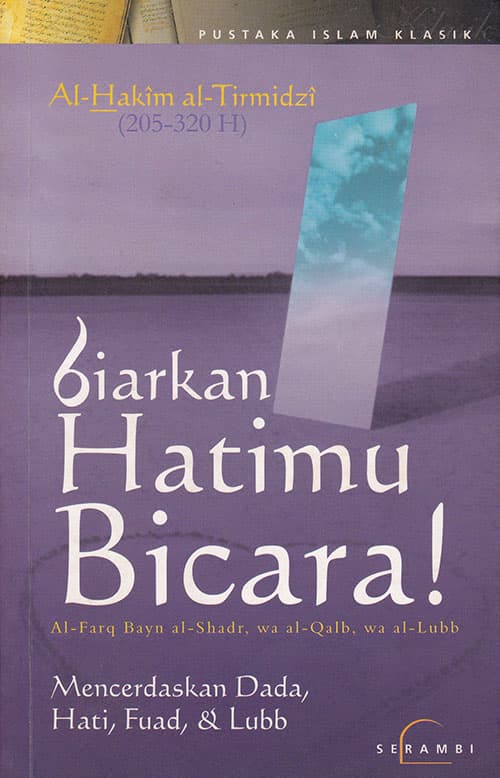
Gunung cahaya Islām berakhir pada mujāhadah yang dilakukan oleh diri kita dan ‘amal-‘amal shāliḥ.
Orang-orang Islām berada dalam tingkatan yang berbeda.
Lalu gunung cahaya īmān berpuncak pada sikap tawakkal dan pasrah.
Akar dan dasar keīmānan orang mu’min sama, tetapi tingkat penyaksian dan buah īmān yang lahir dari cahayanya berbeda-beda.
Gunung cahaya ma‘rifat berpuncak pada pengetahuan akan keabadian dan kefanā’an, serta kelemahan dan kekuasaan.
Ia juga berakhir pada penyaksian akan kebaikan dan kelembutan Allah.
Cahaya ini bisa diketahui lewat keberadaan sesuatu yang fanā’ berikut kehinaan dan kerendahannya, lewat keberadaan Dzāt Yang Maha Kekal berikut kekuasaan dan kemuliaan-Nya, serta lewat ketidakberdayaan makhlūq.
Ahli ma‘rifat dalam hal ini ibarat gunung Allah.
Ma‘rifatnya terwujud lewat melihat keagungan, kebesaran, dan kekuasaan-Nya.
Ia berada dalam genggaman Tuhan sehingga tidak bergeser dan berubah meskipun ditimpa oleh bencana dan ujian.
Sebab, Allah yang menggenggamnya lewat kekuasaan dan kasih-sayangNya.
Makna huruf ‘ain dalam kata ‘arafa seolah-olah artinya bahwa ia ‘alima wa ‘arafa (mengetahui), ‘izzah (kemuliaan), ‘azhamah (keagungan), ‘uluww (ketinggian), dan ‘ilmu (pengetahuan) Allah. Karena itu, dirinya menjadi hina ketika menyaksikan kemuliaan-Nya, menjadi kecil ketika melihat keagungan-Nya, dan menjadi rendah ketika menyaksikan ketinggian-Nya. Sementara, huruf rā’ dalam kata tersebut berarti bahwa ia ra’ā (melihat), rubūbiyyah (ketuhanan), ra’fah (belas kasih), raḥmah (kasih sayang), dan rizq (karunia) Allah. Karena itu, ia percaya dengan-Nya, berīmān kepada-Nya, bersandar kepada belas kasih-Nya, mengharap kasih-sayangNya, dan rida dengan Allah sebagai Tuhan dan Pengaturnya. Lalu huruf fā’ dalam kata tersebut berarti bahwa ia faqiha (memahami) agama Allah s.w.t., fahima (mengenali) tujuannya, faraqa (meninggalkan) segala yang fanā’, farra (lari) dari segala fitnah menuju kepada Dzāt Yang Maha Membuka dan Mengetahui, serta cahaya hatinya fanā’ (melampaui) segala sesuatu yang fanā’. Pendapat lain mengatakan bahwa ma‘na dari huruf ‘ain di atas adalah hatinya ‘ariya (terhindar dari) melihat segala sesuatu selain Tuhan. Maka, Dia memakaikan pakaian taqwā agar hati tersebut senantiasa berada di pintu-Nya. Lalu ma‘na huruf rā’ adalah hatinya ra’ā (melihat) segala sesuatu sebagaimana yang Allah ciptakan. Kemudian makna huruf fā’ adalah fa ra’ā (maka ia melihat) makhlūq yang fanā’ seolah-olah terbuang sehingga ia hanya menghadap kepada Dzāt Yang Esa yang merupakan Tuhannya. Selain itu, ia bisa berarti dirinya ‘azzat (menjadi mulia) dengan īmān, jiwanya rāḥat (merasa nyaman) dengan mengingat Allah, dan Allah fataḥa (membuka) hatinya untuk memahami ‘ilmu-‘ilmu al-Qur’ān, Pendapat lain mengatakan bahwa diri orang yang ‘ārif adalah ‘asyaqat (rindu), hatinya raqqa (lembut), dan jiwanya faqat (mulia). Serta ia juga bisa berarti: ‘abdun (seorang hamba) yang dibantu oleh Tuhan, sehingga ra’a (ia melihat) apa yang tak nampak oleh matanya, serta faraqa (meninggalkan) diri dan seluruh makhluk dengan hatinya, bangkit dengan kekuatan Tuhan bukan dengan kekuatan sendiri, dan sibuk dengan-Nya. Ia mengutamakan Tuhan atas selain-Nya. Ia mengetahui bahwa Dia lebih besar, lebih mulia, lebih agung, lebih perkasa, lebih tinggi, lebih mengetahui, lebih kaya, dan lebih lembut. Cahaya fu’ādnya tenggelam dalam menyaksikan keagungan-Nya. Ia berada dalam lautan karunia Allah yang tidak terhingga dan dalamnya tidak bisa dijangkau oleh siapa saja. Ini merupakan tanda minimal dari seorang ‘ārif (orang yang mengenal Allah). Sebab, ia tidak bisa dicapai oleh angin topan, tidak bisa disentuh oleh kilat yang menyambar, serta tidak bisa dijelaskan oleh gambaran seseorang. Ia senantiasa berputar mengitari rahasia, karunia, kelembutan, kasih sayang, kemurahan, keagungan, dan berbagai nikmat Allah. Berbagai karunia Allah terus mengalir padanya. Ia mengenal Allah, dirinya berada di sisi Allah, serta tidak mengenal akhlak dan perangai buruk yang dibenci oleh dirinya. Ucapan dan perbuatannya penuh dengan hikmah. Semua itu bersumber dari lautan karunia-Nya.
Ia diteguhkan dalam posisi tersebut oleh gunung cahaya tauḥīd yang merupakan gunung keempat. Ia berada di tempat lubb (inti). Ia merupakan gunung yang tingginya tidak terhingga dan besarnya tidak terkira. Ia sumber segala kebaikan. Ia mata air segala kebajikan serta lautan yang menjadi sumber sekaligus muara kebaikan. Tidak seorang pun yang bisa menggambarkan cahayanya lewat lisan ‘ibārah kecuali dengan taufīq dan kemudahan yang diberikan padanya.
Ketahuilah bahwa ia adalah seorang hamba yang terenggut oleh cahaya tauḥīd. Cahaya tersebut meliputinya hingga membuatnya tenggelam di lautannya. Cahaya tauḥīd tersebut bagaikan matahari. Ia lebih panjang di waktu kemarau dan lebih panas. Ia terbit menyinarnya hingga posisi hampir tergelincir. Ia merupakan posisi yang paling tinggi di musim panas. Selain itu, di langit tidak ada mendung, tidak ada yang menghalangi cahayanya, serta tidak ada hambatan yang menghalangi panas dan sinarnya dari kegelapan. Antara matahari dan hamba tersebut tidak ada penghalang sehingga ia menyinari kepalanya dan membakar lewat panasnya. Matahari tersebut mengubah kondisinya. Tidak ada naungan baginya. Kakinya tidak lagi bisa kokoh di atas tanah karena amat panas. Lalu bagaimana dengan ahli tauḥīd yang Allah letakkan dalam posisi tauḥīd dengan pertolongan dan kekuatan-Nya? Ia adalah posisi orang yang merasakan keberadaan singa lalu membunuh dan memakannya. Ia yakin akan mati tanpa ada yang bisa dimintai tolong dan perlindungan. Kondisi orang ini sama dengan kondisi ahli tauḥīd di atas. Ia hidup di tengah-tengah manusia, tetapi merasa telah mati karena begitu dekat dengan Tuhan. Sebab, ia berada di gelapnya batas pengetahuan. Ia tidak mengetahui bagaimana cara bertauḥīd. Hamba ini tersesat, tidak mengetahui caranya. Ia pasrah dalam segala urusan. Ia tidak lagi mau memilih. Sehingga, penghambaan-Nya tertawan dalam genggaman kemuliaan Allah s.w.t. Ia takut terhadap syirik yang samar dan tersembunyi. Dengan hatinya ia melihat dari Tuhan kepada seluruh makhlūq agar tidak menoleh kepada selain-Nya, kepada dirinya, kepada gerakannya, kepada peniadaan sifat Tuhan hingga ia melihat ketidakmampuannya untuk menangkap sifat Tuhan, atau kepada penyerupaan Tuhan hingga ia melihat dirinya tenggelam dalam lautan tauḥīd. Ia merupakan lautan yang besar, dalam, tak bertepi. Dalamnya tidak terhingga. Sementara hamba tadi berada dalam kondisi segar sekaligus dahaga, lapar sekaligus kenyang, telanjang sekaligus berpakaian, melihat sekaligus buta, mengetahui sekaligus bodoh, berakal sekaligus dungu, santun sekaligus pandir, kaya sekaligus miskin, mampu sekaligus lemah, sehat sekaligus sakit, hidup sekaligus mati, kekal sekaligus fanā’, jauh sekaligus dekat, serta kuat sekaligus tidak berdaya. Itulah gambaran seorang ‘ālim yang dekat dengan Tuhan, yang jiwanya mengenal Tuhan dan diliputi oleh cahaya. Ia tidak seperti orang bodoh yang berada dalam kegelapan. Seandainya aku menambahkan penjelasan tentang gambaran ahli tauḥīd, aku khawatir ia menjadi fitnah atas orang yang Allah jauhkan dari ujian ini, yang tenggelam dalam gelapnya maksiat, syahwat dan cinta dunia sehingga tidak bisa menyaksikan berbagai rahasia Tuhan. Sesungguhnya semua ini bersih dari syirik dan keraguan.
Ahli tauḥīd di atas benar-benar berada dalam ujian yang sangat berat sebagaimana telah kugambarkan sebelumnya.
Rasūlullāh s.a.w. bersabda:
“Orang yang paling berat ujiannya di dunia adalah para nabi, kemudian orang-orang sesudah mereka dan sesudah mereka.”(1331).
Rasūlullāh s.a.w. bersabda:
“Seandainya kalian mengetahui seperti yang kuketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa, banyak menangis, dan menaburkan tanah di atas kepala kalian.”
Beliau juga bersabda:
“Siapa yang menyaksikan Allah berikut kebesaran-Nya, ia berada dalam ujian yang berat.”
Beliau bersabda:
“Jika kalian melihat orang yang berada dalam ujian, mintalah keselamatan kepada Allah.”
Cobalah renungkan kondisi orang yang berada dalam ujian di mana pakaian keselamatan terlepas darinya. Bagaimana kira-kira kehidupannya? Bukankah engkau mengetahui bagaimana Rasūlullāh s.a.w. senantiasa berada dalam ujian tersebut pada setiap saat? Jika sedang salat terdengar dari diri beliau suara desis seperti periuk yang sedang mendidih. Wajah beliau juga segera berubah ketika angin berhembus dan ada peristiwa yang terjadi. Kelalaian diri kitalah yang membuat kita terhijab sehingga tidak bisa menyaksikan apa yang disaksikan oleh para ahli ma‘rifat. Lintasan hati kita sudah penuh dengan sesuatu yang lain.
Allah s.w.t. mengecam beberapa kaum dengan berkata:
“Mereka mengetahui apa yang tampak dari kehidupan dunia. Sementara, terhadap akhirat mereka lalai.” (1342).
Hamba yang tenggelam dalam cahaya tauḥīd dan berada dalam ujian hebat, ia hidup nyaman dan tenang bersama Tuhan.
Allah s.w.t. berfirman:
“Kami akan menghidupkannya dalam sebuah kehidupan yang nyaman.” (1353).
Hamba tersebut lupa kepada segala kenikmatan ketika ia sedang menikmati dzikir, ketaatan, ma‘rifat, dan cinta-Nya.
Rasūlullāh s.a.w. bersabda:
“Telah mengecap nikmatnya īmān orang yang rida Allah sebagai Tuhannya.” (1364).
Beliau juga bersabda:
“Tiga hal yang siapa di antara kalian berada di dalamnya, ia akan menemukan manisnya īmān: (1) orang yang Allah dan Rasūl-Nya lebih ia cintai daripada selain keduanya; (2) orang yang tidak ingin kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan ia darinya sebagaimana ia tidak mau dilemparkan ke neraka; (3) orang yang mencintai seseorang hanya karena Allah.” (1375).
Ini bukan tempat yang tepat untuk menjelaskannya. Hamba ini telah Allah beri minum dari lautan petunjuk sehingga ia merasakan kesegarannya. Ia seperti orang gila dalam pandangan manusia, tetapi Allah telah menghiasinya dengan pakaian terindah, telah melindunginya dari jahatnya bisikan makhlūq, dan memuliakannya atas sebagian besar manusia. Kondisi ahli tauḥīd tersebut tidak diketahui lewat penglihatan dan ukuran biasa. Allah telah mengistimewakannya dengan kekuatan yang berasal dari sisi-Nya dalam seluruh kondisinya yang semua itu tidak bisa dijangkau oleh akal dan indra.
Allah s.w.t. berfirman:
“Allah adalah pelindung orang-orang berīmān.” (1386).
“Hal itu karena Allah merupakan pelindung bagi orang-orang yang berīmān, sementara orang-orang kafir tidak mempunyai pelindung.” (1397).
“Dia yang melindungi orang-orang yang shāliḥ.” (1408).