Berakhlaq dengan Akhlaq Allah – Asma’-ul-Husna – Ibnu ‘Ajibah
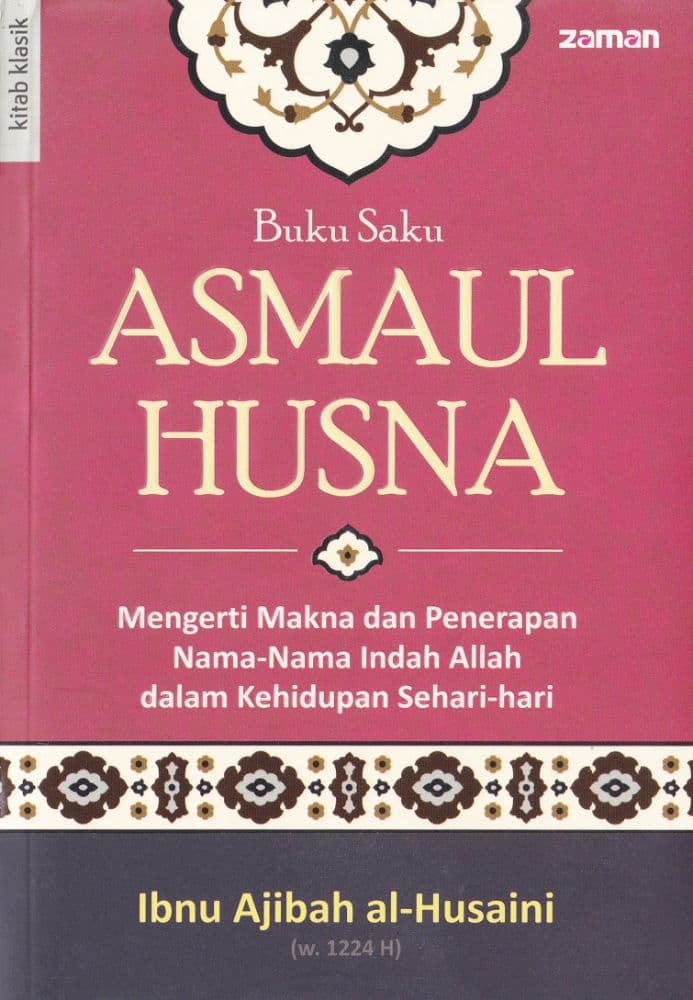
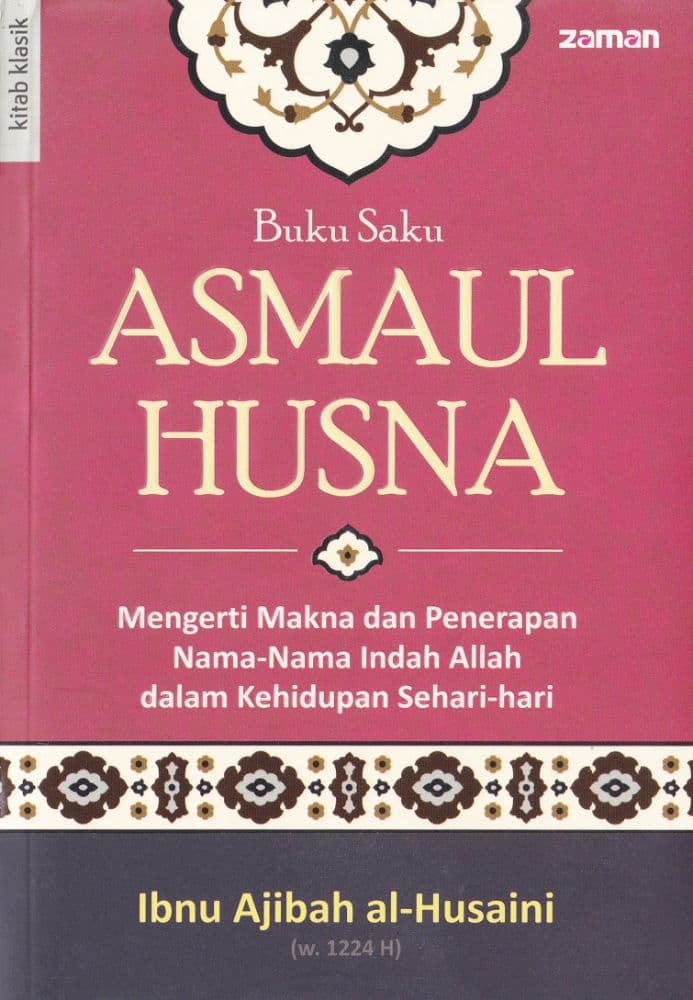
Sebuah Pengantar
Asmā’-ul–Ḥusnā bukan esensi keberadaan Tuhan, karena Dia tetap berhakikat tak terperikan. Segala Puji bagi Allah, Tuhan Yang Tak Terjangkau, jauh di atas apa yang mereka sifatkan. (QS 37: 180). Tak ada satu pun yang serupa dengan-Nya (QS 42: 11). Karena itu kita pun dilarang memikirkan esensi Sang Pencipta, “Tafakkarū fī khalqillāh wa lā tafakkarū fī dzātillāh – Renungkanlah ciptaan Allah, jangan merenungkan Dzāt-Nya,” sabda Nabi s.a.w. Dalam konteks ini, Tuhan seakan berada “jauh” dari kita. Tuhan bersifat transenden.
Asmā’-ul-Ḥusnā adalah pengenalan sifat-sifatNya dalam bahasa kemanusiaan. Tuhan memanifestasikan diri melalui asmā’ (nama-nama)- Nya. Dan nama-nama terindah itu diturunkan agar Dia dijadikan panutan dalam pengembangan potensi-potensi baik dalam diri manusia. Dengan kata lain, nama-nama terindah Allah tidak saja menjadi titik masuk untuk mengenal-Nya, tapi juga mendekatkan diri kepada-Nya, bahkan meneladani sifat-sifatNya (takhalluq bi akhlāq Allāh). Dalam konteks ini, Tuhan serasa sangat dekat dengan kita. Tuhan bersifat imanen.
Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, Tuhan serasa sangat dekat, kita menyeru Nama-nama terindah-Nya itu sesuai dengan cuaca kehidupan yang sedang kita hadapi. Kala kita tersesat, kita bermohon kepada al–Hādī, Tuhan Maha Pembimbing. Saat kita dalam kondisi tak sabar, kita memohon kepada ash–Shabūr, Tuhan Mahasabar, sumber segala kesabaran. Seseorang yang berlumuran dosa lalu sadar, dapat menghibur diri dan membangun rasa percaya diri dengan menyapa al–Ghafūr (Sang Pengampun) dan at–Tawwāb (Sang Penerima tobat), sehingga ia tetap eksis tanpa kehilangan semangat hidup. Begitulah seterusnya.
Lebih dari itu, Kanjeng Rasūl berpesan: takhalluqū bi akhlāqillāh. Lantas, bagaimana caranya kita meneladani akhlāq Allah? Atau, lebih tepatnya, mampukah kita berakhlāq dengan akhlāq Allah?.
Secara garis besar, tahapan seorang mu’min untuk meningkatkan kualitas jiwanya terdiri atas tiga tingkatan: ta‘alluq, takhalluq, dan taḥaqquq.
Pertama, ta‘alluq pada Tuhan. Yaitu berusaha mengingat dan mengikatkan kesadaran hati dan pikiran kita kepada Allah. Di mana pun seorang mu’min berada, dia tidak boleh lepas dari berfikir dan berdzikir untuk Tuhannya (QS 3: 191). Itulah manifestasi dzikrullāh dalam ma‘na sejati.
Pada tahapan ini, asmā’-ul–ḥusnā diulang-ulang diulang-ulang sebagai bacaan, doa, atau dzikir. Bahkan, kini nama-nama terindah-Nya itu telah dilantunkan dalam lagu religi dengan aneka irama musik yang indah.
Namun, memahami Asmā’-ul-Ḥusnā semestinya tak berhenti di tahap ini. Dari sekedar dzikir, lanjutkan ke tingkatan kedua, takhalluq. Takhalluq – menurut ‘ulamā’ klasik – bukan berarti meniru secara aktif nama-nama Allah. Sebab ini, di luar kemampuan manusia. Bahkan, upaya meniru nama-nama Allah sama dengan menyaingi-Nya yang dapat menimbulkan arogansi luar biasa. Takhalluq berarti menafikan sifat-sifat ego kita sendiri dan menegaskan sifat-sifat Allah yang secara potensial telah ada pada diri kita. Takhalluq adalah membuat nama-nama Tuhan berbentuk potensial dalam diri kita menjadi aktual.
Dengan kata lain, ada titik temu antara sifat-sifat kita dan sifat-sifat Tuhan. Sebab, hampir semua kebajikan yang kita kembangkan dalam diri kita, melalui amal kebajikan kita untuk orang lain, memiliki asal-usul dan kesempurnaannya pada Tuhan. Misalnya, kita harus lebih bermurah hati, ramah, berbuat baik, suka memaafkan, menebar kasih sayang, dermawan, menjaga kehormatan, adil, berpengetahuan, amanah, dan bijaksana. Akan tetapi, semua sifat ini bersumber dari Tuhan sebagai sifat-sifat kesempurnaan-Nya. Jadi, dengan menumbuhkan sifat-sifat ini dalam diri kita, kita sebenarnya menjadi semakin dekat kepada sumber sifat-sifat tersebut yang tak terbatas.
Takhalluq dicontohkan dengan sempurna oleh Nabi s.a.w., sehingga Allah menyapanya: “Sesungguhnya engkau mempunyai akhlāq agung.” (QS 68: 4). Nabi juga memproklamasikan: “Aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlāq.”
Selain Rasūl berpesan takhalluqu bi akhlāqillāh, Allah juga berfirman: Wa aḥsin kamā aḥsanallāhu ilaik (al-Qhashash: 77). Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Iḥsān dalam ayat ini seakar kata dengan ḥusnā dan ḥasanah. Artinya, kita semua memiliki “potensi ketuhanan” dalam diri kita. Kita tak mungkin diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang kita tidak mampu melaksanakannya. Nabi juga contoh paripurna dalam mewujudkan iḥsān sehingga beliau disebut sebagai uswatun ḥasanah (teladan yang indah).
Bukan saja ta‘alluq dan takhalluq, tapi buku ini menuntun kita agar melanjutkan ke tingkatan ketiga, yaitu taḥaqquq. Taḥaqquq adalah suatu kemampuan untuk mengaktualisasikan kesadaran seorang mu’min yang dirinya sudah “didominasi” sifat-sifat Tuhan sehingga tercermin dalam perilakunya yang suci dan mulia.
Maqām Taḥaqquq inilah yang didambakan oleh penulis buku kecil tapi bergizi ini. Setelah mengupas lapis-lapis ma‘na dibalik setiap asma secara bernas, kita juga diajak agar benar-benar bisa meresapi ma‘na itu serta dituntun bagaimana melahirkan sikap dan perilaku sehari-hari yang sesuai dengan makna asma tersebut.
Dan, kalau kita cermati, 99 asmā’ ini dapat dirangkai begitu indah ‘ibārat seuntai tasbīḥ. Dimulai lafazh al–jalālah (Allāh) dengan angka 0 (nol), yang biasa dianggap angka kesempurnaan, disusul dengan ar–Raḥmān (Yang Maha Pengasih), ar–Raḥīm (Yang Maha Penyayang), dan seterusnya sampai ke angka 99, ash-Shabūr (Yang Mahasabar) dan kembali lagi ke angka nol, Allah (lafzh-ul-jalālah). Simbol angka nol yang berupa lingkaran atau titik menggambarkan siklus kehidupan. Ia bagaikan a circle, bermula dan berakhir pada satu titik: innā li Allāih wa-innā ilaihi rāji‘ūn (kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada-Nya). Selamat meni‘mati.
Qamaruddin S
اللهُ
Allāh
Sebagian ‘ulamā’ mengatakan, pendapat paling benar menyebutkan bahwa lafal Allāh bukanlah kata derivate atau kata bentukan (musytaqq).
Ḥajjat-ul-Islām al-Ghazālī berkata: “Kata “lillāh” adalah nama bagi Dzāt Yang Maujūd hakiki, yang menghimpun seluruh sifat ilāhiyyah, yang disemati dengan sifat-sifat ketuhanan, dan yang tunggal dalam entitas hakiki. Semua entitas selain-Nya tidak berhak ada dengan sendirinya. Segalanya berasal dari-Nya. Seluruh nama dan benda mengikuti ketentuan ini. Semua yang disebutkan perihal bentukan kata (isytiqāq) “Allāh” atau tashrīf-nya adalah menyimpang.”
Allāh adalah nama paling agung di antara 99 nama lainnya. Ia menunjuk pada Dzāt yang menghimpun seluruh sifat ketuhanan, sesuatu yang tidak dimiliki oleh nama-nama-Nya yang lain. Ia adalah nama-Nya yang paling khusus. Tidak ada yang berhak menyandang nama ini selain-Nya, baik secara hakiki maupun kiasan.
Penulis Syarḥ al-Mawāqif mengatakan: “Allāh” adalah nama yang khusus bagi Dzāt-Nya. Tidak ada yang disebut dengan nama ini selain-Nya. Tidak ada yang menyandang nama ini selain-Nya secara mutlak. Ada yang berpendapat: “Allāh” adalah ism jāmid, kata benda yang tidak berbentuk dari kata lain, tidak memiliki akar kata. Pendapat seperti ini merupakan salah satu dari dua pendapat al-Khalīl dan Sibawayh, juga pendapat Abū Ḥanīfah, asy-Syāfi‘ī, al-Khithabī, dan al-Ghazālī. Menurut pendapat lain, kata “Allāh” adalah ism musytāq (kata derivat). “Allah”) (اللهُ) berasal dari kata “al-ilāh” (الْإلهُ) yang dibuang huruf hamzahnya karena orang ‘Arab sulit mengucapkannya. Menurut pendapat yang shaḥīḥ, kata “Allāh” pada awalnya adalah shifah (sifat), kemudian berubah menjadi ‘alam (nama) yang menghimpun sifat-sifat kesempurnaan.”
Syaikh Zarrūq berkata: “Semua nama Allah (asmā’-ul-ḥusnā) ma‘nanya boleh di-takhalluq (dimanifestasikan dalam bentuk perbuatan), kecuali “Allāh” yang hanya boleh di ta‘alluq (digali ma‘nanya). Semua asmā’-ul-ḥusnā kembali kepada Allāh. Memahami nama “Allāh” berarti mengetahui semua nama-Nya yang lain. “Allāh” menunjukkan bahwa sosok yang menyandang nama itu begitu agung, baik dalam dzāt, sifat, nama, maupun semua hal yang kembali kepada-Nya.”
Bagi para ahli ma‘rifat, mengetahui nama Allāh akan melahirkan fanā’ (melebur) bersama-Nya, pengagungan, dan pemuliaan. Sementara bagi murīdīn (yang menempuh jalan spiritual menuju-Nya), nama Allāh akan melahirkan keintiman (uns) dan kedekatan. Mendekatinya berarti menyingkirkan hawa nafsu dan mencintai Tuhan dengan hati yang fokus yang menyimpan ketauhidan murni. Itu semua memerlukan kondisi (aḥwāl), tingkatan (maqām), dan karāmat.
Al-Junayd pernah ditanya: “Bagaimana mencurahkan diri hanya kepada Allāh?” Beliau menjawab: “Tobat dapat mengikis dosa-dosa kecil. Rasa takut dapat menghilangkan rasa malas-malasan (dalam ber‘ibādah). Rasa harap dapat mendorong seseorang ber‘amal baik dan rendah hati karena rasa harap itu dekat dengan ajal dan jauh dari angan-angan.” Beliau ditanya lagi: “Bagaimana seorang hamba dapat melakukan itu semua? “Beliau menjawab: “Dengan hati fokus dan ketauḥīdan murni.”
Ber-takhalluq dengan kata “Allāh” adalah menenggelamkan sifat-sifat kehambaan ke dalam keagungan ketuhanan. Jadi, sifatmu tertutup oleh sifat-Nya sehingga wujūdmu tersembunyi di dalam wujūd-Nya dan penyaksianmu di dalam penyaksian-Nya, sebagaimana dalam sebuah syair:
Maqāmku hancur dalam semua gambaran-Nya.
Dari jauh atau dekat, aku tidak lagi bisa melihat-Nya
Aku fanā’ bersama-Nya dan dengan-Nya pula kegaiban ku menjadi tampak.
Inilah kemunculan al-Ḥaqq ketika fanā’.
Kami diliputi pengagungan dari segala arah.
Sifat-sifat al-Ḥaqq telah kembali dari mengikuti hamba.
Syaikh Abul-‘Abbās al-Mursī berkata: “Allah mempunyai hamba-hamba yang menghapus perbuatan mereka dengan perbuatan-Nya, menghapus sifat-sifat mereka dengan sifat-sifatNya, dan membawa rahasia-rahasiaNya yang tidak mampu dibawa oleh para kekasih-Nya.”
Syaikh ‘Abd-us-Salām ibn al-Masyīsy berbicara tentang cinta: “Cinta adalah pencampuran sifat dengan sifat, akhlāq dengan akhlāq, cahaya dengan cahaya, nama dengan nama, sifat dengan sifat, dan perbuatan dengan perbuatan.”
Itulah fanā’. Bergantinya sifat-sifat kehambaan dengan cahaya ketuhanan, sifat-sifat qadīm (terbaru) dengan sifat-sifat qadīm (terdahulu).
Al-Ghazālī berkata: “Dari nama ini, seorang hamba harus bisa menjadi tuhan. Artinya, hati dan himmah-nya harus ditujukan hanya kepada-Nya, tidak melihat selain-Nya, tidak berharap dan tidak takut kecuali kepada-Nya. Dari kata “Allāh” jelas bahwa Dia adalah entitas yang hakiki dan pasti. Segala sesuatu selain-Nya pasti binasa dan fanā’, juga tidak ada (bāthil) kecuali dengan-Nya. Jadi, pertama-tama, seseorang harus lihat dirinya binasa dan tidak ada, seperti ungkapan Rasūlullāh: “Perkataan yang paling benar adalah syair yang diucapkan Labīd: “‘Segala sesuatu selain Allah adalah bāthil, dan setiap keni‘matan pasti akan berakhir dan lenyap.”
Sejumlah ‘ulamā’ mengatakan, takhalluq dengan nama “Allāh” berarti berupaya melekati diri dengan semua sifat kesempurnaan sesuai kadar kemampuan spiritual hamba dan kesiapan orang-orang istimewa, seperti para nabi, majdzūbīn (para wali), dan maḥbūbīn (kekasih Allah). Hal ini bisa dilakukan dengan mujāhadah (kesungguhan spiritual), riyādhah (pelatihan diri), dan pendidikan akhlāq. Taḥaqquq dengan nama “Allāh” mengandaikan bahwa matahari seorang hamba harus terbit dari arah timur hatinya. Nama dan pamornya lenyap. Hati dan ruhnya bahkan jasadnya menjadi lembut sehingga kegelapan berganti cahaya, malam yang kelam berganti siang yang terang. Setelah itu, ia akan fanā’ dan kemudian baqā’ dengan wujūd sejati. Ia akan tersembunyi dan kemudian baqā’ dengan sifat mulia Tuhan. Tuhan menjadi pendengarnya, penglihatannya, dan tangannya. Dengan Tuhan, ia mendengar, melihat, dan menghancurkan. Dirinya tidak bisa digambarkan oleh orang lain, tidak pula dipahami oleh orang-orang ‘ārif.”