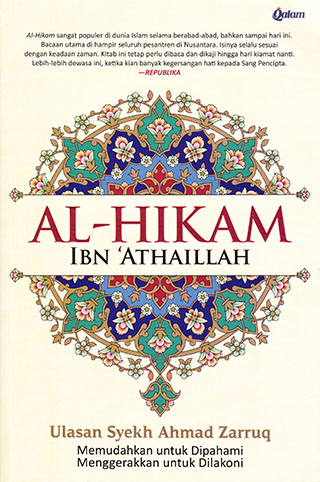29. شَتَّانَ بَيْنَ مَنْ يَسْتَدِلُّ عَلَيْهِ:……
“Jauh berbeda antara orang yang memperoleh petunjuk karena-Nya dengan orang yang mencari petunjuk kepada-Nya.”
Kedua kelompok itu berbeda jauh meskipun keduanya sama-sama mencari al-Ḥaqq dan berusaha mencapai ma‘rifat kepada-Nya. Banyak di antara manusia yang melihat dengan cahaya alam sementara kelompok lainnya melihat dengan cahaya sang pencipta alam.
29. الْمُسْتَدِلُّ بِهِ عَرَفَ الْحَقَّ لِأَهْلِهِ؛ .
“Orang yang memperoleh petunjuk karena-Nya mengetahui Tuhan dari ahlinya.”
Al-Ḥaqq melihat kepada yang niscaya ada sebelum melihat yang mungkin ada. Sesungguhnya Dia niscaya ada pada dzāt-Nya dan Dia mahalahir dalam realitas yang mungkin ada karena petunjuk akal menunjukkan kepada-Nya secara mutlak. Sesungguhnya Dia wujud yang dikenal kemudian memunculkan maujud yang sebelumnya tidak diketahui keberadaannya. Dengan demikian, Dia adalah wujud yang mutlak, bukan muqayyad (terbatas atau terikat). Kemutlakan-Nya itu meniscayakan bahwa Dia mahasempurna dari segala sisi. Sebagai konsekuensi, Dia haruslah disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Dan dari sifat-sifat kesempurnaan itu muncullah ciptaan. Seorang ‘ārif mengetahui Maujūd dalam wujud, mengetahui sifat-sifat Maujūd itu, dan juga mengetahui perbuatan-perbuatan setiap sifat itu. Maka, bisa dikatakan, ia melihat suatu perkara dari sudut pandang-Nya.
29. فَأَثْبَتَ الْأَمْرَ ……
“sehingga ia menetapkan urusan.”
Yakni urusan yang merupakan wujud setiap makhluk dan hukum-hukum yang berlaku atasnya.
29. مِنْ وُجُوْدِ أَصْلِهِ، .
“dari wujud aslinya.”
Yakni pengadaan makhluk dengan kemuliaan al-Ḥaqq dan keutamaan-Nya, dan penampakan mereka di atas jejak dan pengaruh sifat serta perbuatan-Nya. Ini merupakan tarekat orang-orang yang mencari dan mendekati petunjuk. Sekelompok orang mengingkarinya, tetapi pengingkaran mereka tidak disertai dengan penjelasan.
Sekelompok orang mengatakan: “Ma‘rifat pada awalnya hanya seperti tawanan perempuan yang statusnya semakin tinggi sehingga menjadi perempuan merdeka.” Perubahan status itu mempengaruhi penglihatan atau pandangan orang lain kepadanya. Inilah yang dipahami kebanyakan manusia. Tentang hal inilah Ibnu ‘Athā’illāh memperingatkan dalam….., yang akan dijelaskan kemudian (dalam) Bagian Ketiga, Allah tajallī kepada sebagian hamba-Nya dengan hakikat sehingga seorang hamba melihat-Nya di medan a‘yān (indriawi) ketika ia tidak merasakan dengan dalil untuk merendah dan tidak memahami maknanya untuk meninggi (taraqqī) sebagaimana dikatakan anak kecil itu kepada pamannya, padahal ia baru berumur tiga tahun. Anak kecil itu berkata: “Wahai anakku, sungguh sirr-ku telah menyibukkanku. Tidakkah kautahu, barang siapa yang tajallī untuk hatinya maka ia bersujud kepadanya.” Pamannya bertanya: “Sampai kapan?” ia menjawab: “Sampai abadi.”
Seperti itu pulalah yang terjadai kepada Ibrāhīm a.s. ketika mengetahui hakikat yang tidak berubah dan tidak menghilang. Kemudian ia melihat hakikat alam maujūdāt yang agung secara indriawi. Lalu ia berkata pada setiap ujung perenungannya: aku tidak menyukai apa pun yang tenggelam. Seandainya ia tidak melihat hakikat yang tidak tenggelam dan tidak hilang, tentu ia tidak akan menafikan yang tenggelam, tetapi akan menegaskan pada akhir perenungannya apa yang ia ungkapkan di awal perenungannya: “Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku.” Ia merenungkannya sehingga mengetahui bahwa upaya mencari dalil merupakan petunjuk akan jauhnya seseorang dari hakikat yang dicarinya. Sebagaimana dikatakan Ibnu ‘Athā’illāh r.a.:
29. وَ الْاِسْتِدْلَالُ عَلَيْهِ مِنْ عَدَمِ الْوُصُوْلِ إِلَيْهِ .
“Dan orang yang mencari petunjuk kepada-Nya sesungguhnya ia tidak pernah sampai kepada-Nya.”
Sebab, orang yang mencari dalil tentang sesuatu berarti ia merasa samar atau asing terhadap sesuatu itu. Ibnu ‘Athā’illāh r.a. berkata dalam Lathā’if-ul-Minan: “Ketahuilah bahwa dalil itu berlaku bagi orang yang mencari al-Ḥaqq, bukan orang yang menyaksikan al-Ḥaqq. Sebab, sang penyaksi telah cukup dengan yang disaksikan sehingga tak lagi butuh dalil. Maka, ma‘rifat dari sisi hubungan berbagai wasīlah adalah seperti tawanan perempuan yang pada akhirnya menjadi orang merdeka. Jika di antara alam semesta ini ada sesuatu yang tampak jelas sehingga tak membutuhkan dalil maka tentu saja al-Ḥaqq Sang Pencipta mahasuci dan mahacukup dari dalil. Kemudian Ibnu ‘Athā’illāh r.a. menyebutkan sisi dalil bahwa sesungguhnya istidlāl itu menunjukkan jauhnya seorang hamba. Ia mengatakan:
29. وَ إِلَّا فَمَتَى غَابَ حَتَّى يُسْتَدَلَّ عَلَيْهِ وَ مَتَى بَعُدَ حَتَّى تَكُوْنَ الْآثَارُ هِيَ الَّتِيْ الْمَوْصِلَةُ إِلَيْهِ.
“Karena, kapan Tuhan lenyap sehingga dia mencari petunjuk tentang-Nya? Dan kapan Dia jauh sehingga makhluk dijadikan perantara untuk sampai keapda-Nya?.”
Jika mencari dalil tidak mengantarkan seseorang kepada wushūl, justru hanya menunjukkan kejauhan dan keghaiban, sementara al-Ḥaqq Yang Maha Suci tidak ghaib dan tidak jauh, Ibnu ‘Athā’illāh r.a. menegaskan bahwa istidlāl menunjukkan jauh dan asingnya seseorang dari yang dicarinya. Ia mengatakan dalam Lathā’if-ul-Minan: “Di antara yang paling mengherankan adalah menjadikan alam ciptaan sebagai penghubung kepada Allah. Bagaimanakah dengan rambutku? Apakah pada rambutku ini ada wujud yang menghubungkan kepada Allah? Atau apakah pada rambutku itu ada bagian-bagian lahir yang tidak ada pada-Nya sehingga rambut menjadi tempat kemunculan-Nya? Meskipun dikatakan bahwa semesta ciptaan merupakan penghubung yang dimaksud bukan pada dzāt-nya, melainkan pada Dia yang mengatur proses tawshīl sehingga seorang hamba terhubung kepada-Nya. Dan tidaklah semesta ciptaan menjadi penghubung, kecuali karena keilāhiyyahan-Nya. Sesungguhnya Yang Maha Bijaksana adalah yang menempatkan dan menjadikan segala sebab. Artinya, siapa pun yang berhenti bersama asbāb tidak akan mencapai kekuasaan-Nya, karena ia sepenuhnya terhijab. Baik yang mencari dalil maupun yang menggunakan dalil dapat menentukan bahwa ia bisa mengikuti apa yang disingkapkan kepadanya. Sebab, ia tidak mungkin berpindah dari satu keadaan kepada keadaan lain. Alih-alih, ia harus mengikuti apa yang disingkapkan baginya, sebagaimana dikatakan Ibnu ‘Athā’illāh r.a. seraya mengutip ayat al-Qur’ān: (lihat Ḥikam # 30)