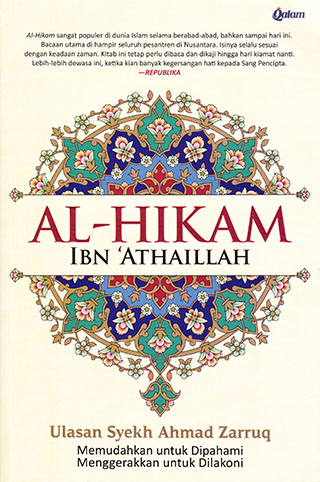7. لَا يُشَكِّكَنَّكَ فِي الْوَعْدِ عَدَمُ وُقُوْعِ الْمَوْعُوْدِ وَ إِنْ تَعَيَّنَ زَمَنُهُ
“Jangan sampai tidak terwujudnya apa yang Dia janjikan membuatmu ragu meskipun waktunya telah ditentukan.”
Maksudnya, seorang hamba tidak semestinya merasa bimbang dan ragu terhadap hasil atau buah dari doa-doa yang dipanjatkannya. Jangan sampai kau mengatakan: “Janji-Nya benar dan waktunya juga telah ditentukan dengan jelas. Namun, apa yang dijanjikan tidak kunjung terjadi dan mewujud.” Perilaku seperti ini melahirkan sikap ragu dan bimbang. Ini diakibatkan oleh pengetahuan yang sempit karena ia hanya melihat sisi lahiriah janji tersebut, tanpa melihat sisi batiniah dan hakikatnya. Sebab, jika ia memiliki pengetahuan yang luas, ia akan menyadari bahwa lahiriah janji tidak melenyapkan hakikat yang terkandung dalam janji tersebut. Dengan begitu ia meyakini janji yang ada seraya melihat kepada sisi batinnya. Caranya, ia selalu mengaitkan setiap urusan dengan syarat yang Allah sembunyikan. Sebab, tidak wajib bagi-Nya menyebutkan apa yang hendak Dia persyaratkan. Sebaliknya, ia disimpan dalam hikmah-Nya guna memperlihatkan rubūbiyyah-Nya dan untuk tetap mewujudkan ‘ubūdiyyah pada diri hamba.
Sebagai contoh, Allah telah menjanjikan kemenangan kepada Nabi-Nya dalam Perang Uhud dan Aḥzāb, serta untuk memasuki Makkah. Namun Dia menyembunyikan syaratnya yang berupa sikap tawadhu‘ yang lewat hukum-Nya melahirkan pertolongan. Karena itu, Allah memperlihatkan syarat-Nya ketika mengingatkan kaum beriman akan karunia-Nya: “Allah telah memenangkan kalian di Badar saat kalian merendah.” Allah juga befirman: “Pada Perang Ḥunain saat kalian bangga dengan banyaknya jumlah kalian….” (13). Nabi s.a.w. berpesan kepada Ibn ‘Abbās r.a.: “Ketahuilah bahwa kemenangan diraih bersama ketawadhu‘an.” Dengan demikian, sikap tawadhu‘ adalah rahasia yang disyaratkan jika permohonan ingin dikabulkan. Pasalnya Allah berfirman: “Dia melenyapkan keburukan dan menjadikan kalian sebagai pemimpin di muka bumi.” (14)
Penentuan waktu disebutkan dengan maksud sebagai bentuk penegasan bagi hamba-hambaNya yang percaya kepada-Nya. Kemudian Ibnu ‘Athā’illāh menyebutkan sebab larangan bersikap ragu dengan berkata:
7. لِئَلَّا يَكُوْنَ ذلِكَ قَدْحًا فِيْ بَصِيْرَتِكَ وَ إِخْمَادًا لِنُوْرِ سَرِيْرَتِكَ
“Itu supaya tidak merusak pandangan mata hatimu dan memadamkan cahaya jiwamu.”
Dikatakan bisa merusak pandangan mata hati karena hamba melihat suatu urusan dengan caya yang tidak semestinya. Ia melihat suatu urusan bukan dengan keluasan ilmu. Kebiasaan melihat dengan cara semacam itu akan menciptakan bias dan merusak pemikiran sehingga kebenaran semakin samar, bahkan akhirnya benar-benar tersembunyi. Kemudian dikatakan bisa memadamkan cahaya jiwa karena cahaya jiwa terbit dari luasnya penglihatan. Maka, orang yang berhenti hanya memperhatikan lahiriah janji berarti menafikan hal tersebut sehingga cahaya jiwanya padam. Sementara, bashīrah itu bagaikan mata lahir. Jika tertutup benda kecil sekalipun, mata tidak dapat melihat meskipun tidak sampai menjadi buta. Lintasan hati termasuk keburukan yang akan merusak penglihatan dan mengeruhkan pandangan. Di sisi lain, kehendak dan keinginan juga dapat menghilangkan kebaikan. Dan upaya yang dilakukan untuk merealisasikan keinginan akan si pemilik kehilangan bagian dari Islam. Alih-alih, ia tercerabut dari akar syariat dan keislamannya. Jika terus berada dalam keburukan, Islam akan terlepas darinya sedikit demi sedikit. Jika akhirnya berani mencela para imam dan loyal kepada kaum zhalim karena menginginkan jabatan dan kedudukan, serta karena lebih mencintai dunia daripada akhirat, maka bisa dikatakan Islam secara total sudah lepas darinya. Janganlah tertipu dengan tampilan lahiriah semata.
Orang seperti ini tidak lagi memiliki ruh dan makna. Ruh Islam adalah cinta kepada Allah dan Rasūl-Nya, cinta kepada orang baik dan orang saleh. Ada sufi yang mengatakan: “Singkirkan lintasan hati yang hina sebelum ia menjadi keinginan agar tidak menjadi bencana bagimu.”
Sufi lainnya mengatakan: “Dosa berawal dari lintasan pikiran sebagaimana banjir berawal dari tetes air.” Sebagaimana seseorang tidak boleh berprasangka negatif terhadap janji-Nya, ia juga tidak boleh berprasangka buruk terhadap perbuatan-Nya. Ia harus berprasangka baik kepada keseluruhannya. Inilah yang dimaksud Ibnu ‘Athā’illāh dengan ucapannya: (lihat Ḥikam # 8)