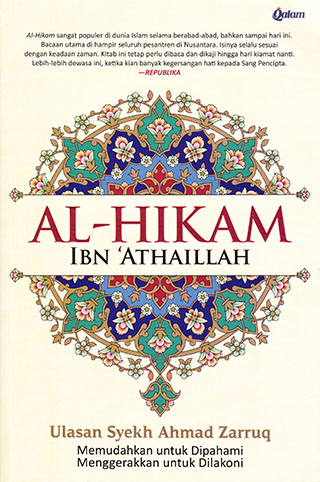4. أَرِحْ نَفْسَكَ مِنَ التَّدْبِيْرِ
“Istirahatkan dirimu dari ikut mengatur!”
Hamba diperintahkan untuk berhenti dan beristirahat karena melakukan sesuatu yang bukan tugasnya hanya akan melahirkan lelah dan penat. Mengatur bukanlah tugas hamba. Maka, jika hamba ikut mengatur, ia pasti ditimpa penat, lelah, dan gelisah. Karena itulah ia hamba diperintah untuk beristirahat dari ikut mengatur. Kelelahan itu muncul karena ketika seseorang ikut pengatur, berarti ia tengah berupaya melawan serta menentang ketentuan dan taqdir Tuhan. Sahl ibn ‘Abdillāh r.a. berkata: “Tidak usah ikut mengatur dan memilih. Sebab, keduanya hanya memperkeruh kehidupan manusia.”
Nabi s.a.w. bersabda: “Allah s.w.t. menghadirkan ketenangan dan kelapangan pada sikap ridhā dan yaqīn....” (al-ḥadīts).
Beliau juga bersabda: “Ikut mengatur adalah setengah kehidupan.”
Ada sufi yang mengatakan: “Tidak ikut mengatur adalah kehidupan seluruhnya. Pasalnya, siapa yang tidak ikut mengatur maka segala urusan akan diaturkan untuknya. Meskipun tidak mengerahkan kekuatan, maknanya bagus dan indah. Sebab, ikut mengatur berarti merancang urusan di masa mendatang berkaitan dengan apa yang ditakuti atau yang diharapkan. Larangan ikut mengatur itu berlaku pada perencanaan atau rancangan yang disertai keyakinan atau sikap menetapkan, bukan dengan kepasrahan. Jika seseorang merancang atau merencanakan sesuatu tetapi jiwanya dipenuhi kepasrahan akan hasil yang akan diperoleh maka ia tidak disebut ikut mengatur. Penggunaan frasa “ikut mengatur” yang mengandung makna umum ini dimaksudkan agar paparan ini lebih mudah dipahami. Wallāhu a‘lam.
Maka, kemudian Ibnu ‘Athā’illāh menyebutkan satu cara yang bisa kita tempuh agar kita tidak ikut mengatur bersama Allah. Caranya adalah senantiasa melihat ketentuan dan taqdir Allah yang sudah digariskan. Ia mengatakan:
4. فَمَا قَامَ بِهِ غَيْرُكَ عَنْكَ لَا تَقُمْ بِهِ لِنَفْسِكَ
“Sebab, apa yang telah dikerjakan selainmu untukmu tak perlu lagi kau lakukan.”
Melakukan sesuatu yang telah dilakukan orang lain untukmu adalah tindakan sia-sia yang tidak memberi manfaat apa-apa. Sungguh itu perbuatan yang tidak berguna yang hanya melahirkan penat, lelah, dan gelisah.
Makna lain dari hikmah di atas: apa yang dipercayakan kepadamu tidak layak diserahkan kepada orang lain. Dengan demikian, terdapat dua hal seperti yang disebutkan oleh Ibrāhīm al-Khawwāsh r.a. (7): “Ilmu tercakup dalam dua kalimat: jangan memaksakan diri terhadap apa yang sudah dicukupkan untukmu dan jangan mengabaikan apa yang diminta darimu.”
Sahl ibn ‘Abdillāh r.a. (8) mengatakan: “Ada tiga hal yang menjadi kewenangan Allah atas hamba: menugaskan mereka, menetapkan ajal mereka, dan mengurus mereka. Dan ada tiga hal yang menjadi kewajiban hamba kepada Allah: mengikuti Nabi-Nya, tawakkal kepada-Nya, serta bersabar menetapinya hingga mati.”
Ungkapan itu memperjelas hikmah Ibn ‘Athā’illāh di atas. Tiga bagian pertama disebut sebagai wewenang Allah atas diri hamba karena di dalamnya tidak dibutuhkan sebab apa pun, Allah maha mengerjakan apa pun yang Dia kehendaki. Tidak ada sebab apa pun untuk terjadinya segala yang dikehendaki Allah. Tiga bagian kedua disebut sebagai kewajiban hamba karena merekalah yang diberi perintah. Siapa saja yang tidak mau mengikutinya berarti ia telah melakukan bid‘ah. Barang siapa tidak bertawakkal berarti ia ikut mengatur. Barang siapa tidak sabar berarti ia menentang. Barang siapa melaksanakan semua pada tempatnya maka ia memiliki bashīrah yang tajam dan hati yang bersinar. Jika tidak, berarti sebaliknya sebagaimana yang diingatkan oleh Ibnu ‘Athā’illāh: (lihat Ḥikam # 5)
Catatan: