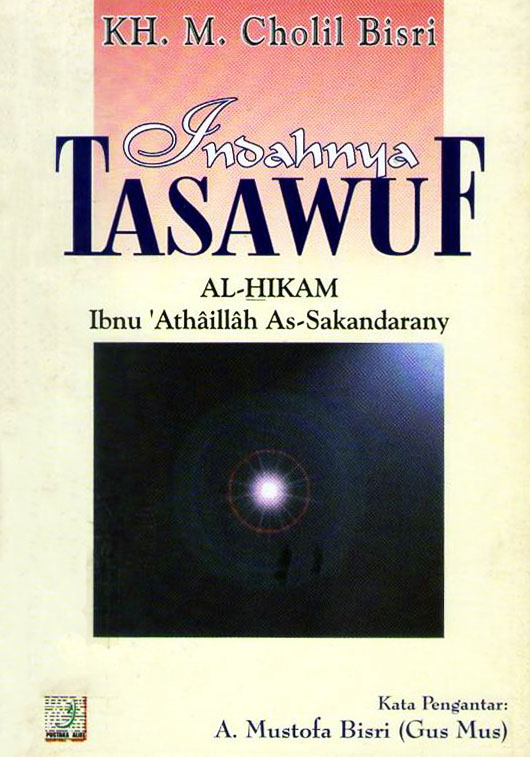2. Gambaran Manusia di Dunia
24. لَا تَسْتَغْرِبْ وُقُوْعَ الْأَكْدَارِ مَا دُمْتَ فِي هذِهِ الدَّارِ فَإِنَّهَا مَا أَبْرَزَتْ إِلَّا مَا هُوَ مُسْتَحِقُّ وَصْفِهَا وَ وَاجِبُ نَعْتِهَا
(Jangan kamu merasa asing dengan datangnya kekeruhan yang kamu alami selagi kamu hidup di dunia ini. Karena apa yang terlihat di depanmu hanyalah sesuatu yang pasti dari Allah dan tidak dapat berubah lagi, jelas sifatnya dan niscaya).
Allah menjadikan dunia sebagai medan fitnah dan cobaaan, ujian, agar masing-masing penghuninya melakukan sesuai dengan asal dan awal penciptaannya. Kemudian Allah mengevaluasinya dan memberi imbalan sesuai dengan apa yang dilakukan di akhirat nanti. Firman Allah:
وَ نَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةٌ وَ إِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ.
(Dan Aku uji kamu sekalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai fitnah (gangguan). Dan kepada-Ku kamu sekalian akan kembali). (Surah XXI: 35)
Disebut “fitnah” karena bisa cocok atau bertentangan dengan nafsu. Disukai atau dibenci, dengan cara melakukan atau meninggalkan. Karena itu, ciri dari duniawi adalah adanya hal-hal yang tidak disukai terjadi dan ada yang dirindukan terjadinya tidak terjadi. Itulah yang menyebab “kekeruhan”. Apalagi jika dinalar apa yang “akan” terjadi di dunia ini, semua serba “menduga”. Orang menanam menduga akan menuai, panen. Orang kawin menduga akan menghasilkan keturunan. Orang berobat menduga akan menyembuhkan sakit. Murid menggarap soal ujian menduga benar dan akan lulus dan seterusnya. Jika antara kebenaran dugaan benar dan akan lulus dan seterusnya. Jika antara kebenaran dugaan dan kesalahannya seimbang, maka akan timbullah “kekeruhan” itu. Oleh sebab itu, salahlah orang yang “yakin” terhadap sesuatu yang masih diduga. Seorang penyair berkata:
“Tuthlab-ur-rāḥatu fī dār-il-fanā’ khāba man yathlubu syay’an lā yakūnu”
Kenyamanan kok dicari di dunia fanā’.
Kecewalah orang yang menuntut sesuatu yang tidak akan ada.
Namun, Kanjeng Nabi pernah berpesan kepada Ibnu ‘Abbās begini:
إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَعْمَلَ للهِ بِالرِّضَا فِي الْيَقِيْنِ فَافْعَلْ وَ إِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَاصْبِرْ.
(Jika kamu mampu ber‘amal karena Allah (semata) dengan ridha dalam yakin, lakukanlah. Dan jika kamu tidak mampu, bersabarlah).
Peyakinan terhadap dugaan tentu saja melalui perencanaan yang matang.
25. مَا تَوَقَّفَ مَطْلَبٌ أَنْتَ طَالِبُهُ بِرَبِّكَ وَ لَا تَيَسَّرَ مَطْلَبٌ أَنْتَ طَالِبُهُ بِنَفْسِكَ
(Tidak sulit mendapatkan capaian yang kamu mengharapkannya dari Tuhanmu. Dan tidak mudah mencapai tuntutan yang kamu hanya mengandalkan dirimu).
Secara sederhana dhawuh ini dapat diterjemahkan. Kalau kamu punya keinginan, kepentingan atau hajat, dan kamu hanya mengandalkan “kemampuan”mu saja, tercapainya tentu tidak mudah. Sebaliknya, kalau kamu mengandalkan rahmat, anugerah dan kemurahan Allah, itu tidak akan sulit tercapainya. Capaiannya atau keinginan, hajat, kepentingan itu bisa berkaitan dengan masalah duniawi maupun ukhrawi. Karena itu, mengembalikan persoalan kepada Allah dengan jalan tawakkal kepada-Nya, adalah sikap bijak.
26. مِنْ عَلَامَاتِ النُّجْحِ فِي النِّهَايَاتِ الرُّجُوْعُ إِلَى اللهِ تَعَالَى فِي الْبِدَايَاتِ
(Tanda-tanda keberhasilan pada akhir (perjalanan) adalah mengembalikan kepada Allah ta‘ālā pada permulaan perjalanan.)
Start itu menentukan finish. Jika startnya benar, seseorang akan sampai finish dengan selamat. Dan bahkan berhasil memenangkan permainan. Jika start dirujukkan kepada Allah, dijamin akan menentukan finish keberhasilan. Sebab penentu segalanya adalah Allah ta‘ālā. Dan Allah menyediakan jalan untuk menuju ke sana. Itulah jalan lempeng. Shirāth mustaqīm.
27. مَنْ أَشْرَقَتْ بِدَايَتُهُ أَشْرَقَتْ نِهَايِتُهُ
(Barang siapa yang pada permulaannya cemerlang, dia akan mengakhirinya dengan kecemerlangan pula.)
Memulai dengan mengembalikan persoalan kepada Allah dalam arti tawakkal kepada-Nya adalah awal yang cemerlang. Karena itu tentu dia akan mendapatkan hasil akhir cemerlang pula.
28. مَا اسْتُوْدِعَ فِيْ غَيْبِ السَّرَائِرِ ظَهَرَ فِيْ شَهَادَةِ الظَّوَاهِرِ
(Apa saja yang dititipkan dalam lindungan keghaiban hati, tampak dalam kasat nyata.)
Atau kita balik: apa yang tampak dalam tingkat laku nyata adalah cerminan dari yang tersimpan dalam hati. Apa yang menjadi sikap batin seseorang mempengaruhi penampilan dalam tindakan dan perilaku. Kanjeng Nabi bersabda: “Law khasya’a qalbu hadzā kasya‘at jawāhiruhum” jika khusyu‘ (tunduk) hati orang ini, pasti tunduk pula semua anggota badannya. Karena itulah Kanjeng Nabi diutus untuk “menggarap” hati dengan menitikberatkan pada akhlak mulia dan kasih-sayang. Tentu saja yang menempatkan ialah Allah. Menurut Imām Abū Thālib al-Makkī, apa yang ditempatkan Allah itu mempengaruhi aura wajah dan anggota badan. Bercahaya atau kusam.
29. شَتَّانَ بَيْنَ مَنْ يَسْتَدِلُّ بِهِ أَوْ يَسْتَدِلُّ عَلَيْهِ الْمُسْتِدِلُّ بِهِ عَرَفَ الْحَقَّ لِأَهْلِهِ فَأَثْبَتَ الْأَمْرَ مِنْ وُجُوْدِ أَصْلِهِ وَ الْاِسْتِدْلَالُ عَلَيْهِ مِنْ عَدَمِ الْوُصُوْلِ إِلَيْهِ وَ إِلَّا فَمَتَى غَابَ حَتَّى يُسْتَدَلَّ عَلَيْهِ وَ مَتَى بَعُدَ حَتَّى تَكُوْنَ الْآثَارُ هِيَ الَّتِيْ تُوْصِلُ إِلَيْهِ
(Jauh sekali bedanya antara orang yang menunjukkan semua orang dengan keagungan Allah dan orang yang mengambil dalil terhadap keagungan Allah hanya kepada orang yang menanyainya. Karena orang yang disebut terdahulu itu mengerti kebenaran bagi Pemilik kebenaran, Allah. Maka dia dapat menempatkan perkara pada wujud asalnya. Mencari dalil atas keagungan Allah haruslah berangkat dari ketiadaan wushūl – sampai pada kesimpulan yang benar – kepada kebenaran Allah. Jika tidak demikian, maka manakala Allah tetap ghaib baginya sehingga harus didasarkan dalil yang nyata; manakala Allah jauh darinya sampai hasil sentuhan Allah tampak nyata. Maka itulah yang bisa membuatnya wushūl kepada Allah.)
Ungkapan di atas memang sulit difahami, jika tidak dijelaskan. Menurut istilah tashawwuf, ‘Ābid itu ada dua “Murād” dan “Murīd”. Yang pertama biasa disebut “Majdzūb”; yaitu dia yang telah tergolong sebagai “Ahl-usy-syuhūd” (yang menyaksikan keagungan Allah) dan “al-‘Ārif billāh”. Dia tidak memerlukan dalil untuk meyakini keagungan Allah. Dia perlu merenung dan berfikir, karena Tuhannya masih ghaib darinya. Dia perlu melakukan sulūk (menenpuh jalan) sampai batas akhir yang menjadi permulaan “jadzab”; terbetotnya (tercabut, tertarik) hati untuk hanya “bergaul” dengan Allah. Hingga mencapai tataran “al-‘Ārif billāh”. “Yang menunjukkan semua orang”, dialah “Murād”, sedang “orang yang mengambil dalil” adalah “Murīd”. Yang menunjukkan semua orang itu, mengarahkan segalanya hanya kepada Allah. Dalam menunjukkan keagungan Allah, begitu meyakinkannya, karena dia “tahu sendiri” akan kebenaran dari Pemilik kebenaran. Yaitu Allah.
30. لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ الْوَاصِلُوْنَ إِلَيْهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ السَّائِرُوْنَ إِلَيْهِ
(Orang yang mendapat keluasan, hendaknya memberi nafkah dari keluasannya itu. Arti dari orang yang mendapat keluasan adalah mereka yang telah wushul, sampai kepada Allah. Dan siapapun yang rizkinya telah ditentukan, merekalah yang berjalan menuju kepada Allah.)
Memberi nafkah, atau infak adalah pemberian yang tidak mengharap imbalan. Kalaupun ada harapan imbalan adalah dari Allah. Bukannya dari yang diberi nafkah. “Orang yang diberi keluasan” diartikan oleh pengarang sebagai orang yang telah wushūl; orang yang telah sampai pada derajat ma‘rifat kepada Allah. Kewajiban dia adalah memberi dan memberi. ‘Ābid yang belum sampai pada tataran washil, dapat disebut “Sā’ir”; orang dalam perjalanan menuju ke sana. Dia diibaratkan sebagai yang kemampuannya belum sampai pada tataran memberi tanpa imbalan. Lalu mengapa disebut-sebut “nafkah” yang biasanya berhubungan dengan penghidupan sehari-hari, seperti makan, sandang dan papan. Ya sebab rizki itu bukan hanya harta benda, tetapi juga ilmu, nasib, menang dan lain sebagainya yang dari Allah. Orang yang mendapatkan keluasan rizki (apapun ragamnya) tidak seyogyanya menikmatinya sendiri. Anugerah, berkah, rahmat dan lain-lain itu adalah alat untuk menjalin hubungan kemasyarakatan yang harmonis, sesuai dengan nama kemakhlukan manusia: yaitu: “Insān” (dari ansun) yang berarti harmoni(s).
Sampai di sini, kita telah memperoleh beberapa istilah tashawwuf dengan “‘Ābid”, “‘Ārif”, “Murīd”, “Murād”, “Sā’ir” dan “Wāshil”.