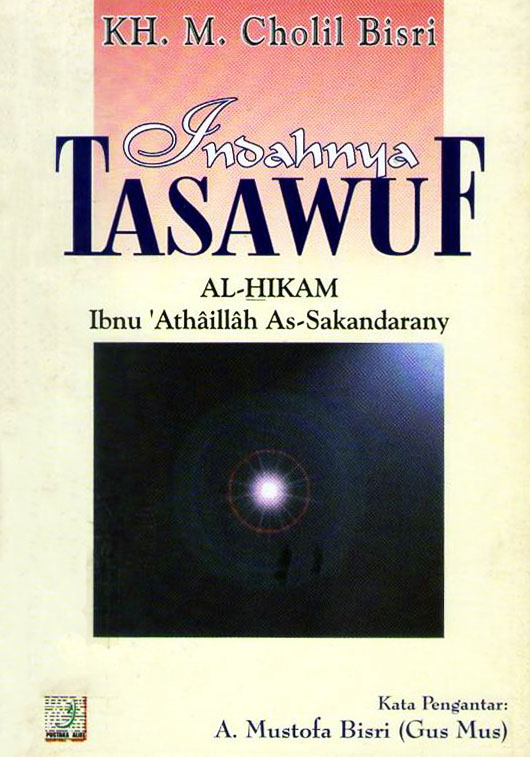Bagian 1
Manusia dan ‘Amal Perbuatannya
1. Antara Rajā’ dan ‘Amal
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ
1. مِنْ عَلَامَاتِ الْاِعْتِمَادِ عَلَى الْعَمَلِ نُقْصَانُ الرَّجَاءِ عِنْدَ وُجُوْدِ الزَّلَلِ
(Kurangnya rajā’ ketika ada kesalahan, menandakan pengandalan terhadap ‘amal)
Ketika kita mengandalkan ‘amal ibadah kita, maka itu bertanda rajā’ (harapan) terhadap rahmat Allah berkurang. Harapan kita terhadap fadhal, karunia, rahmat, pengampunan, pahala dan ridha Allah menjadi berkurang, jika kita hanya mengandalkan ‘amal semata-mata. Kanjeng Nabi Muḥammad s.a.w. pernah ditanya tentang: apakah orang Mu’min dapat masuk surga dengan mengandalkan ‘amal ibadahnya? Beliau menjawab: “Tidak!” Selanjutnya beliau bersabda: “Wa lā ana illā an yataghammadaniy-al-llāhu bi-raḥmatihi wa maghfiratih” (Tidak juga aku, kecuali Allah telah memayungkan dengan rahmat dan pengampunan-Nya).
Jika Nabi saja tidak dapat dan tidak pernah mengandalkan ‘amal, (yang pasti selangit itu) apalagi kita, hamba Allah biasa: “Mengadalkan ‘amal inilah barangkali yang menjadi sebab iblis dengan jumawa-nya (merasa dirinya hebat) menolak “sujūd” kepada Nabi Ādam. Padahal sujūd itu diperintahkan Allah. Akibatnya, iblis diusir dari surga. Diceritakan oleh banyak mufassir, iblis itu penghuni langit yang paling banyak ber‘amal, di samping paling pandai di antara para Malaikat. Karena dia mengandalkan ‘amal (dan ilmu)nya itulah dia menolak sujud kepada Nabi Ādam di mana iblis tahu kalau Ādam diciptakan dari “tanah liat” sedangkan dia dari “api”. Iblis yang angkuh itupun diusir dari Surga.
Rajā’ adalah sikap terus mengharap rahmat dan pengampunan Allah. Sikap itu perlu diambil, apalagi ketika kita tidak akan “berani” mengandalkan ‘amal kita. ‘Amal, yang mungkin, bisa meningkatkan derajat hamba Allah di sisi-Nya; dari derajat “‘Ābid” ke “‘Ārif” itu banyak sekali kendalinya, jika persyaratannya harus ikhlas dan lain-lain. Karena itu kita tidak boleh kehilangan harapan. Rajā’ itu dapat dibagi menjadi sikap “‘Ābid” dan sikap “‘Ārif” Rajā’ sikap “‘Ābid” adalah “masuk surga” dan selamat dari “neraka”. Sedangkan rajā’ sikap “‘Ārif” adalah harapan mendapatkan Allah dan ridhā-Nya. “‘Ārif” menyaksikan dan tahu sendiri bahwa hakikat dari semua yang dikerjakan adalah “hanya” kehendak Allah. Bahkan “al-Fā‘il”, pelaku pekerjaan ialah Allah. Sementara itu, sebagai makhluk manusia berkemungkinan berbuat kesalahan demi kesalahan. Andaikata tidak mendapat rahmat dan pengampunan Allah, celakalah manusia. Rajā’ yang dilandasi dengan baik sangka (ḥusn-uzh-zhann) kepada Allah Yang Maha memberi segala hamba, akan membuat seorang mu’min juga tidak akan meninggalkan ‘amal yang diperintahkan. Jadi antara kepatuhan melaksanakan perintah dan rajā’ terhadap rahmat dan pengampunan tidaklah dapat dipisahkan oleh ‘Ābid yang ingin meningkat ke derajat “‘Ārif billāh.”
Tentu saja sikap tersebut tidak mudah bagi kebanyakan mukmin, seperti kita ini. Namun ikhtiyār ke arah itu, dengan terus-menerus menumbuhkan semangat beribadah dan ber-“‘amal shāliḥ”, sangat dianjurkan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Setidak-tidaknya, dengan demikian ketenangan hidup dalam keridhaan dapat dinikmati sepanjang usia.
Ḥikam mengawali dengan rajā’. Mungkin hal itu dimaksudkan agar rajā’ itu menjadi modal dasar setiap mu’min untuk bersiap-siap masuk ke dalam kebeningan dan keheningan jiwa yang pada gilirannya, tentu saja, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat yang merupakan dambaan setiap orang beriman.
(2. إِرَادَتُكَ التَّجْرِيْدُ مَعَ إِقَامَةِ اللهِ إِيَّاكَ فِي الْأَسْبَابِ مِنَ الشَّهْوَةِ الْخَفِيَّةِ وَ إِرَادَتُكَ الْأَسْبَابَ مَعَ إِقَامَةِ اللهِ إِيَّاكَ فِي التَّجْرِيْدِ انْحِطَاطٌ مِنَ الْهِمَّةِ الْعَلِيَّةِ
Keinginanmu untuk lepas dari kesibukan urusan duniawi, padahal Allah telah menempatkanmu di sana, termasuk syahwat yang tersamar. Dan keinginanmu untuk masuk ke dalam kesibukan urusan duniawi, padahal Allah telah melepaskannya dari itu, sama saja dengan mundur dari tekad luhur.)
(Ini tidak ada dalam teks asli – SH.)
Allah s.w.t. memberi hidup kepada manusia, bahkan semua yang melata di bumi-Nya, juga menjamin kehidupan mereka, rizki mereka (38: 6). Karena sudah dijamin, pengertian dangkalnya: “Buat apa mencari?” Karena itu pula, seharusnya manusia hanya berkonsentrasi kepada ibadah saja (51: 56). Tetapi jika seseorang menjadikan jaminan Allah itu sebagai tumpuan, berarti dia telah menyimpan keinginan yang berlebihan (syahwat).
Sementara itu, ada saja ‘Ābid yang mempunyai pendapat bahwa dia tidak akan mampu berkonsentrasi untuk beribadah dengan khusyu‘ tanpa ditopang oleh kehidupan yang tenang. Kehidupan tenang itu tidak akan lahir begitu saja, tanpa diupayakan. Karena dia yakin akan dhawuh (ucapan, ajaran, nasihat): “Innallāha idzā arāda syai’an hayya’a asbābah.” (Allah itu jika menghendaki sesuatu, pasti menyiapkan sebab-sebabnya). Atau: “kullun muyassarun limā khuliqa lahu.” (Segalanya dipermudah menuju ke arah yang ditetapkan baginya, H.R. Aḥmad, al-Bukhārī, Muslim, Abū Dāūd dari ‘Imrān bin Ḥushain. H.R. at-Tirmidzī dari ‘Umar dan H.R. Aḥmad dari Abū Bakar ash-Shiddīq). Jadi dia beribadah untuk meningkatkan dirinya menjadi al-‘Ārif, tetapi juga bekerja keras mengupayakan kehidupan tenang. Demikian itu dapat menyebabkan dia mengalami degradasi dalam mencapai cita-cita luhurnya. Karena – oleh keterpakasannya – dia harus bergantung kepada “makhluk” sesudah dia berkehendak untuk hanya bergantung kepada Allah semata. Dia telah membuka peluang masuknya syaithan untuk mempengaruhi keyakinannya.
3. سَوَابِقُ الْهِمَمِ لَا تَحْرِقُ أَسْرَارَ الْأَقْدَارِ
4. (أَرِحْ نَفْسَكَ مِنَ التَّدْبِيْرِ)
(Beberapa yang mendahului keinginan tidak akan membakar batas ketentuan/takdir Allah. Karena itu, tenangkan hatimu dari mengatur urusanmu).
Dengan kata lain, kemauan dan cita-cita bagaimanapun tidak akan bisa merubah ketentuan atau takdir Allah. Karena itu rencana secanggih apapun, jika gagal dilaksanakan tidak perlu membuat seseorang kehilangan semangat untuk terus beribadah, terus berusaha dan – tentu saja – sambil terus berdoa.
Itulah sulitnya. ‘Ābid yang manusia itu mempunyai sifat “kepingin” mendapatkan sesuatu sesuai dengan desakan nafsunya. Tetapi di saat yang sama dia juga “kepingin” meningkatkan pangkat dirinya – di sisi Allah – menjadi ‘Ārif. Jika dia memenangkan yang pertama, dia akan disibukkan dengan dunia dan banyak berurusan dengan sesama. Dengan demikian, ibadahnya akan kehilangan kemurniaan (keikhlasan). Bahkan bisa saja waktunya habis untuk mencari dan bercapai-capai dengan urusan duniawi itu. Jika yang dimenangkan yang kedua, apalagi mencari dan bercapai-capai mendapatkan pemenuhan keinginan nafsu, merencanakan untuk memperolehnya saja harus ditinggalkan. Dengan keyakinan, apapun yang direncanakan, jika itu berada di luar “qadar” dan “takdir” Allah, pasti akan “terbakar”. Hanya yang dikehendaki Allah saja yang akan terjadi.
4. (أَرِحْ نَفْسَكَ مِنَ التَّدْبِيْرِ) فَمَا قَامَ بِهِ غَيْرُكَ عَنْكَ لَا تَقُمْ بِهِ لِنَفْسِكَ
5. اِجْتِهَادُكَ فِيْهَا ضُمِنَ لَكَ وَ تَقْصِيْرُكَ فِيْمَا طُلِبَ مِنْكَ دَلِيْلٌ عَلَى انْطِمَاسِ الْبَصِيْرَةِ مِنْكَ
(Apa yang sudah diurus oleh selainmu dari keperluanmu, jangan kamu ikut mengurusnya pula untuk kepentinganmu.
Kesungguhanmu dalam urusan yang sudah dijamin, dan keterbatasanmu dalam mendapatkan tuntutanmu menunjukkan hilangnya mata hatimu).
“Selainmu” itu, yang dimaksud adalah Allah. Jadi semua urusan yang sudah ditanggung dan dijamin Allah, kamu tidak perlu ikut mencampuri. Serahkan saja semuanya, Allah akan menyelesaikannya dengan sempurna. Kalau kamu masih ngotot juga, malahan menunjukkan kesungguhan maksimal, itu artinya kamu telah dihilangkan nurani, kehilangan mata hati. Hal-hal yang dijamin Allah bagi kepentingan manusia, antara lain: rizki, kedudukan/pangkat, hidup/mati, nasib/keberuntungan, jodoh, dan lain-lain. Oleh banyak ‘Ārifīn, yang saya sebut itu bagaikan “bayang-bayang”; bila dikejar, lari, bila ditinggal pergi, mengikuti dan bila dibiarkan, menanti. Waktu yang – barangkali – disediakan untuk mengejar rizki, misalnya, sudah seharusnya digunakan untuk mempergiat ibadah.