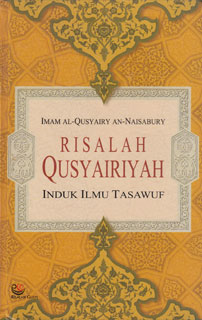BAB II-6
TAWĀJUD, WUJD DAN WUJŪD
Tawājud adalah upaya memohon ekstase ruhani (wujd), melalui salah satu ragam ikhtiyar. Orang yang memiliki tawājud tidak dapat dikategorikan sempurna wujd-nya. Sebab, kalau ia sempurna, pasti disebut wajīd.
Dalam bab wazan Tafa‘ul lebih banyak menampakkan sifat. Padahal bukan demikian, seperti dalam syair:
Bila kelopak mata menjadi sempit,
Dan padaku tiada lagi sulit membuka,
Lalu kurobek mata, tanpa cela.
Ada pandangan yang mengatakan: “Tawajud tidak terpasrahkan kepada pemangkunya karena adanya beban dan masih jauh dari tahqiq.”
Ada pula yang mengatakan: “Tawājud diserahkan kepada para fakir yang secara internal mengintai untuk menemukan makna-makna tersebut,”
Hakikat yang bisa dikenal, muncul dari kisah Abū Muḥammad al-Jurairiy r.a. bahwa ia berkata: “Ketika aku di sisi al-Junaid, di sana ada Ibnu Masrūq. Tiba-tiba Ibnu Masrūq dan yang lain berdiri, sementara al-Junaid tetap saja diam. Aku berkata: “Tuanku, tidakkah anda mempunyai suatu pengalaman dalam penyimakan?” Al-Junaid menjawab: “Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka ia tetap di tempatnya, padahal ia jalan seperti jalannya awan.” (An-Naml:88). Lalu al-Junaid pun bertanya: “Anda, wahai Abū Muḥammad, tidakkah anda berpengalaman juga dalam penyimakan?” Aku katakan: “Tuanku, ketika aku hadir di suatu tempat yang di dalamnya sedang berlangsung penyimakan, tiba-tiba di sana ada orang-orang yang bersenang-senang dengan rasa malu, maka aku mengekang diri dan wujūd-ku. Ketika aku menghindar, aku mengirimkan wujūd-ku, lalu aku ber-tawājud.”
Kemudian kata tawājud disebut dalam hikayat tersebut, sedangkan al-Junaid tidak mengingkarinya.
Saya mendengar Syaikh Abū ‘Alī ad-Daqqāq r.a. berkata: “Apabila manusia menjaga diri dengan etika keutamaan saat dalam penyimakan, Allah menjaga diri dan waktunya, karena berkat etikanya.”
Sedangkan ekstase ruhani (wujd) itu sendiri merupakan sesuatu yang bersesuaian dengan hati anda, yang datang tanpa kesengajaan ataupun diupayakan. Karena itu para syaikh mengatakan: “Wujd adalah persesuaian hati, sedangkan al-mawājid (jam‘-ul-wujd) merupakan buah dari wirid. Setiap orang yang bertambah upaya ruhaninya, Allah pun akan menambah kelembutannya.”
Saya mendengar Syaikh Abū ‘Alī ad-Daqqāq r.a. berkata: “Sesuatu yang sampai ke dalam hati itu, muncul dari sisi wirid. Siapa yang tidak wirid dengan lahiriahnya, maka tidak wirid pula dalam sirr-nya. Setiap ada sesuatu di dalam diri pelaku al-wujd, maka tidak dapat dikategorikan sebagai wujd. Seperti sesuatu hal yang dilakukan melalui muamalat lahiriah akan menemukan manisnya ketaatan, dan apa yang turun dalam batin hamba seputar hukum-hukum batin, akan menemukan al-mawājid. Kemanisan adalah buah dari mu‘āmalāt, dan mawājid merupakan produk dari karunia yang turun.”
Sedangkan wujūd, merupakan suatu kondisi setelah menapaki tahap wujd. Wujūd al-Ḥaqq tidak dapat dicapai kecuali setelah memadamkan unsur manusiawinya. Karena kemanusiawian tidak akan baqā’ ketika muncul kekuasaan Hakikat. Inilah arti dari ucapan Ḥusain an-Nūriy: “Sejak dua puluh tahun aku berada antara Ada dan tiada, yakni: Ketika kutemui Tuhanku, sirnalah hatiku, dan ketika kutemui hatiku, aku kehilangan Tuhanku.”
Pernyataan ini relevan pula dengan ucapan al-Junaid: “Ilmu Tauhid merupakan wahana penjelasan bagi wujūd-nya, dan wujūd-nya merupakan wahana bagi ilmunya.” Dalam konteks artian ini, penyair berkata:
Wujūd-ku ada ketika aku ghaib dari wujūd,
Karena yang tampak padaku,
Dalam syuhūd (penyaksian).
Tawājud merupakan permulaan, dan wujūd adalah tujuan akhir. Sedangkan wujūd sebagai perantara antara permulaan dan tujuan akhir.
Saya mendengar Syaikh Abū ‘Alī ad-Daqqāq berkata: “Tawājud mengharuskan adanya kecelaan hamba. Sedang wujd mengharuskan setenggelaman hamba. Demikian pula wujūd mengharuskan kesirnaan hamba. Seperti orang yang menyaksikan lautan. Kemudian mengarungi lautan itu, lantas tenggelam di dalamnya. Struktur persoalan ini dikatakan secara berurutan, mulai dari: “Qushūd (bermaksud), Wurūd (sampai), kemudian Syuhūd (penyaksian), lalu Wujūd, terakhir Khumūd (sirna). Dengan kadar kriteria wujūd-lah, khumūd dapat dicapai.”
Bagi orang yang ber-wujūd memiliki kesadaran (shahw) dan ketidaksadaran (mahw). Kondisi shahw adalah keabadiannya dengan al-Ḥaqq, sedang kondisi mahw-nya adalah kefana’annya dengan al-Ḥaqq. Keduanya saling berkelindan selamanya. Apabila shahw dengan al-Ḥaqq yang lebih unggul, ia telah sampai (wushūl). Karena itu, Rasūlullāh s.a.w. bersabda: (Hadits Qudsi): “Dengan-Ku ia mendengar dan dengan-Ku ia melihat.”
Manshūr bin ‘Abdullāh berkata: “Seseorang berada dalam halaqah asy-Syiblī, dan orang itu kemudian bertanya: “Apakah pengaruh keabsahan wujd itu tampak pada diri orang-orang yang mencapai al-wujūd?” “Benar. Cahaya yang memancar, bersamaan dengan sinar kerinduan, sehingga pengeruhnya mewarnai lubuk hatinya,” demikian jawab asy-Syiblī.”
Gambaran ini jelas dalam syair Ibn-ul-Mu‘tazz:
Gelas yang dibasahi air karena cemerlang beningnya,
Lalu mutiara tumbuh dari bumi emas,
Sedang kaum menyucikan karena kagum,
Pada cahaya air di dalam api dari anggur yang ranum,
Diwarisi ‘Ād dari negeri Iram,
Sebagai simpanan Kisra, mulai dari nenek moyangnya.
Suatu kisah berkenaan dengan Abū Bakr ad-Duqqy: “Jahm ad-Duqqy mengambil kayu di tangannya ketika sedang menyimak dalam ghairahnya, kemudian ia mencabut dari akarnya. Keduanya kemudian berkumpul ketika secara bersamaan saling memanggil. Ad-Duqqy sendiri seorang yang buta. Lalu Jahm berdiri sambil berkeliling dengan penuh emosi, Abū Bakr ad-Duqqy berkata: “Jika mendekat kepadaku, ulurkan kayu itu!” Sementara Jahm ad-Duqqy adalah manusia lemah, lantas ia menemukan sepotong kayu di dekatnya, seraya berkata: “Ini ia!” Lalu ad-Duqqy memegang kaki Jahm, hingga membuatnya tidak dapat bergerak lagi. “Wahai Syaikh, tobat!” teriak Jahm ad-Duqqy. Barulah kemudian Abū Bakr ad-Duqqy melepaskannya.”
Semangat Jahm benar, dan pengekangan ad-Duqqy juga benar. Ketika Jahm menyadari bahwa tindakan ad-Duqqy di atas kondisi ruhaninya, seketika itu pun ia insaf dan berdamai.
Begitu pula dengan orang yang tidak berbuat maksiat, ia benar. Namun demikian, apabila yang mengalahkan dirinya adalah kesirnaan diri, maka ia tidak berilmu dan tidak pula berakal, tidak paham serta tidak merasa.
Istri Abū ‘Abdillāh at-Targhundy berkata: “Ketika bencana kelaparan sedang melanda, sementara manusia dijemput maut karena paceklik itu, tiba-tiba Abū ‘Abdillāh at-Targhundy masuk ke dalam rumah. Ia melihat ada dua kilogram gandum. Berkatalah ia: “Orang-orang mati karena kelaparan, sedang aku masih mempunyai simpanan gandum di rumah.” Lalu ia pun kehilangan akal. Dan sejak saat itu ia tidak pernah bangkit, kecuali pada waktu-waktu shalat fardhu. Usai shalat kembali pada tingkah laku semula, dan begitu seterusnya sampai ia meninggal dunia.”
Kisah ini menunjukkan, bahwa laki-laki tersebut selalu menjaga diri dalam adab syariat, ketika dilanda oleh hukum-hukum hakikat. Demikianlah sifat ahli hakikat. Mengenai faktor penyebab hilangnya akal pada dirinya, dikarenakan kepeduliannya (syafaqah) terhadap nasib sesama kaum Muslimin. Inilah derajat yang lebih kuat dalam sikap perilakunya.