01-7 Thariqah, Tarekat dalam Pandangan Ibnu Taimiyah – Sabil-us-Salikin
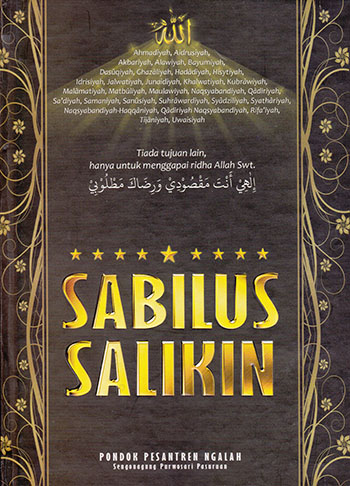
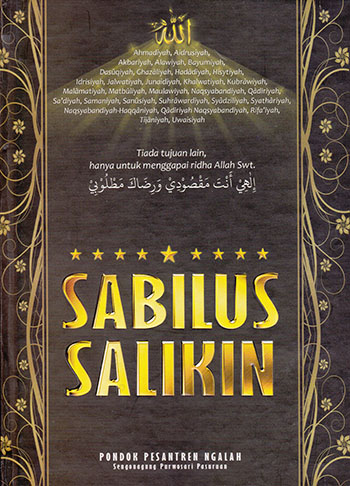
Penjelasan Ibn Taimiyah mengenai tarekat sangat penting untuk dikemukakkan lebih jauh di sini, sebab – sekali lagi – selama ini ia sering dituding sebagai antitharīqah, bahkan dijadikan rujukan utama oleh sebagian kecil umat untuk menentang tharīqah. Padahal Ibnu Taimiyah tidak pernah menentang tharīqah/tashawwuf kecuali yang nyata sekali bertentangan dengan al-Qur’ān dan as-Sunnah.
Ketika memuji Imām al-Junaid al-Baghdādī berkenaan dengan kewajiban seorang salik (Orang yang berjalan menuju Allāh s.w.t. agar mengenal Sang Pencipta sehingga dapat beramal dan berubudiyah secara ikhlas), Ibn Taimiyah menegaskan dalam kitabnya al-Istiqāmah: “Ini (mengenal sang Pencipta) termasuk di antara pokok-pokok ‘aqīdah ahl-us-Sunnah dan imam-imam para syaikh, khususnya syaikh-syaikh sufi, karena pokok pangkal tharīqah para sufi adalah kehendak (al-Irādah), yang merupakan fondasi amal. Mereka dalam hal kehendak, ibadah, amal, dan akhlak lebih besar keteguhannya daripada dalam hal perkataan dan ilmu pengetahuannya. Mereka dengan semua itu lebih besar perhatiannya dan lebih banyak pemeliharaanya. Orang yang belum memasuki semua itu tidak dapat serta-merta menjadi ahli tharīqah mereka.”
Dalam kitabnya yang lain al-Ḥasanatu was-Sayyi’ah, Ibn Taimiyah menegaskan lebih lanjut bahwa orang yang mengikuti Imām al-Junaid adalah orang yang memperoleh hidayah, selamat dan bahagia: “Barang siapa menempuh jalan yang ditempuh oleh al-Junaid yang merupakan salah seorang pakar tashawwuf dan ma‘rifah, maka ia benar-benar telah mendapat hidayah, selamat dan bahagia.”
Selain Imām al-Junaid al-Baghdādī, Ibn Taimiyah juga memuji dan membela para Syaikh tharīqah lainnya, seperti: Abū Yazīd al-Busthāmī, Syaikh ‘Abd al-Qādir al-Jailānī, dan bahkan juga Imām al-Ghazālī. Tentang Syaikh ‘Abd al-Qādir al-Jailānī, misalnya Ibn Taimiyah menggambarkannnya sebagai berikut: “Syaikh ‘Abd al-Qādir al-Jailānī dan syaikh tharīqah seperti beliau merupakan syaikh yang paling gigih memerintahkan menetapi syarī‘ah, perintah dan larangan, serta mengedepankan agar meninggalkan keinginan dan kehendak nafsu, karena kesalahan dalam berkehendak dilihat dari segi kehendak itu sendiri hanya terjadi dari sisi hawa nafsu ini. Beliau memerintahkan seorang sālik (murid yang menempuh sulūk/perjalanan menuju Allāh s.w.t.) agar tidak memiliki sama sekali kehendak yang bersumber dari hawa nafsu melainkan ia berkehendak sesuai dengan yang dikehendaki Allāh ‘azza wa jalla.”
Pada bagian sebelumnya sudah disinggung bahwa Ibn Taimiyah menyebut para sufi sebagai ahlu ‘ulūm-il-Qulūb (pakar-pakar ilmu hati) yang bebas dari bid‘ah ketika ia mengatakan: “Perkataan pakar-pakar ilmu hati dari kalangan sufi dan yang selain mereka, seperti Abū Ḥāmid Muḥammad al-Ghazālī pula Ibn Taimiyah mengutip pernyataan yang mengukuhkan kebenaran tarekat para sufi: “Tharīqah para sufi adalah tujuan (ghāyah), karena mereka menyucikan qalbu mereka dari hal-hal selain Allāh dan memenuhinya dengan dzikrullāh; dan ini merupakan prinsip dakwah para rasūl.” Pengakuan Ibn Taimiyah mengenai kebenaran tharīqah para sufi juga mencuat dari pernyataanya yang dituangkan dalam kitabnya yang berjudul Syarḥ-ul-‘Aqīdat-ul-Ishfāhāniyyah, yaitu ketika ia berbicara tentang mu‘jizat para Nabi: “Tidak ada jalan bagi akal untuk memahami mu‘jizat para nabi hanya dengan komoditi akal semata. Hal-hal lain dari keistimewaan para nabi hanya dapat dipahami dengan “rasa” oleh orang yang menempuh tharīqah tashawwuf…”
Jika Nabi memiliki suatu keistimewaan yang anda tidak punya modelnya, maka anda sama sekali tidak akan memahami keistimewaan itu, apalagi membenarkannya, karena pembenaran hanya muncul setelah pemahaman, dan model yang dimaksudkan di sini terdapat di awal tharīqah tashawwuf. Adapun rasa (dzauq) maka ia seperti ‘menyaksikan’ dan ‘mengambil dengan tangan’ dan hal itu tidak ada kecuali dalam tharīqah para sufi.
Ibn Taimiyah bahkan tidak mengingkari konsep “mabuk” yang kadang-kadang melahirkan berbagai ungkapan yang sepintas terkesan berbau syirik tetapi sebenarnya tidak dimaksudkan demikian, ungkapan-ungkapan yang dikenal dengan syathaḥāt.
Ungkapan-ungkapan pada dasarnya muncul secara otomatis dari kondisi fanā’ (“ekstase”) yang sama sekali tidak dipengaruhi oleh pertimbangan atau kesadaran apapun kecuali semata-mata karena terbuai oleh keagungan dan keindahan Tuhan. Dalam kaitan ini ia mengatakan: “Sebagian tokoh sufi yang mengalami kondisi spiritual tertentu (dzawi-l-aḥwīl) kadang-kadang mengalami ‘mabuk dan lenyap dari selain Allāh’ dalam keadaaan fanā’ yang singkat. Keadaan mabuk seperti itu terjadi tanpa disengaja, tanpa pertimbangan. Kadang-kadang dalam keadaan itu ia berkata: subḥānī (maha suci aku), atau ungkapan-ungkapan lain seperti yang mempengaruhi Abū Yazīd al-Busthāmī dan orang-orang berjiwa sehat (al-ashiḥḥah) lainnya.”
Hal itu menurut Ibn Taimiyah sejalan dengan makna-makna hadits qudsi yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī. Dalam hadits itu disebutkan bahwa apabila seorang hamba selalu berupaya menempuh jalan pendekatan diri kepada Allāh dengan melaksanakan secara intensif al-farā’idh (perkara-perkara yang diwajibkan) dan al-nawāfil (perkara-perkara yang disunnahkan), sebuah upaya yang bermuara pada suatu keadaan (ḥāl) yang dalam hadits itu diungkapkan dengan “sampai Aku mencintainya” (ḥattā uḥibbahu), “maka Akulah yang menjadi telinga, mata, tangan dan kakinya.” Semua ini dikemukakan Ibn Taimiyah ketika ia membela ahli tharīqah yang sejalan dengan sunnah.
Di sela-sela pembelaan ini ia menegaskan: Pokok-pokok madzhab ahli tharīqah yang Islami adalah mengikuti para nabi dan para rasūl.