01-6 Dasar Hadits – Sabil-us-Salikin
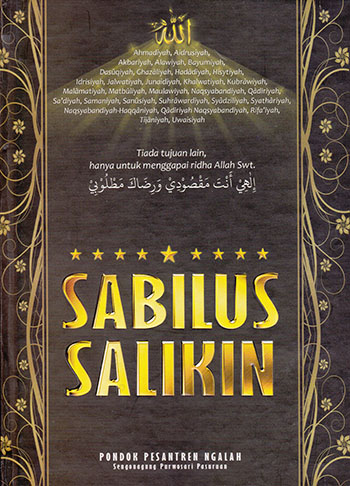
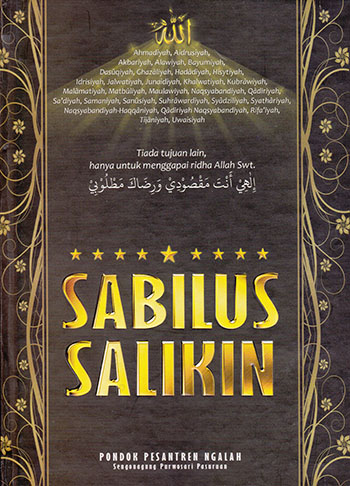
Sejalan dengan apa yang disitir dalam al-Qur’ān, sebagaimana dijelaskan di atas, ternyata tashawwuf juga dapat dilihat dalam kontek Hadits. Umumnya yang dinyatakan sebagai landasan dan dasar ajaran-ajaran tashawwuf adalah hadits-hadits berikut.
مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ
“Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka akan mengenal Tuhannya.” (Iḥyā’u ‘Ulūm-id-Dīn, juz 4, halaman: 301)
كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ فَبِهِ عَرَفُوْنِيْ
“Aku adalah perbendaharaan yang tersembunji, maka Aku menjadikan makhluk agar mereka mengenal-Ku.” (Atsar-ul-Aḥādīts-idh-Dha‘īfati wal-Maudhū‘āti fil-‘Aqīdah, ‘Abd-ur-Raḥmān ‘Abd-ul-Khāliq, juz 1, halaman: 15, Tafsīr-ul-Alūsī, juz 19, halaman: 418)
لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَاِذَا اَحْـبَبْتُهُ كُنْتُ سَمِعَهُ الَّذِيْ يَسْمَعُ وَ بَصَرَهُ الَّذِيْ يُبْصِرُ بِهِ وَ لِسَانَهُ الَّذِيْ يَنْطِقُ بِهِ وَ يَدَهُ الَّذِيْ يَبْطِشُ بِهَا وَ رِجْلَهُ الَّذِيْ يَمْشِيْ بِهَا فَبِيْ يَسْمَعُ فَبِيْ يَبْصُرُ وَ بِيْ يَنْطِقُ وَ بِيْ يَعْقِلُ وَ بِيْ يَبْطِشُ وَ بِيْ يَمْشِيْ
“Senantiasa seorang hamba itu mendekatkan diri kepada-Ku dengan amalan-amalan sunnat sehingga Aku mencintainya. Maka tatkala mencintainya, jadilah Aku pendengarnya yang dia pakai untuk mendengar, penglihatannya yang dia pakai untuk melihat, lidahnya yang dia pakai untuk berbicara, tangannya yang dia pakai untuk mengepal, dan kakinya yang dia pakai unluk berjalan, maka dengan-Ku lah dia mendengar, melihat, berbicara, berpikir, mengepal, dan berjalan.” (Jāmi‘-ul-‘Ulūmi wal-Ḥukum, juz 1, halaman: 365)
Hadits di atas memberi petunjuk bahwa manusia dan Tuhan dapat bersatu. Diri manusia dapat melebur dalam diri Tuhan, yang selanjutnya dikenal dengan istilah fanā’, yaitu fanā’-nya makhluk sebagai yang mencintai kepada Tuhan sebagai yang dicintainya.
Berikut ini dikemukakan beberapa hadits yang merupakan landasan lahirnya tashawwuf:
1). ‘Ā’isyah berkata:
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لِمَ تَصْنَعُ هذَا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ. قَالَ: أَفَلَا اُحِبُّ أَنْ أَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا.
“Adalah Nabi bangun shalat malam (qiyām al-lail), sehingga bengkak kakinya. Aku berkata kepadanya: ‘Gerangan apakah sebabnya, wahai utusan Allāh, engkau sekuat tenaga melakukan ini, padahal Allāh telah berjanji akan mengampuni kesalahanmu, baik yang terdahulu maupun yang akan datang?’ Beliau menjawab: Apakah aku tidak akan suka menjadi seorang hamba Allāh yang bersyukur?.” (HR. al-Bukhārī dan Muslim).
2). Rasūlullāh s.a.w. bersabda:
وَاللهِ إنِّيْ لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَ أَتُوْبُ اِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً
“Demi Allāh, aku memohon ampunan kepada Allāh dalam sehari semalam tak kurang dari tujuh puluh kali.” (H.R. al-Bukhārī, (Riyādh-ush-Shālihīn, juz 2, halaman: 338, Shaḥīḥ-ul-Bukhārī – Thūq-un-Najāḥ, juz 8, halaman :67)
3). Rasūlullāh s.a.w. bersabda:
إِنَّ اللهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ اَذَنْـتُهُ بِالْحَرْبِ. وَ مَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ عَبْدِيْ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَ مَا يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمِعَهُ الَّذِيْ يَسْمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّذِيْ يُبْصِرُ بِهِ وَ يَدَهُ الَّتِيْ يَبْطِشُ بِهَا وَ رِجْلَهُ الَّتِيْ يَمْشِيْ بِهَا وَ إنْ سَأَلَنِيْ لَأَعْطِيَنَّهُ وَ لَئِنِ اسْتَعَاذَنِيْ لَأُعِيْذَنَّهُ.
“Sesungguhnya Allāh s.w.t. telah berfirman,: “Siapa memusuhi kekasih-Ku, maka Aku menyatakan perang kepadannya Tidak ada yang paling Aku sukai dan hamba-Ku yang mendekatkankan diri kepada-Ku selain menjalankan kewajibannya. Hendaklah hamba-Ku mendekatkan diri dengan-Ku juga dengan menjalankan kesunahan-kesunahan sehingga Aku mencintainya. Jika Aku sudah mencintainya, maka Aku akan menjadi pendengaran dan penglihatannya, juga akan menjadi tangan dan kakinya. Setiap permohonannya pasti akan Aku kabulkan. Jika meminta perlindungan, Aku akan melindunginya”. (HR al-Bukhārī, (Riyādh-ush-Shāliḥīn, juz 1, halaman: 91, Shaḥīḥ-ul-Bukhārī – Thūq-un-Najāḥ, juz 8, halaman :105)
Maksudnya: pernyataan bahwa Allāh akan menjadi pendengaran, penglihatan, tangan, dan kaki hamba yang dicintai-Nya merupakan majaz untuk menjelaskan pertolongan Allāh.
4). Rasūlullāh s.a.w. bersabda:
لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللهِ حَتَّى تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ يَغْدُوْ خِمَاصًا وَ تَرُوْحُ بِطَانًا
“Seandainya kalian benar-benar bentawakkal kepada Allāh, maka Allāh akan memberikan rezeki pada kalian sebagaimana burung yang pergi dalam keadaan perut kosong dan pulang sudah kenyang”. (HR. At-Tirmidzī. Hadits Ḥasan, (Sunan Ibn Mājah, juz 2, halaman: 1394)
5). Rasūlullāh s.a.w. bersabda:
اِزْهَدْ فِى الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللهُ وَ ازْهَدْ فِيْمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّوْكَ
“Berzuhudlah terhadap dunia maka Allāh akan mencintaimu. Zuhudlah pada apa yang ada di tangan orang lain maka mereka akan mencintaimu”. (Sunan Ibn Mājah, juz 3, halaman :1373).
Selanjutnya, dalam kehidupan Nabi Muḥammad s.a.w. juga terdapat petunjuk yang menggambarkan bahwa dirinya adalah sebagai seorang sufi. Nabi Muḥammad s.a.w. telah melakukan pengasingan diri ke Gua Ḥirā’ menjelang datangnya wahyu. Beliau mejauhi pola hidup kebendaan saat orang ‘Arab tengah tenggelam di dalamnya, seperti dalam praktik perdagangan yang didasarkan pada prinsip menghalalkan segala cara.
Selama di Gua Ḥirā’, Rasūlullāh s.a.w. hanyalah bertafakkur, beribadah, dan hidup sebagai seorang zahid. Beliau hidup sangat sederhana, bahkan terkadang memakai pakaian tambalan, tidak memakan makanan atau meminum, kecuali yang halal, dan setiap malam senantiasa beribadah kepada Allāh s.w.t., sehingga Siti ‘Ā’isyah, istrinya, bertanya: “Mengapa engkau berbuat begini, ya Rasūlullāh, padahal Allāh s.w.t. senantiasa mengampuni dosamu?’ Rasūlullāh s.a.w. menjawab: “Apakah engkau tidak menginginkanku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allāh s.w.t.?” Kalangan sahabat pun ada yang mengikuti praktik bertashawwuf sebagaimana yang dipraktekkan Nabi Muḥammad s.a.w., Abū Bakar ash-Shiddīq, misalnya, pernah berkata: “Aku mendapatkan kemuliaan dalam ketaqwaan, ke-fanā’-an dalam keagungan dan kerendahan hati”. Khalīfah ‘Umar bin al-Khaththāb r.a. pernah berkhutbah di hadapan jamā‘ah kaum Muslimin dalam keadaan berpakaian yang sangat sederhana. Khalīfah ‘Utsmān Ibn ‘Affān r.a. banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah dan membaca al-Qur’ān. Baginya, al-Qur’ān ibarat surat dari kekasih yang selalu dibawa dan dibaca ke mana pun ia pergi. Demikian pula, sahabat-sahabat lainnya, seperti Abū Dzarr al-Ghiffārī, Tamīm ad-Dārī, dan Ḥudzaifah al-Yamanī.
Uraian dasar-dasar tashawwuf di atas, baik al-Qur’ān, al-Ḥadīts, maupun suri teladan para sahabat, ternyata merupakan benih-benih tashawwuf dalam kedudukannya sebagai ilmu tentang tingkatan (maqāmāt) dan keadaan (aḥwāl). Dengan kata lain, ilmu tentang moral dan tingkah laku manusia terdapat rujukannya dalam al-Qur’ān. Di sini, jelaslah bahwa pertumbuhan pertamanya, tashawwuf ternyata ditimba dari sumber al-Qur’ān itu sendiri.
Faktor intern yang dapat dipandang sebagai penyebab langsung lahirnya tashawwuf di dunia Islam, selain berupa pernyataan al-Qur’ān dan Hadits, adalah perilaku Rasūlullāh s.a.w. sendiri. Sebagaimana telah dimaklumi, beliau di dalam bertaqarrub (mendekatkan diri kepada Allāh) tidak jarang pergi meninggalkan keramaian dan hidup menyepi untuk merenung dan berkontemplasi dan ber-tahannuts di Gua Ḥirā’. Ternyata, di tengah-tengah kesendiriannya inilah, beliau berkomunikasi dengan Allāh dan mendapat petunjuk dari-Nya.